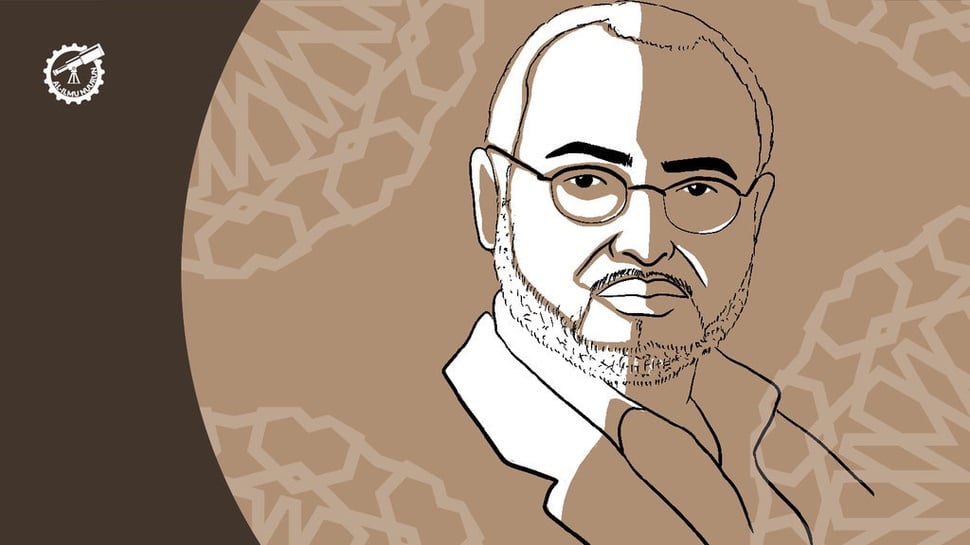tirto.id - Tulisan Khaled Abou El Fadl terbagi menjadi dua jenis. Pertama, disertasinya dan tulisannya bersama sarjana lain. Kedua, proyek intelektual jangka panjangnya. Proyek kedua ini ingin mengartikulasikan konsep kecantikan (beauty) dalam ajaran Islam. Sedangkan jenis yang pertama tidak mewakili konsep ini.
Disertasinya di Princeton di bawah bimbingan fakih Syiah dan sarjana modern ternama, Hossein Modarressi, ialah kajian sistematis atas gagasan dan perlakuan terkait pemberontakan dan perlawanan politik dalam hukum Islam klasik. Pada 2001 disertasi ini dibukukan menjadi Rebellion and Violence in Islamic Law. Ia tentu saja tidak membahas ‘apa yang cantik’ dalam pemberontakan, perampokan, dan perbanditan. Saat ia menulis bersama dengan yang lain, misalnya dalam Democracy and Islam in the New Constitution of Afghanistan (2003),yang difasilitasi lembaga tangki pemikiran Amerika RAND, juga tidak menguraikan soal ‘kecantikan’.
Menggali Keindahan Fikih
Konsep ‘kecantikan’ dalam pemikiran Abou El Fadl tak diperoleh melalui analisis seni dan sufisme dalam kebudayaan Islam. Ia menggalinya justru di dalam hukum Islam. Potongan surah Al-Muddatstsir ayat 31, wa ma ya`lamu junuda rabbika illa huwa (Tak ada seorang pun yang mengetahui tentara Tuhan kecuali Tuhan) menjadi pemantik untuk mencari siapa yang berhak menggenggam predikat muslim sejati.
Ayat itu mendorongnya untuk menegasikan sikap otoriter dalam menafsir teks lalu dihadapkan dengan sikap otoritatif. Penjelasannya sarat dengan analisis teks dan hermeneutika. Surah Al-Muddatstsir ayat 31, menurutnya, menolak setiap klaim seseorang sebagai tentara Allah yang dianugerahi otoritas-Nya, lalu dengan seenaknya sendiri menerjemahkan hukum-Nya. Otoritarianisme di sini lebih mengacu pada metodologi hermeneutik yang membajak dan memalsukan mekanisme mencari makna dari teks yang sangat subjektif dan pilah-pilih. Ini mengancam kemajemukan makna.
Sedangkan sikap otoritatif meniscayakan makna teks yang taksa dan ambigu yang umum dalam proses penggalian dan dinamika hukum Islam. Dalam pandangan ini, frasa ‘tentara Allah’ tidak boleh sembarangan diterjemahkan untuk merebut absolutisme Tuhan. Sikap otoritatif terbangun dari kejujuran, ketekunan, kelengkapan, kelayakan, dan pengekangan diri yang mesti dimiliki seorang fakih dalam memahami teks agama. Dalam timbangan hermeneutika Abou El Fadl, ini bagian dari kewajiban rasional (daruriyyat `aqliyyah).
Pembahasan hermeneutis macam itu sebenarnya hal yang lazim dalam kajian usul fikih (filsafat atau metodologi mendasar tentang hukum Islam). Karena itu Abou El Fadl sangat mementingkan pendekatan usuli yang berpegangan pada prinsip penafsiran rasional yang menjadi payung bagi penerapan hukum. Pandangan ini pertama kali dibukukan pada 1997 dalam And God Knows the Soldiers: The Authoritative and Authoritarian in Islamic Discourses.
Ini bagian dari upaya Abou El Fadl untuk menentang otoritarianisme yang berorientasi puritan dan non-rasional, seperti kalangan Wahabi. Ia tak kenal lelah berupaya untuk mengembalikan makna syariah dalam kehidupan modern, merebutnya dari kalangan ekstremis, serta menegakkan soal yang cantik dalam ajaran Islam. Makna dasar dari 'syariah' ialah ‘jalan menuju kebaikan dan etika’. Syariah dalam pandangannya, mengutip dokumen dari Al-Azhar, setara dengan prinsip-prinsip hukum alam. Kebebasan, egalitarianisme, serta keadilan adalah prinsip mendasar syariah.
Perlu diingat, syariah di sini bukan dalam pengertian sempit ‘syariah Islam’ yang menjadi jargon otoriter sebagian pihak untuk menentukan apa itu hukum Islam dalam pengertian cabang hukum Islam (furu`i). Syariah merupakan payung dari keindahan Tuhan. Keindahan-Nya termanifestasi oleh cinta, kasih sayang, kemuliaan, dan keadilan. Jika hukum-Nya tidak memenuhi unsur ini, maka itu tidak memenuhi kriteria otoritatif, sehingga bisa menimbulkan sikap tiranik dan despotik dalam beragama. Satu-satunya kekuatan tradisional yang mampu untuk melawan kecenderungan ekstremisme beragama dan bahkan meminggirkannya ialah fukaha (para ahli fikih), sebab mereka berhak dalam menafsirkan teks agama.
Sikap intelektual Abou El Fadl semakin kentara setelah peristiwa 11 September 2001 terjadi. Ekstremisme telah menjadi ancaman global. Ia terus-menerus menyuarakan bahaya ekstremisme beragama dalam kehidupaan saat ini. Ia bahkan menjadi penasihat Presiden George W. Bush untuk menentukan makna moderat dan puritan dalam kelompok Islam kontemporer. Posisinya dalam the US Commission on International Religious Freedom semasa Bush Jr. dianggap sebagai "suara moderat Islam" melawan elemen Islam radikal dan memperjuangkan "Islam yang plural, toleran, dan non-kekerasan".
Penunjukan ini bukan sesuatu yang enak. Ada yang menuding ia ikut melegitimasi agenda imperialis Amerika dalam memerangi terorisme global dengan menyuarakan Islam moderat dan demokratis. Para pembenci Islam menudingnya telah menginfiltrasi pemerintahan Bush Jr. Daniel Pipes, misalnya, menyebut Abou El Fadl sebagai ‘Islamis penipu’ dalam artikel bertajuk “Stealth Islamist: Khaled Abou El Fadl” di jurnal Middle East Quarterly.
Pipes, yang pernah berkuliah bareng Nurcholish Madjid di Universitas Chicago, menyuarakan islamofobia dalam masyarakat Amerika. Ia menuding Abou El Fadl sebagai ‘New Islamist’ (sebab mengikuti gairah intelektual Muhammad al-Ghazali, ulama moderat Ikhwanul Muslimin) meskipun anti-Wahabi. Bahkan Pipes menuduhnya diam-diam telah bersekongkol dengan komplotan teroris yang didanai Arab Saudi. Dalam kacamata Pipes, syariah yang diajarkan Abou El Fadl sama dengan hukum yang mendorong perbudakan, pembunuhan kafir, penindasan perempuan, dan non-muslim sebagai warga kelas dua.
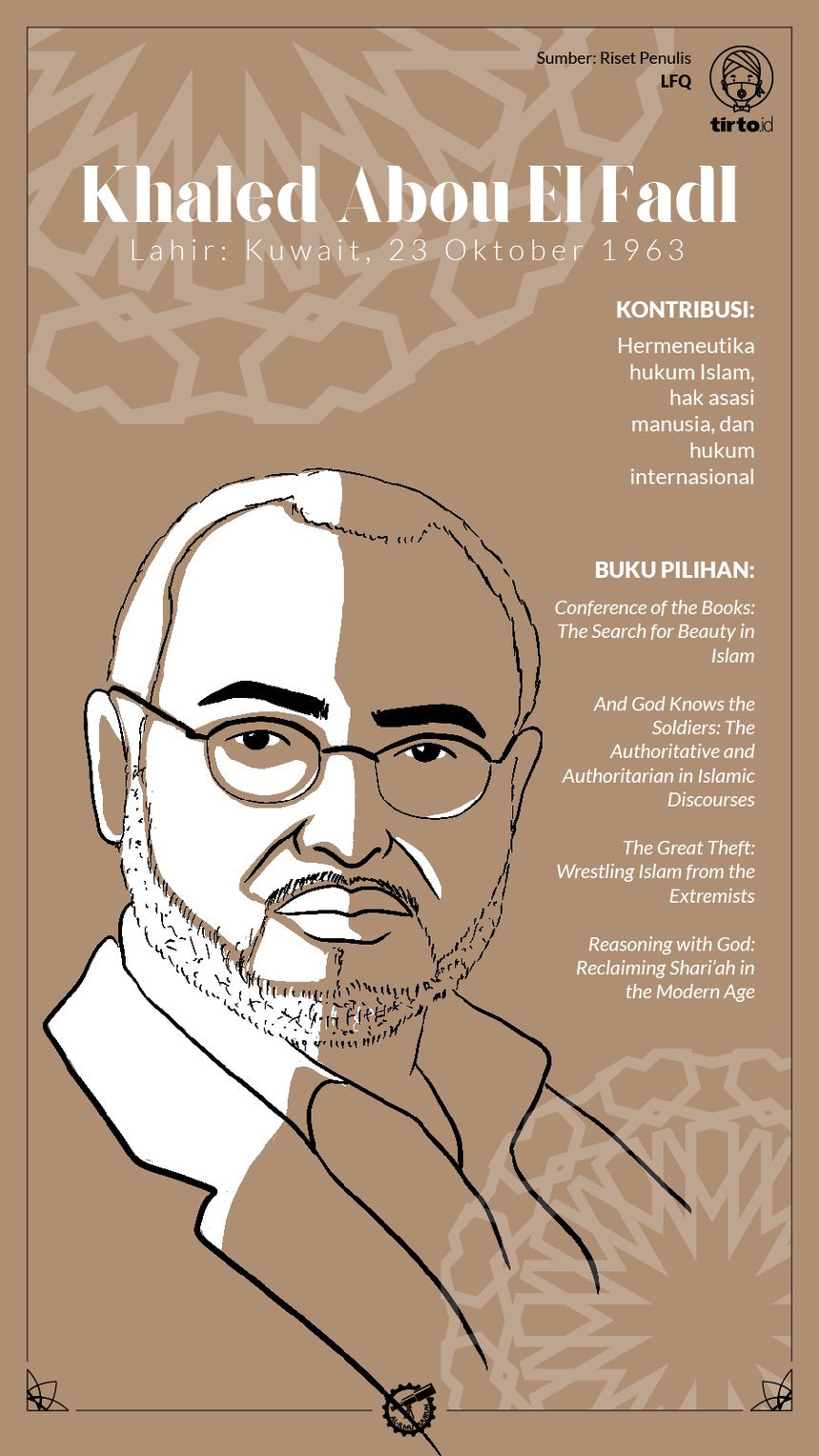
Spirit Kemodernan dalam Syariat
Terlepas dari penunjukannya pada masa itu, kedua pandangan tersebut tidak mewakili pemikiran Abou El Fadl secara umum. Apalagi pandangan sinis dan membahayakan dari orang seperti Pipes yang mendukung neokonservatisme di Amerika. Abou El Fadl dengan jelas dan terperinci mengartikulasikan syariah dalam spirit kemodernan dan bagaimana ia tak berseberangan dengan demokrasi dan hak asasi manusia. Sebab, pijakan dasar darinya ialah pada pandangan usuli.
Karena itu, selain mengajar di UCLA School of Law, ia aktif dalam menyuarakan gagasan melalui dua gerakan. Gerakan pertama diambil langsung dari refleksi bukunya yang ia tulis semasa menjadi mahasiswa doktoral di Princeton: "The Search for Beauty". Gerakan kedua jihad intelektual sebagai perlawanan atas makna jihad yang salah yakni melalui pembentukan Usuli: the Institute for Advanced Usuli Studies. Lembaga ini dibentuk pada 2017 sebagai upaya mengidupkan kembali semangat usul fikih klasik hingga zaman al-Andalus di Spanyol.
Kedua gerakan itu penting untuk memenangkan perang pemikiran (ghazw al-fikr), sesuai keterangan di laman Usuli: help us win the war of ideas. Tentu, berbeda dari tujuan jihadis-teroris, baginya kemenangan peran ini ialah mencari ‘kecantikan’ ajaran Islam yang universal.
Terbukti apa yang ditakutkan Pipes tapi juga dibenci kalangan puritan Wahabi ialah kesinambungan Abou El Fadl dalam menyuarakan Islam yang ramah dan rahmah untuk semua, tidak terkecuali soal perempuan. Abou El Fadl sangat menghargai posisi perempuan dalam Islam. Dalam Speaking in God’s Name: Islamic Law, Authority and Women, ia menelusuri pandangan otoritatif mengenai perempuan yang dimuliakan di dalam Islam, termasuk mengutip pendapat fakih al-Tabari (m. 923) yang membolehkan perempuan memimpin salat dengan jamaah lelaki serta menjadi hakim dalam pengadilan untuk segala kasus.
Sama dengan Fatema Mernissi, Abou El Fadl juga mempertanyakan posisi Abu Bakrah, periwayat hadis yang sinis dengan kepemimpinan Aisyah. Dengan menguraikan berbagai laporan sejarah dan riwayat hadis, Abou El Fadl mempertanyakan apakah suara "otoritatif" dari Abu Bakrah itu juga mewakili suara otoritatif dari Nabi Muhammad. Kendati Abou El Fadl secara apologetik mengakui tidak berkompeten untuk membahas kajian gender atau fikih feminis, ia memberi kata pengantar yang positif dan apresiatif untuk buku Amina Wadud, Inside the Gender Jihad (2006).
Mengapa Abou El Fadl sangat serius dalam mempertentangkan mana yang ‘cantik dan baik’ dan mana yang ‘buruk dan jelek’ dalam Islam? Bagi yang memahami usul fikih, jawabannya tak sulit diterka. Ada pembahasan oposisi biner dalam disiplin ilmu rasional masa klasik seperti konsep husn dan qubh yang mewakili dua timbangan etis: yang bermoral dan yang tak bermoral. Ia berusaha untuk mengangkat kategori usuli ini dalam wacana modern dalam rangka menentukan hukum Islam yang adil dan seimbang.
Gagasan itu sebenarnya serupa etika universal yang berkembang sejak masa Yunani. Lagi pula, Abou El Fadl juga menekankan pada norma umum husn al-khuluq, yakni penekanan pada perbaikan karakter atau etika sebagai panduan dalam berhubungan dengan Tuhan dan manusia.
Dengan mempelajari Islam secara tradisional kepada banyak syekh di Timur Tengah dan juga gelar kajian Islam dari Yale, Pennsylvania, dan Princeton, Abou El Fadl adalah suara otoritatif dalam membaca hukum Islam klasik dan hukum modern. Hukum di matanya berwajah lembut dan cantik jelita. Beauty dan beatiful adalah preferensi semantiknya, bahkan untuk menyebut lelaki etis: beautiful man.
==========
Redaksi Tirto kembali menampilkan rubrik khusus Ramadan "Al-Ilmu Nuurun". Tema tahun ini adalah para cendekiawan muslim global abad ke-20 dan ke-21. Kami memilih 33 tokoh untuk diulas pemikiran dan kontribusi mereka terhadap peradaban Islam kontemporer. Rubrik ini diampu kontributor Zacky Khairul Umam selama satu bulan penuh.
Zacky Khairul Umam adalah alumnus Program Studi Arab FIB UI dan kandidat doktor sejarah Islam di Freie Universität Berlin. Saat ini sedang menyelesaikan disertasi tentang pemikiran Islam di Madinah abad ke-17. Ia pernah bekerja sebagai peneliti tamu pada École française d'Extrême-Orient (EFEO) Jakarta 2019-2020.
Editor: Ivan Aulia Ahsan