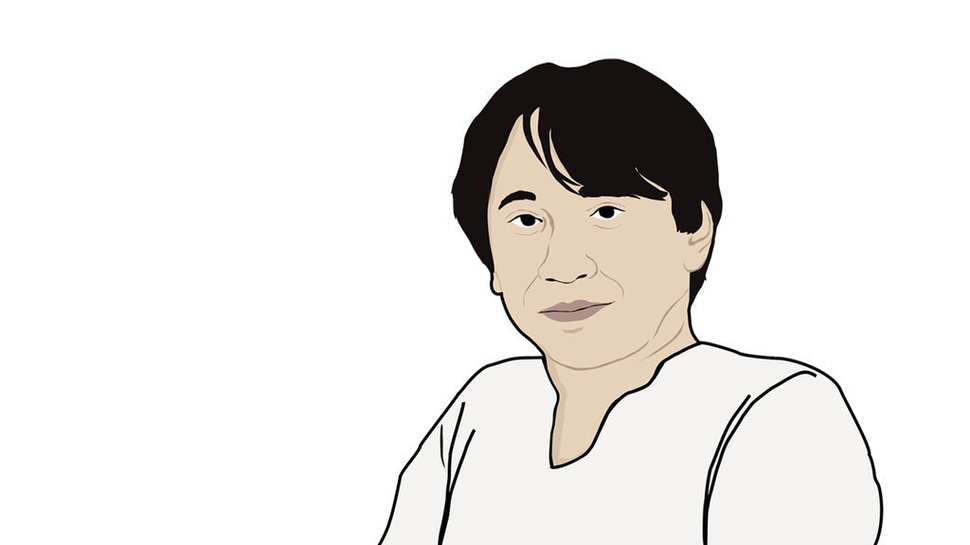tirto.id - Ada sebuah foto lama bergambar Sitor Situmorang duduk menghadapi meja kerja kayu jati besar yang membatasinya dengan Adam Malik. Di atas meja itu sebuah papan kayu tebal hampir seperti balok berukir tulisan yang segera menjelaskan posisi orang yang duduk di depan Sitor: Menteri Luar Negeri RI.
Tahun baru 1975 belum lama berlalu. Tepat 1 Januari tahun itu Sitor baru saja dibebaskan bersama 767 tahanan politik (tapol) “Golongan A”—kategori yang dibuat Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkokamtib). Kategori itu merujuk kepada orang-orang yang didakwa terlibat langsung dengan yang mereka sebut pemberontakan G30S/PKI. Sitor menandatangani surat pembebasan sekaligus pernyataan tidak akan menuntut dan menerima perkaranya dituntaskan tanpa pengadilan setelah delapan tahun dijebloskan Orde Baru ke penjara Salemba.
Isterinya, Tio Minar Gultom, telah lebih dulu menandatangani dokumen yang berbunyi “bahwa bersama ini oknum G30S/PKI Sitor Situmorang dibebaskan dengan persyaratan tidak boleh menerima tamu, tidak boleh berkirim surat dalam dan luar negeri, juga harus mendaftar seminggu sekali ke kantor CPM Guntur. Atas diikutinya semua perarturan ini bertanggungjawab nyonya Sitor Situmorang.” Artinya, sang istri diminta menjadi polisi yang memata-matai suaminya yang eks tapol.
Dalam ingatan keluarga pembebasan Sitor selalu dikaitkan dengan peran Adam dan politik luar negerinya. Di sekitar masa-masa pembebasan Sitor pemerintah militer Orde Baru memang tampak mulai mengkhawatirkan citranya di dunia internasional. Soeharto maupun beking-bekingnya yang berasal dari Amerika, Inggris, Jepang, Australia, atau negara Barat lainnya mulai menunjukkan ketertarikan terhadap upaya Amnesty International, TAPOL (British Campaign for the Defence of Political Prisoner and Human Rights in Indonesia), dan organisasi serupa yang memperjuangkan nasib tapol.
Demi Kepentingan & Citra Orde Baru
Tetapi, apakah pembebasan Sitor hanya terbatas kepada upaya Orde Baru mempermak wajahnya agar sedikit lebih manusiawi di hadapan dunia internasional dan khalayak nasional?
Jawaban atas persoalan itu perlahan-lahan terbuka dalam pertemuan Sitor dengan Adam. Sitor mengenal Adam sejak masa perang kemerdekaan ketika ia di Yogyakarta meliput suasana revolusi antara 1947 sampai 1948. Adam saat itu adalah pendiri dan pimpinan kantor berita nasional Antara tempat Sitor bekerja sebagai jurnalis. Bahkan ketika pecah Agresi Militer Belanda II pada 1948 dan Sitor ditangkap Nefis (Netherland Forces Intelligence Service) serta dipenjarakan di penjara Wirogunan sampai akhir 1949, intel Belanda mencatatnya sebagai jurnalis harian Waspada dan kantor berita nasional Antara.
Pada pertengahan 1950-an Sitor semakin dekat dengan Adam dan kawan-kawan kelompok Tan Malaka yang berkumpul di Partai Murba (Musyawarah Rakyat Banyak) seperti Chaerul Saleh. Chaerul malah menjadi orang yang dianggap paling tepat untuk menuliskan pengantar risalah politik yang ditulis Sitor sebagai penanda awal masuknya ia ke dalam politik kiri, yaitu Marhaenisme dan Kebudayaan.
Meski pada awal 1965 Adam sempat terpental dari kabinet karena aktivitasnya di Murba yang menyerang Sukarno, Adam, sebagaimana Sitor dan Chaerul, sesungguhnya adalah orang di lingkaran dekat Sukarno sampai mendekati hari-hari terakhirnya. Tetapi semua berubah setelah G30S meletus. Sitor dan Chaerul mengalami penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi. Chaerul bahkan meninggal akibat serangan jantung di dalam penjara karena tidak mendapat penanganan dokter.
Sebaliknya justru pada saat-saat kejatuhan Sukarno yang cepat dan luar biasa itu, Adam menjadi salah satu dari triumvirat simbolik Orde Baru bersama Soeharto dan Dorodjatun (Hamengkubuwana IX). Ia termasuk menteri yang selamat ketika Soeharto mengumumkan 15 menteri Sukarno yang ditangkap pada 18 Maret 1966, selang seminggu setelah Supersemar yang disebut para sejarawan menjadi penanda pengambilan kekuasaan Sukarno oleh Soeharto secara de facto.
Adam pun ditetapkan sebagai Wakil Perdana Menteri (Waperdam) II merangkap Menteri Luar Negeri. Belum dua minggu Adam kemudian masuk kabinet yang dirombak dan ia dibenum sebagai salah satu dari enam Waperdam yang menjadi anggota presidium. Adam tampak dengan cepat mampu mengemban tugas menangani warisan eksperimen politik luar negeri Sukarno yang dianggap membuat runyam, seperti politik Konfrontasi Ganyang Malaysia. Tetapi upaya menyetop konfrontasi itu menggambarkan bahwa pada akhirnya semua adalah ihwal bagaimana menciptakan kondisi yang memungkinkan Indonesia mendapat kepercayaan menerima bantuan dana dari Barat. Dengan kepercayaan itu, stabilitas ekonomi yang goyah pada 1965 diharapkan bisa pulih sehingga kekuasaan Soeharto dapat diperkuat.
Pada awal 1975 kala Adam mengundang Sitor ke kantornya itu juga masih terkait urusan menangani warisan politik Sukarno. Adam memanfaatkannya pula untuk bermacam-macam kepentingan yang dapat menjelaskan bagaimana Orde Baru dengan latar belakang aspirasi mendapatkan sumber ekonomi itu membentuk lanskap politik nasional dan internasional. Sebagian besar sumber tentang politik luar negeri masa Adam mengulas faktor kecakapannya merebut kepercayaan pemerintah-pemerintah asing, terutama Amerika yang ingin menghilangkan kesan bahwa mereka mendukung rezim militer di Indonesia.
Bukan hanya kepada pihak luar negeri, tetapi Adam juga cakap mengelola citra Orde Baru di dalam negeri. Harold Crouch dalam bukunya yang telah menjadi klasik dan diterjemahkan dengan judul Militer dan Politik di Indonesia mengungkapkan tentang bagaimana "Presiden Soeharto menyadari kebutuhan untuk memberikan gambaran yang menguntungkan di luar negeri dan menghormati pendirian Adam membentuk citra bahwa Indonesia dikuasai oleh suatu 'perikatan militer-sipil'."
Citra ini telah dibangun selama Sitor mendekam dalam penjara. Dimulai oleh kesadaran Angkatan Darat bahwa walaupun mereka berhasil menjatuhkan Sukarno dan semakin menguasai pemerintahan, partai-partai politik tetap mewakili kekuatan-kekuatan yang sesungguhnya dalam masyarakat. Sebab itu betapapun pemimpin-pemimpin AD enggan melaksanakan pemilu sebagaimana tercermin dalam seminar di Bandung pada 1966, tetapi mereka akhirnya wajib mendengarkan permintaan penasihat sipil dan perwira senior. Mereka, selain harus terus membersihkan unsur-unsur kiri di partai-partai serta mengisinya dengan orang-orang yang pro-Orde Baru, juga mesti menjalankan sistem pemilu yang dapat direkayasa sedemikian rupa agar tidak akan menguntungkan partai-partai.
Pada 1971 pemilu digelar dan, sebagaimana telah diperkirakan, partai-partai tidak beruntung. Hanya mesin non-partai buatan Angkatan Darat yang mendapat untung fantastis, yaitu Golkar. Kekalahan itu betul-betul melemahkan partai-partai sehingga membuat kemampuan beroposisi merosot drastis. Dalam situasi itulah mereka dipaksa membubarkan diri atau kembali menjadi organisasi massa dan melakukan fusi.
Pada akhir Januari 1973 dua partai baru terbentuk menggantikan partai-partai yang ada. Partai Persatuan pembangunan (PPP) menggantikan partai-partai Islam dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) sebagai pembauran partai-partai nasionalis serta Kristen. Kedua partai umumnya dipimpin orang-orang yang menuruti keinginan pemerintah dan menerima bantuan dari pemerintah untuk kegiatan-kegiatan mereka.
Tetapi, menjelang 1975, muncul kebutuhan baru untuk memperlihatkan warna nasionalis kiri di dalam PDI. Hal itu tak lagi sebatas untuk menegakkan citra bahwa Indonesia bukan tengah membangun kediktatoran militer, lebih jauh adalah sebagai tindakan untuk memulihkan citra politik luar negeri bebas aktif dan cita-cita non-blok ala Indonesia.
Motif politik itu juga berkaitan dengan upaya Adam menjaga kesempatan mendapatkan sumber dana dari negara-negara komunis agar Indonesia terhindar dari ketergantungan berlebihan kepada negara-negara Barat. Adam menyatakan bahwa memelihara hubungan yang “tepat” dengan Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur selalu terbuka apabila yang dipersyaratkan Barat terlalu memberatkan. Untuk inilah persambungan dengan masa Sukarno yang telah lalu dan orang-orangnya diperlukan kembali.
Berlatarbelakang itulah Adam menawarkan Sitor untuk bergabung mengisi struktur elite PDI. Adam tahu betul Sitor adalah orang yang paling tepat sebab Sitor bukan sekadar “jubir USDEK” alias propagandis yang mengubah pikiran Sukarno menjadi ajaran, tetapi lebih tampil sebagai sosok yang melakukan pembaruan pemikiran Sukarno.
Menolak Jadi Kolaborator
Sitor adalah bagian dari sedikit orang yang ikut merintis pentingnya membangun tradisi bahwa situasi pasca-kemerdekaan menuntut perhargaan kembali atas warisan intelektual nasionalis, terutama karya-karya Sukarno. Oleh sebab itu Herbert Feith menyebut Sitor termasuk bagian dari sedikit elite yang ideologinya tepat di belakang Sukarno. Ia tidak memperlakukan pemikiran intelektual nasionalis sebagai warisan keramat. Sebaliknya, Sitor menyerukan kebutuhan atas penyegaran (rejuvenation) dengan menerapkan metodologi baru untuk melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks intelektual nasionalis dalam menyelesaikan isu-isu sosial, budaya, ekonomi, hukum, dan politik kontemporer.
Terlebih lagi posisi Sitor dengan pemikirannya itu diharapkan Adam akan memenuhi harapannya yang lain. Bagi Adam, bergabungnya Sitor ke PDI dapat membantu memobilisasi wacana di kelompok pendukung pemikiran Sukarno dalam menghadapi timbulnya kesan bahwa Indonesia mempunyai rencana-rencana ekspansionistis. Pada 1973 hal ini pernah dirasakan negara-negara tetangga, tetapi Adam berhasil meredamnya.
Tak selang lama, pada 1974, Adam melihat nafsu ekspansionistis itu akan terjadi kembali di Timor Timur. Sejak setahun sebelum Sitor bebas itu Adam sudah bersitegang dalam pandangan terkait Timor Timur. Sementara Adam menjanjikan kepada Ramos Horta tidak akan mencampuri urusan Timor Timur, Menteri Pertahanan dan Keamanan Jenderal Maraden Pangabean dan Wakil Kepala BAKIN Ali Murtopo terus mengungkapkan nafsu ekspansionis. Adam sedang menghadapi figur-figur yang besar pengaruhnya pada karakter pemerintah Indonesia.
Sampai di situ pertemuan berakhir. Sitor pulang. Lalu sebuah foto lagi dari waktu yang berbeda selang hampir sebulan setelahnya. Tampak Sitor menghadapi Adam. Tanpa jarak. Mereka duduk bersama di sebuah bangku panjang berukir. Itulah pertemuan kedua mereka dan kesempatan Sitor menolak tawaran Adam.
Sitor menyatakan bahwa partainya sudah berakhir bersama jatuhnya Sukarno dan ditangkapinya para pimpinan PNI, Ali Satroamidjojo dan Surachman, yang diejek sebagai PNI-Asu. Tentang harapan Adam membangkitkan pikiran Sukarno di dalam PDI, Sitor mengungkapkan sebagai hal yang tidak mungkin lagi bisa dilakukan olehnya dan siapapun selama Sukarno dianggap kotoran lalu dilupakan dan disangkal.
Kisah yang dialami Sitor ketika menghadapi tawaran Adam membuka tabir kondisi internal rezim Orde Baru. Tentu saja—tanpa mengurangi hormat atas kerja keras organisasi-organisasi hak asasi manusia yang seharusnya tidak diremehkan—telah banyak studi bahwa program pembebasan itu adalah praktik pencitraan yang sengaja dilakukan untuk mengalihkan perhatian sekaligus meredam kritik atas kebijakan represif di dalam negeri. Sebab, di luar pencitraan yang dilakukan Orde Baru, Sitor dan para eks tapol harus menghadapi represi terlembaga yang parah dan serangkaian viktimisasi dalam masyarakat bebas. Bahkan putrinya kehilangan kesempatan kerja hanya karena bapaknya eks tapol. Sementara isterinya harus mengusir setiap tamu yang hendak menemuinya.
Sitor Situmorang, yang meninggal pada 21 Desember 2014, tepat hari ini 5 tahun lalu, melihat sebenarnya Orde Baru tidak berhenti pada satu kasus kejahatan serius seperti pelanggaran HAM. Pemerintahan Orde Baru menghadapi masalah ketidaksesuaian antara demokrasi dan praktik politik, hukum dengan keadilan. Dalam situasi ini, bagi Sitor, jalan untuk memperoleh kemerdekaan, keadilan, dan demokrasi tidak akan dapat dicapai dengan menjadi—meminjam istilah Patrick Flanagan dan Julie Southwood dalam Teror Orde Baru—kolaborator, baik yang melempem maupun kritis.
Sebab bila menempuh jalan itu akhirnya betapapun berani dan beratnya perlawanan, mereka ditakdirkan untuk menjadi defensif atau lebih tepatnya tunduk. Mereka berada dalam sistem tersebut hanya untuk dikesampingkan, dan diperhitungan selama mereka melayani kekuasaan.
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.