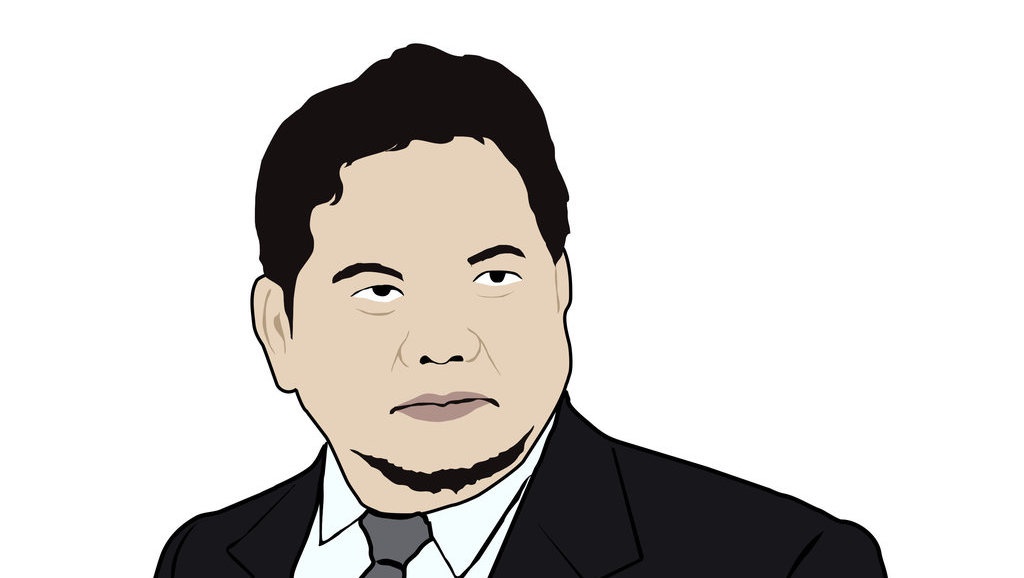tirto.id - Bagaimana seorang Majid Majidi, sutradara besar Iran yang acap mengangkat tema anak-anak (Children of Heaven, Color of Paradise, Baran) dan problematika keluarga kelas menengah ke bawah (Pedar, Song of Sparrows), menafsirkan kisah hidup Nabi Muhammad, manusia paling paripurna dan mulia?
Sepenting apa film Muhammad the Messenger of God (2015) ini, dan mengapa film ini kurang disambut secara komersail, bahkan tak masuk seleksi unggulan Film Asing Terbaik Academy Awards?
Kisahnya bermula dari semangat dakwah di industri film global dan melawan Islamofobia di Barat, khususnya sesudah kasus kartun Denmark—yang membuat Majidi menarik film Willow Tree (2005) dari festival film di Denmark sebagai aksi protes. Majidi, yang filmnya Children of Heaven masuk nominasi Film Asing Terbaik Academy Awards, ingin menggarisbawahi bahwa Nabi Muhammad adalah sosok yang welas asih, bahkan jauh sebelum Ia menikah pada usia 25 tahun dan diangkat menjadi Nabi pada umur 40 tahun.
Untuk tujuan itulah Majidi membentuk tim impian kelas dunia: Vittorio Storaro (Sinematografer peraih Oscar untuk Apocalypse Now, 1979; Reds, 1981; dan The Last Emperor, 1987) dan musisi andal AR Rahman (peraih Oscar, Grammy Awards, dan Golden Globe untuk film Slumdog Millionaire, 2009).
Republik Islam Iran pun mendukung penuh ide Majidi. Ia pun mulai menyiapkan produksi film ini sejak 2007 dan selesai menulis naskahnya—bersama Kambuzia Partovi—dua tahun kemudian. Pada 2011, Shahrak Sinamai Nour, sebuah daerah di antara jalan tol Teheran-Qum, disulap menjadi Mekkah (dan Madinah) tahun 570-an (sebagian kecil lain disyut di Afrika Selatan).
Pembangunan set yang dirancang semirip mungkin dengan situasi zaman Muhammad hidup ini tak lepas dari peran tim internasional, perancang produksi Miljen Kreka Kljakovic, serta perancang kostum Michael O’Connor dan Seyed Mohsen Shahebrahimi. Hasilnya, film ini menjadi film termahal dalam sejarah sinema Iran dalam 5 tahun terakhir, dengan ongkos produksi sekitar 50 juta dolar AS.
Untuk mendapatkan ide tentang masa lalu sang Nabi, dan menyamakan persepsi demi menghindari konflik, Majidi meminta masukan para ulama Syiah dan Sunni sebagai penasihat, dari Aljazair, Maroko, Lebanon, dan Irak. Pada tahap akhir, Majidi juga berkonsultasi dengan Ayatullah Ali Khamenei (pemimpin spiritual tertinggi Iran), Ali Al-Sistani, Ayatullah Wahid Khorasani, dan filsuf Iran Ayatullah Jawadi Amuli, serta kalangan Sunni seperti Hayrettin Karaman dari Turki.
Namun, tetap saja, fatwa yang melarang film ini bermunculan.
Dekan Fakultas Teologi Universitas Al-Azhar, Kairo, Abdulfatah Al-Awari, misalnya, melarang film ini karena dianggap "merendahkan" kesucian sang utusan tuhan. Mufti Agung Arab Saudi Abdul Aziz ib Abdullah Al-Shaykh mengutuk film ini karena terkesan "menghina" nabi dan dan "melemahkan peran penting" yang dimainkannya dalam Islam. Organisasi Liga Muslim Dunia, yang diwakili Abdullah bin Abdulmohsen Al-Turki, juga mengkritisi penggambaran fisik Nabi. Di India, Raza Academy juga mengeluarkan fatwa melarang film ini. Walhasil, film ini agak susah di pasaran, tetapi versi ilegalnya muncul di dunia maya sejak beberapa pekan lalu.
Jadi, kembali ke pertanyaan awal, bagaimana kisah seorang Nabi Besar, bukan rakyat biasa, hadir dalam semesta pikiran dan karya Majid Majidi?
Nabi Muhammad dalam film pertama dari trilogi ini dikisahkan dari baru lahir dan berakhir saat Ia berusia sekitar 13 tahun kala berdagang ke Syria dan bertemu Pendeta Bahira. Spesialisasi Majidi membuat film ini lihai mengemas kisah dan bahasa audio visual seorang Muhammad kecil. Karena ada larangan penggambaran Nabi, maka tiap adegan Muhammad kecil, wajah dan tubuhnya dibaluri cahaya yang menyilaukan mata, kecuali bagian kaki dan tangan.
Saat balita dan menjelang remaja, Nabi tak pernah diperlihatkan wajahnya, hanya dari belakang terlihat sosoknya yang berambut gondrong dan berbusana serba putih cemerlang. Untuk suara, ada sedikit dialog yang diucapkan, yang tak terdengar tapi digantikan dengan teks. Namun, khusus untuk suara, ada beberapa bagian yang bisa multitafsir, yaitu saat surat Al-Fil (Gajah) dilantunkan dan menjadi pengantar untuk kilas-balik ke era kelahiran. Apakah itu suara sang Nabi ataukah sang narator, Abu Thalib?
Sebagai sineas yang karya-karyanya kental dengan pendekatan neorealis, Majidi acap memunculkan karakter-karakter sederhana dari kalangan rakyat jelata. Tak terkecuali dalam film yang dinarasikan oleh karakter Abu Thalib ini. Selain menceritakan narasi besar, seperti serangan Pasukan Gajah dari Abrahah (Pasukan Gajah) Sang Penguasa Habasyah (Etiopia), Majidi juga mengisahkan narasi kecil dari manusia-manusia biasa di sekitarnya. Misalnya, kisah Halimatus Sa’diah dan suaminya Hamzah sang inang (wet nurse) asal Badui, dan Tsuwaibah (budak milik Abu Lahab yang dilarang menyusui bayi Muhammad).
Bahkan kisah Aminah, sang Bunda, diceritakan secara manusiawi yang merasakan kesengsaraan, misalnya saat ia kebingungan tak bisa memproduksi ASI dan tak boleh mendapatkan inang karena dilarang iparnya, Abu Lahab dan sang istri, Jamilah. Aminah juga harus terpisah dari anaknya untuk dibawa ke dusun Badui, menghindari ancaman kaum Yahudi pimpinan Samuel. Dan, saat ada serangan Pasukan Gajah, pada saat mengungsi dan panik, Aminah yang hamil tua tetap bertahan walau terlihat cemas, meski sudah diajak Fathimah binti Asad, istri Abu Thalib.
Penafsiran Sejarah Nabi
Sebagaimana misi utamanya mempromosikan Rasulullah yang welas asih, film berdurasi nyaris 3 jam ini pun menggambarkan Muhammad kecil sebagai sosok penuh kasih sayang, khususnya kepada para budak dan golongan tertindas.
Ia dikisahkan mencegah seorang ayah yang hendak menguburkan hidup-hidup putrinya yang baru lahir—sebuah tradisi yang wajar saat itu. Muhammad kecil bahkan berdialog dengan Abu Lahab—paman dan orang yang paling memusuhinya—agar Tsuwaibah, budaknya yang sempat menyusuinya, untuk dibebaskan dan berjanji bahwa kelak ia akan membayar tebusannya.
Sifat mulia ini, sepertinya, diturunkan dari kakeknya, sang pemimpin Bani Hasyim dan Penjaga Kakbah yang, seperti direpresentasikan dalam film, tak hanya mengundang orang kaya dan kaum elite tapi memberi makan fakir-miskin untuk menyambut kelahiran sang cucu, walaupun hal ini melawan arus tradisi saat itu.
Majidi memang punya tafsiran yang agak berbeda dari arus utama seputar tokoh-tokoh utama di sekitar Nabi.
Pertama, bukan karena tradisi Arab saat itu yang mengirim bayi-bayi mereka ke dusun untuk disusui, tapi kondisi Aisyah yang tak punya ASI-lah yang menjadi alasan Muhammad harus mendapatkan ibu susu. Dengan begitu, Aminah terasa sangat manusiawi, ditambah ia terlihat berat hati melepas anaknya ke kampung halaman Halimah.
Kedua, Abdul Muthalib dan Abu Thalib digambarkan sebagai sosok yang hanif(lurus, masih menganut monoteisme), tak menyembah berhala, dan sangat saleh. Dalam upacara menamakan cucunya, ia lebih memilih memegang Hajar Aswad, bukan berhala. Bahkan sang Kakek mengajarinya bertawaf mengitari Kakbah sambil menegaskan niatnya lurus untuk tak menyembah berhala. Hal ini secara tak langsung menegasikan pendapat banyak kalangan yang menyatakan Abdul Muthalib (dan Abu Thalib) mati dalam keadaan kafir karena belum sempat bersyahadat.
Kisah lain yang baru saya tahu adalah kisah Tsuwaibah. Bagaimana Nabi mengobati sang ibu susu Halimah dan menyingkirkan dukun musyrik, yang menyebabkannya menjadi target penculikan. Juga soal panen di Yastrib dan Muhammad cilik yang sakit panas.
Saya juga baru ngeh bahwa Nabi sering menghabiskan waktunya di Yastrib, yang kelak menjadi pusat pemerintahan umat Islam era itu, demi menghindari kejaran Rahib Yahudi. Peristiwa lain yang saya baru tahu adalah tentang kunjungan ke sebuah desa nelayan penyembah berhala. Dikisahkan, dengan ijin Tuhan, ombak seperti mengamuk, tetapi membawa rezeki dari laut.
Versi Majidi juga menggarisbawahi salah satu pusat cerita adalah kisah intrik keluarga besar, atau katakanlah, sibling rivalry—di samping persaingan antar-klan antara Bani Hasyim dan Bani Umaiyah.
Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan sesungguhnya adalah paman-paman Nabi alias saudara Abdullah sang ayah, sama seperti Hamzah dan Abu Thalib. Dikisahkan bagaimana mereka cemburu dengan Aminah, sang janda dari anak emas Abdul Muthalib bernama Abdullah, apalagi saat itu ia sedang hamil tua. Sebagai para tetua, paman-paman Nabi menolak mengakui kekuasaan ilahiah sang Nabi, walau dalam hatinya mengakui kebenaran risalahnya.
Kedengkian ini pun diakibatkan oleh rasa sebal Abu Lahab yang dianaktirikan karena menikah dengan wanita dari Bani Umaiyah, dan karenanya menolak mengirimkan budaknya untuk meneteki sang keponakan.
Dan tentu saja, urusan dapur alias perekonomian yang menjadi penghambat. Bagaimana mungkin berhala-berhala yang menjadi sumber uang mereka harus dicoret dari ritual keagamaan? Embargo ekonomi yang diprakarsai Abu Sofyan—yang dikenal dengan istilah “Tahun Duka Cita” karena wafatnya dua tokoh penting dalam dakwah awal Rasulullah—makin menggarisbawahi perkara politik dan ekonomi. Dan akhirnya, serangan Pasukan Gajah untuk menghancurkan Kakbah juga menggarisbawahi urusan perebutan kekuatan ekonomi berskala global.
Tak Sekadar Fatwa
Bagi saya, Muhammad the Messenger of God adalah kompromi yang sempurna antara daya kreatif seni dan hukum syariat. Apalagi Majid Majidi sudah terlatih sejak 1980-an untuk mengakali film agar tidak melanggar aturan agama yang ketat. Sebuah film yang tak hanya puitis, melainkan membuat haru karena kita ditarik ke semesta lain: Mekkah pada 570-an; era kanak-kanak Rasulullah.
Seperti saya tuliskan di awal, beragam reaksi yang mengharamkan film ini dengan pelbagai pertimbangan. Dan, fakta bahwa pembuatnya adalah seorang warga Iran yang Syiah dan didukung penuh oleh negaranya, seakan-akan makin menambah daftar “dosa” film ini.
Namun, membaca beberapa ulasan, tak sedikit pula yang tersentuh. Muhammad the Messenger of God adalah film Muhammad pertama sejak Ar-Risalah (The Messenger) yang disutradarai Moustapha Akkad pada 1976. Beberapa resensi menyatakan Muhammad the Messenger of God begitu puitis dan emosional, khususnya bagi pencinta Nabi, melihat junjungannya dipresentasikan secara visual, meski tetap tak memperlihatkan wajah, tak sekadar huruf “Muhammad” dalam lingkaran.
Perbedaan pandangan yang melahirkan fatwa ini terjadi karena, mengutipLesley Hazleton (penulis The First Muslim), kaum Sunni punya aturan lebih ketat soal penggambaran Rasulullah.
Muhammad the Messenger of God akhirnya berbuah balasan. Seperti dilansir Hollywood Reporter dan The Guardian pada 2013, Alnoor Holdings, sebuah tim dari Qatar, menggandeng produser The Lord of the Rings dan Matrix Barrie Osborne untuk membuat film tandingan, di bawah pimpinan ulama besar Yusuf Qardhawi. Film berbujet 150 juta dolar AS ini untuk sementara berjudul The Messenger of Peace, dan akan mengangkat sisi manusiawi sang Nabi.
Syukurlah balasannya adalah film juga, bukan sekadar protes dan fatwa.
=======
Penulis bisa dikontak di @ekkyij
Editor: Windu Jusuf
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id