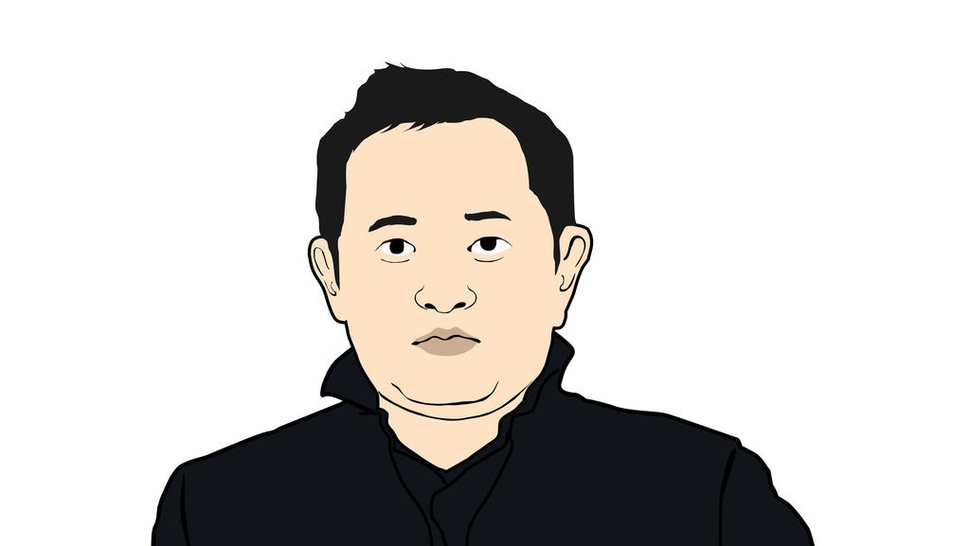tirto.id - Ketika media dikuasai liputan arus mudik selama libur lebaran 2019, bencana banjir terjadi di Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kabupaten Konawe Utara. Banjir menerjang sejak 1 Juni 2019, merendam lebih dari 40 desa, dan mengakibatkan lebih dari lima ribu penduduk mengungsi.
Tirto menyoroti dugaan kuat konsesi pertambangan dan perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir bandang. Entengnya pemberian izin tambang dan perkebunan mempunyai andil terhadap degradasi hutan secara ekstensif. Terlebih, hal ini pun diakui oleh Wakil Gubernur Lukman Abunawas bahwa kerusakan lingkungan di kawasan hutan menjadi penyebab banjir bandang yang melumpuhkan Konawe Utara.
Selama enam bulan terakhir ada tiga bencana yang mirip dengan yang terjadi di Konawe Utara, yakni bencana banjir bandang di Sentani, Papua (16 Maret); bencana banjir di Bengkulu (27 April); dan bencana banjir bandang di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah (awal Mei).
Bencana-bencana itu sekilas memiliki pola yang hampir mirip, yakni disebabkan oleh kerusakan lingkungan. Lebih jauh lagi, ada kesan kuat kerusakan lingkungan yang terjadi berhubungan dengan maraknya aktivitas pertambangan dan perkebunan yang tidak terkendali. Kegiatan pertambangan dan perkebunan yang eksesif bisa muncul karena adanya permainan kuasa yang berbasis kepentingan ekonomi dan politik.
Empat bencana beruntun dengan pola yang hampir mirip tersebut jelas menyiratkan persoalan krusial dalam pengelolaan sumber daya alam. Kita pun akhirnya dituntut melihat bencana bukan dari kacamata konvensional. Bencana tak hanya disebabkan reaksi alam semata namun berhubungan erat dengan kepentingan ekonomi-politik dan relasi kuasa.
Kita memerlukan cara pandang lain dalam melihat bencana terutama yang terkait dengan dimensi politik. Pertanyaannya, bagaimana ilmu politik bisa membantu memberikan penjelasan alternatif tentang kebencanaan?
Human-made Disaster dan Klientelisme
Secara konvensional, bencana selalu dipahami lewat pendekatan yang tidak menyertakan perspektif politik. Diskursus bencana didominasi oleh disiplin ilmu alam seperti geologi, planologi, dan klimatologi. Selain dari ilmu-ilmu alam, sebenarnya cabang keilmuan dari rumpun ilmu sosial juga sering kali disertakan seperti ekonomi.
Pendekatan ekonomi dibutuhkan misalkan untuk menghitung ongkos ekonomi yang dihasilkan oleh suatu bencana ataupun melakukan penghitungan potensial kerugian dari bencana. Baru-baru ini, pendekatan antropologi juga mulai sering dilibatkan untuk membantu efektivitas mitigasi bencana agar sesuai dengan budaya lokal.
Namun, walaupun ilmu sosial memang sudah mulai cukup jamak untuk digunakan dalam studi kebencanaan namun pendekatan politik belum lazim untuk disertakan. Hal ini cukup problematis untuk studi kebencanaan karena baik dalam mitigasi maupun kerja penanggulangan bencana tidak bisa dilepaskan dari relasi kuasa di masyarakat. Alih-alih datang dari ruang hampa, mitigasi dan penanggulangan bencana berada di tengah relasi negara, arus modal, dan masyarakat.
Secara sederhana, kita bisa menempatkan kebencanaan yang dekat dengan dimensi politik adalah bencana yang disebabkan oleh manusia atau human-made disaster. Kita bisa berargumen bahwa bencana yang disebabkan manusia merupakan konsekuensi dari kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam yang eksesif dan koruptif.
Lebih jauh lagi, oligarki ekonomi dan klientelisme politik menyebabkan pemanfaatan sumber daya alam tidak bisa lepas dari resource curse atau kutukan sumber daya alam. Sumber daya alam yang seharusnya dikelola untuk distribusi kesejahteraan justru menimbulkan kerugian seperti kerusakan lingkungan yang berujung pada bencana. Oligarki dan klientelisme membuat pengelolaan sumber daya alam serampangan karena minimnya akuntabilitas pengelolaan yang jelas.
Elite oligarki mempunyai modal besar mampu mengondisikan untuk memperoleh konsesi pengelolaan sumber daya alam tanpa melewati mekanisme dan prosedur yang terjamin integritasnya. Klientelisme lewat praktik rente (rent-seeking) mengakibatkan kegiatan eksploitasi sumber daya alam tidak tersentuh oleh pengawasan negara baik pusat dan terutama pemerintah daerah.
Perbandingan Empat Bencana
Untuk lebih memperjelas argumen sebelumnya, kita bisa menggunakan bencana-bencana yang terjadi pada enam bulan terakhir sebagai bagaimana kerusakan lingkungan akibat praktik koruptif klientelisme bisa berujung kepada bencana.
Pertama adalah bencana banjir bandang di Sentani, Provinsi Papua dan kedua bencana banjir di Kabupaten Gunung Mas. Banjir bandang yang terjadi di Sentani, Papua, pada 16 Maret 2019 menelan korban jiwa hingga 112 orang dan kerugian material hingga hampir mencapai Rp500 milyar rupiah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan bahwa banjir terjadi akibat penggundulan hutan di Kawasan Gunung Cyclop sehingga tanah tidak mampu lagi menyerap air. Penggundulan hutan di lereng Cyclop berawal dari maraknya praktik penebangan pohon secara tidak bertanggung jawab. Penggundulan hutan besar-besaran di lereng Gunung Cyclop dikabarkan melibatkan beberapa elite lokal sehingga praktik tersebut sulit untuk dihentikan.
Kedua, 30 orang meninggal dan lebih dari 12 ribu warga mengungsi akibat bencana banjir yang melanda sejumlah kabupaten di Provinsi Bengkulu pada 27 April 2019. Gubernur Bengkulu menyampaikan bahwa banjir disebabkan di antaranya oleh aktivitas pertambangan dan penggundulan hutan sebagai bagian dari Hak Guna Usaha (HGU) yang menyebabkan persoalan di hulu sungai.
Ketiga, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, mengumumkan status tanggap darurat bencana banjir pada awal Mei. Bencana banjir merendam hampir semua kecamatan di Kabupaten Gunung Mas. Bencana banjir tersebut sebenarnya bukan hal yang mengejutkan setelah melihat deforestasi besar-besaran menyusul masifnya industri perkebunan sawit di daerah tersebut. Deforestasi dan besarnya industri sawit di Kabupaten Gunung Mas menjadi salah satu fokus dari kerja jurnalisme investigasi lintas dunia yang berada dalam payung The Gecko Project. Tempo dan Mongabay merupakan dua media dari Indonesia yang menjadi kolaborator dalam sindikasi tersebut.
Fakta yang kemudian terungkap The Gecko Project di Gunung Mas adalah masifnya industri sawit yang tidak lepas dari kesepakatan rahasia antara dinasti lokal yang berkuasa di daerah tersebut dengan oligarki nasional di Jakarta. Kemudahan memperoleh izin investasi untuk perkebunan sawit sudah dikondisikan oleh kerjasama dengan elite lokal setempat. Kuatnya jejaring klientelistik tersebut tidak heran menempatkan Kabupaten Gunung Mas sebagai salah satu daerah dengan angka Indeks Persepsi Klientelisme (IPK) terburuk di Indonesia (Berenschot, 2018).
Pengawasan terhadap industri perkebunan sawit sangat lemah sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan berskala besar lewat deforestasi yang tidak terkontrol. Walhasil, publik menyaksikan bahwa Kabupaten Gunung Mas selalu dirundung bencana banjir tiap tahun.
Keempat, banjir bandang yang terjadi di Konawe Utara semakin memperlihatkan keterkaitan antara bencana dengan praktik klientelisme. Penerbitan izin usaha pertambangan di Konawe Utara mengalami tren kenaikan di masa-masa mendekati pemilihan kepala daerah. Lebih jauh, KPK resmi menyatakan mantan Bupati Konawe Utara sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari sejumlah pengusaha tambang untuk memuluskan perizinan.
Dari kasus-kasus tersebut, kita bisa mengatakan bahwa dimensi politik tidak bisa dilepaskan dari bencana terutama dalam human-made disaster. Tanpa menyertakan dimensi politik dalam studi kebencanaan bisa dipastikan kita tidak akan mampu merumuskan solusi yang komprehensif. Relasi kuasa yang timpang menjadikan kerusakan lingkungan keniscayaan dalam pengelolaan sumber daya alam. Lagi-lagi, ujung-ujungnya adalah bencana.
Pendekatan politik baik dalam mitigasi maupun penanggulangan bencana merupakan persoalan yang krusial. Riset-riset kebencanaan penting untuk melibatkan pendekatan politik sehingga tidak abai dengan aspek permainan kuasa yang seringkali menjadi faktor utama penyebab bencana.
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.