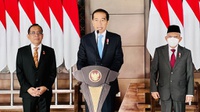tirto.id - “Siapa pun yang mempersilakan pengungsi masuk, jika Anda bilang 'biarkan mereka masuk', Anda bertanggung jawab atas Brussels. Dan Anda masih juga tak menyadarinya."
Cuitan itu berasal dari kolumnis berpandangan anti-imigran asal Britania, Katie Hopkins. Ia menyalahkan pemimpin Eropa karena membuka gerbang bagi pengungsi. Mantan bintang acara televisi Apprentice ini pun pada twit sebelumnya menyebut Brussels yang diserang teror bom pada 22 Maret 2016 lalu sebagai pusat jihadis.
"Jika Anda mendengar lagi seseorang berkata kita lebih aman DALAM Uni Eropa – ingatlah Brussels. Kota yang sebelumnya dilihat sebagai jantung Eropa, kini adalah pusat jihadis.” Hopkins mengkontraskan peristiwa teror itu dengan status Brussels yang dikenal sebagai kota tempat Uni Eropa berkantor.
Tak ketinggalan, Hopkins pun melengkapi cuitan tanggapan atas peristiwa yang menewaskan setidaknya 34 orang itu dengan tagar #Brexit (British Exit). Negaranya, Britania Raya, memang akan menghadapi referendum keanggotaannya di Uni Eropa pada 23 Juni mendatang.
Reaksi penolakan yang menyatakan tak setuju dengan cuitan Hopkins pun bermunculan. Mereka tak merasa diwakili oleh kata-kata yang bernada permusuhan terhadap kaum imigran itu. Bahkan salah satu pengguna Twitter, Kat Brown, kepada The Independent mengatakan bahwa ia melaporkan tweet itu ke Polisi Metropolitan karena mengandung ujaran kebencian.
Cuitan yang menyalahkan tangan terbuka terhadap imigran itu juga di-retweet sebanyak empat ribu kali. Meski retweet tak otomatis menandakan kesetujuan, pada kenyataannya Katie Hopkins tak sendiri. Ia adalah noktah kecil dari simpul-simpul gerakan ekstrem kanan di Eropa. Ada tokoh-tokoh yang jauh lebih terkenal dan berpengaruh karena memimpin partai, contohnya Geert Wilders di Belanda dan Marine Le Pen di Perancis.
Wall Street Journal melaporkan, Lega Nord atau Liga Utara, partai regional di Italia menyerukan agar perbatasan-perbatasan dan masjid-masjid ditutup. Le Pen di Perancis meminta agar penjagaan perbatasan dan penyisiran oleh polisi ditingkatkan. Pemimpin kanan-jauh Austria juga tak mau kalah. Heinz-Christian Strache berpendapat serangan teror itu menunjukkan bahwa imigrasi dari dunia Arab dan terbukanya perbatasan Uni Eropa harus benar-benar diakhiri.
Lebih dari semua tokoh di atas, respons paling keras datang dari Polandia.Al Jazeera menulis pernyataan perdana menteri Polandia bahwa negara ini tak lagi siap menerima pengungsi karena serangan Brussels. Padahal, sedianya Polandia akan akan membuka perbatasannya bagi 7 ribu pengungsi saat bernegosiasi dengan Uni Eropa.
Beata Szydlo berkata ia “tak melihat ada kemungkinan bagi para pengungsi untuk masuk Polandia.” Polandia tadinya berencana menerima 400 pengungsi tahun ini, dan sisanya akan masuk bertahap dalam tiga tahun mendatang.
Sikap berbalik menjadi penolakan ini tak terlalu mengejutkan. Tahun lalu, ada ribuan warga Polandia berunjuk rasa di jalanan dan media sosial mengampanyekan gerakan anti-imigran di seluruh penjuru negaranya. Kampanye besar ini diorganisasi oleh gerakan-gerakan kanan-jauh seperti National Radical Camp.
Presidennya, Andrzej Duda juga sempat melontarkan pernyataan bahwa pengungsi membawa kemungkinan wabah penyakit. Saat itu, ia merujuk pada penyakit kolera di kepulauan Yunani dan disentri di Wina, Austria, yang menurutnya dibawa oleh para pengungsi. Duda sendiri adalah anggota Law and Justice Party, partai yang dikenal kerap menggaungkan pendapat senada.
Persepsi Negatif terhadap Pengungsi, Muslim, Imigran
Selain ada gerakan anti-imigran, hasil survei juga menunjukkan kecenderungan warga Polandia yang mengarah ke sana. Dalam survei perilaku global yang dilakukan 2014, Pew Research Center mencatat 80 persen orang Polandia tak ingin kedatangan imigran dalam jumlah lebih banyak.
Separuh dari jumlah itu menginginkan lebih sedikit imigran yang datang, sedangkan sebagian lainnya menginginkan jumlah imigran yang kira-kira sama dengan yang biasanya. Hanya 9 persen orang Polandia yang sudi menyambut imigran lebih banyak.
Namun Polandia ternyata tak sendiri. Warga di negara Eropa lain pun tak jauh berbeda dengan warga di negara ini. Negara yang lebih dari 10 persen warganya mau menyambut lebih banyak pengungsi hanya Jerman. Di Yunani dan Italia, mayoritas penduduknya bahkan hanya ingin kedatangan imigran dalam jumlah lebih kecil.
Tapi tentu, angka-angka itu juga harus dilihat dengan mempertimbangkan tingkat kemakmuran negara terkait. Bagaimanapun, ekonomi Italia dan terutama Yunani amat buruk pada tahun-tahun ini. Tak terlalu mengherankan bila mereka keberatan menyambut pengungsi, sebab negaranya sendiri berada di ambang kebangkrutan.
Di sisi lain, meski sikap orang Polandia terkait gelombang imigran tak jauh berbeda dengan warga di negara lain, pandangannya terhadap Muslim cukup mencolok. Sebanyak 56 persen orang Polandia tak terlalu menyukai Muslim. Negara ini hanya kalah dari Italia yang 61 persen warganya punya sentimen negatif, atau menganggap kaum Muslim “unfavorable.” Penduduk di negara-negara yang lebih liberal seperti Inggris, Perancis, dan Jerman, melihat Muslim secara lebih positif. Hanya sekitar 20 persen dari warga-warga di negara itu yang memandang Muslim tak bisa disukai.
Tak hanya punya persepsi negatif terhadap Muslim, orang Eropa juga banyak yang menganggap kaum imigran tak mau berbaur. Survei Pew 2014 menunjukkan lebih dari 40 persen responden menganggap kaum imigran tetap ingin berbeda dari masyarakat Eropa keseluruhan. Responden yang beranggapan kaum imigran mau menyesuaikan diri dengan kebiasaan orang Eropa, lebih sedikit jumlahnya.
Dari data-data di atas, tidak mengejutkan juga bahwa respons negatif tidak hanya muncul dalam hal penerimaan atas pengungsi. Penyerangan dan sikap rasis pada Muslim dan kaum imigran pun kerap terjadi setelah peristiwa teror. France24.com melaporkan setidaknya terjadi 281 persen peningkatan serangan pada kaum Muslim pada minggu-minggu setelah pembunuhan di kantor Charlie Hebdo, awal 2015.
Di tempat lain pun sama. Di Britania, misalnya, terdapat 115 serangan selama satu minggu setelah serangan Paris. Tempat yang jauh dari Eropa juga terimbas. Di Amerika Serikat, serangan terhadap mesjid meningkat setelah teror Paris November 2015 itu.
Persepsi terhadap Muslim dan kaum imigran ini bisa menjadi persoalan jangka panjang, apalagi jika melihat tren pertumbuhan penduduk beragama Islam di Eropa. Secara keseluruhan, pada 2010 ada sekira 6 persen Muslim di Eropa. Angka itu naik dari angka pada 1990 di mana kaum Muslim berjumlah 4 persen. Menurut estimasi Pew, jumlah itu kemungkinan bisa meningkat mencapai 8 persen pada 2030.

Lanskap Politik Uni Eropa
Khusus dalam masa pasca-teror seperti sekarang ini, penolakan terhadap bakal imigran dan serangan reaktif terhadap kaum Muslim merupakan persoalan pelik bagi Eropa yang kerap mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan. Apalagi jika melihat gelombang pengungsi dari Suriah yang masih berdatangan ke benua ini dan mengharap suaka.
Dari data EU Syrian Refugee, per 23 Maret saja 214.985 pemohon suaka dari Suriah ke Eropa. Perancis dan Belgia setidaknya masing-masing dimohon oleh 5.000 peminta suaka. Negara dengan pemohon suaka terbanyak adalah Jerman yang mencapai lebih dari 60 ribu pengungsi.
Selain soal penerimaan terhadap imigran dan sentimen antar-kebudayaan, soliditas Uni Eropa juga diuji. Data-data yang memuat persepsi publik terhadap Muslim dan kaum imigran di atas menunjukkan pernyataan tokoh-tokoh ekstrem kanan tak bisa diabaikan. Persoalan ini bahkan lebih aktual di Britania Raya yang hendak melaksanakan referendum keanggotaannya dalam Uni Eropa, Juni mendatang.
Katie Hopkins yang sinis atas keanggotaan Britania di Uni Eropa pun tak sendirian di negaranya. Juru bicara pertahanan U.K. Independence Party (UKIP), Mike Hookem, menyatakan bahwa aksi terorisme menunjukkan aturan-aturan gerakan-bebas Uni Eropa dan kurangnya kontrol perbatasan adalah “ancaman terhadap keamanan kita.”
Namun, seperti dilansir Bloomberg, David Cameron langsung bereaksi keras terhadap komentar itu. “Ini bukan waktu yang pantas untuk membuat pernyataan semacam itu. Hari ini adalah hari untuk simpati dan belasungkawa, [dan] untuk meningkatkan keamanan kita sendiri,” katanya.
Terkait soliditas Uni Eropa, pendapat Jürgen Habermas layak ditilik. Pemikir terbesar di daratan Eropa ini pernah ditanyai pendapatnya soal imigran dan Uni Eropa setelah aksi teror di Paris, November tahun lalu. Terpetik dalam www.socialeurope.eu, ia berharap aksi teror tak mengubah sikap Jerman terhadap pengungsi. Baik aksi teror maupun krisis pengungsi, menurutnya merupakan tantangan yang memerlukan kerja sama dan solidaritas antar-negara Eropa, melebihi isu apapun.
Jika melihat respons Angel Merkel kemarin, harapan Habermas tampaknya tak akan tumpas. Setelah menyatakan kecamannya atas aksi teror dan menyebutnya sebagai musuh dari semua nilai Eropa, Merkel menegaskan pandangannya soal pengungsi dan pentingnya Uni Eropa bersatu menghadapi terorisme.
Seperti dikutip Deutsch Welle, Merkel menekankan untuk tetap memegang teguh nilai yang menghargai "hidup berdampingan dalam damai”, yang bisa dilihat sebagai retorika sang kanselir atas persoalan kaum imigran. Sebagai anggota Uni Eropa, ucapnya, “kita percaya pada […] nilai-nilai kebebasan, demokrasi, dan hidup berdampingan dalam damai, sebagai warga negara yang percaya diri.”
"Kekuatan kita ada dalam persatuan kita, dan dengan cara itulah masyarakat bebas kita akan membuktikan bahwa kita lebih kuat daripada terorisme," tandas pemimpin de facto Uni Eropa ini.
Penulis: Maulida Sri Handayani
Editor: Nurul Qomariyah Pramisti