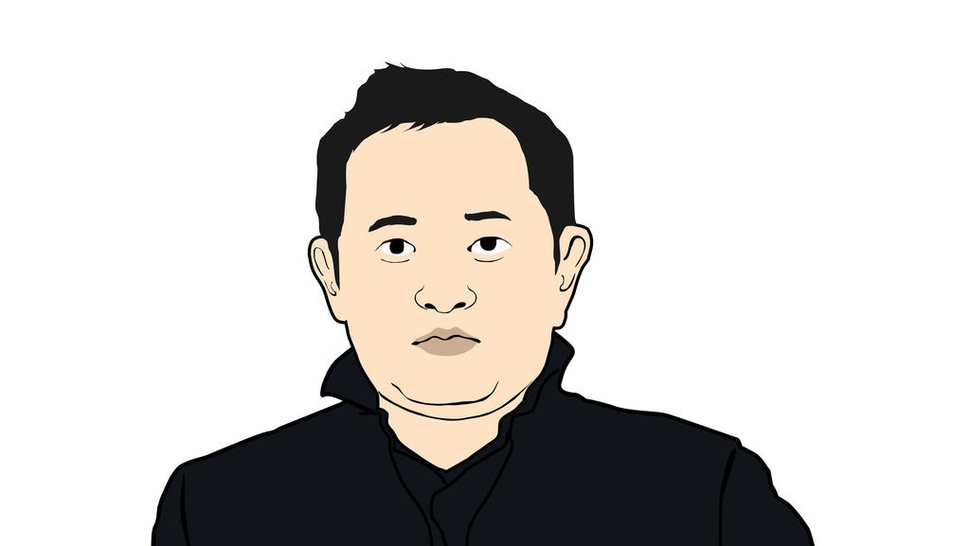tirto.id - Awal Januari 2019, beberapa orang yang mendaku sebagai bobotoh Persib Bandung mendatangi kediaman Ma’ruf Amin di Jalan Situbondo, Jakarta. Tujuannya: memberikan dukungan kepada paslon Jokowi–Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019. Tak berapa lama kemudian, muncul sanggahan dari kelompok bobotoh yang lain yang menyatakan bahwa kedatangan sejumlah bobotoh di rumah Ma’ruf Amin tak mewakili aspirasi politik bobotoh secara keseluruhan.
Dukungan kelompok suporter sepak bola untuk kandidat tertentu dalam politik elektoral Indonesia memang bukan hal baru. Sudah banyak calon kepala daerah, legislator, hingga presiden yang mencoba mendekati kelompok suporter sepak bola. Janjinya macam-macam, mulai dari renovasi stadion, dana bantuan kepada kelompok suporter, penguatan tim sepak bola, hingga bantuan untuk kewirausahaan suporter.
Hampir semua jaringan sosial di Indonesia, tulis ilmuwan politik Edward Aspinall, bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Kelompok suporter—sebagai kantong massa dengan jumlah ribuan plus loyalitas dan kerekatan—hanya salah satu yang didekati politikus.
Pertanyaannya, apakah bisa dan mudah bagi kelompok suporter sepak bola untuk dipolitisasi dalam kompetisi elektoral? Sejauh mana mereka bisa dimanfaatkan dalam mobilisasi politik dan apa saja batasannya? Adakah faktor utama yang bisa mempengaruhi suporter sepak bola untuk dipolitisasi?
Belajar dari Argentina
Saya kira pertanyaan-pertanyaan seperti itu relevan untuk diajukan untuk menjernihkan anggapan umum bahwa kelompok suporter sepak bola mudah dipolitisasi.
Dalam konteks global, relasi sepak bola dan politik sudah menjadi bidang kajian yang mapan. Bahkan, ada dua jurnal internasional yang khusus untuk mendiskusikan persinggungan sepak bola dengan kehidupan sosial-politik yakni Sport in Society dan Soccer & Society.
Namun, sebagian besar diskusi para peneliti di jurnal-jurnal tersebut berkisar pada tema sepak bola dan kontestasi identitas baik pada level lokal maupun nasional. Misalnya, soal posisi sepak bola dalam ketegangan relasi pusat–pinggiran antara Kerajaan Spanyol dengan Catalan atau Basque. Sepak bola sebagai alat perjuangan anti-kolonialisme seperti di Indonesia dan di India, atau sebagai media kampanye gerakan fasis di Italia era Mussolini juga jamak ditemukan di jurnal-jurnal tersebut.
Meski studi tentang pelibatan suporter sepak bola untuk kepentingan elektoral sulit ditemukan, ada perkembangan menarik dari negara-negara Amerika latin yang mulai menyoroti fenomena ini—seperti yang dilaporkan dalam tulisan-tulisan Eugenio Paradiso, Joel Horowitz, Vic Duke, dan Liz Crolley tentang klientelisme politik di Argentina.
Sepak bola di Argentina tak bisa dilepaskan dari politik. Bahkan, salah satu penopang klientelisme politik di Argentina adalah infstrastruktur sepak bola. Keterbatasan infrastruktur organisasi partai-partai politik yang baru terbentuk di Argentina pada awal abad ke-20 membuat mereka ‘menumpang’ pada infrastruktur organisasi sepak bola yang lebih dulu mapan dan berbasis lingkungan pemukiman (barrios).
Para pengurus klub mulai dari presiden hingga official biasa dipilih secara langsung oleh semua anggota masyarakat (socios). Partai politik memainkan peranan dominan dalam pemilihan, karena di sinilah politikus memiliki kesempatan untuk mengkampanyekan dirinya untuk pemilu, meraih konstituen, membangun jaringan, dan mendapatkan loyalitas.
Walhasil, nyaris seluruh presidentes (presiden klub) dan dirigentes (direktur klub) yang terpilih adalah polititikus. Politisi yang terpilih kerap disebut dengan padrino karena memiliki akses terhadap sumber daya dan mampu mendistribusikannya kepada kaum miskin. Oleh karena itu, dalam sistem klub ‘direct supporter’ seperti itu, peran kelompok suporter menjadi sangat krusial bukan saja bagi keberlangsungan klub, namun juga karir para politikus.
Persis pada titik inilah, fenomena barras brava dalam politikyang dikenal dalam bahasa Inggris sebagai ‘fierce opponents’ menguat di Argentina pada 1980-an.
Barras brava adalah organisasi formal suporter pada tiap klub sepak bola Argentina dengan barrios-nya masing-masing yang terkenal loyal, militan, dan tak ragu terlibat dalam aksi-aksi kekerasan. Barras brava inilah yang kemudian menjadi simpul penting dalam jaringan klientelisme politik.
Dalam konteks politik populisme Argentina hari ini, mobilisasi massa menjadi faktor yang sangat krusial. Menguatnya barras brava beriringan dengan semakin kuatnya fungsi sosial dari klub sepak bola di masing-masing barrio, tak hanya sebagai olahraga semata tapi juga sebagai entitas sosial-politik yang menjadi bagian dari jalur distribusi fasilitas kebutuhan dasar bagi warga lokal nya dalam skema jaringan klientelisme.
Praktik politik klientalisme di Argentina semakin menguat sejak tahun 1990-an ketika Carlos Menem mengeluarkan kebijakan-kebijakan neoliberal yang membuka jalan bagi politisi untuk memperkuat jaringan ke akar rumput. Di Argentina, praktik politik semacam ini tak hanya dimaknai sebagai transaksi ekonomi, melainkan juga—dalam perspektif kaum miskin—sebagai solusi untuk semakin tidak terjangkaunya kebutuhan dasar.
Struktur Adalah Kunci
Baik di Indonesia maupun Argentina, struktur/pola pengorganisasian dan kultur kelompok ternyata menjadi hal krusial dalam politisasi suporter sepak bola.
Dalam Pemilukada Kota Batu 2017, struktur atau pola pengorganisasian dan kultur kelompok inilah yang menjadi batas dari Aremania untuk bisa digunakan sebagai alat mobilisasi politik. Dua faktor ini juga menjelaskan mengapa kelompok-kelompok suporter sepak bola lain di Indonesia dianggap bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politikus.
Barras brava dilembagakan dengan struktur hierarki yang ketat, rantai komando yang kuat, dan mengadopsi gaya militeristik. Ketuanya pun menyandang julukan El Jefe. Anggotanya direkrut melalui rangkaian tes untuk menguji komitmen serta strategi calon yang bersangkutan agar memperoleh status ‘militan profesional penuh waktu’. Calon anggota, misalnya, wajib mengerjakan tugas-tugas ‘kecil’ seperti melakukan vandalisme atas kereta api. Selanjutnya, mereka akan diberikan tugas khusus seperti terlibat dalam perencanaan serangan serta pengorganisasian kegiatan mingguan. Calon anggota yang bisa lolos semua rangkaian ujian dipandang memiliki loyalitas serta komitmen yang tinggi terhadap organisasi dan pemimpinnya.
Dengan struktur organisasional yang ketat dan sistem komando yang kuat, kelompok ini bisa digunakan sebagai mesin politik jika ketuanya bisa terkooptasi dalam jejaring klientelisme. Struktur atau pola organisasi barras brava membuatnya relatif mudah dan efektif untuk digerakkan walau jumlah anggotanya sangat banyak. Lawan-lawan politik pun takut dengan intimidasi yang mereka lakukan.
Motivasi politik barras brava dilatarbelakangi oleh ikatan dengan pemilik klub yang membutuhkan dukungan suporter untuk kepentingan elektoral atau demo pesanan. Imbalannya, Barras brava akan mendapatkan bayaran dan bantuan ekonomi baik berupa uang tunai atau fasilitas lainnya. Keuntungan ini di luar uang bulanan dan hasil penjualan tiket sepak bola yang rutin mereka dapatkan.
Banyak studi telah menjelaskan barras brava sebagai entitas oportunis, bahkan ‘serdadu bayaran’ (mercenaries). Mereka mengabdi kepada para para patron (padrinos)yang bisa mendistribusikan paling banyak sumber daya. Barras brava juga harus mendistribusikan sumber daya dari para padrinos-nya sampai ke barrios.
Aremania berbeda. Mereka tidak memiliki struktur/pola pengorganisasian dan kultur kelompok yang mendukung terjadinya politisasi secara intensif. Aremania, yang lebih egaliter dan non-hirarkis, tidak memiliki struktur organisasi yang ketat. Tak ada pula ketua umum dan pengurus pusat. Mereka terdesentralisasi dalam cabang-cabang yang tersebar di seluruh Malang Raya dalam bentuk korwil-korwil yang sifatnya otonom sehingga sulit untuk dimobilisasi secara mutlak.
Aremania memiliki acuan prinsip nilai tertentu atau kultur kelompok seperti “No leader just together”. Selain itu, ada hukum tidak tertulis yang melarang membawa Aremania ke dalam politik praktis. Hukum tidak tertulis ini masih dipegang oleh para anggota Aremania hingga saat ini. Secara historis, Aremania memang didirikan untuk melampaui sekat-sekat politik sehingga bisa tetap eksis sebagai identitas yang menyatukan berbagai fragmen masyarakat Malang Raya.
Kecenderungan Aremania nampaknya bisa menjadi peringatan bagi politikus Indonesia. Tak perlu menghabiskan energi dan sumber daya finansial untuk mempolitisir suporter sepak bola karena memang mereka sulit diseret untuk kepentingan politik. Para suporter rupanya sadar bahwa masuknya politik ke dalam sepak bola justru hanya akan memecah belah rajutan kolektif yang sudah bertahun-tahun berusaha diciptakan.
Salah seorang narasumber saya di lapangan pernah mengatakan: "Suporter sepak bola ibarat pasir. Semakin erat digenggam, semakin lepas terurai."
=============
Artikel ini ditulis berdasarkan publikasi penulis bertajuk “When the Supporters do not Support: Politicising a Soccer Fan Club in an Indonesian Election" yang terbit di Journal of Contemporary Southeast Asia (2017).
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.