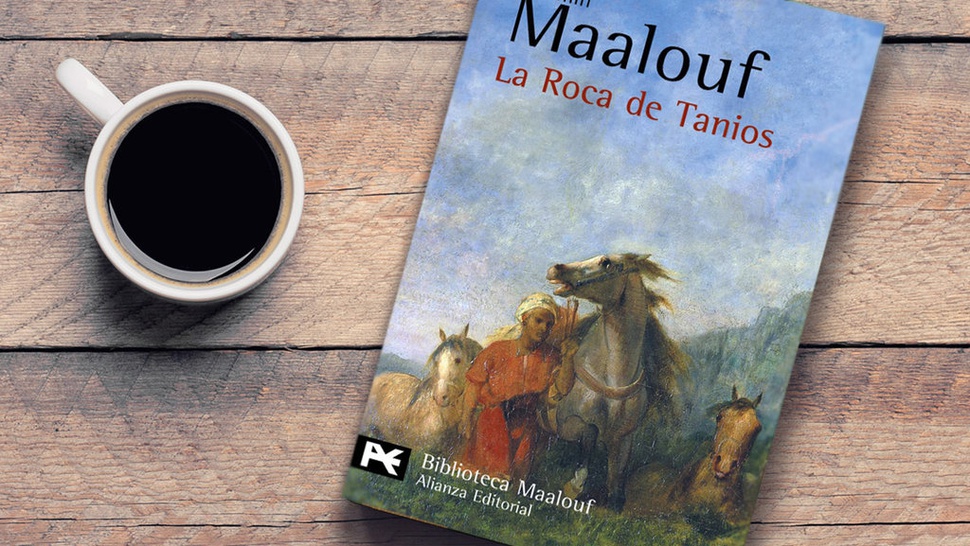tirto.id - Bagdad, Agustus 1099, dua hari sebelum Idul Fitri. Kadi tinggi Damaskus Abu Saad al-Harawi memasuki diwan khalifah al-Mustazhir Billah secara paksa. Ia tak mengenakan serban dan rambutnya tercukur habis, tanda dukacita. Di belakangnya, dengan penampilan serupa, sejumlah pengungsi dari Yerusalem ikut masuk sambil bicara di antara mereka sendiri.
Kepada orang-orang di diwan itu, termasuk sang khalifah, Abu Saad al-Harawi berseru:
"Tega benar kalian bermalas-malasan, berlindung di balik bayangan keamanan yang angkuh, hidup seperti bunga-bunga di taman," ujarnya. "Sementara saudara-saudaramu berumah di atas punggung unta dan di dalam perut burung pemakan bangkai. Darah telah ditumpahkan! Gadis-gadis belia telah dinistakan, dan mereka menutupi wajah-wajah mereka yang cantik dengan tangan! Apakah bangsa Arab yang pemberani mulai terbiasa menerima hinaan dan bangsa Persia yang gagah diam saja saat diinjak-injak?"
“Belum pernah umat muslim dihina seperti sekarang, belum pernah tanah air kita hancur lebur seperti sekarang,” katanya, merujuk penaklukan Yerusalem oleh tentara Franj (Franks) pada 15 Juli 1099. Hanya dalam dua hari, kota itu nyaris steril dari pemeluk Islam dan Yahudi. Sebagian berhasil menyelinap dan mengungsi, tetapi ribuan yang lain tewas berkubang darah mereka sendiri, sebagaimana di Antioch dan Beirut.
Kata-kata Abu Saad al-Harawi membuat para pendengarnya tertunduk dan menangis. Selama tiga pekan di musim panas, dalam keadaan berpuasa, ia menempuh perjalanan Beirut-Bagdad. Ia melintasi gurun Suriah yang tak kenal ampun tentu bukan buat memerah air mata para elit kekhalifahan Abbasiyah.
“Senjata terburuk laki-laki,” kata Abu Saad al-Harawi, “adalah meneteskan air mata ketika pedang masih mengaduk bara peperangan.”
Kisah itu disampaikan Amin Maalouf, penulis Perancis kelahiran Lebanon, 25 Februari 1949, dalam Les Croisades vues par les Arabes (1983). Seperti terbaca dari judulnya, buku itu menuturkan bagaimana kaum muslim Arab memandang serangkaian perang yang berkobar selama nyaris dua abad tersebut. Maalouf tak hanya menggunakan karya-karya para sejarawan, tetapi juga catatan-catatan yang ditulis sejumlah saksi mata dan serdadu yang lolos dari cengkeraman maut.
Amin Maalouf menganut Katolik dan—sejak berumur 26 tahun—tinggal di Perancis. Namun itu tak membuat matanya buram. Ia melaporkan kejahatan-kejahatan pasukan Franj yang seiman dan “setanah air” dengannya.
Di Ma'arra, kata Maalouf, setelah mengepung kota selama dua pekan, pasukan Franj berjanji tak bakal melukai warga seandainya mereka berhenti melawan. Persetujuan tercipta. Namun, begitu warga Ma'arra meletakkan senjata, mereka melemparkan obor ke rumah-rumah dan membunuh dan memenjarakan ribuan orang. Menurut sejumlah catatan yang dirujuk Maalouf, beberapa di antara mereka bahkan menyantap daging warga Ma'arra dengan alasan kekurangan pangan.
Perang Salib telah berakhir tujuh abad silam, tapi gambaran Barat sebagai musuh yang liar dan keji tetap hidup dalam benak dan tindakan jutaan umat Islam Arab. Dendam kolektif itu boleh jadi ikut menentukan situasi sosio-politik dunia hari ini. Bukankah tak sedikit muslim yang menganggap Barat sebagai entitas yang buruk secara inheren dan senantiasa punya rencana jahat? Tidakkah demikian pula sebaliknya?
Bagi Maalouf, sejarah tak dilabur dengan satu warna. “Kau tak bisa mengatakan bahwa sejarah mengajarimu ini atau itu,” ujarnya. “Sejarah selalu memberikan lebih banyak pertanyaan ketimbang jawaban, dan lebih dari satu jawaban untuk setiap pertanyaan.”

Amin Maalouf memulai pengalaman menulisnya sebagai wartawan harian An-Nahar di Lebanon. Untuk koran itu, ia pernah meliput berbagai peristiwa penting di dunia, mulai dari kejatuhan monarki Ethiopia sampai pertempuran di Saigon. Pada 1975, perang antara milisi Kataib dan Palestine Liberation Organization (PLO) mengoyak Beirut (hingga 1990, perang sipil itu melibatkan hampir seluruh kelompok masyarakat di Lebanon dan menelan sekitar 120 ribu korban jiwa).
Maalouf memilih pindah. Di Perancis, ia melanjurkan karier jurnalistiknya. Ia sempat menjadi editor An-Nahar edisi internasional dan pemimpin redaksi mingguan Jeune Afrique sebelum memutuskan untuk pensiun dini dari jurnalisme dan menjadi penulis penuh-waktu pada 1985.
Novel pertama Maalouf, Léon l'Africain (1986), mendapat Le Prix de l'amitié franco-arabe, hadiah sastra tahunan yang diberikan Asosiasi Persahabatan Perancis-Arab. Buku yang diterjemahkan Ahmad Santoso ke dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan Bentang Pustaka pada 2005 itu bercerita tentang Hasan al-Wazzan, pengembara Mur abad ke-16 yang dikenal dengan julukan Singa Afrika.
Al-Wazzan meninggalkan kota kelahirannya, Granada, untuk menghindari lembaga inkuisisi Spanyol. Ia bertualang ke Fez, Maroko, sebagai pedagang; menjalankan ibadah haji di Mekah; menjadi seorang nasrani dan terlibat intrik-intrik Vatikan di Roma pada masa Renaisans; dan kembali memeluk Islam.
Novel tentang perpindahan terus-menerus dan situasi mengambang di atas pelbagai negeri, agama, dan bahasa itu dibuka dengan kata-kata yang menggemakan kehidupan penulisnya sendiri: “Aku tak datang dari negara, kota, atau suku tertentu. Aku adalah anak yang dilahirkan jalanan … Segenap bahasa dan doa adalah milikku, tetapi aku bukan milik mereka.”
Kemudian Maalouf menerbitkan Samarkand (1988). Novel ini mereka ulang kehidupan penyair Persia abad ke-11 Omar Khayyam, menjalinnya dengan kisah-kisah lain, mulai dari kiprah kaum Hashasin hingga Revolusi Iran pada 1979, dan meramu semua itu menjadi bacaan seru yang kaya akan informasi sejarah. Tentang proyek sastrawi yang ambisius itu, Maalouf mengatakan bahwa ia menulisnya hanya untuk “memahami hubungan antara politik, agama, dan kebudayaan di Persia dari masa ke masa.”
Setelah bertahun-tahun menulis novel dengan latar yang beragam, Maalouf menerbitkan Le Rocher de Tanios pada 1993. Novel yang memenangkan Prix Goncourt—salah satu hadiah sastra tahunan paling bergengsi untuk karya-karya sastra Perancis—itu menggunakan Lebanon periode 1830-an sebagai latarnya. Pada 1999, Yayasan Obor Indonesia menerbitkannya, terjemahan Ida Sundari Husen, dengan judul Cadas Tanios.
“Tanios anak Lamia. Kau pasti pernah mendengar namanya disebut-sebut orang. Sudah jauh sekali di masa lalu, kakek sendiri belum lahir, bahkan juga ayah kakek. Pada masa itu, pacha atau penguasa tertinggi Mesir sedang berperang melawan kerajaan Ottoman, nenek moyang kita menderita sekali...,” kata narator utama novel itu, mengutip kakeknya, di bagian pembuka.
Berawal dari rasa penasaran, Tanios menjadi obsesi sang narator. Ia bertanya kepada orang-orang tua di desanya: Siapa Tanios? Apa yang ia lakukan? Mengapa ada cadas di desa mereka dinamai dengan namanya?
Kemudian, ia menemukan manuskrip seribu halaman berjudul Catatan Montagne atau Sejarah desa Kfaryabda, dusun-dusun dan tanah pertaniannya, tonggak-tonggak bersejarah yang berdiri di situ, adat-istiadatnya, tokoh-tokoh terkenal yang pernah hidup di situ, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di situ atas perkenan Yang Maha Kuasa karya Rahib Elias. Dari cerita-cerita lisan—serta manuskrip Catatan Montagne dan dua naskah lain—sang narator mengetahui kisah hidup Tanios yang kemudian ia sampaikan kepada pembaca dalam gaya seorang sejarawan.
Tanios adalah buah perselingkuhan Syekh penguasa Kfaryabda dan Lamia, perempuan tercantik di kawasan itu. Ia dibesarkan dalam lingkungan istana sang Syekh dan memperoleh pendidikan unggul, meski tak jarang warga desa memandangnya rendah berkat gosip-gosip tentang asal usulnya (pada usia 15 tahun, rambutnya tiba-tiba memutih, seakan-akan menandai bahwa memang ada yang keliru dengannya). Ketika Gerios, suami Lamia dan ayah “resmi” Tanios, membunuh pemimpin umat nasrani Kfaryabda—saingan politiknya, Gerios dan Tanios terpaksa melarikan diri. Dalam pelarian itulah keduanya kemudian terlibat urusan-urusan rumit yang menentukan sejarah Lebanon.
Pada masa itu, Lebanon adalah lokus permainan politik besar-besaran: Mesir dan Kekaisaran Utsmani berebut pengaruh, Perancis dan Inggris mencari celah, Islam dan Kristen saling mendesak, perlawanan terhadap kaum penguasa tumbuh subur, dan intrik bersipongang di mana-mana.
Dalam Cadas Tanios, Maalouf sanggup “merangkum” perkara besar itu lewat sejarah kecil sebuah desa di pegunungan dan beberapa penghuninya. Ia juga menyingkapkan kehidupan sosial, religius, dan politik masyarakat Lebanon—yang kompleks, kaya, dan tak bisa dengan mudah dipilah hanya sebagai “kami” atau “mereka.”
Lebih jauh, dalam Les Identités meurtrières (1998), Maalouf menyatakan bahwa identitasnya dibentuk oleh paradoks. Ia warga negara Perancis, berbicara dalam bahasa Perancis dan Inggris, beragama Katolik, namun terlahir dan tumbuh dewasa sebagai orang Arab, dengan bahasa Arab, bahasa kitab suci umat Islam, sebagai bahasa ibunya.
Menurut penulis Cile-Amerika Serikat Ariel Dorfman, sebagaimana dikutipGuardian, “Saat dunia dipenuhi para pencari identitas yang berangasan, Amin adalah suara kebijaksanaan dan kewarasan, suara yang menyanyikan kerumitan sekaligus keindahan menjadi bagian dari banyak hal.”
Penulis: Dea Anugrah
Editor: Maulida Sri Handayani