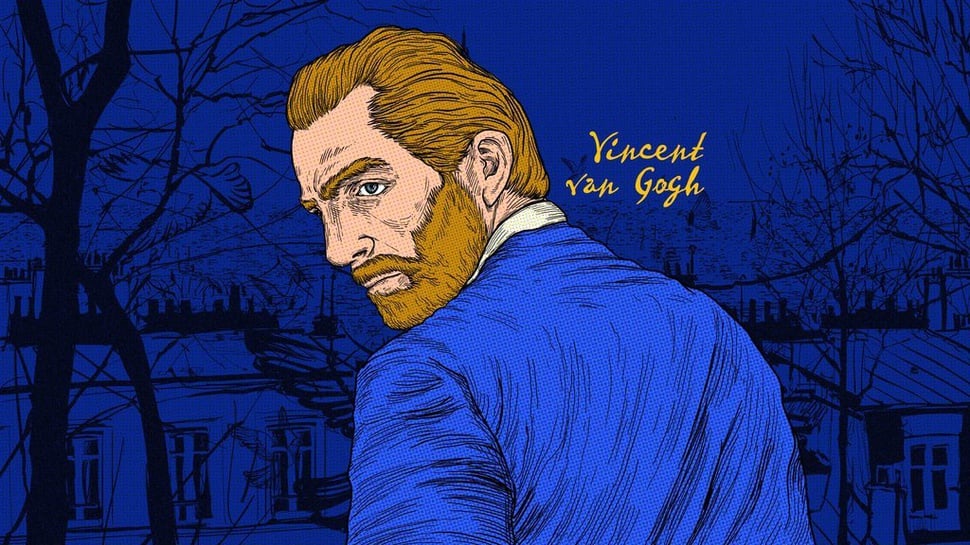tirto.id - Bintang-bintang kuning menyala terang, langit biru menyelimuti. Keindahan desa di Saint-Rémy-de-Provence, Perancis terekam dalam sapuan-sapuan kuas besar Vincent Willem van Gogh.
La Nuit étoilée (1889) atau Malam Penuh Bintang adalah nama lukisan yang kini terpampang di Museum of Modern Art di New York, Amerika Serikat. Mahakarya van Gogh yang menafsirkan pemandangan melalui emosinya ini seakan menjadi bagian dari kebudayaan populer. Bahkan tidak sedikit yang mengkomersialkannya; dari replika lukisan yang terpajang di rumah-rumah, menempel di gelas, kaos, casing ponsel, hingga kaos kaki.
Mungkin ketenaran dan kekayaan terlintas di pikiran saat membayangkan nasib pria yang lahir pada 30 Maret 1859 di Groot-Zundert, Belanda ini. Namun kenyataannya berbeda, selama hidupnya van Gogh tidak pernah tenar apalagi menjadi sosok terpandang dalam dunia seni abad ke-19.
Bahkan menurut surat yang ditulis untuk adiknya pada 15 Januari 1884, pelukis yang gagal menjadi vikaris ini beberapa kali mengalami kesulitan finansial. Karena itulah van Gogh meminta bantuan ekonomi kepada adiknya yang bernama Theodorus “Theo” van Gogh.
Seperti yang dilansir dari Vangoghmuseum.nl, di masa mudanya van Gogh seringkali menukar karyanya dengan makanan atau alat-alat melukis. Salah satu lukisan yang berhasil terjual adalah La Vigne rouge (1888) atau Kebun Anggur Merah. Dengan harga 400 franc atau sekitar Rp27 juta, karya ini dibeli oleh Anna Boch, kakak dari teman van Gogh yang bernama Eugene Boch.
Malam Penuh Bintang menjadi saksi bisu atas kesedihan di masa hidupnya. Pria yang telah membuat sekitar 863 lukisan ini membuat karyanya yang paling populer di Rumah Sakit Jiwa Saint-Paul-de-Mausole pada 1889. Ia melukis pemandangan yang terlihat dari jendela kamarnya di rumah sakit jiwa.
Di akhir hayatnya Vincent van Gogh menulis “La tristesse durera toujours” (“Kesedihan ini takkan pernah berakhir”) dalam sepucuk surat yang dikirimkan Theo kepada Elisabeth van Gogh, adik perempuan kedua van Gogh bersaudara di tanggal 5 Agustus 1890. Pernyataan melankolis terakhir van Gogh ini merangkum hidupnya yang berakhir dengan tragis.
Rumah Sakit Jiwa Hingga Peluru di Dada
Dalam Vincent van Gogh (2011), Victoria Charles mengatakan bahwa van Gogh masuk ke rumah sakit jiwa setelah bertengkar dengan teman sekaligus pelukis pasca-impresionis lain bernama Paul Gauguin.
Klimaks dari konfik yang terjadi di Arles, Perancis pada Desember 1888 ini mendorong van Gogh memotong telinganya sendiri, membungkusnya di koran, dan mengirimkannya ke seorang pelacur bernama Rachel.
Tulisan “jaga objek ini dengan hati-hati” ditemukan bersamaan dengan telinga yang ia kirim. Seisi rumah bordil ketakutan.
Setelah insiden mutilasi itu, van Gogh pulang ke rumah dan melukis dirinya sendiri. Wajah berperban itu ia abadikan dalam Autoportrait à l'oreille bandée (Potret Diri dengan Perban di Telinga), sebuah karya yang menggambarkan ambruknya kesehatan fisik dan mental sang pelukis.
Pada 1889 van Gogh masuk ke rumah sakit jiwa secara sukarela di daerah Saint-Rémy de Provence. Menurut buku Van Gogh, The Life (2011), seorang dokter bernama Théophile Peyron memberikan vonis epilepsi ke sang pelukis. Setelah berjuang melawan gejala seperti serangan vertigo hingga hilang kesadaran, van Gogh akhirnya dianggap sembuh pada 16 Mei 1890.
Ia menemui Theo di Paris. Namun karena merasa memberatkan sang adik, ia pindah ke Auvers yang terletak di sebelah utara Perancis.
Pada Minggu malam 27 Juli 1890, van Gogh kembali ke penginapan sambil memegang dadanya. Sang pemilik penginapan menemukan sang pelukis tengah merintih. “Saya terluka,” ujarnya. Ternyata sebuah peluru telah bersemayam di dadanya. Setelah 30 jam, Vincent van Gogh yang pada saat itu berumur 37 mengembuskan napas terakhir pada 29 Juli 1890, tepat hari ini 130 tahun lalu.
Bagaimana peluru itu bisa bersarang di dada van Gogh terus diperdebatkan. Julius Meier-Graefe dalam Vincent van Gogh: A Biography (1910) mengatakan bahwa maestro pasca-impresionis ini meninggal karena bunuh diri.
Namun menurut catatan Steven Naifeh dan Gregory W. Smith dalam Van Gogh, The Life (2011), luka di dada itu berasal dari tembakan jarak jauh sehingga kematiannya bukan akibat tindakan bunuh diri. Tanpa otopsi, saksi mata, dan barang bukti, tak seorang pun tahu siapa pelakunya—kendati ada pula dugaan bahwa sang pelaku adalah René Secrétan, seorang pelajar asal Paris yang tak sengaja menembak van Gogh.

Semasa hidupnya, van Gogh bukan siapa-siapa di bidangnya. Tapi semua itu berubah saat ia tutup usia. Tanda-tanda ketenaran luar biasa itu pun terlihat pada 1890, tahun di mana ia tutup usia. Pada Januari 1890, pelukis dan kritikus Albert Aurier menulis ulasan awal tentang karya-karya van Gogh.
“Vincent van Gogh bukan hanya pelukis hebat antusias pada karyanya, palet, atau alam; ia lebih seperti pemimpi, orang yang percaya pada kegembiraan hati, pelahap utopia indah, ia hidup dengan ide dan mimpi,” tulis Aurier dalam artikel berjudul “Les Isolés: Vincent van Gogh”yang dipublikasikan majalah Mercure de France.
Pada 1891 seorang kritikus seni dan jurnalis bernama Octave Mirbeau menulis ulasan positif. Julius Meier-Gaefe, penulis asal Jerman pun memublikasikan beberapa telaah tentang van Gogh sejak 1902.
Pameran seni yang menampilkan van Gogh pun mulai digelar di Brussels, Belgia dan Paris sejak 1891. Pada 1892 pameran besar pertamanya diselenggarakan di Gedung Panorama Amsterdam. Sejak itu lukisannya menyebar ke pameran-pameran bagian lain Eropa seperti Norwegia dan Swedia (1893), Berlin (1902), hingga London (1910).
Apabila dahulu van Gogh sulit untuk menjual lukisannya, kini karya jadi salah satu yang termahal. Sebut saja Le Portrait du docteur Gachet (Potret Dr. Gachet) yang terjual sebesar $82.500.000 atau sekitar Rp1,1 triliun pada 1990.
Kini karya van Gogh abadi di berbagai museum, dari Van Gogh Museum di Amsterdam hingga Museum of Modern Art di New York. Visualisasi pasca-impresionis yang dipancarkan lukisannya telah menginspirasi dunia selama lebih dari 100 tahun, memperlihatkan kesedihan dan kebahagiaan sang pelukis.
==========
Artikel ini pertama kali ditayangkan pada 30 Maret 2018. Kami melakukan penyuntingan ulang dan menerbitkannya kembali untuk rubrik Mozaik.
Editor: Windu Jusuf & Ivan Aulia Ahsan