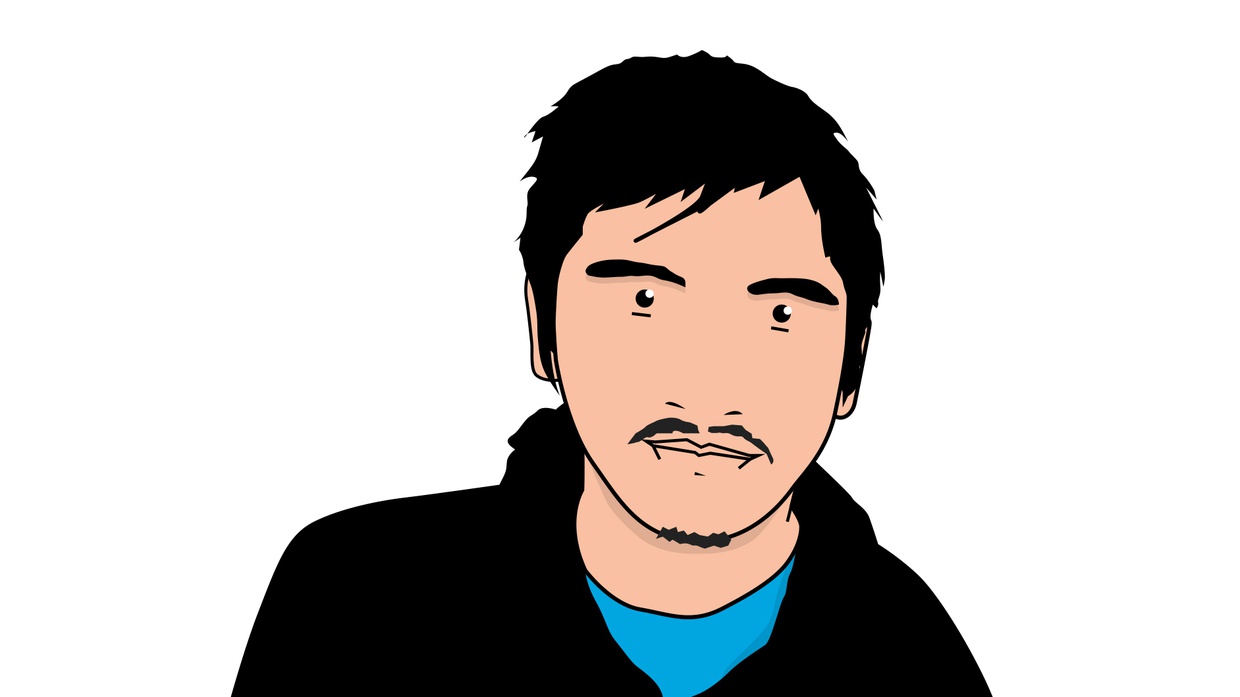tirto.id - Cara SBY menghadapi situasi dalam beberapa bulan terakhir mengesankan seakan-akan dirinya tidak punya instrumen politik.
Dalam rentang waktu 3 bulan lebih, dari 26 Oktober 2016 sampai 1 Februari 2017, ia sudah tiga kali menggelar konferensi pers. Pada 26 Oktober untuk menanggapi raibnya dokumen Tim Pencari Fakta Munir. Pada 2 November untuk menanggapi kasus dugaan penistaan agama dan kaitannya dengan pencalonan Agus serta aksi Bela Islam 4 November. Pada 1 Februari 2017 untuk menanggapi rangkaian pertanyaan tim kuasa hukum Ahok di persidangan terkait komunikasi SBY dengan Ma’ruf Amin.
Dalam seluruh konferensi pers itu, SBY sendiri hadir dan ia sendiri pula yang berbicara. Pada konferensi pers 26 Oktober ia tak bicara sendirian, tapi didahului oleh Sudi Silalahi. Selebihnya, pada dua konferensi pers berikutnya, hanya SBY yang berbicara. Dua konferensi pers pertama bahkan digelar di “ruang privat” yaitu kediamannya di Cikeas. Hanya pada konferensi pers terakhir digelar di kantor Partai Demokrat.
Hal yang sama terjadi pasca konferensi pers 1 Februari 2017 itu. Responsnya terhadap aksi demonstrasi (konon) mahasiswa di kediamannya yang lain, Kuningan, juga dilakukan oleh dirinya sendiri. Kali ini ia tidak mengadakan konferensi pers, melainkan langsung berkicau di Twitter, dengan jempolnya sendiri.
Merespons situasi oleh dirinya sendiri juga dilakukan di Twitter dalam isu penyadapan komunikasi dengan Ma’ruf Amin. Seakan tidak puas dengan konferensi pers pada 1 Februari, SBY masih merasa perlu berkicau di Twitter meminta Ma’ruf Amin bersabar, bahkan walau Ketua Umum MUI itu secara personal sudah memaafkan serangan Ahok di persidangan.
Seluruh respons itu dilakukan dengan “tubuh-personal”, bukan “tubuh-politik”.
Yang dimaksud dengan “tubuh-personal” adalah ketika SBY menggunakan tubuhnya sendiri, mulutnya dalam konferensi pers atau jempolnya saat berkicau di Twitter. Menggunakan “tubuh-personal” kian kentara saat ia menggunakan rumah pribadinya di Cikeas sebagai tempat konferensi pers, bukan di markas partai atau di tempat yang lain. Akun Twitter juga adalah rumah pribadinya yang lain, rumah maya, di mana ia sudah mendapatkan centang alias verifikasi di Twitter.
Sedangkan yang dimaksud “tubuh-politik” adalah saat ia menggunakan instrumen politik, baik itu pernyataan/tindakan resmi partai maupun pernyataan/tindakan kader-kader partai.
Mengapa menggunakan kata “tubuh” untuk instrumen politik? Karena Partai Demokrat adalah partai yang sangat identik dengan SBY, sebagaimana PDIP dengan Megawati atau Gerindra dengan Prabowo Subianto. Di Partai Demokrat, SBY adalah pendiri, Ketua Majelis Tinggi, Ketua Umum, anaknya Ibas menjadi Sekertaris Jenderal selama lima tahun, dan anaknya yang lain yaitu Agus menjadi calon gubernur di DKI Jakarta. Tanggal dan bulan lahir Demokrat bahkan sama persis dengan tanggal dan bulan lahir SBY. Sehingga ulang tahun SBY adalah juga ulang tahun Demokrat. Dan ulang tahun Demokrat adalah ulang tahun SBY.
SBY adalah sosok yang nyaris penuh-seluruh merepresentasikan Demokrat. Seluruh pernyataan/tindakan partai dan kader-kadernya dapat dibaca sebagai gesture SBY itu sendiri. Sehingga ketika Partai Demokrat merespons berbagai situasi, dari sisi SBY hal itu bisa diperlakukan sebagai “tubuh-politik”-nya. Begitu juga sebaliknya: saat SBY menggunakan “tubuh-personal”, maka hal itu juga merepresentasikan “tubuh-politik” di Partai Demokrat.
Karena itulah menggunakan dan memaksimalkan instrumen politik untuk merespons situasi sebenarnya opsi yang sangat mungkin diambil. Tidak perlu ada kekhawatiran bahwa pernyataan/tindakan partai dan kader-kadernya akan dianggap bukan sebagai pesan/pernyataan SBY. Pesan akan sampai sebagai pernyataan/sikap SBY sendiri.
Inilah yang bertahun-tahun dilakukan Megawati. Tidak semua situasi direspons langsung oleh Mega. Hampir dalam banyak kasus, instrumen politik alias “tubuh-politik” yang digunakan untuk merespons situasi yang dianggap relevan ditanggapi, termasuk serangan-serangan yang mengarah padanya. Kader-kader PDIP biasanya akan maju ke depan membela Sang Ketua Umum.
Teuku Umar, kediaman Megawati, cukup selektif dipakai sebagai tempat konferensi pers yang menghadirkan dirinya sendiri. Bukan berarti Mega jarang tampil, tapi jika pun tampil ia lebih sering menggunakan medium “tubuh-politik”, seperti acara-acara partai. Salah satunya saat ia berpidato di HUT PDIP pada 10 Januari lalu.
Hal yang kurang lebih sama dilakukan Prabowo Subianto. Ia selektif menggunakan “tubuh-personal” untuk mengomentari atau merespons situasi-situasi khusus. Publik atau media cukup sering mendengar pernyataan-pernyataan tidak langsung Prabowo melalui kader-kader Gerindra, misalnya Fadli Zon.
Terakhir ia menggunakan “tubuh-personal” saat berbicara langsung dalam konferensi pers dalam peristiwa penangkapan Rahmawati, dkk., dalam kasus makar, Prabowo melakukannya di kantor DPP Gerindra pada 2 Desember 2016. Sikap yang cukup tepat dalam konteks, terutama, Rahmawati adalah pengurus DPP Gerindra.
Prabowo bukannya tidak pernah berbicara kepada wartawan di kediamannya di Hambalang. Itu terjadi saat ia menerima kunjungan Jokowi pada 31 Oktober 2016 silam. Prabowo (bersedia) menjawab pertanyaan wartawan, dan dengan demikian ia menggunakan “tubuh-personal”. Namun topik pembicaraan di area privat itu, di kediamannya itu, tidak sepenuhnya soal dirinya sendiri, melainkan juga soal (kedatangan) Jokowi.
Salah satu keuntungan memaksimalkan “tubuh-politik” adalah “tubuh-personal” tidak langsung menjadi sorotan. Reaksi, bahkan serangan, bisa dikurangi dampaknya karena akan di/terbentur “tubuh-politik” lebih dulu. Jika pun pernyataan/tindakan partai dan kadernya dianggap blunder, menggelikan atau berlebihan, jalan keluarnya pun mudah: katakan saja itu bukan ucapan Prabowo/Megawati, melainkan inisiatif kader/partai.
Hal inilah, reaksi atau serangan kepada “tubuh-personal”, yang sulit dielakkan oleh SBY karena ia justru semakin intens menggunakan “tubuh-personalnya”. Menjadi lebih problematis karena situasi yang direspons SBY dengan “tubuh-personal” itu berasal dari sumber yang tidak jelas atau datang dari subjek yang tak setara dengannya.
Dalam kasus raibnya dokumen TPF Munir, sebenarnya tidak ada pernyataan pemerintah yang terang-terangan menunjuk SBY. Sidang di Komisi Informasi Publik juga sudah memanggil Sudi Silalahi, Menteri Sekretaris Kabinet era SBY, dan dengan demikian bisa saja dianggap sebagai “tubuh-politik”-nya SBY. Bahwa perkara ini menyinggung era kepemimpinan SBY itu memang betul, tapi sebenarnya tidak ada sumber pemerintah, apalagi sumber yang setara levelnya dengan SBY (katakanlah Jokowi atau Mega) yang melemparkan pernyataan.
Begitu juga dalam konferensi pers pada 2 November. SBY mengklarifikasi tuduhan bahwa ia berada di balik rencana Aksi Bela Islam 4 November adalah rumor yang, jika pun itu dikerjakan oleh Istana, sebenarnya tidak jelas. Hampir pasti kuasa hukum Ahok yang mempersoalkan komunikasi antara SBY dan Ma’ruf Amin juga tidak setara level politiknya dengan SBY. Itu juga yang terjadi saat ia merespons, melalui Twitter, demonstrasi sekelompok mahasiswa.
Problemnya: berkomunikasi dengan “tubuh-personal” itu membuat SBY menjadi “terjangkau”, untuk tak mengatakan setara, dengan isu, rumor dan kuasa hukum Ahok atau bahkan sekelompok mahasiswa yang tempo hari berdemonstrasi. Akan lain jika SBY bereaksi terhadap, misalnya, pernyataan Jokowi atau Megawati atau Prabowo -- sebab di situlah level SBY sebagai tokoh politik. Ia Presiden RI ke-6 (setara dengan Megawati atau Jokowi), pendiri dan ketua partai (setara dengan Prabowo), bukan anggota DPR atau fungsionaris seperti Roy Suryo atau Adian Naputupulu.
Yang lebih membingungkan adalah serial kicauan Twitter soal akun-akun palsu yang menggunakan namanya. Saya kira seisi Twitter sudah tahu mana akun SBY yang terverifikasi. Merespons akun-akun palsu ini, sembari menyebut-nyebut jumlah pengikut akunnya, mengingatkan pada polah para selebtweet kebanyakan yang mengolah realitas maya di media sosial berbasiskan jumlah pengikut.
SBY tentu berhak kesal, namun kekesalan itu mestinya bisa dijawab dengan -- merujuk Judith Butler-- keahlian dalam “performatifitas”. Butler menunjukan bahwa berbicara dan berpidato (singkatnya: berkomunikasi) semestinya dilakukan untuk meladeni kebutuhan merumuskan identitas dan otoritas. Seorang Kapolri menyatakan buronan X telah ditembak mati, Ketua KPK menyatakan Si Y telah ditangkap lewat OTT, seorang hakim mengatakan Jessica bersalah adalah contoh tindakan performatif yang memperlihatkan identitas (sebagai kapolri, sebagai ketua KPK dan sebagai hakim) sekaligus menegaskan otoritas.
Menggunakan pilihan kata seperti “Ya Allah, Tuhan YME” atau “Saya bertanya kepada Bapak Presiden dan Kapolri” bukanlah tindakan performatif karena, alih-alih menguatkan identitasnya dan meneguhkan otoritas sebagai tokoh politik kelas atas, justru memperlihatkan SBY sebagai orang biasa.
Demonstrasi di kediaman SBY amat mudah untuk dilabeli pelanggaran hukum karena (1) tidak memberitahu polisi dan (2) dilakukan di kediaman pribadi. Namun merespons pelanggaran hukum yang, harus dikatakan, sepele itu dengan “tubuh-personal” sendiri, apalagi sambil menyinggung soal keselamatan dan hak tinggal di rumah sendiri, membuat SBY ada di level orang biasa, katakanlah seorang artis, yang panik karena rumahnya dikepung paparazzi.
Komunikasi politik yang berhasil untuk level SBY mestinya tidak berhenti di tataran kebenaran (bahwa bukan ia yang mengerahkan massa Bela Islam dan bahwa demonstrasi di kediamannya adalah melanggar hukum). Namun mestinya dilakukan sebagai, merujuk Geofrey Craig, “[...] presentation of a habitus that fuses political authority with performative style: politician must convey their knowledge and expertise as well as an appealing and engaging personality.” (Performing Politics: Media Interviews, Debates and Press Conferences, 2016).
Bukan kebetulan jika Rachland Nasidik, fungsionaris Partai Demokrat, mengatakan bahwa pernyataan SBY soal isu penyadapan sebagai “[...] a cry for help yang disampaikan oleh seorang warga negara kepada Presidennya.”
Diksi “warga negara” yang digunakan Rachland sangat tepat, bahkan jika diposisikan sebagai kalimat denotatif dan konotatif sekaligus. Ya, SBY memang sedang memposisikan dirinya bukan sebagai tokoh politik papan atas, seorang pendiri dan partai politik yang penting, atau seorang Presiden RI ke-6 yang memiliki privilese berlimpah (dari masih dikawal Paspampres hingga akses ke tokoh-tokoh penting lain), melainkan warga biasa.
Faktanya SBY bukan sekadar “warga biasa”. Segala ucapannya di Twitter atau di konferensi pers langsung menjadi bahan berita (sesuatu yang tak akan dialami oleh “warga biasa” yang lain). Bahwa gelombang isu Ahok vs NU yang sempat pasang pekan lalu akhirnya "terusik" oleh kicauan dan gesture SBY adalah dampak lain yang, mungkin akan disesali atau tidak oleh Demokrat, menjelaskan ia memang tak sekadar “warga biasa”
Jika pilihan-pilihan kata SBY pun menjadi bahan plesetan di media sosial, selain karena habitus cyberculture yang memang anti-hierarki bahkan cenderung anarki, hal itu juga mesti dibaca sebagai dampak pilihan SBY yang sedang mengutamakan status sebagai warga negara biasa, bukan menegaskan identitas dan otoritas sebagai sosok penting, berpengaruh, politikus kelas atas apalagi negarawan.
Editor: Zen RS
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id