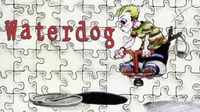tirto.id - Kalau ditinjau secara etimologi, kata pop memang sempalan dari kata populer. Tapi kalau kita bicara pop sebagai genre, maka tidak serta merta merujuk pada band atau musisi yang populer.
Begitu pula dalam konteks pop punk.
Untuk memahaminya, kita perlu pisahkan dulu kata pop dengan kata populer. Karena banyak band-band pengusung subgenre tersebut yang kurang populer, atau bisa dibilang underated.
Kata pop-punk terdiri dari dua suku kata “pop” dan “punk”, yang artinya ada fusion yang terjadi antara dua genre, sehingga melahirkan subgenre baru. Pop sendiri merupakan genre yang sudah eksis lama, jauh sebelum ledakan punk rock yang terjadi pada pertengahan dekade 1970.
Fusion genre sebetulnya hal yang lumrah dalam industri rekaman. Fusion genre merupakan hasil dari proses kreatif dan kemampuan band/musisi, yang menjumput pengaruh dari mana saja (termasuk aspek budaya, dan spiritual), kemudian memformulasikannya sedemikian rupa untuk menciptakan karakteristik sound sendiri.
Dalam domain punk rock pun fusion genre jamak terjadi, itulah mengapa ada hardcore punk, celtic punk, glam punk, horror punk, ska punk, termasuk pop punk.
Lantas bagaimana sebuah terminologi atau genre tercetus? Pertama, bisa klaim dari komunitas, band atau musisi yang bersangkutan, contoh: Brutal Juice yang memproklamirkan diri sebagai band acid-punk, atau seperti hadirnya subgenre khrisnacore dalam komunitas New York Hardcore.
Kedua, pengategorian itu sengaja diciptakan oleh industri rekaman. Ketiga, berasal dari analisis jurnalis, contoh; Garry Bushell yang menyematkan kata “oi!” untuk style musik yang dimainkan Cockney Rejects, Angelic Upstarts, dan lain sebagainya.
Tapi kadang ada juga jurnalis musik yang keliru dalam mendeskripsikan, sehingga memunculkan ambiguitas. Semisal ketika Tim Stegall dari Alternative Press, menyematkan NOFX sebagai band pop-punk dalam artikelnya.
Lalu mengapa ada pengategorian genre? Tujuannya agar mempermudah kita mengenali (sound) antara band yang satu dengan yang lain (Fabian Hold, 2007:3). Di sisi lain, pengkategorian genre amat membantu para musisi/band, untuk membidik taget pasar atau calon pendengarnya.
Namun di sini saya tidak bicara sejarah pop-punk, apalagi mengaitkannya dengan Ramones, Buzzcocks, dan Descendents, seperti yang dilakukan Jason Heller sang kontributor Vice. Tulisan ini lebih menelusuri bagaimana pop-punk hadir di Tanah Air, yang saya bagi dalam tiga fase. Di awali dari fase unidentified yangterjadi pada pertengahan, hingga jelang akhir dekade 1990.
Fase Unidentified
Ketika arus informasi belum terbuka lebar dan pengetahuan masih minim, baik Green Day, Bad Religion, The Exploited, hingga The Clash, cukup disebut dengan punk rock. Tanpa embel-embel ini itu, atau dengan kata lain pengategorian genre secara spesifik belum terlalu dikenal.
Makanya tak heran, bila penggemar musik punk era 90-an membeli kaset punk apapun yang rilis resmi di Indonesia karena didorong rasa haus akan referensi band. Seringkali pembeli ini tidak menyadari bahwa sebagian dari band-band itu belakangan disebut pop punk.
Rilisan berkategori pop punk yang paling awal beredar di Indonesia, adalah Dookie (Reprise, 1994) milik Green Day. Dalam Dookie, Green Day seperti terjebak dalam pattern lagu pop, ada chorus dan hook yang berulang, ritme yang melodius, mid tempo, dan membuat orang sing along. Berbeda dengan suksesornya Insomniac (1995), yang sisi punk rock-nya lebih dapat.
Menurut kritikus musik kawakan Simon Frith, musik pop itu punya tiga aspek, yakni; komersial, fana, accesable (mudah rasuk ke telinga orang). Dan Dookie punya unsur itu semua.
Rilisan pop-punk lainnya yang beredar di dalam negeri pada dekade 1990, antara lain Waterdog self-titled (Atlantic, 1995), Blonder and Blonder milik The Muffs (Reprise, 1995), Dear You dari Jawbreaker (DGC, 1995), Buglite yang merilis Love and other sorrow (Onefoot Records, 1996), dan album ketiga Smoking Popes, Destination Failure (Capitol, 1997).
Diterimanya Green Day di komunitas, terlihat dari banyaknya punker yang datang ke konser mereka pada Februari 1996.
Kemudian ketika aktifitas mail order dan rekam-merekam marak, kebanyakan penggemar musik punk era 90-an juga mendengarkan band-band rilisan Lookout! Records, yang notabenenya bisa dikategorikan pop-punk (ramonescore). Seiring dengan itu mulai dikenal pula istilah melodic, penyebutan lain dari skate punk/melodic hardcore versi kearifan lokal.
Fase Eksploratif
Selanjutnya adalah fase eksploratif, yangterjadi pada 1999 hingga pertengahan 2000. Fase ini ditandai dengan menjulangnya popularitas Blink-182 lewat Enema of the State (MCA, 1999), dan merebaknya film-film remaja Hollywood semacam 10 Things I Hate About You, American Pie, juga Can't Hardly Wait.
Film-film tersebut selain mengenalkan fashion, lifestyle, juga tren musik, dan cukup banyak memang band-band pop-punk yang berpartisipasi dalam album-album soundtrack.
Saat itu keberadaan pop-punk di industri musik Amerika mulai diperhitungkan. Band dari genre ini dianggap sejajar dengan hip metal (nu metal/rap rock) dan post-grunge, yang melejitkan nama-nama seperti The Calling, Vertical Horizon, Creed, hingga 3 Doors Down.
Menanjaknya popularitas subgenre tersebut di AS, berimbas dengan banyaknya rilisan-rilisan pop-punk beredar Tanah Air. Sebut saja New Found Glory self-titled (Drive-Thru, 2000), Sum 41 yang merilis All Killer No Filler (Island, 2001), Lechuza dari Fenix TX (Drive-Thru, 2001), Hurry Up and Wait karya Riddlin' Kids (Columbia, 2002), Drunk Enough toDance-nya Bowling for Soup (Jive/Silvertone, 2002), Box Car Racer self-titled (MCA, 2002), Leaving Through the Window dari Something Corporate (Drive-Thru, 2002), GOB yang punya Foot in Mouth Disease (Arista, 2003), So Long, Astoria-nya The Ataris (Columbia, 2003), hingga Yellowcard yang melepas Ocean Avenue (Capitol, 2003).
Ciri paling umum band-band tersebut adalah, cenderung mengangkat tema-tema konyol, percintaan remaja, hobi, pesta, persahabatan, kehidupan sekolah/kampus, dan tak lupa keceriaan menyambut musim panas.
Dengan disokong oleh keberadaan MTV Indonesia dan radio-radio, band-band tersebut mendapat porsi pendengar yang lebih luas, dan mulai memengaruhi band-band anyar di skena “melodic” Ibu Kota, Jakarta, yang semula terfokus pada band-band jebolan Lost and Found, Epitaph, dan Fat Wreck Chords.

Fase Rekognisi
Terjadi pada paruh kedua dekade 2000, hingga awal dekade 2010. Berbeda dengan band-band pop-punk sebelumnya yang secara sound masih beririsan dengan punk rock, kemunculan band-band pop-punk Amerika di periode ini berbarengan dengan tren musik emo.
Faktor itu pula yang membuat musik band pop punk era ini jadi lebih blend, dan cenderung elusif. Tak hanya emo, kadang ada elemen power pop, rock alternatif, pop-dance, sampai synthpop. Tema-tema lagu yang diangkat jauh lebih mature dan sentimentil. Dari segi fesyennya juga berbeda. Celana Dickies, sepatu Vans, skate web belt, rambut spike, perlahan mulai ditinggalkan.
MySpace, kegiatan download via Napster atau LimeWire, dan tumbuhnya kultur distro, adalah faktor-faktor yang menopang penyebaran pop-punk di skena lokal. Kalau kita datang ke distro-distro pada pertengahan 2000 hingga awal dekade 2010, maka bisa dipastikan hampir semua toko memutar jenis musik tersebut.
Di Jakarta, subgenre ini berkembang pesat di venue seperti Parkit Dejavu, Nirvana Café, Stardust Cafe, Marotti Café, hingga Rossi di Fatmawati. Namun diakui Allay Error, salah satu penggiat skena Parkit Dejavu, saat itu gig pop punk masih bercampur dengan gig “melodic”. Band pop-punk yang ada pun, masih berkiblat pada Drive-thru Records. Sebagian lagi mulai menjumput pengaruh pada rilisan Hopeless Records, dan Fueled by Ramen.
Dalam rentang waktu 2005 - 2011, begitu banyak band pop-punk mancanegara yang menggelar konser di Ibu Kota, mulai dari Simple Plan di 2005, Good Charlotte dan Fall Out Boy di 2007, New Found Glory dan Sum 41 di 2008, The All-American Rejects di 2009, All Time Low, Forever The Sickest Kids dan Boys Like Girls di 2010, The Starting Line, Paramore, dan Yellowcard di 2011 dan masih banyak lagi.
Rilisan-rilisan band pop-punk Ibu Kota juga mulai bermunculan, di antaranya; Pee Wee Gaskins yang punya album ikonik Stories From Our High School Years EP(2008), Miss Universe dengan E For Effort (2008), Love Like Pizza EP milik Tinkerbell (2008), Timeless Rawk EP-nya Bitter Ballen (2009), juga Last Child yang mulai dikenal berkat Everything We Are Everything (2009).
Yang unik pada fase ini adalah, maraknya band-band pop-punk Jakarta yang tampil menggunakan synthesizer, memasukkan unsur chiptune, hingga mengklaim mengusung easycore.
Dikotomi dalam Skena
Pertanyaan yang sering dilontarkan: mengapa genre musik yang disukai ini sekaligus dibenci?
Tak hanya di luar, di dalam negeri pun begitu. Bahkan Billie Joe (Green Day) sangat benci dengan terminologi tersebut.
Bisa jadi karena secara karakter modern pop-punk dianggap cemen, komersil, gaul, norak, dan melenceng dari estetika punk. Sangat kontras dengan punk rock yang digambarkan sebagai “loud, fast, and deliberately offensive style of rock music”. Di sisi lain ada pihak-pihak yang menganggap pop punk itu bukan punk, dan menginginkan punk tetap eksklusif, segmented, dan berada di jalurnya.
Imej pop-punk juga cenderung melekat pada generasi muda, membuat generasi yang lebih tua dihinggapi sikap superiority complex, merasa lebih unggul dari segi pengetahuan maupun selera musik. Ini pernah dilakukan Mike Ness (Social Distortion) yang meremehkan Blink-182, dalam film dokumenter Punk’s Not Dead (Vision Films, 2007).
Kemudian secara musikal pop-punk lebih radio friendly, sehingga mudah digemari orang, dan sesuatu yang digemari orang akan memunculkan gelombang tren. Kalau sudah menjadi tren, maka akan muncul penikmat musik baru dan dianggap bisa membuat genre/subgenre tersebut nampak jadi kacangan.
Tentu kita ingat, bagaimana ska punk/core dieksploitasi oleh industri arus utama dalam negeri sekitar 1999 - 2001, dan memunculkan penikmat musik ska yang mengenakan kemaja pantai, membawa pluit, serta koper. Sehingga membuat para rude boy militan gigit jari.
Akan tetapi pop punk terlanjur menjadi sebuah entitas, yang mau tidak mau mesti diterima jadi bagian dari payung besar punk rock. Dan subgenre ini hadir sebagai wujud dari keberagaman musik. Mengingat selera dan pilihan musik di setiap generasi itu berbeda.
Ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa, setiap individu yang terjun ke skena berawal dari poser. Saya rasa kita semua sepakat dengan itu. Sekarang yang harus kita lakukan adalah saling suportif, produktif, inovatif, dan melebarkan jaringan. Karena toh semua ada penggemar masing-masing.
Penulis: Nor Rahman Saputra
Editor: Nuran Wibisono