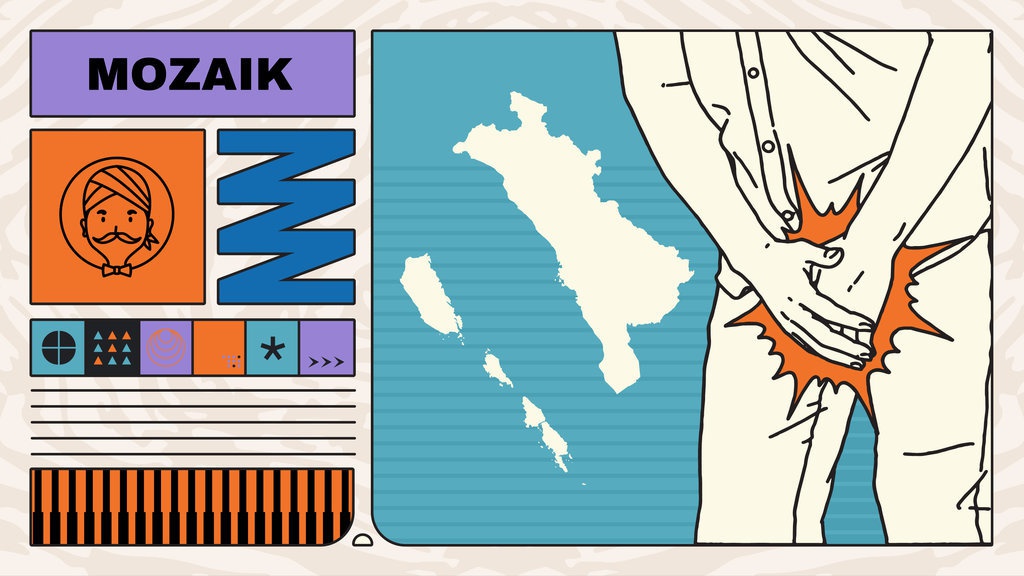tirto.id - Magek Takangkang, anggota keluarga bangsawan Pagaruyung turun ke Muara Padang sekitar paruh pertama abad ke-19. Ia datang ke kota pelabuhan utama di pesisir barat Sumatra itu untuk membeli berkodi-kodi kain dan berkarung-karung opium. Demikian diceritakan Pinto Anugrah dalam novel berjudul Segala yang Diisap Langit (2021).
Salah satu yang disebut dalam kisah ini adalah rumah candu merangkap rumah bordil milik pedagang Tionghoa bernama Peng Kok di pelabuhan tersebut. Peng Kok mempekerjakan "gundik-gundik Nias nan ayu" yang menemani anggota keluarga Raja Pagaruyung dan pelanggan-pelanggan lain menikmati candu. Para pelanggan bisa mengajak mereka bercinta. "Berancuk," tulis Pinto.
Saya tidak tahu dari mana Pinto Anugrah mencuplik narasi-narasi semacam itu. Yang pasti, Nias dan dataran utama Sumatra, tulis C. Dobbin misalnya dalam Gejolak Ekonomi, Kebangkitan Islam, dan Gerakan Padri (2008), memang telah cukup lama menjalin kontak dagang dengan dunia luar, utamanya soal jual beli budak.
Mungkin saja budak-budak perempuan dari pulau di lepas pantai itu juga dipasok untuk kebutuhan rumah-rumah bordil dan lapak candu di kota-kota pelabuhan semisal Padang, seperti yang dimaksud dalam cerita fiksi tersebut.
"Gundik-gundik dari Nias" dalam bahasa Pinto Anugrah mungkin sama dengan "koetjieng-koetjieng dari poelau" dalam bahasa Me' Saleh--saudagar besar dari Pariaman pada akhir abad ke-19.
Dalam Tjoerito perasaian Me’ Saleh gala Datoe’ Oerang Kajo Basa (1933), diceritakan tentang perjalanan Me' Saleh dengan biduk dari Pariaman ke Sibolga pada 1865.
Perahunya singgah di kuala Air Bangis selama dua hari, tempat ia menyaksikan "kucing-kucing dari pulau" pada malam hari berkeliaran mencari pelanggan di sekitar kapal-kapal yang ditambatkan di pelabuhan.
Pada satu malam, Me' Saleh tergolek di buritan kapal tak bisa tidur, karena mengapit banyak uang hasil berdagang. Sementara juru mudi dengan juru batu biduknya bersenang-senang di haluan ditemani perempuan-perempuan yang mereka bawa ke perahu.
"Dalam dua malam itu mata saya tidak bisa terpejam, sebab nyamuk banyak sekali, bentol-bentol badan digigitnya. Menjaga uang juga mengurangkan tidur. Perempuan jalang datang pula ke perahu dibawa juru mudi dan juru batu. Saya tidur sendiri di belakang," ujar Me' Saleh.
Praktik berancuk atau bersenggama dengan gundik, pekerja seks, masuk keluar rumah bordil, dan sejenisnya, telah lama dianggap memicu penyebaran penyakit sipilis secara luas. Penyakit ini kadang disebut raja singa, atau penyakit raja, atau kencing nanah--sekalipun yang terakhir ini tidak persis sama karena berasal dari bakteri yang berbeda.
Setelah kemunculannya pada awal abad ke-16, ia menjadi salah satu penyakit kelamin yang paling banyak menjangkiti penduduk Hindia Belanda, juga paling ditakuti.
Ramuan Tumbuh-tumbuhan
Penyebarannya yang tertinggi melalui pintu prostitusi. Kepemilikan gundik serta gaya hidup di kalangan militer dan pejabat pemerintahan yang menyukai kegiatan pelacuran telah memudahkan penyebaran.
Maka itu, Gani A. Jaelani dalam Penyakit Kelamin di Jawa 1812-1942 (2013) menyebut hampir 90 persen yang terjangkit penyakit ini di Jawa pada kurun yang dibicarakannya itu ialah tentara dan pejabat.
Sementara di wilayah luar Jawa seperti Minangkabau, belum diketahui dengan baik perkembangan dan pertumbuhannya pada era yang sama, tetapi diperkirakan kelas pengidapnya tidak akan jauh berbeda.
Sebagai contoh, Suryadi dalam Syair Sunur (2002) menyebut bahwa pada paruh kedua abad ke-19 di Padang, pemerintah kolonial menyediakan fasilitas untuk pemeriksaan dan pengobatan penyakit kelamin akibat prostitusi di rumah sakit militer.
Sekalipun telah tampak di berbagai kota pantai sejak abad ke-19, namun penyakit ini nyaris belum banyak disebut menjalar hingga ke desa-desa di pedalaman.
Namun E. W. A. Ludeking dalam Natuur en Geneeskundige Topographie van Agam (1867) menyebut orang Minangkabau punya obat khusus untuk menyembuhkan raja singa, yang dalam bahasa Melayu atau Minangkabau dinamakan "penjakiet radja".
Artinya, jika telah ada obat khusus dalam alam pengetahun mereka, tentu penyakit ini sesungguhnya telah menjadi momok sejak lama, sekalipun dengan jumlah pengidap yang amat terbatas.
Menurut Ludeking, penyakit ini dapat diobati dengan semacam ramuan yang diracik dari tumbuh-tumbuhan setempat. Berikut rincian obatnya:
"Akar anjalei, beras yang belum dikupas, akar rumput sarut, akar tabu, akar padi siarang, dicampur jadi satu, direbus, dan dimakan dengan sirih.
Akar bunga putih, dicampur akar anjelai, daun tapak leman, direbus, dan diminum airnya.
Air kelapa hijau, nanas mentah, akar basong berduri, beras, direbus airnya, dan diminum ketika pagi."
Senada dengan itu, William Marsden mengatakan bahwa orang Melayu tradisional mengobati penyakit ini dengan ramuan dari tumbuh-tumbuhan. Marsden mencatat di antaranya: air rebusan akar cina yang disebut gadung.
P.J. Veth dalam Midden-Sumatra (1882) juga menyebut, apa pun penyakitnya, termasuk raja singa, orang-orang Minangkabau akan membawanya ke dukun untuk diurut atau direkomendasikan ramuan dari jenis tanaman tertentu. Sayangnya, Veth tidak merinci ramuan yang dimaksud.
Sekalipun telah ada pengetahuan tentang obat penyakit ini, namun penyebarannya di pedalaman sepanjang abad ke-19 tetap tidak diketahui.
Sampai abad ke-20, juga masih terbilang sulit menemukan keterangan tentang penyebaran raja singa di kawasan itu pada surat-surat kabar sezaman maupun laporan resmi pemerintah. Padahal kota-kota kolonial di dataran tinggi sudah cukup berkembang.

Diredam di Pedalaman
Barangkali, seperti kata Marsden dalam History of Sumatra (1966), di dunia Melayu penyakit kelamin ini hampir tidak dikenal di daerah hulu atau daerah pedalaman. Biasanya hanya ditemukan di wilayah pesisir, terutama di pasar dan pelabuhan.
Kalaupun ada kampung-kampung di pedalaman yang terjangkit, pada umumnya penyakit itu dibawa oleh orang dari pesisir.
Lingkungan alamnya yang terisolasi, tersuruk jauh di dalam bentangan pergunungan Bukit Barisan yang rapat, bisa jadi telah menghindarkannya dari amuk penyakit ini.
Di samping itu, kehidupan masyarakatnya yang rata-rata masih berbasis kampung, yang dengan gampang dapat memindai anggotanya dengan perangkat mata awas nilai-nilai adat dan Islam yang cukup dominan dan berkuasa, membuat penyebaran penyakit ini relatif dapat ditahan.
Atau minimal "dikedapkan" sebagai temuan kejadian luar biasa yang kehadirannya dapat mencoreng nama baik adat dan agama.
Selain itu, praktik pengucilan tanpa ampun, misalnya, mungkin juga membuat eksistensi penyakit ini tidak begitu terlihat. Di pedalaman, penderita raja singa akan mendapat pengucilan yang kasar, dianggap penuh dosa dan mendapat bala karena dosanya itu.
"... kalaupun ada orang yang kemudian membawa penyakit itu ke dusunnya di pedalaman, orang tersebut akan dijauhi, dicap sebagai orang yang kotor dan tak boleh didekati," tulis Marsden.
Semua itu adalah cara-cara lama yang diskriminatif terhadap si sakit. Kiwari, ketika angka pengidap penyakit ini meningkat lagi, cara-cara yang lebih modern mesti dikedepankan.
Penulis: Deddy Arsya
Editor: Irfan Teguh Pribadi
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id