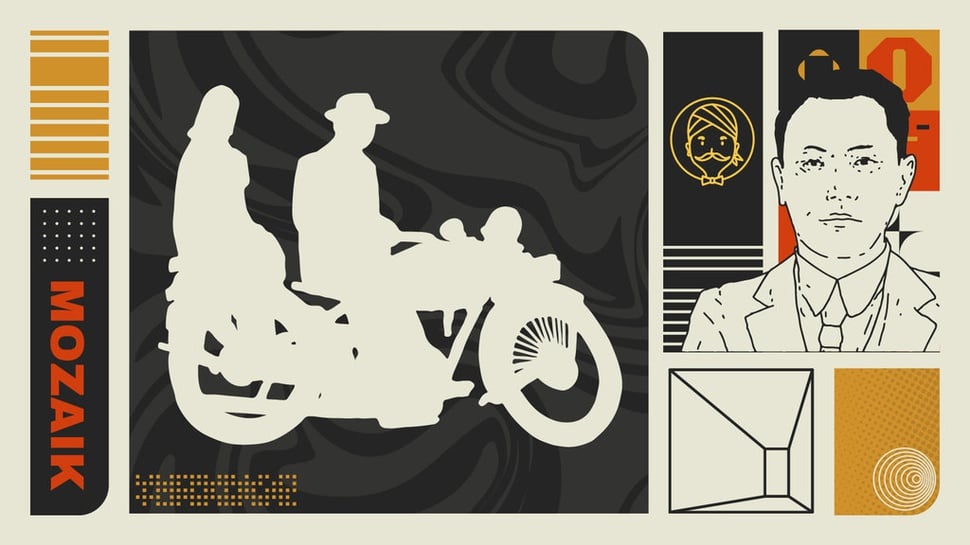tirto.id - Suatu hari yang cerah warsa 1960-an, Indonesianis Benedict Anderson mengitari pasar loak di Surabaya. Saat asyik menyisiri satu kios ke kios lain, matanya tiba-tiba tertuju pada satu buku lusuh bertajuk Indonesia dalem Api dan Bara.
Ben tergelitik melihat nama penulisnya: Tjamboek Berdoeri. Unik, pikirnya. Tanpa penerbit dan hanya tercantum tempat dan waktu terbit, Malang tahun 1947. Ben akhirnya membeli buku itu.
"Ketika saya bertanya kepada teman-teman tentang buku tersebut, ternyata hanya satu dari mereka yang pernah mendengarnya, apalagi membacanya, dan orang tersebut tidak tahu siapa sebenarnya Tjamboek Berdoeri itu," catat Ben Anderson dalam buku A Life Beyond Boundaries: A Memoir (2018).
Kosongnya oase pustaka tentang siapa sosok Tjamboek Berdoeri membuat Ben bertekad melacak identitas orang itu.
Dari ragam teman yang ia temui, hanya Ong Hok Ham yang sekilas pernah membaca dan tidak punya petunjuksiapa Tjamboek Berdoeri. Ben akhirnya berangkat ke Cornell pada 1964 untuk menyumbangkan salinan buku Tjamboek Berdoeri ke bagian buku langka di perpustakaan Cornell.
Publikasi Cornell Paper (1971) menjegalnya untuk masuk ke Indonesia dan menghentikan sementara penelusuran tentang Tjamboek Berdoeri. Jatuhnya Orde Baru mewujudkan impian Ben yang tertunda puluhan tahun.
Pencarian yang penuh dinamika menemui ujung saat Ben tahu bahwa Tjamboek Berdoeri adalah Kwee Thiam Tjing.
"Kamu Orang Tionghoa?"
Kwee Thiam Tjing lahir di Pasuruan pada 9 Februari 1900. Ketika hendak menginjak sekolah dasar, bapaknya mulai mencari cara agar dia bisa tembus ke Europese Lagere School (ELS). Beruntung sang bapak punya akses khusus dari sebuah keluarga Belanda.
Diskriminasi rasial ia alami sejak belia. Di hari pertama masuk ELS, Kwee duduk paling depan di sebelah murid Belanda. Anak Belanda itu terus memerhatikannya sejak ia masuk dan mulai mendekatinya.
"Apakah kamu orang Tionghoa?"
Kwee hanya menganggukkan kepala.
Mengetahui itu, teman sebangkunya berteriak, "Dia seorang Tionghoa!" hingga terdengar oleh satu kelas.
“Bisa bajangkan bagaimana semua mata ditudjukan kepada saja. Saja rasa seperti tersiksa,” tulis Kwee dalam memoar Menjadi Tjamboek Berdoeri (2010).
Dalam buku Prominent Indonesian Chinese: Biographical Sketches (2015), Kwee terdaftar sebagai murid di Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) di Malang kemudian Tulungagung setelah lulus dari ELS.
Ejekan rasial yang disasar pada Kwee masih berlanjut saat di MULO. Kali ini dia tahu bagaimana memberi pelajaran bagi orang-orang Belanda itu, yakni mendaratkan tinju ke badan mereka.
"Dalam begitu banjak perkelahian jang saja lakukan buat balas hina’an dan pandangan rendah jang ditudjukan kepada saja, 'si Tjina loleng, buntute digoreng,' saja musti akui sianak totok umumnja lebih fair,” catat Kwee dikutip Ben Anderson dalam Sadur: Sejarah Terjemahan di Indonesia dan Malaysia (2021).
Setelah lulus dari MULO, Kwee keranjingan membaca tentang apapun. Hobi itu mengantarkannya terjun ke dalam dunia jurnalistik dengan bekerja sebagai juru tulis di Perusahaan S.L. Nierop S. di Surabaya.
Pada perkembangannya Kwee tak betah dan memutuskan hengkang. Sementara itu, Liem Koen Hian, wartawan Tionghoa-Indonesia kondang, telah memimpin harian baru, Pewarta Soerabaja. Kwee berlabuh ke harian yang diasuh Liem itu.
Pada 1923, Liem berhenti dari Pewarta Soerabaja. Ia kemudian mendirikan Soeara Publiek. Kwee yang tengah berada di Malang ditarik oleh Liem untuk menjadi anggota dewan redaksi.
"Sikap politik Koen Hian jang baru itu sangat tjotjok untuk Kwee muda," tulis Ben (2021).
Di harian itu, Kwee telah memakai nama samaran Tjamboek Berdoeri.
Dijebloskan ke Penjara
Suatu hari di tahun 1925, Kwee mendapat undangan khusus dari Wali Kota Surabaya untuk datang di Simpang Societeit. Agendanya meriah, yakni penyambutan pemimpin konglomerat dari Jepang. Kwee duduk manis sambil mencatat untuk laporan Soara Publiek edisi esok hari. Tak disangka, laporan yang dibikin Kwee semalaman itu membuat gempar seantero kota.
"Belum pernah ada terdjalin persahabatan apalagi jang sampai 300 tahun lamanja, antara Belanda dan Djepang," lapor Tjamboek. "Dari sini ada bukti njata Belanda pandai djuga mendjilat, biarpun jang warna kuning [seperti tahi]. Sebabnja? Sebab meriam Djepang lebih besar dari meriam Belanda."
Laporan itu sampai ke Jaksa Agung. Oleh Pengadilan Surabaya, Kwee dijebloskan ke Penjara Kalisosok. Untuk pertama kalinya ia merasakan penderitaan di bawah pemerintah kolonial dengan menempati sel ukuran 2,5 x 4 m. Di sana pula ia memandang perlakuan berbeda antara tahanan golongan Inlander dan Eropa. Salah satunya perihal makanan.
"… bedanja seperti makanan di warung desa dengan restoran jang mendingan besarnja di kota," terang Kwee.
Pada Juli 1926, ia bersama 80 tahanan lainnya diperintahkan berjalan kaki ke Stasiun Semut. Mereka dipindahkan dari Penjara Kalisosok ke Penjara Cipinang menggunakan kereta api.
Tanggal 1 November 1926, ia dibebas. "Begitulah achirnja saja bisa lewat lagi pintu pendjara sebagai orang merdeka," kenangnya.
Menurut Leo Suryadinata (2015), Kwee kembali bergulat dengan dunia jurnalistik yang ditandai kepindahannya ke Sin Jit Po—yang kemudian beralih nama Sin Tit Po—mengikuti jejak Liem Koen Hian. Jenjang karier di Sin Tit Po mencapai puncaknya sebagai pemimpin redaksi pada 1931.
Kesadaran politiknya matang setahun kemudian. Kwee bersama rekan-rekan lain mendirikan Partai Tionghoa Indonesia (PTI) di Surabaya dan berusaha menjalin ikatan dengan Persatuan Bangsa Indonesia (PBI)-nya Dr. Soetomo. Apa yang diinginkan oleh Kwee via wadah partai itu cuma satu: persamaan hak antarkalangan.
"… jang kami tentang sedapat-dapatnja jalah itu perbeda’an perlakuan antara golongan Eropa dan jang diselempitkan ke dalam golongan Inlander," ujarnya.
Pada 1939, Kwee tengah menyusuri jalanan di Surabaya dengan santai. Matanya melirik plakat bergambar tiga roman lelaki bertuliskan tebal "De Stadswacht Waakt!" Stadswacht adalah barisan penjaga kota yang dibentuk pemerintah kolonial.
Melihat plakat itu, Kwee tertarik untuk menjadi stadswacht. Alasannya sederhana, sebagai jurnalis ia bebas dan ingin memberikan bantuan untuk rakyat. Segera ia mengisi formulir dan tak lama kemudian resmi menjadi regu stadswacht.
Awas, Ada Fasis!
Keadaan menjadi kacau menjelang kejatuhan Hindia Belanda. Hari itu 8 Maret 1942, seperti biasa Kwee berpatroli di batas Malang. Tepat pukul 7 pagi muncul mobil jeep yang berpapasan dengan Kwee sembari melemparkan selebaran. Di kertas itu terbaca Malang adalah kota terbuka.
"Alias tidak boleh dibela lagi. Semua perlawanan harus diberhentikan," kata Kwee.
Sebagai sersan, Kwee tahu ia telah dikhianati oleh bawahan-bawahannya dengan cara membelot. Tersisalah stadswacht dari kelompok orang-orang pribumi.
Masa Pendudukan Jepang menuntut Kwee untuk mampu menyesuaikan dengan kondisi kalut. Jurnalisme dirongrong oleh sensor. Hal ini memaksanya melamar pekerjaan di asosiasi Tonarigumi, yang kemudian ia menjabat sebagai kepala cabang lokalnya.
"Dia melakukan yang terbaik [di Tonarigumi] untuk melindungi perempuan dan anak-anak Belanda di lingkungannya ketika laki-laki mereka dipenjara dan dibunuh," catat Benedict Anderson (2018).
Pengalaman yang tidak mengenakkan menghampirinya. Suatu hari Kwee bertemu seorang Kempeitai yang tengah menyiksa seorang warga sipil. Kwee menyaksikan sejak mula hingga akhir bagaimana penyiksaan tersebut berjalan dalam Indonesia dalem api dan bara.
"… di tangsi pendjagaan [ia] disiksa boekan main dari bengkaknja ia poenja sekoedjoer badan, achirnja orang jang sial tadi mati," tulisnya.

Bayi Merah Republik
Jepang akhirnya takluk di hadapan Sekutu. Posisi demikian melenyapkan organisasi Tonarigumi dan badan-badan bentukan Jepang lainnya.
Pada 21 Juli 1947, Kwee beranjak dari santainya dan mengambil sepeda lantas memboncengkan bibinya. Kayuhannya semakin tak kenal putus dari selatan Malang, rumahnya, hingga pusat kota, persisnya di balai kota.
Pusat Kota Malang telah tersapu prahara saat itu. Balai kota telah dilahap api. Orang-orang berlarian menyelamatkan diri.
"Namun, rasa penasaran mendorong Kwee menerobos huru-hara," tulis TEMPO edisi 7 Maret 2020.
Detik-detik itu menjadi waktu menegangkan bagi Kwee. Hingga tiba sepedanya di Jalan Kelenteng yang menyuguhkan seseorang yang tergeletak di depan rumah seorang Tionghoa. Kwee menghampirinya dan berkata pada orang itu.
"Siapa jang tembak?
"Belanda."
Kwee lalu meneruskan perjalanannya hingga ujung jalan Kidul Pasar. Tampak di sana Toko Kediri telah luluh lantak dibakar dan dirampok. Sang empunya toko, sepasang suami istri, telah dibunuh oleh penduduk setempat yang menganggapnya sebagai kaki tangan Belanda.
Suasana getir selama periode pendudukan militer Belanda dicatat baik oleh Kwee dalam lembar demi lembar. Susunan lembar yang terhimpun dalam naskah kemudian ia kirimkan di percetakan di Pecinan Malang. Dari sana lahirlah karya monumentalnya: Indonesia dalem Api dan Bara (1947).
Setelah masa Revolusi usai, Kwee hilang peredaran di panggung publik Indonesia. Dekade berikutnya pada 1960-1970, ia bersama anaknya tinggal di Kuala Lumpur. Pada 1971 ia pulang ke Indonesia sekaligus muncul lagi di muka publik dengan menulis serangkaian artikel di harian Indonesia Raya hingga dua tahun ke depan.
Satu tahun setelah rampung menulis seri-seri artikelnya, Kwee meninggal dunia pada 1974.
Penulis: Alvino Kusumabrata
Editor: Irfan Teguh Pribadi