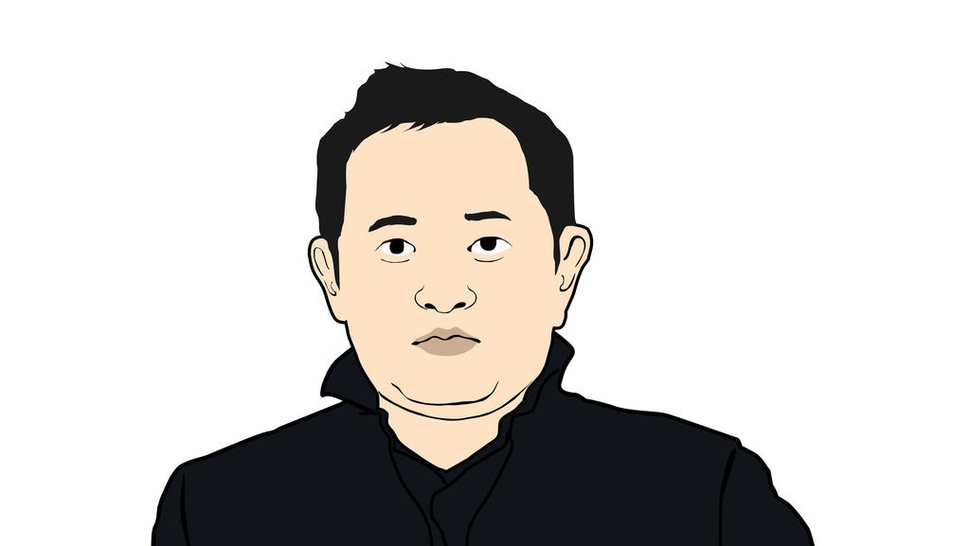tirto.id - Awal Maret 2019, Presiden Jokowi menghadiri acara deklarasi dukungan Pemuda Pancasila di Istora Senayan Jakarta. Seperti diberitakan oleh Tirto, Ketua Umum Pemuda Pancasila, Japto Soerjosumarno, dengan mantap menyatakan “sebenarnya kami tidak mendukung, tapi kami memilih (Jokowi)”.
Pemuda Pancasila resmi sudah mendukung Jokowi dalam Pilpres 2019. Berita Tirto lainnya tentang topik yang sama menjelaskan lebih jauh relasi antara elite politik dengan kelompok-kelompok seperti Pemuda Pancasila dari masa Orde Lama hingga setelah Soeharto jatuh. Namun tulisan ini bukan hendak mengulas lebih dalam hubungan Jokowi atau elite politik dengan kelompok-kelompok kekerasan.
Saya justru lebih tertarik kepada referensi yang dipakai oleh media, seperti halnya dalam pemberitaan Tirto. Mereka biasanya akan menggunakan buku karya Indonesianis Australia bernama Ian Douglas Wilson untuk menerangkan mengapa kelompok-kelompok keamanan seperti Pemuda Pancasila bisa bertahan setelah Orde Baru berakhir. Sebagai genre media yang bukan hanya menawarkan kecepatan namun juga kedalaman, saya sangat mengapresiasi penggunaan referensi ilmiah dalam redaksi pemberitaan Tirto. Bobot berita bertambah dan akhirnya menambah asupan informasi bermutu kepada publik di tengah simpang siur informasi belakangan ini.
Namun, penting untuk diketahui juga bahwa ada kritik mendasar terhadap karya Wilson yang selama ini selalu menjadi rujukan.
Buku Ian D. Wilson The Politics of Protection Rackets in Post-New Order Indonesia: Coercive Capital, Authority and Street Politics diterbitkan oleh Routledge pada 2015. Tiga tahun kemudian, Marjin Kiri menerbitkan edisi terjemahan Bahasa Indonesianya dengan judul Politik Jatah Preman: Ormas dan Kuasa Jalanan di Indonesia Pasca Orde Baru.
Tak bisa dipungkiri, karya pengajar Universitas Murdoch, Australia ini adalah sumbangan signifikan dalam khazanah akademik kita tentang isu premanisme, gangster, kelompok kekerasan, dan kelompok keamanan informal dalam kaitannya dengan demokratisasi Indonesia. Dari sekian banyak sarjana asing yang meneliti Indonesia, mungkin hanya Wilson yang mendedikasikan diri sejak 2006 hingga 2014 untuk menulis satu buku akademik serius tentang kelompok kekerasan dalam politik Indonesia kontemporer.
Argumentasi pokok Wilson kira-kira begini: kelompok-kelompok kekerasan dan keamanan informal yang muncul pada masa pasca-Orde Baru bukan hanya suatu bentuk kriminalitas biasa yang timbul akibat lemahnya penegakan hukum, melainkan juga terkait erat dengan relasi kuasa dinamis antar beragam aktor dan kelompok sosial. Alih-alih hanya dilakukan oleh aktor negara, jasa ‘keamanan yang melibatkan kekerasan’ juga bisa digarap oleh kelompok sipil. Wilson menyebut kondisi ini “new frontiers of legitimacy”, di mana legitimasi untuk melakukan kekerasan bukan hanya sepihak datang dari negara namun bisa muncul dari kelompok sosial mana pun sebagai konsekuensi konteks sosial politik yang kompleks.
Konteks tersebut bisa bernama desentralisasi, demokrasi elektoral, politik identitas dan populisme, hingga pasar bebas. Kelompok-kelompok sosial yang melakukan tindak koersif tadi bisa mengatasnamakan kelompok yang terpinggirkan secara sosial dan ekonomi, moralitas, hukum dan ketertiban, partai politik, korporasi, dan lain-lain. Ujungnya, kelompok-kelompok kekerasan ini kemudian rentan terkooptasi kepentingan predator politik yang telah melemahkan pelembagaan demokrasi di Indonesia.
Bias Jawa
Yang perlu kita sadari, karya Wilson berpijak pada studi kasus di Pulau Jawa dengan ormas-ormas seperti pada Front Pembela Islam (FPI) atau Forum Betawi Rempug (FBR) sebagai contohnya. Walhasil, pilihan lokus studi yang hanya berbasis di Pulau Jawa berpotensi untuk mengganggu kemapanan argumen yang dibangun di dalam karya Ian.
Lebih jauh, wilayah studi yang hanya di Pulau Jawa melemahkan klaim bahwa pertumbuhan kelompok-kelompok sekaligus dilema legitimasi kekerasan non-negara pada masa pasca Orde Baru terkait erat dengan desentralisasi. Desentralisasi mengondisikan munculnya ketidakseragaman bagaimana pemerintahan harus dijalankan di daerah karena menyesuaikan dengan konteks lokal.
Setelah sebelumnya diseragamkan oleh Soeharto, desentralisasi meniscayakan keberadaan ruang negosiasi soal bentuk kehadiran negara di daerah. Oleh karena itu, keragaman corak relasi masyarakat dan negara pasti lebih menguat ketika membandingkan antara Pulau Jawa dengan Luar Jawa terutama pulau-pulau terluar dan wilayah Indonesia timur. Dengan demikian, seharusnya ada disclaimer bahwa studi yang dilakukan dalam batasan ruang tertentu tidak bisa serta merta bisa digunakan untuk menjelaskan fenomena yang ada di wilayah lain yang tentunya mempunyai perbedaan lokalitas.
Contoh yang kita bisa gunakan untuk memperkuat kritik terhadap karya Wilson adalah kasus kelompok-kelompok serupa di pulau terluar seperti Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sudah sejak lama para sarjana menaruh perhatian terhadap keberadaan kelompok kekerasan di Lombok, salah satunya John McDougall.
Menurut McDougall, jumlah kelompok keamanan informal di Lombok relatif paling banyak jika dibandingkan dengan daerah-daerah Indonesia lainnya seiring dengan maraknya kriminalitas. Lebih jauh lagi, McDougall (2007) memperkirakan kelompok-kelompok keamanan informal di Lombok menyerap hingga 25% pemuda untuk menjadi anggota terutama pada awal 2000-an.
Terlepas dari akurasinya, paparan McDougall bisa menjadi gambaran betapa masifnya kehadiran kelompok-kelompok keamanan informal di Lombok yang sisanya masih bisa dijumpai hari ini, mulai dari Buru Jejak ‘Kumpul, Tiga Bersatu, Elang Merah, hingga AMPHIBI.
Eksistensi kelompok-kelompok keamanan informal di Lombok selama hampir dua dekade tidak bisa dilepaskan dari faktor belum tercukupinya pemenuhan kebutuhan akan keamanan oleh negara secara efektif. Sebagai tambahan ilustrasi, di Kabupaten Lombok Tengah sendiri tercatat hanya ada 800 anggota polisi yang bertanggung jawab terhadap keamanan 800.000 penduduk Lombok Tengah pada 2013. Padahal, PBB merumuskan rasio ideal perbandingan jumlah polisi dan penduduk adalah 1:400.
Dengan kata lain, kelompok-kelompok tersebut pada awalnya memang didirikan sebagai bagian dari niat baik untuk memenuhi kebutuhan keamanan secara mandiri oleh masyarakat. Permintaan untuk jasa keamanannya pun tidak hanya datang dari kelompok sosial dan ekonomi terpinggirkan namun juga dari kelas menengah.
Artinya, kelompok keamanan informal ini muncul sebagai alternatif pemenuhan hak dasar atas keamanan yang seharusnya disediakan oleh negara. Oleh karena itu, walau kelompok-kelompok seperti ini juga rentan dipolitisasi dalam politik lokal, kita tidak bisa langsung melabelinya sebagai menifestasi dari kepentingan politikus predator. Ada kebutuhan objektif dan akar persoalan yang perlu dibenahi terlebih dahulu, yakni akses hak atas keamanan secara setara.
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.