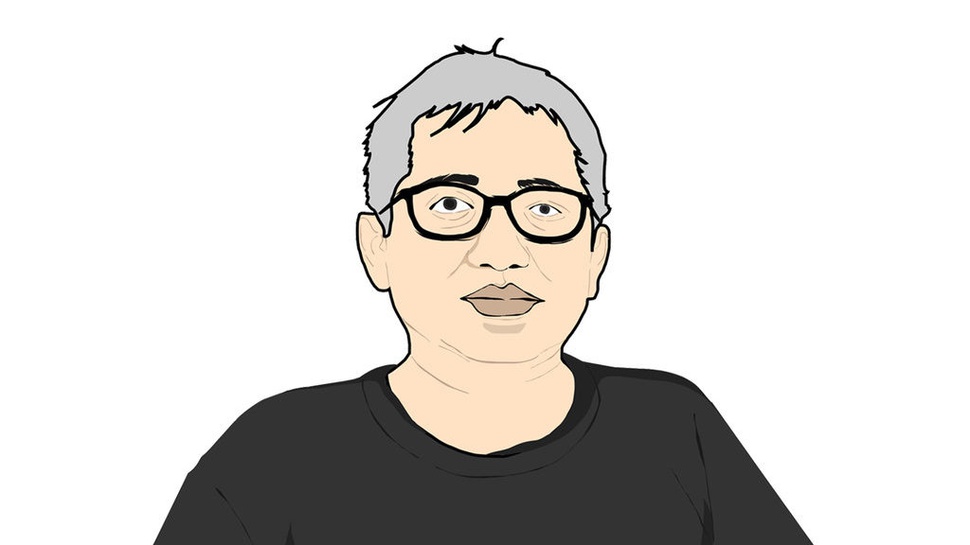tirto.id - Tahun ini, kali kedua saya ikut menjadi juri Fetisov Journalism Awards di Jenewa. Ada 126 karya jurnalistik harus saya nilai dalam empat kategori: hak asasi manusia, lingkungan hidup, membongkar korupsi,dan usaha perdamaian. Pesertanya dari seluruh benua: Afrika, Asia, Amerika Latin, sampai Eropa.
Hadiah ini dibuat oleh Gleb Fetisov, seorang dermawan dari Rusia. Fetisov semula ekonom zaman Uni Soviet, lantas masuk perusahaan Alfa Group ketika Perestroika bergulir, berperan dalam beberapa investasi, mendapat banyak uang.
Pada 2012, Fetisov masuk politik, memimpin Aliansi Hijau, partai yang memperjuangkan lingkungan hidup dan sosial demokrasi. Pada 2014, dia menjual semua sahamnya, total 1,4 miliar dolar AS. Namun, dia ditangkap dan membayar denda 200 juta dolar AS, bebas dari penjara, lantas bekerja di bidang kebudayaan. Pada 2019, dia mulai memberikan penghargaan untuk jurnalisme.
Total hadiah Fetisov sekitar 525.000 dolar AS untuk empat kategori. Ini hadiah jurnalisme paling mahal di dunia. Sebagai perbandingan, Pulitzer Prize dari New York memberikan total 315.000 dolar AS buat 21 kategori. Bedanya, Pulitzer mulai sejak 1917, hadiah jurnalisme tertua di dunia. Staminanya sudah teruji hampir satu abad.
Saya merasa penjurian Fetisov tahun ini lebih berat dari tahun lalu. Ada lebih banyak karya yang bermutu.
Ketika jurnalisme sedang tertekan karena penghasilan mereka menurun—Google, Facebook dan lain-lain mengambil kue iklan—banyak wartawan tak menyerah. Saya juga melihat karya bermutu di luar media mapan dari New York, London, atau Washington.
Ada dari Lagos, Qatar, Kairo, New Delhi, Rio de Janeiro, dan lainnya.
Saya merasa belajar lagi, dari isu air dan hutan sampai pencucian uang. Banyak isu masyarakat adat muncul. Ada wartawan Turki membantah konspirasi anti-vaksin. Ada wartawan India membela orang Dalit—kasta paling rendah dalam Hinduisme. Saya juga melihat beberapa peserta menggunakan data raksasa. Banyak peta. Banyak gambar. Banyak statistik.
Kriteria penilaian ada tujuh butir:
- Akurasi: Memastikan informasi berdasarkan fakta dan dapat diandalkan;
- Independensi: Menghindari bias kepentingan politik atau bisnis serta berbagai pengaruh lain yang tidak semestinya;
- Imparsial (berjarak, tak berpihak) dan fairness (tak berat sebelah);
- Kemanusiaan: Bagaimana prinsip-prinsip non-diskriminasi dan penghormatan terhadap korban, kalangan minoritas dan kelompok rentan diterapkan;
- Transparansi: Bagaimana proses pelaporan dilakukan secara terbuka dan si penulis membuat diri sendiri bertanggungjawab terhadap liputan dan karya;
- Promosi etika dalam jurnalisme;
- Dampak positif publikasi terhadap situasi politik, ekonomi atau sosial di suatu daerah, negara, atau dunia.
Media Indonesia bagaimana?
Seharusnya, ada beberapa karya dari Jakarta yang bisa dipertandingkan di sini, sayang, mereka tak ikutan. Saya terpikir liputan kekerasan seksual di kampus-kampus Indonesia bisa masuk. Karya #NamaBaikKampus sudah mendapatkan penghargaan Society of Publishers in Asia dari Hong Kong. Ia kolaborasi dari empat media: Tirto, The Jakarta Post, VICE Indonesia, dan BBC Indonesia. (BBC Indonesia belakangan mengundurkan diri.)
Pada 2019, Mongabay mendapat juara dua dari Fetisov. Laporan “The secret deal to destroy paradise” juga karya kolaborasi dari Malaysiakini, Tempo, dan Mongabay.
Dari luar Jakarta, rasanya masih jauh. Penjurian ini menyadarkan saya, sekali lagi, jarak antara media di provinsi-provinsi dan media di Jakarta.
Tak perlu emosi karena jurang antara Jakarta dan daerah, dalam jurnalisme, tercipta berkat negara Indonesia—rezim Soekarno dan Soeharto—melakukan sentralisasi media. Hindia Belanda jauh lebih terdesentralisasi. De Locomotief, suratkabar liberal di Hindia Belanda, berada di Semarang. Manado punya banyak pelopor jurnalisme lewat Tjahaja Sijang.
Ketika Jepang menduduki Asia Tenggara, militer Jepang menutup semua media. Dalam tragedi 1965, entah berapa puluh surat kabar ditutup, berapa ratus wartawan dan redaktur ditangkap, dipenjara, tanpa pengadilan. Lembaga-lembaga jurnalisme, baik surat kabar, radio, televisi maupun sekolah jurnalisme, banyak diberedel, dilumpuhkan dalam dua rezim itu.
Kebebasan pers praktis baru muncul dengan agak leluasa sesudah Presiden Soeharto mundur pada 1998.
Warisan dua rezim itu belum selesai.
Etika dalam jurnalisme masih perlu dibangun. Banyak kritik terhadap media Indonesia ketika pengadilan Manchester, Inggris, menyatakan bersalah Reynhard Sinaga, mahasiswa Indonesia, dengan hukuman penjara minimal 30 tahun setelah melakukan 136 pemerkosaan.
Selama dua tahun, sesuai permintaan pengadilan, media Inggris tidak melaporkan sidang itu sampai vonis keluar pada 6 Januari 2020. Ini dilakukan guna melindungi para korban dari trauma dan membantu proses penyelidikan dan pengadilan. Media Inggris taat. Mereka meliput tapi tak memberitakan.
Remotivi, organisasi pemantau media, mengkritik liputan Sinaga di kalangan media Indonesia, sesudah vonis, mulai dari sensasionalisme hingga menonjolkan identitas pelaku—seorang lelaki gay. Ini tak relevan karena kejahatan seksual terjadi baik pada heteroseksual maupun homoseksual.
Bayangkan bila penangkapan dan pengadilan Sinaga terjadi di Indonesia?
Bias agama juga meningkat di kalangan wartawan. Tantangan banyak wartawan di Indonesia adalah tak membiarkan Islamisme mendikte liputan mereka. Wartawan tentu sah bila beragama atau berkeyakinan tapi mereka seyogyanya menjadikan agama atau iman guna memperkaya ruang redaksi. Bukan buat mendikte. Ini membuat misogini, sektarianisme, dan homofobia meningkat di berbagai ruang redaksi.
Bagaimana wartawan beginian bisa taat prinsip non-diskriminasi dan menghormati korban, kalangan minoritas dan kelompok rentan, adalah tantangan besar di Indonesia?
Bagaimana wartawan bisa menjaga independensi dari kepentingan bisnis atau politik, termasuk dari para pemilik di mana mereka bekerja, juga jadi tantangan besar di Indonesia.
Banyak hukum di Indonesia juga masih bisa dipakai untuk mengkriminalisasi wartawan. Dalam bahasa Inggris, banyak pasal bisa dipakai buat criminal defamation, dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana sampai Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bila terjadi penyerangan terhadap wartawan, terutama oleh aparat keamanan, praktis tak ada sanksi terhadap pelaku.
Khusus Papua dan Papua Barat, sudah lima dasawarsa kedua provinsi ini dibatasi untuk wartawan asing. Setiap wartawan asing, yang hendak liputan ke sana, harus lolos dari clearing house di Kementerian Luar Negeri. Ini terdiri 18 wakil dari berbagai kementerian dan lembaga. Banyak pegawai, sipil maupun militer, paranoid di sana.
Salah seorang redaktur yang terlibat dalam tim Mongabay, Phil Jacobson, sempat ditahan 45 hari di Palangka Raya, dengan tuduhan tak memakai visa wartawan. Dia ada dalam tahanan imigrasi ketika Fetisov mengumumkan Mongabay dapat hadiah.
Saya memperhatikan wartawan-wartawan dalam penjurian Fetisov ini kebanyakan bikin karya bemutu dengan kolaborasi. Mereka bekerja sama dengan dasar profesionalisme—bukan kewarganegaraan atau keagamaan. Mereka menghasilkan liputan soal hak asasi manusia, perlindungan lingkungan hidup, atau melawan kejahatan kerah putih.
Anda perhatikan nama-nama dari media Indonesia yang dapat penghargaan dalam dua tahun terakhir termasuk Jacobson. Kolaborasi, bukan?
Selama empat hari pada akhir pekan lalu melakukan penjurian, saya menilai, Indonesia terlihat perlu lebih banyak media bermutu, yang sanggup punya brand internasional. Media semacam ini, suka atau tidak, perlu liputan luar negeri, bekerja sama dengan wartawan asing. Tak cukup hanya mengandalkan liputan nasional.
Media seperti itu, tentu saja, perlu punya penyuntingan halus, bahasa yang serasa lukisan (ingat Roy Peter Clark dengan “The Writing Tools”), dan news design yang bersahabat dengan mata (ingat Society of News Design?). Saya melihat naskah-naskah yang bermutu juga terbit lewat website dengan desain bermutu dan penyuntingan halus.
Makin bermutu jurnalisme dalam suatu masyarakat, makin bermutu informasi yang didapat, hingga makin bermutu pula demokrasinya. Sebaliknya, makin rendah mutu jurnalisme, makin rendah pula mutu masyarakat itu.
Indonesia jelas memerlukan jurnalisme yang makin bermutu. Indonesia tak boleh membiarkan pelbagai warisan masa lalu menggerogoti kebebasan pers, buah dari kemenangan demokrasi pada 1998.
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.