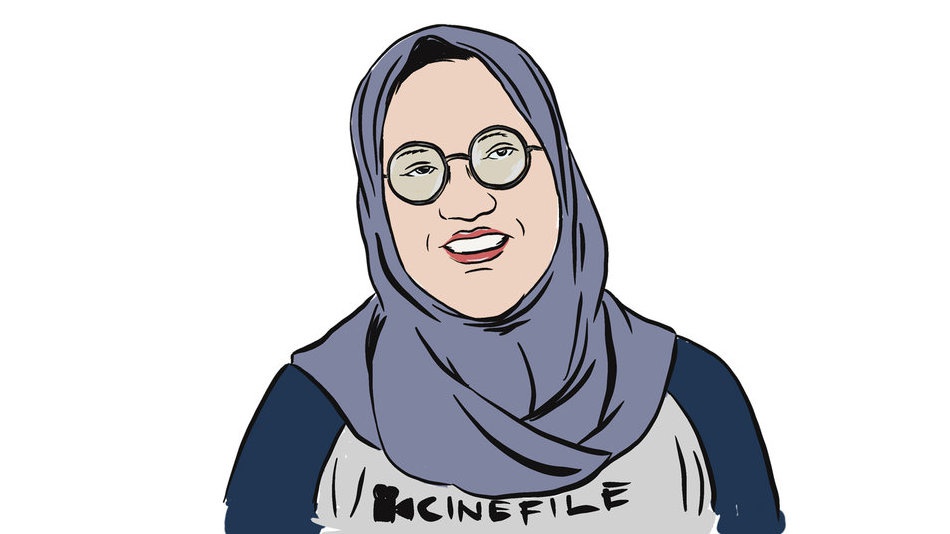tirto.id - Positif.
Satu kata berwarna merah itu terlihat begitu kontras dibanding barisan huruf lainnya yang berwarna hitam. Tengah malam di pertengahan bulan Januari, saya menerima hasil tes PCR dari sebuah klinik. Setelah sebelumnya mengalami demam, sakit kepala, dan sakit tenggorokan, saya memutuskan untuk melakukan pengecekan mandiri.
Dugaan saya benar: positif.
Divonis positif COVID adalah pengalaman ironis. Sebagai orang yang setiap hari memantau misinformasi terkait COVID dan kerap membaca jurnal akademik terkait pandemi, saya merasa kalah setelah berbulan-bulan kucing-kucingan dengan virus. Terlebih, vonis positif itu jatuh sehari sebelum Presiden Jokowi menerima vaksinasi. Kurang lebih, rasanya seperti pejuang yang kalah dalam skenario film-film apokalips, tepat ketika pertolongan datang. “Kalian pergi saja, selamatkan diri sendiri, aku akan bertahan!”
Saya langsung mengabari dua kawan kos. Mereka meminta saya tenang, menawarkan dukungan, dan meyakinkan bahwa isolasi mandiri dapat dilakukan di kamar kos. Saya berusaha tegar mengabaikan segala keraguan soal bertahan hidup di ruangan berukuran 3x4 meter dalam 14 hari ke depan.
Keesokan paginya, pemilik kos menaruh ransum di depan kamar. Isinya: alkohol pembersih luka, detergen, susu, makanan ringan, disinfektan, dan kebutuhan penting lainnya agar saya mampu bertahan. Dia juga menyarankan agar saya mengisolasi diri di kos. Pilihan untuk isolasi di Wisma Atlet terasa begitu asing dan menakutkan buat saya. Mungkin saja sebenarnya tidak begitu. Namun, sebagai seseorang yang tinggal sendiri di perantauan, kos dan kawan-kawan dekat adalah obat keterasingan. Belum lagi, saya harus berhadapan dengan gejala-gejala ajaib yang ditimbulkan virus Corona.
Setelah riuh rendah notifikasi pesan yang tak henti-hentinya datang dari kolega dan Satgas Covid, saya mencoba berkontemplasi kira-kira kapan dan di mana saya terinfeksi. Kemungkinan terbesar: saya terpapar virus saat melakukan perjalanan dari Sumatera ke Jakarta, awal Januari silam.
Saya kembali mengingat-ingat bagaimana memutuskan pulang kampung pada November lalu. Keputusan untuk pulang bukanlah sesuatu yang begitu saja dilakukan. Saya membuat catatan baik-buruknya keputusan itu. Dalam list baiknya, saya punya kesempatan bertemu bapak dan ibu yang khawatir anaknya luntang-lantung di ibukota. Mereka sempat kelelahan mengurusi rumah yang seperti kapal pecah setelah kebanjiran. Mereka jatuh sakit karena sering khawatir.
Fakta bahwa saya tidak hadir cukup membuat saya merasa tak berbakti. Apalagi, sudah setahun saya tak pulang.
Nomor kedua dalam daftar kebaikan adalah istirahat pikiran. Menjalankan kehidupan dari kamar kos mini di Jakarta tentu tidak mudah. Selama ini, bepergian ke kantor atau beraktivitas di luar rumah adalah cara membebaskan diri dari perasaan terkungkung di kamar—dan sialnya saya tak punya banyak pilihan selama pandemi. Pandemi juga yang membuat saya lebih khawatir akan hari esok: apakah saya masih punya pekerjaan beberapa minggu atau bulan ke depan? Akankah saya kena Corona? Bagaimana nasib orang-orang terdekat?
Bagian buruknya, keputusan untuk pulang sebenarnya bisa jadi bumerang. Jangan-jangan saya malah menyebarkan virus dan membuat keadaan di rumah jadi berantakan. Belum lagi label di jejaring pertemanan sebagai Covidiot karena memilih untuk bepergian. Ya, jika saja mereka mengerti posisi saya atau setidaknya menunda untuk menghakimi dari rumah yang luas, keluarga yang dekat, dan pemasukan yang stabil. Lagipula, keputusan untuk bepergian sebenarnya juga dibolehkan oleh Pemerintah, dengan prosedur tertentu. Namun, memang bepergian bukan hal yang etis dilakukan saat ini.
Tapi, akhirnya saya ambil juga keputusan itu. Saya membeli tiket pesawat setelah dinyatakan non-reaktif oleh rapid test. Sabtu, November 2020, saya terbang dengan proteksi berlapis; dua lapis masker, hand sanitizer, dan berjauhan dari orang lain.
Saya menyaksikan orang-orang di bandara bergegas membawa koper besar dan menggendong kardus. Tak sedikit yang menunjukkan wajah kuyu. Yang lain kesulitan mengeja nama maskapai. Mereka nampak memilih kembali ke kampung halaman. Ibukota, dan juga pandemi, membuat mereka kalah.
Ketika ingatan saya masih melayang-layang, seorang kawan mengetuk pintu dua kali. Itu adalah tanda ia menggantungkan makanan di gagang pintu. Isolasi yang saya lakukan demikian ketat. Tak hanya mengurung diri di kamar dan tidak membuka jendela, saya baru bisa mengambil makanan setelah dia pergi. Hampir semua aktivitas memang dilakukan di kamar. Kadang, saya masih menyaksikan kawan-kawan makan di dapur dari jendela, dan hanya bercakap dengan mereka hanya lewat video call. Mereka juga mengecek kondisi saya setiap hari.
Dalam kurun waktu isolasi, ada hal yang tak terelakkan setiap harinya: kesepian. Isolasi, kesendirian akibat isolasi, dan kesepian kadang muncul begitu saja. Memang ada waktu ketika saya sibuk berkonsultasi dengan dokter puskesmas, menghibur diri dengan streaming Netflix, membaca pesan instan, atau browsing meme di internet. Namun, ada pula kondisi ketika saya kelelahan menatap layar, jemu dengan rutinitas, dan bosan menatap dinding berwarna putih.
"Kesepian,” tulis Hannah Arendt dalam bab terakhir The Origins of Totalitarianism (1951), “membuat orang kehilangan tempat di dunia". Mereka yang kesepian "adalah orang-orang yang dicampakkan dunia. Inilah pengalaman kemanusiaan yang paling radikal lagi menyesakkan".
Arendt memang sedang menjajaki kondisi mental masyarakat di bawah rezim totaliter di mana orang dibuat takut untuk bertindak mandiri dan berkumpul. Tapi, kini, Anda tak perlu rezim otoriter (atau sudah?) untuk kehilangan pijakan. Orang bisa terisolasi dan kesepian—dan mereka tidak sendirian. Ada banyak orang yang saya yakini mengalami hal yang sama dengan saya; meski kondisi kami berbeda. Saya sendiri masih beruntung bisa menjalani isolasi di kos dengan dibantu seorang kawan. Bagaimana mereka yang tidak punya atap untuk berlindung atau harus bekerja di jalan?
Anda mungkin bertanya: “Kenapa kau kembali lagi ke Jakarta, tempat zona merah Covid, dasar kau idiot!”
Jika bisa, saya juga tak ingin kembali. Well, banyak orang yang harus mengungsi dari Jakarta selama pandemi. Tapi, berapa lama? Tak jarang saya dengar cerita orang yang sudah mengungsi dari Jakarta harus kembali ke Jakarta untuk mengurus tetek bengek administrasi terkait pekerjaan, sekolah, kehidupan. Halo, otonomi daerah?
Pulang Atau Tidak Pulang
“Jadi kamu akan pulang lagi kan ketika lebaran?” tanya ibu ketika saya hendak pamit ke Jakarta.
Waktu itu saya diliputi ragu. Kini keraguan itu sudah menjelma trauma ; trauma hidung dicolok kesekian kalinya, trauma dengan gejala-gejala Covid, lelah dengan prosedur yang harus diterapkan ketika melakukan perjalanan, hingga ketakutan situasi akan bertambah buruk.
Tahun ini, pemerintah memangkas lima dari tujuh hari jatah cuti bersama
Tujuannya? Agar pergerakan masyarakat bisa dibatasi dan tidak terjadi penumpukan massa pada satu hari. Masalahnya, jika itu tujuannya, banyak kebijakan negara yang terbukti kontraproduktif dengan langkah-langkah penanganan pandemi: PT KAI memberkan diskon tiket Desember lalu, PSBB dilonggarkan, dan pilkada tetap digelar.
Hari ini saya mantap bilang tidak akan pulang, setidaknya hingga bapak dan ibu di rumah mendapat injeksi vaksin. Semoga vaksinasi di daerah dapat bergulir dengan cepat dan menjadi prioritas.
Sudah satu tahun kita ketakutan dan resah. Kita takut akan ancaman yang tiba-tiba berlipat ganda, entah itu pemangkasan gaji atau risiko PHK. Hal-hal sehari-hari yang biasanya dilakukan mendadak terasa mengerikan. Dan kita takut seandainya pertemuan kita akan jadi pertemuan terakhir. Saya gelisah seandainya orang tua saya sakit dan saya tak berada di sana—dan inilah yang memicu saya untuk pulang.
Sayangnya keputusan terbaik jarang sekali muncul dari ketakutan semata. Ada kalanya keputusan untuk mengambil tindakan X, Y, Z demi bertahan hidup justru mengakhiri kehidupan itu sendiri. Ketika pemerintah dan para pesohor sibuk membicarakan pentingnya menerapkan protokol kesehatan agar terhindar dari Covid, kita melupakan satu barang berharga yang kini betul-betul langka di tengah hiruk pikuk timeline, feed, story, dan episodes: disiplin emosi.
Betul. Disiplin untuk berpikir ribuan kali sebelum mengambil tindakan apapun. Anggap saja ini latihan mental di tengah masyarakat impulsif yang memuja kecepatan, kelekasan, spontanitas.
Saya percaya Anda tak perlu jadi rahib untuk punya displin itu.
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.