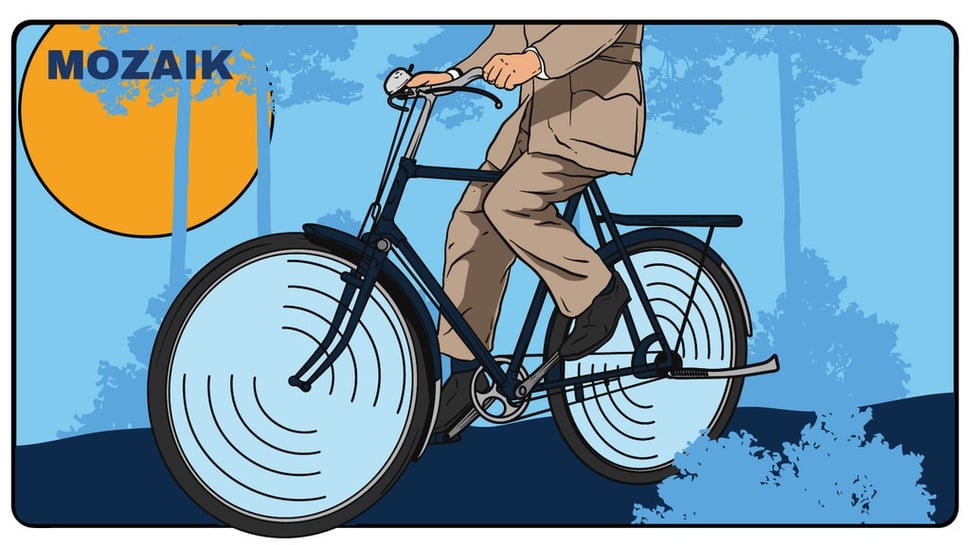tirto.id - Pandemi Covid-19 dan ditetapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) beberapa tahun lalu membuat sejumlah orang menekuni hobi bersepeda. Data dari Kementerian Perhubungan tahun 2020 menyatakan tren bersepeda mengalami lonjakan jumlah pengguna hingga 1000 persen.
Angka tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah pesepeda terbesar ke-8 di dunia. Kenyataan ini mungkin tidak pernah terbayang di benak warga Belanda yang untuk pertama kalinya memperkenalkan sepeda pada masyarakat bumiputra.
Pengaruh Belanda dan Jepang
Sepeda sudah melintas di jalanan Hindia Belanda sejak 1910 dan meraih puncak popularitasnya pada dekade 1950 hingga 1970. Awalnya sepeda yang digunakan oleh masyarakat adalah produk buatan Belanda dan diimpor langsung dari negeri tersebut, di antaranya bermerek Fongers, Batavus, Sparta, dan Gazelle.
Banyaknya sepeda yang dipasok dari Belanda, selain karena Hindia Belanda adalah koloni negara tersebut, juga karena sejak 1925 Belanda sudah menjadi Negeri Sepeda, sejumlah pabrik sepeda berskala internasional didirikan dan warga sangat menggandrunginya, bahkan menjadi ikon budaya mereka.
Seturut Tjong Tjin Tai dkk dalam "How the Netherlands Became A Bicycle Nation" (2015:1), sebelum 1931 sekira 58 persen sepeda yang digunakan warga Belanda merupakan buatan dalam negeri, tapi pada 1931 angka tersebut melonjak hingga 99 persen. Pada 1939, dari 8,7 juta penduduk Belanda, 38 persennya atau sekitar 3,3 juta jiwa memiliki sepeda.
Sementara menurut Dedi Arman dalam "Kisah Sepeda Onthel Merek Banteng", dalam perkembangannya sepeda-sepeda yang masuk ke Hindia Belanda bukan hanya produk Belanda, tapi juga merek-merek asal Inggris dan Jerman, seperti Humber, Phillips, Raleigh, Göricke, dan Fahrrad.
Sepeda berbagai merek itu dipasarkan pasca Perang Dunia I oleh perusahaan-perusahaan dagang Eropa di sejumlah kota besar di Hindia Belanda, seperti Batavia, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Banjarmasin, dan Makassar.
Pada 1937 jalan-jalan di Jakarta makin banyak dilalui sepeda. Jumlahnya diperkirakan 70 ribu unit. Pada tahun yang sama di Surabaya jumlahnya sekitar 36 ribu unit. Sementara itu di Bandung pada 1942 terdapat lebih dari 40 ribu unit.
Pada 1942 ketika Jepang menguasai Hindia Belanda, muncul larangan menggunakan sepeda buatan Eropa. Sebagai gantinya, pemerintah pendudukan Jepang membuka keran impor sepeda buatan negeri mereka. Merek-merek seperti Bike Pals, Club, Milton, Oryx, Prima, Wee Bee, dan Woodcock menggantikan sepeda buatan Eropa.
Seturut M. C. Ricklefs dalam A History of Modern Indonesia since c.1200 (2001:249), sejak merebut Indonesia dari tangan Belanda, Jepang memang memprioritaskan dua kebijakan yang searah, yaitu memobilisasi rakyat Indonesia dalam Perang Asia Timur Raya dan menghapuskan pengaruh Barat.
Bermula dari Letusan Tambora
Andrew Cleveland Honeycutt dalam “The Birth of the Bicycle: The Development, Aesthetic form, and Social Attitude Towards the Velocipede of the 19th Century” (2022:8) mengatakan, sejumlah ilmuwan berteori bahwa letusan Gunung Tambora yang terjadi pada 1815 berkontribusi terhadap penemuan sepeda.
Erupsi gunung yang terletak di Pulau Sumbawa itu menyemburkan partikel vulkanik ke atmosfer bumi sehingga menghalangi masuknya sinar matahari. Akibatnya suhu permukaan bumi anjlok hingga tiga derajat Celcius selama beberapa waktu.
Peristiwa tersebut juga membuat daratan Eropa dan Amerika Utara pada 1816 tidak mengalami musim panas, sehingga menyebabkan rusaknya tanaman atau gagal panen dan berujung pada krisis pangan yang dahsyat.
Keadaan ini mendorong Baron Karl Von Drais, seorang pengawas hutan di Dutchy of Baden (Jerman) bereksperimen menciptakan kendaraan yang bisa mengurangi ketergantungan manusia terhadap kuda. Eksperimen Von Drais itu menghasilkan kendaraan roda dua atau sepeda tanpa pedal yang disebut Laufmaschine.
Hampir semua komponen Laufmaschine terbuat dari kayu. Cara mengendarainya sangat sederhana, yakni dengan mendorong tanah menggunakan kaki. Dorongan kaki itulah yang membuat roda-roda sepeda berputar. Nenek moyang sepeda yang diluncurkan pada 1817 itu selanjutnya populer dengan sebutan Draisienne atau hobby horse.
Sementara menurut Dana Duclo dalam “History of the Bicycle” (2012:4), pada 1865 roda depan Draisienne diberi tambahan pedal dan engkol, sedang rangka dan rodanya diganti besi. Roda yang terbuat dari besi membuat pengguna sepeda generasi ini terguncang tiap melewati jalan berbatu, sehingga kendaraan tersebut dijuluki boneshaker alias “pengguncang tulang”.
Boneshaker ditinggalkan setelah sepeda generasi berikutnya yakni Penny-Farthing ditemukan. Penny-Farthing memiliki roda depan yang lebih besar dibanding roda belakangnya, juga pedal yang bersambung dengan poros roda depan. Meski bisa meningkatkan kecepatan, roda depan yang besar membuat penggunanya kesulitan untuk naik dan turun.
Pada 1885, John Starley dari Inggris mengubah desain Penny-Farthing dengan menyamakan ukuran roda depan dan belakang serta menggunakan karet pejal sebagai pelapisnya. Ia juga menempatkan pedal di bawah sadel dan mengaitkannya dengan rantai ke roda belakang.
Berkat desain sepeda buatan Starley, yang kemudian dilengkapi ban udara (pneumatic tire) temuan John Dunlop dari Skotlandia, sepeda makin diminati. Sepeda generasi inilah yang selanjutnya diproduksi secara massal dan booming, bukan hanya di Eropa tapi juga di belahan bumi lain, termasuk Hindia Belanda.
Meski popularitas sepeda di Hindia Belanda diawali dengan merek-merek asal Eropa, salah satu komponen pentingnya sangat bergantung pada komoditas perkebunan yang menjadi produk andalan Hindia Belanda, yakni karet yang merupakan bahan baku pembuatan ban.
Menurut M. C. Ricklefs dalam A History of Modern Indonesia since c.120” (2001:194-195), pada abad ke-20 karet memang komoditas yang menempatkan Hindia Belanda di garis depan kepentingan ekonomi dunia. Pada 1930, sekira 44 persen luas perkebunan Hindia Belanda ditanami karet dan memasok hampir separuh kebutuhan karet dunia.
Yogyakarta Kota Sepeda
Sebagaimana di kota-kota besar lain di Hindia Belanda, jalanan di Yogyakarta mulai dilalui sepeda ketika orang-orang Belanda yang banyak bermukim di kawasan Loji Kecil dan Kotabaru menjadikan kendaraan tersebut sebagai alat transportasi sehari-hari.
Menurut Puji Rahayu dalam “Romantisme Kereta Angin (Sepeda Onthel) di Yogyakarta Tahun 1970an” (2020:26), warga Eropa yang menempati permukiman itu membawa serta budaya mereka, salah satunya sepeda, yang dalam perkembangannya memberikan pengaruh terhadap masyarakat bumiputra.
Masyarakat Yogyakarta lebih mengenal sepeda dengan istilah pit, serapan dari bahasa Belanda fiets. Pada 1930-an, sepeda tergolong barang mewah, sebab itu tidak sembarang orang memilikinya. Sepeda berjenama Gazelle (Belanda), Simplex (Prancis), dan Raleigh (Inggris) dijual dengan harga setara satu ons emas murni atau tiga ton beras.
Sepeda-sepeda impor dipasarkan di Yogyakarta di sejumlah toko, di antaranya Wiriosoeseno, HWA, dan Sien Hok Hien. Selain di tiga toko tersebut, juga di beberapa toko lain yang lebih kecil. Sebagian besar toko-toko sepeda itu dimiliki oleh saudagar keturunan Tionghoa.
Pada 1950-an, sepeda makin banyak terlihat di jalan-jalan Yogyakarta, terlebih setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta membagikan 1.000 unit sepeda kepada para pegawai pemerintah di Yogyakarta pada 1952. Dari 1.000 sepeda tersebut, 600 unit diberikan pada pegawai yang sering melakukan perjalanan dinas (tourne), sedang sisanya untuk pegawai yang membutuhkan meski tidak untuk keperluan dinas.
Sepeda-sepeda itu tidak diberikan secara gratis. Para penerimanya diharuskan membayar dengan cara kredit melalui mekanisme potong gaji. Alasan di balik kebijakan tersebut tidak lain untuk memperlancar kegiatan operasional pemerintahan, khususnya bagi pegawai yang kerap melakukan perjalanan dinas.
Seiring waktu, sepeda bukan lagi barang eksklusif, sebab kalangan yang menggunakannya makin luas dan beragam, termasuk pedagang dan petani. Khusus untuk pedagang dan petani, sepeda yang digunakan bukan buatan pabrik, tapi rakitan. Sepeda rakitan mereka pilih karena selain lebih murah juga lebih bisa diandalkan untuk mengangkut barang.
Memasuki dekade 1970, sepeda yang mengaspal di jalan-jalan Yogyakarta makin banyak. Pada 1972 jumlahnya mencapai 165.640 unit. Hingga 1978, jumlahnya menunjukkan tren yang terus meningkat, yaitu 175.136 unit (1973), 227.482 unit (1975), dan 251.663 unit (1978). Memasuki tahun 1980, Yogyakarta kehilangan predikatnya sebagai Kota Sepeda karena kendaraan bermotor mulai marak.
Penulis: Firdaus Agung
Editor: Irfan Teguh Pribadi