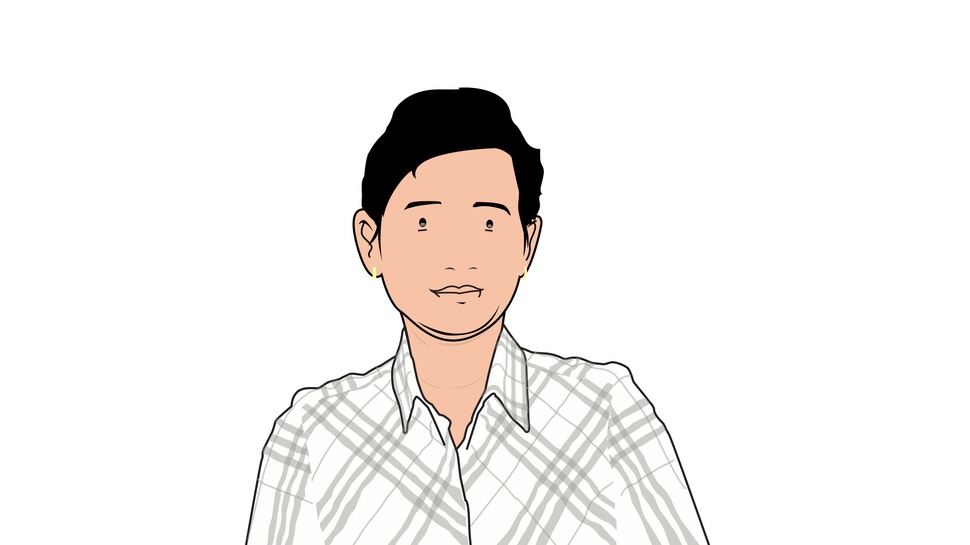tirto.id - Dua pekan lalu, media massa dan media sosial penuh bertabur nama Saeni, 53 tahun, seorang ibu pemilik warung tegal, yang terkena razia Satpol PP Serang, Banten. Ia dikatakan menyalahi Perda Kota Serang No 2 Tahun 2010 yang melarang warung makan buka pada siang di bulan Ramadhan.
Di layar televisi, saya menyaksikan raut wajah Saeni yang tampak memelas dan kebingungan ketika serombongan petugas Satpol PP, lebih dari tujuh orang, menerobos masuk ke warungnya. Airmatanya runtuh. Petugas berseragam itu berwajah dingin, tak hirau dengan lolongan Saeni. Piring dan kuali berisi sayur dan lauk tak luput dijamah, dituang ke kantong plastik dan diangkut pergi. Dua piring dengan sisa-sisa nasi teronggok di atas meja ditinggalkan penyantapnya yang terbirit lari ketika datang razia. Tinggallah Saeni meratap. Modal sebesar 600 ribu untuk memasak hari itu pun amblas.
Di Bogor, 13 orang dibawa petugas ke kantor kecamatan karena kedapatan makan siang saat puasa. Mereka diberi pengarahan dan dihukum push up. Di Padang, seorang petugas Satpol PP memperlihatkan serenteng ikan bakar yang telah matang, barang bukti penyitaan dari sebuah warung yang dirazia.
Saya nyaris tersedak ketika membaca komentar Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah: “Kita melakukan razia ini untuk menjaga kekhusyukan umat muslim berpuasa. Jika terus dibiarkan dan tidak diambil ikan bakarnya, bisa-bisa bau ikan itu menyebar dan merusak puasa para umat muslim di Kota Padang ini,” ujarnya di hadapan wartawan. (Harian Haluan, 14 Juni 2016).
Parade razia tersebut terjadi di minggu-minggu pertama bulan puasa. Bagi umat Islam, Ramadhan adalah bulan penuh berkah dan ampunan. Pengendalian diri adalah esensi puasa, tentu tak hanya urusan makan minum dan syahwat, tetapi juga mengendalikan segala pikiran, tuturan serta perilaku. Kita diajak untuk kembali ke dalam diri kita, agar semakin terlatih mendengar dan merasakan suara batin sendiri, yang kemudian menjadi pintu untuk mempertebal iman, dan solidaritas kemanusiaan.
Saya yakin di kepala Saeni, berasal dari Tegal dan telah belasan tahun merantau di Serang, tak sedikitpun terlintas pikiran untuk tidak menghormati orang yang berpuasa. Pikirannya sederhana saja: bekerja dan bekerja untuk melanjutkan hidup. Berdagang adalah kerja yang ia bisa, untuk menyekolahkan anaknya.
Beberapa hari kemudian, di layar televisi, sambil menunduk takzim Saeni mengucap maaf untuk perbuatan melanggar perda. Saeni tentu tak tahu menahu kenapa harus dibuat perda, padahal berbelas tahun ia berjualan ketika bulan Puasa, ia dan warung-warung lainnya telah menutup tirai dan semua baik-baik saja. Ia meminta maaf saja, karena telah membuat kehebohan sehingga presiden pun turun tangan. Ia bahkan lebih berjiwa besar dibanding pemimpinnya, yang kini latah membuat berbagai aturan untuk mengatur perilaku penduduknya, sementara abai mengurus amanat utama: menyejahterakan rakyat.
Serombongan anak muda melompat dengan iniasitif cepat. "Saya terpikir membantu hanya karena tidak tega melihat si ibu bersedih akibat jualannya disita," kata Dwika Putra, netizen yang aktif di media sosial, lalu berinisiatif menggalang dana untuk membantu Saeni. Solidaritas menjalar cepat. Dalam jangka waktu 36 jam total terkumpul dana Rp 265.534.758, sumbangan dari 2.427 netizen. Sebagian besar diserahkan pada Saeni, sebagian yang lain dibagikan kepada pada pedagang yang mengalami nasib serupa.
Hati saya dijalari rasa hangat menyaksikan ujung drama ini. Kewarasan dan kemanusiaan kita ternyata tidak benar-benar kandas. Kendati, setelah itu ada saja yang usil mempertanyakan: kenapa malah membela orang yang melawan Perda? Kenapa bersolidaritas pada orang yang tidak menghormati orang yang berpuasa? Diimbuhi dengan drama-drama lainnya, tuduhan bahwa bahwa Saeni tak semiskin yang diperkirakan, dan seterusnya dan seterusnya. Seperti biasa, kita lebih sibuk mengkritisi dan menghakimi kerja orang lain, sementara kita sendiri tak berbuat apa-apa.
Benarkah warung Saeni menampar puasa kita? Saya terkenang momen puasa di masa kecil. Puasa adalah sebuah keriaan bersama: ramai-ramai sholat tarawih di masjid dan berebut kudapan takjil. Menjelang sahur, tengah malam serombongan anak muda menabuh kentongan berjalan ke setiap gang dan memainkan irama merdu, tidak asal teriak hingar bingar seperti sekarang. Lebaran, seisi kampung kuyup diguyur kehangatan. Saling hantar makanan, saling kunjung ke tetangga dan sanak saudara, yang bukan muslim pun tak terlewatkan. Lebaran menjelma menjadi ritual bersama untuk mempererat persaudaraan. Toleransi dan saling menghormati sudah lama hidup dan berakar dalam tanah yang kita pijak. Saat itu, saya pun tak tahu dan tak hirau bahwa ada sekat-sekat pembeda: Syiah, Sunni, Ahmadiyah, seperti yang kini selalu diributkan.
Beberapa tahun belakangan ini, kita disuguhi keributan serupa: warung buka dan tidak ketika bulan puasa? Bulan suci penuh berkah direduksi menjadi sebatas urusan syahwat dan tenggorokan. Bangsa yang telah 70 tahun merdeka, yang sejak pendiriannya para founding fathers dari beragam latar belakang politik, suku dan agama telah berdialog sangat panjang dan alot untuk menemukan rumusan negara berbhineka, tiba-tiba harus meributkan aneka simbol dan luput mencerna esensi puasa untuk mempertebal kepekaan sosial dan spirit kebangsaan.
"Keheningan adalah akar segala sesuatu. Jika kau memasuki pusarannya, ribuan suara akan kau dengar bergemuruh di dalam jiwa", kata sufi Jalaluddin Rumi. Hening dan refleksi diri tentu memerlukan latihan yang keras dan tekun. Kita selalu ingin berkata sebanyak-banyaknya sehingga lupa mendengarkan pihak lain. Kita susah menahan diri untuk tidak menyebarkan fitnah dan berita bohong di sosial media, hingga luput menggunakan akal sehat.
Saeni menampar puasa kita. Peristiwa penutupan warungnya, dan kejadian serupa lainnya telah membuat kita terhenyak. Ia mengajak kita untuk bertanya pada diri, seberapa dalam menangkap makna puasa. Ia mencolek hati kita untuk kembali pada diri dan haribaan cinta dan kemanusiaan itu sendiri.
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.