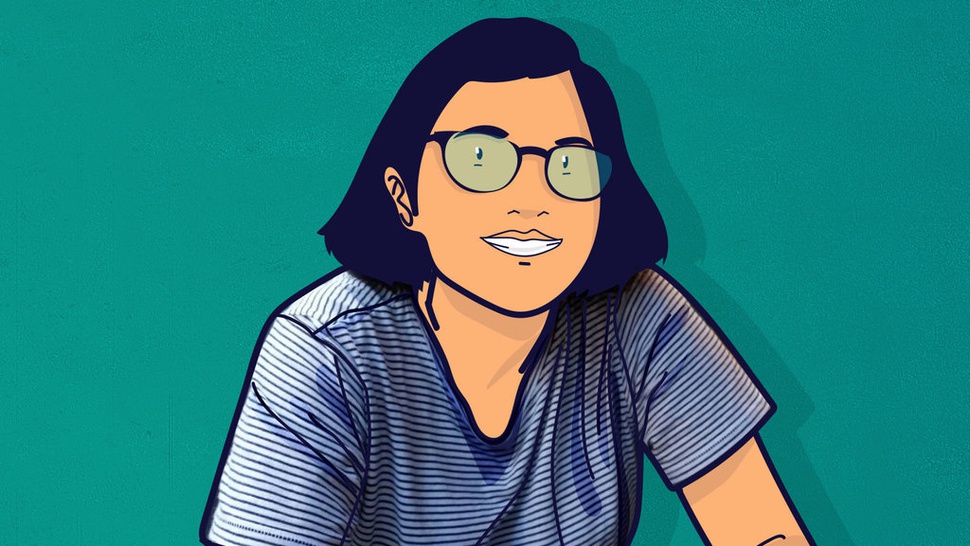tirto.id - Penggemar film laga pasti familiar dengan adegan penyiksaan. Misalnya, di film Casino Royale terdapat adegan di mana James Bond (si protagonis, diperankan oleh Daniel Craig) ditelanjangi, disekap di sebuah ruang gelap, diikat di sebuah kursi yang alas duduknya sengaja dilubangi, dan diinterogasi sembari dicambuk oleh musuhnya, Le Chiffre (sang antagonis, diperankan Mads Mikkelsen).
Adegan tersebut pasti melahirkan reaksi beragam. Barangkali, ada orang-orang yang merasa bahwa Bond tidak pantas mendapatkan perlakuan merendahkan martabat tersebut. Mungkin, ada pula kelompok yang mendapatkan kepuasan karena merasa penyiksaan oleh Le Chiffre adalah karma buruk atas kesewenang-wenangan Bond selama ini. Boleh jadi, ada juga orang-orang yang tidak merasakan apa-apa.
Tidak ada sambutan yang salah. Kita sama-sama mafhum bahwa adegan tersebut hanyalah bagian kecil dari sebuah karya seni. Alhasil, reaksi yang ditimbulkan merupakan sensasi yang harus ditempatkan secara spesifik ke dalam konteks penikmatan produk artistik. Artinya, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa orang-orang yang menolak penyiksaan Bond benar-benar menentang perlakuan tersebut di dunia nyata. Sebaliknya, kita tidak dapat beranggapan bahwa kelompok yang setuju Bond disiksa akan mendukung praktik tersebut di keseharian.
Namun demikian, saya yakin bahwa kebanyakan orang tidak mendukung penyiksaan. Apa lagi saat praktik tersebut keluar dari layar kaca atau kreasi imajinatif lainnya dan terjadi di kenyataan. Penyiksaan adalah tindak kekerasan yang tidak bermoral, merendahkan martabat, dan mengganggu hati nurani sehingga wajib ditolak dalam situasi apa pun, kapan pun, dan saat menimpa siapa pun.
Sayangnya, saya rasa belum semua orang percaya akan hal itu. Masih terdapat kelompok yang mewajarkan dan melakukan penyiksaan. Contohnya, aparat penegak hukum Republik Indonesia.
Praktik Penyiksaan di Indonesia Setahun Terakhir
Selama Juni 2021 sampai Mei 2022, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat ada setidaknya 50 kasus penyiksaan, perlakuan, atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia di Indonesia.
Laporan terbaru KontraS menunjukkan bahwa aparat Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menempati urutan pertama terduga pelaku penyiksaan dengan jumlah 31 kasus, disusul oleh anggota Tentara Nasional Republik Indonesia (TNI) dengan 13 kasus, dan sipir tempat-tempat penahanan sebanyak enam kasus.
Praktik penyiksaan yang meliputi pemukulan, penendangan, penyetruman, sampai penembakan terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Tercatat paling sedikit delapan kasus penyiksaan terjadi di Sumatera Utara, tujuh kasus di Papua, lima kasus di Jawa Barat, dan 32 kasus tersisa di daerah-daerah lain. Sekurang-kurangnya, 32 kasus penyiksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan dan 18 kasus sebagai metode penghukuman. Secara keseluruhan, terdapat paling sedikit 144 korban, dengan perincian 126 korban luka dan 18 kematian.
Namun, kita perlu menempatkan temuan KontraS dengan skeptis. Pasalnya, jumlah dugaan kasus penyiksaan yang dilaporkan KontraS hanya berlandaskan pada sumber yang dapat dibuktikan, seperti pengaduan langsung, pemberitaan di media massa, dan data dari jejaring. Barangkali, terdapat kasus-kasus lain yang tidak dilaporkan dan luput dari perhatian publik. Walhasil, bisa saja kasus penyiksaan yang sebenarnya terjadi lebih banyak dari data yang KontraS miliki.
Kejahatan yang Mengusik Nurani
Terlepas dari berapa jumlah kasus yang akurat, penyiksaan adalah kejahatan yang mengusik nurani manusia. Berbagai putusan di beragam peradilan internasional menyebutkan bahwa hak untuk bebas dari ancaman dan tindakan penyiksaan bersifat mutlak. Artinya, tidak ada landasan yang sah untuk tak mencegah dan menghentikan praktik ini, melakukan pencarian fakta, mengadili terduga pelaku, memastikan ketidakberulangan, dan memulihkan hak-hak korban dan orang-orang terdekatnya. Satu kasus sudah terlalu banyak, apa lagi 50 atau lebih.
Aneka ragam peradilan internasional pun memutuskan bahwa terduga pelaku pelanggaran hak untuk bebas dari ancaman dan tindakan penyiksaan di manapun, dapat diadili di mana saja. Misalnya, seorang terduga pelaku penyiksaan berkebangsaan Indonesia dapat diadili di Turki jika Indonesia tidak mampu atau enggan menuntutnya. Hal ini menunjukkan besarnya keseriusan komunitas dunia dalam mengelompokkan penyiksaan sebagai kejahatan yang tidak bermoral dan mengusik nurani.
Indonesia sejatinya sepakat dengan norma tersebut. Buktinya dapat dilihat dari kerelaan pemerintah mengadopsi berbagai standar-standar anti-penyiksaan internasional, seperti ratifikasi Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (CAT) pada 28 Oktober 1998.
CAT menyatakan, “Tiada ada keadaan pengecualian apapun, apakah keadaan perang atau ancaman perang, ketidakstabilan politik dalam negeri ataupun keadaan darurat, yang dapat digunakan sebagai pembenaran untuk penyiksaan.”
Berbagai undang-undang dan peraturan dalam negeri pun gamblang menolak penyiksaan. Contohnya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menjamin bahwa setiap orang “berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.” UU HAM bahkan mengklasifikasi penyiksaan sebagai pelanggaran HAM berat, bersama dengan genosida, penghilangan paksa, pembudakan, dan lain-lain.
Saatnya Tampilkan Adegan Perbaikan
Sayangnya, meski terdapat berbagai aturan yang melindungi hak untuk bebas dari ancaman dan tindakan penyiksaan, penerapan di lapangan masih mengecewakan. Di periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo saja, KontraS mencatat setidaknya 264 dugaan kasus penyiksaan; 72 kasus sepanjang 2018 sampai 2019, 62 kasus di antara 2019 dan 2020, 80 kasus di 2020 sampai 2021, dan 50 kasus setahun ke belakang.
Saya yakin Presiden Joko Widodo sependapat dengan saya dan banyak orang lainnya bahwa penyiksaan adalah tindak kekerasan yang tidak bermoral, merendahkan martabat, dan mengganggu hati nurani. Sehingga, saya pun percaya bahwa Presiden Joko Widodo sepakat untuk membatasi ruang gerak terduga pelaku penyiksaan.
Presiden Joko Widodo dapat memulai dengan mendesak aparat penegak hukum melakukan investigasi atas semua dugaan, mengadili para terduga pelaku melalui proses peradilan yang transparan, memastikan perlindungan terhadap saksi dan korban, serta memberikan ganti rugi kepada korban dan orang-orang terdekat mereka.
Secara bersamaan, perbaikan Polri, TNI, dan penegak hukum lainnya dapat dilakukan. Mereka dapat membuka diri terhadap mekanisme pengawasan eksternal yang independen sembari membuat dan menerapkan peraturan yang mewajibkan pemasangan dan penggunaan perlengkapan yang dapat mengawasi perilaku anggotanya, seperti kamera tubuh atau kamera sirkuit tertutup (CCTV) di tempat-tempat yang rawan praktik penyiksaan.
Jangan ikuti film-film James Bond yang tidak pernah mempertontonkan adegan pertanggungjawaban negara atas kasus penyiksaan. Presiden Joko Widodo wajib menunjukkan langkah-langkah menolak kekerasan dan merawat kebebasan dengan konkrit. Ini dunia nyata, bukan produk fiksi!
*) Opini kolumnis ini adalah tanggungjawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi tirto.id.
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.