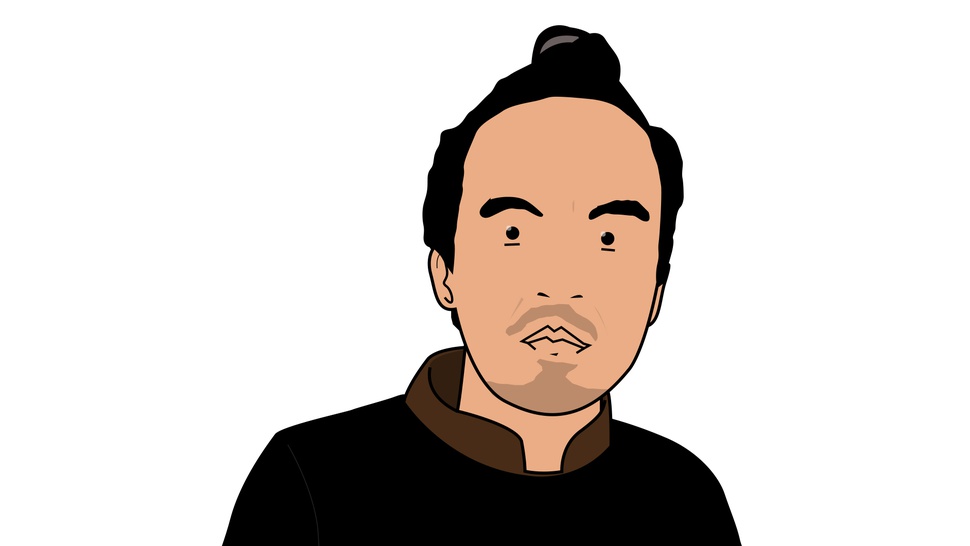tirto.id - Mari mundur ke bulan Mei. Bukan untuk mengenang Mas Wiranto yang saat ini dengan tenang dan datar menjadi "puncak" penata-teknis semua urusan politik di RI di bulan Mei, di tahun "kejatuhan" Harto. Tetapi hanya kembali 60 hari ke belakang saat hantu pelarangan buku dan pelarangan ini-itu melakukan opera terbuka.
Sumbu opera itu dinyalakan dari Medan Merdeka Barat, dari Gedung Kementerian Pertahan. Tatkala tarian gempita para laskar menyambut sumbu api itu, terdengar suara "kompak" dari Istana Merdeka yang mendukung sepenuh pikiran opera pembersihan (kembali) buku kiri. Dalam satu tarikan napas, sikap dari Sekretariat Kabinet yang dipimpin pejabat teras dari PDIP yang terus-menerus mengglorifikasi Sukarno itu langsung mendapat dukungan dari Kepolisian Republik Indonesia.
Sebuah persekutuan sempurna. Kita melihat Presiden Jokowi seperti bukan lagi manusia "lugu", "ndeso" yang dikira di mana saat kedatangannya sebarisan para penyintas menitipkan harapan "perbaikan nasib" HAM di Indonesia kepadanya. Bahkan, dengan suara yang pasti si Presiden dengan kekuasaan besarnya ingin mencari ikon aktivis 1998 yang (di_hilang(kan) lewat operasi intelijen militer. Lupakan. Bahkan tak ada drama reshuffle di hari Kudatuli itu pun, para pegiat dan pejuang HAM mesti melupakan janji-janji menyebalkan itu.
Sekali lagi, persekutuan itu nyaris saja sempurna, bukan saja dalam satu tali komando pikiran, melainkan juga ditunggu para laskar untuk menjadi dalih bergerak di lapangan mengganyang apa yang disebut "produsen literatur Kiri" oleh pimpinan mereka yang terkoneksi dengan Medan Merdeka Barat. Saya sebut nyaris karena tanpa diduga sama sekali, elemen yang selama ini selalu memberikan dukungan penuh kepada upaya pengganyangan "literatur Kiri" di Indonesia, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, rupanya bersuara lain.
Pernyataan yang keluar dari gedung yang bercokol di Senayan Jakarta itu memang normatif dan itu sudah cukup sebunyi-sebenang dengan yang disuarakan elemen sosial pembela kebebasan berpendapat, pegiat HAM, pekerja literatur, aktivis literasi.
Suara dari Senayan itu keluar saat para polisi yang diboncengi para "laskar-binaan" bersiap memasuki kamar-kamar penerbit dan toko buku, memeriksa barang cetak, dan menyitanya. Daftar nama dan alamat sudah dikantongi intelijen. Satu langkah kaki sudah di pintu-pintu produsen literatur. Dan kemudian kaki itu pun tertahan. Semua rencana aksi itu menjadi berantakan.
Anies Baswedan, menteri yang pikirannya waras itu, kata-kata yang dikeluarkannya untuk "melawan" koleganya yang barangkali sejak lahir sudah disuntik oleh gen "anti hantu kiri", menaikkan moral para pembela literatur dan pegiat literasi nasional. Di saat Kepala Perpustakaan Nasional RI, dengan bahasa Indonesia yang buruk, mengambil posisi lebih baik mengkhianati buku ketimbang pembela literatur dan perpustakaan itu, Anies Baswedan tampil ke depan. Dengan bahasa Indonesia yang tertata mengucapkan kembali kata-kata sederhana itu: "Negara tak punya landasan hukum melakukan pelarangan menulis buku atau ide tertentu. Seburuk apa pun ide itu. Inilah zaman saat perlombaan ide menjadi niscaya".
Anies Baswedan di saat persekutuan setan-buku dalam tubuh-negara itu nyaris bulat mencoba mengingatkan hukum dan sekaligus situasi bagaimana mestinya bersikap pada pikiran di zaman yang terbuka.
Mungkin Anies mengambil langkah yang berseberangan itu Anda anggap sebagai watak oportunistiknya mengambil "simpati" untuk "digunakan suatu hari kelak" ketika militer-militer yang tak pernah menang dalam perang ini memakai kewenangannya bermain-main di ruang sosial warga yang kompleks. Namun, dalam pengap penyelesaian HAM serta isu "tak sedap" dari Den Haag, Anies datang sebagai "penguasa" di bidang pendidikan dan kebudayaan mengingatkan kembali marwah reformasi: kebebasan berpendapat itu direbut dari watak militerisme; ia bukan pemberian gratis dari juragan akun-akun gratis media sosial. Apalagi pemberian dari orang-orang macam pedagang-bersenjata semacam Luhut Pandjaitan, pemberi hadiah DOM terakhir kepada Aceh Ryamizard Ryacudu, dan pembantu dekat "Pak Harto", Wiranto.
Penolakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dipimpin Anies Baswedan itu membuat Sekretaris Kabinet yang sekaligus pejabat teras PDI-P itu melunak lagi. Setelah suara dari Anies Baswedan itu bergema, lahirlah perintah telegram dari Kapolri untuk menghentikan semua aksi kekerasan literatur di semua tingkatan.
Teman saya, Bilven Sandalista, dan ribuan pekerja buku lainnya yang terkait dengan literatur yang disebut "kiri kekomunis-komunisan" itu bisa bernapas lega. Ultimus Bandung tak lagi ketakutan saat pintu pagar rumah kontrakan mereka berderit karena kedatangan tamu.
Anies Baswedan, tanpa berusaha melebih-lebihkannya, adalah sosok yang tampil meneguhkan keragaman bacaan warga dipertahankan untuk kepentingan pendidikan dan pengayaan pengetahuan. Selain itu, suaranya yang notabene suara-pemerintah-yang-bersuara-lain dalam membela marwah literatur dari sentuhan bedil dan api pemberangusan, menenangkan para produsen buku, terutama penulis, penerbit, percetakan, dan toko buku. Literatur pun kembali hening, kembali tenang, memikirkan kembali barang dagangan dan memeriksa neraca pembukuannya setelah tercekam dalam suasana was-was.
Sementara itu, keputusan Kemendikbud yang menolak "program bodoh" dari Kementerian Pertahanan dan Sekretariat Kabinet soal "literatur kiri" itu masih satu napas dengan "program kecil" yang sudah dilakukan pemerintah di ruang kelas sekolah: membaca buku non-pelajaran 15 menit sebelum kegiatan belajar kelas dimulai. Pesannya jelas: kenali sesuatu dengan membaca isinya. Hadapi buku dengan hati, buka buku dengan hati, dan buku akan membuka dirinya kepadamu. Kebencian dan amarah hanya memadamkan peradaban.
Dan kita melihat kenyataannya sekarang pasca peringatan satu dekade Kudatuli. Anies Baswedan diberhentikan dari Kemendikbud karena dianggap "tidak kompeten" dan rapor prestasinya buruk oleh Presiden RI. Praktis, Anies hanya efektif menjalankan tugasnya 20 purnama. Posisinya memberikan pembelaan pada literatur di saat mesti berhadapan dengan rekan sejawatnya dari Kementerian Pertahanan sudah lebih dari cukup untuk diingat para pegiat literatur dan aktivis literasi.
Sementara di ruang lain, klise negatif Republik menunjukkan potret yang tak berubah dan bahkan makin kukuh: persekutuan anti-literatur (kiri) makin kukuh, sementara Sukarnois makin “tenang” di Istana. Apalagi ditambah dengan masuknya Wiranto. Kelar dah!
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.