tirto.id - Wajah Riyad Mahrez terlihat sangat tegang. Keringatnya mengucur deras dan tatapan matanya hanya fokus ke depan. Ia tengah bersiap-siap mengambil tendangan bebas. Menit menunjukkan angka 94. Pertandingan hampir selesai. Ini menjadi peluang terakhir Aljazair untuk menang atas Nigeria, atau mereka mesti menunggu 30 menit lagi dalam babak perpanjangan waktu.
Namun, Mahrez berhasil menuntaskan tugasnya. Tendangan bebasnya berbuah gol kemenangan. Ia langsung berlari, berteriak, dan tak mampu menyembunyikan air mata kegembiraannya. Aljazair menginjakkan kakinya di final dan akan bertarung menghadapi Senegal pada Jumat esok (19/7).
Lolosnya Aljazair ke final sontak disambut suka cita. Orang-orang berhamburan di jalan untuk menyanyi dan meluapkan keriaannya. Di Perancis, parade kemenangan ini bahkan berujung penangkapan besar-besaran oleh aparat keamanan. Sekitar 282 orang diciduk karena dianggap bikin ribut maupun kerusakan.
Bagi masyarakat Aljazair, sepakbola bukan sekadar olahraga yang dimainkan 22 orang. Lebih dari itu: ia adalah peluru perlawanan dan simbol pembebasan.
Beberapa bulan silam, antara Februari sampai April, puluhan ribu orang yang didominasi anak-anak muda melakukan aksi protes di seantero Aljazair. Tujuannya cuma satu: meminta Abdelaziz Bouteflika, yang sudah menjabat presiden selama dua dekade, untuk turun takhta.
Poster berisikan tuntutan perbaikan hidup—dibalut dengan sarkasme sekaligus humor—seperti merangkum kekecewaan yang dirasakan sebagian besar masyarakat Aljazair terhadap pemerintahan Bouteflika yang makin ke sini makin korup, gagal menyediakan lapangan pekerjaan, dan bertindak otoriter.
Aksi protes masyarakat tak jarang dibalas dengan perlakuan represif dari aparat. Bayangan Aljazair bakal kembali berdarah saat perang sipil meletus pada era 1990-an, yang melibatkan tentara dan kelompok Islamis serta menyebabkan 200 ribu orang tewas, pun berkeliaran di kepala.
“Kami tidak takut lagi,” kata Amina Djouhadi, mahasiswa ilmu politik berusia 22 tahun, kepada BBC. “Kami masih muda dan penuh keberanian.”
Bouteflika merupakan veteran perang yang pernah bergabung dengan barisan tentara dalam upaya melawan kekuatan kolonial Perancis. Sebelum duduk di kursi presiden, Bouteflika sempat jadi Menteri Luar Negeri di kabinet Houari Boumediene, yang berkuasa setelah mengkudeta Ben Bella dan kemudian memerintah secara diktator. Rezimnya lantas kolaps akibat tekanan ekonomi.
Pada 1999, Bouteflika terpilih sebagai presiden. Empat kali terpilih, catat Farah Souames dalam “Algeria’s Bloodless Coup,” rupanya tak cukup bagi Bouteflika. Ia ingin terus berkuasa, apa pun caranya, termasuk dengan mengubah konstitusi dan memanipulasi peraturan.
Seiring berjalannya waktu, kesehatannya memburuk. Kondisi ini membikin ia tak bisa memerintah dengan baik. Walhasil, serangkaian kebijakan pemerintah banyak dipegang oleh elite militer, pengusaha, dan para oligark politik yang berdiri di belakang Bouteflika. Mereka disebut sebagai “Le Pouvoir.”
Segala kekacauan inilah yang mendorong lahirnya protes, tak terkecuali dari lapangan sepakbola Aljazair yang resonansi penolakannya paling nyaring terdengar.
Di sepakbola, lapor Al Jazeera, protes diinisiasi oleh para pendukung dari dua klub besar Aljazair, MC Alger (MCA) dan USM Alger (USMA). Masing-masing pendukung klub berandil besar dalam memompa api perlawanan yang menjalar di jalanan Aljazair melalui chant (nyanyian).
Para pendukung USMA yang tergabung dalam Ouled El Bahdja, misalnya, menulis lagu berjudul “La Casa de Mouradia.” Lagu ini terinspirasi dari series Spanyol yang tayang di Netflix, La Casa de Papel (Money Heist). Oleh mereka, bagian “de Papel” diganti dengan “de Mouradia”, merujuk pada nama istana kepresidenan Aljazair. Begini bunyi liriknya:
“In the first [term], they tricked us with ‘reconciliation’,
In the second [term] it became clear: 'La Casa del Mouradia',
In the third [term] the country suffered due to personal interests,
In the fourth [term] the puppet died and the problem remains."
Sementara pendukung MCA, Torino, membikin video protes berjudul “3am Said” (“Happy New Year”) yang mengkritik sistem peradilan Aljazair di bawah rezim Bouteflika. Tak hanya itu saja, mereka juga membuat chant berjudul “Fi Sog Elil” (“The Night Market”).
"Ask me why? I'll tell you to look underneath you,
There are people who have lunch but not dinner,
Ask me how? I'll tell you it's just like this,
The authorities have left nothing,
Ask me since when? I'll tell you for a while,
In fact, I don't even remember,
None of us have lived a good life..."
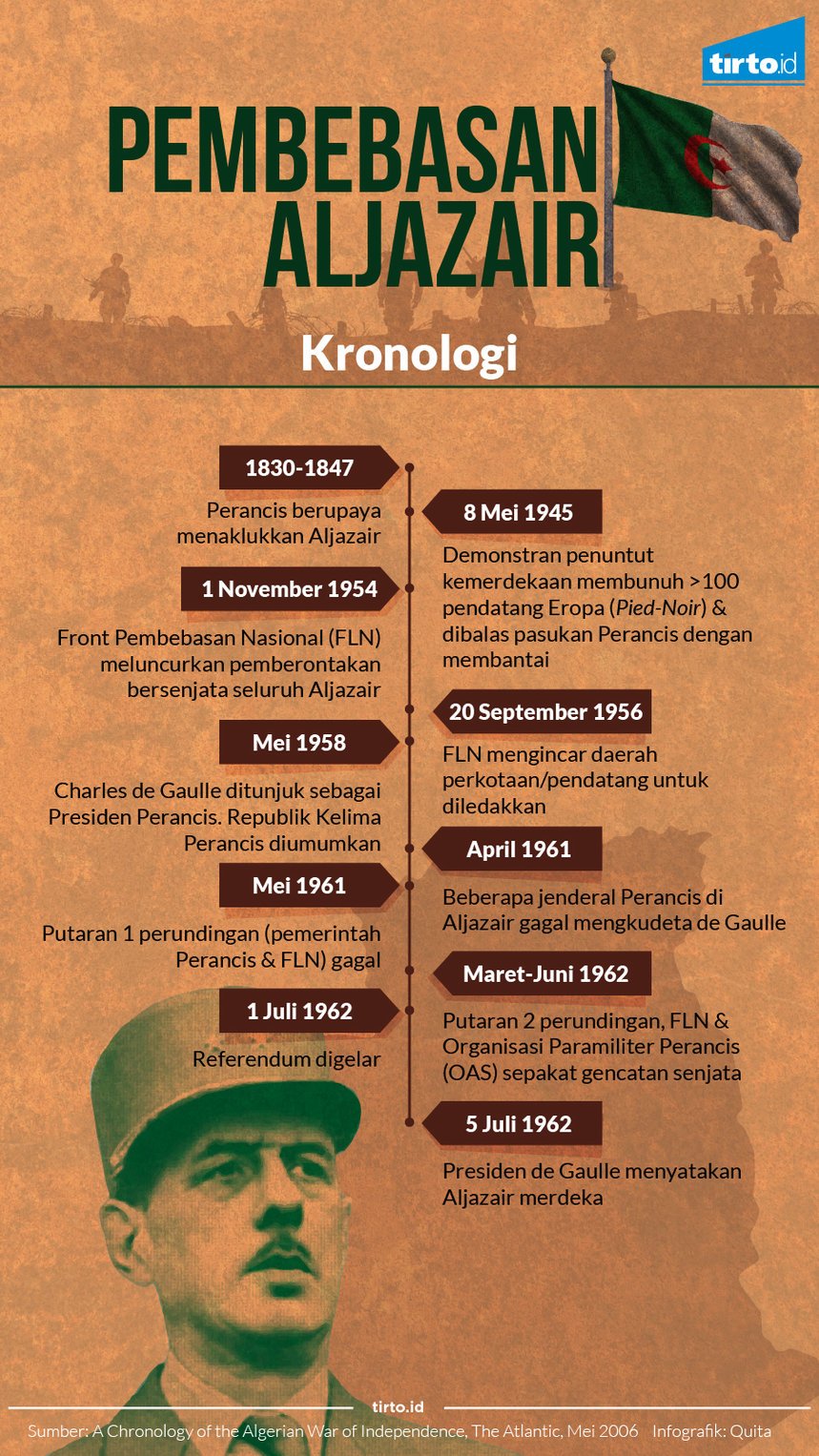
Di Aljazair, sepakbola selalu menyediakan jalan keluar bagi ketegangan. Pada masa kolonial, contohnya, para pendukung bola sering menyanyikan nasyid (lagu-lagu agama) sebagai bentuk penegasan identitas Arab-Muslim mereka. Selepas Aljazair merdeka, suporter menyanyikan chant untuk kebobrokan pemerintah ketika dipimpin Boumediene.
“Sejak kemerdekaan pada 1962, stadion-stadion tersebut telah menjadi ruang untuk memperkuat tuntutan sosial para anak-anak muda,” terang sosiolog dari Universitas Paris Nanterre, Youcef Fates. “Secara historis, klub sepakbola [Aljazair] selalu menjadi tempat untuk menantang pihak berwenang. Mereka memiliki dimensi perlawanan sosial-politik dan perjuangan anti-kolonial.”
Mickaël Correia, penulis Une Histoire Populaire du Football (A Popular History of Football) dalam “The Soccer Fans That Toppled a Government” yang diterbitkan The Nation menerangkan bahwa akar dari gerakan protes suporter di Aljazar bisa ditarik ke kultur ultras yang tumbuh subur di Italia pada dekade 1960-an.
Di Italia, ultras merupakan suporter garis keras yang cenderung politis dan radikal. Mereka menjadikan sepakbola tak sebatas hiburan, melainkan juga suar perlawanan. Spanduk, koreografi, hingga chant yang mereka bikin merepresentasikan sisi politis tersebut. mereka banyak terinspirasi oleh strategi dan taktik yang dipraktikkan organisasi sayap kiri macam Red Brigade maupun Tupamaros di Uruguay.
Pengaruh ultras, catat Correia, baru singgah di Afrika Utara pada warsa 2000-an, bersamaan dengan masifnya penggunaan internet dan media sosial. Kelompok yang muncul pertama kali ialah Ultras L’Emkachkhines (Multicolored Ultras), pendukung Espérance Sportive de Tunis, klub asal Tunisia, yang berdiri pada 2002. Dari Tunisia, kultur ultras lalu menyebar sampai Maroko, Aljazair, dan Mesir.
Karena geraknya yang radikal, kelompok ultras di Afrika Utara seringkali menghadapi perlawanan dari negara. Mereka dianggap sebagai sumber masalah dan ancaman untuk stabilitas pemerintah. Maka, gerak ultras pun dipersempit lewat penangkapan sewenang-wenang dan pembubaran.
Tapi, gelora perlawanan ultras tetap membara. Pada 2011, ketika Arab Spring meletus di beberapa negara, ultras berdiri di garda terdepan demonstrasi. Di Mesir, misalnya, ultras dari Al Ahly dan Zamalek bergandengan tangan di Tahrir Square: melawan aparat dan memobilisasi massa dengan chant yang menuntut adanya perubahan.
Budaya ultras, masih mengutip tulisan Correia, sampai juga di Aljazair pada 2007, dengan berdirinya Verde Leone yang mendukung MCA. Eksistensi ultras di Aljazair seketika menarik anak-anak muda yang merasa muak dengan otoritarianisme. Stadion pun jadi ruang berseminya suara-suara protes yang menyasar pemerintahan. Di gelaran final Piala Aljazair pada Mei 2018, misalnya, pendukung klub JSK memprotes pemerintah, aparat hukum dan keamanan, serta perdana menteri saat itu, Ahmed Ouyahia.
Dari lapangan, pengaruh ultras menjalar pula hingga jalanan. Masyarakat Aljazair terkesan dengan militansi ultras kala menggemakan protes secara terorganisir. Mereka bersatu dalam atap yang sama ketika rezim Bouteflika mulai tak bisa lagi diajak berkompromi. Para suporter mengesampingkan sejenak rivalitas yang ada dan menggantinya dengan kolektivitas perlawanan terhadap rezim. Saat derby yang melibatkan USMA dan MCA, ambil contoh, para ultras mengajak untuk memboikot pertandingan dan meminta suporter yang lain turun ke jalan.
“Mari boikot lapangan demi negara dan klub. Kami meminta semua pendukung untuk turun ke jalan yang sama. Mari dukung Aljazair,” begitu isi selebaran pamflet yang menyebar di dalam stadion.
Propaganda mereka cukup efektif. Saat pertandingan dimulai, hanya ada beberapa ratus anggota dari Ouled El Bahdja yang tetap mendukung klub kebanggaannya sembari menyanyikan “La Casa del Mouradia.” Tiga perempat dari kapasitas yang ada, sekitar 80 ribu kursi, kosong. Ini pertama kalinya laga derby tidak mendatangkan penonton dalam jumlah yang banyak.
“Dua warna klub kami, merah dan hijau, melambangkan Islam dan darah para martir. Kami meneruskan sejarah perlawanan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kami berdemonstrasi melawan rezim ini bukan sebagai ultras, tapi sebagai orang Aljazair,” kata Kacem, salah satu anggota ultras Verde Leone.
Upaya masyarakat Aljazair untuk memperoleh pemerintahan—sekaligus kehidupan—yang lebih baik terwujud kala pada awal April lalu Bouteflika mengumumkan pengunduran dirinya sebagai presiden. Rakyat bersorak. Kemenangan ada dalam genggaman sekalipun ini baru permulaan dan prosesnya masih panjang dan berliku.
Lolosnya tim nasional Aljazair ke final Piala Afrika, pada akhirnya, hanyalah kepingan kecil yang melengkapi keriaan masyarakat. Terlepas dari apa pun hasilnya nanti, menang atau kalah, Aljazair tak akan kecewa sebab mereka sudah lebih dulu memperoleh kemenangan dalam skala yang besar.
Editor: Nuran Wibisono












