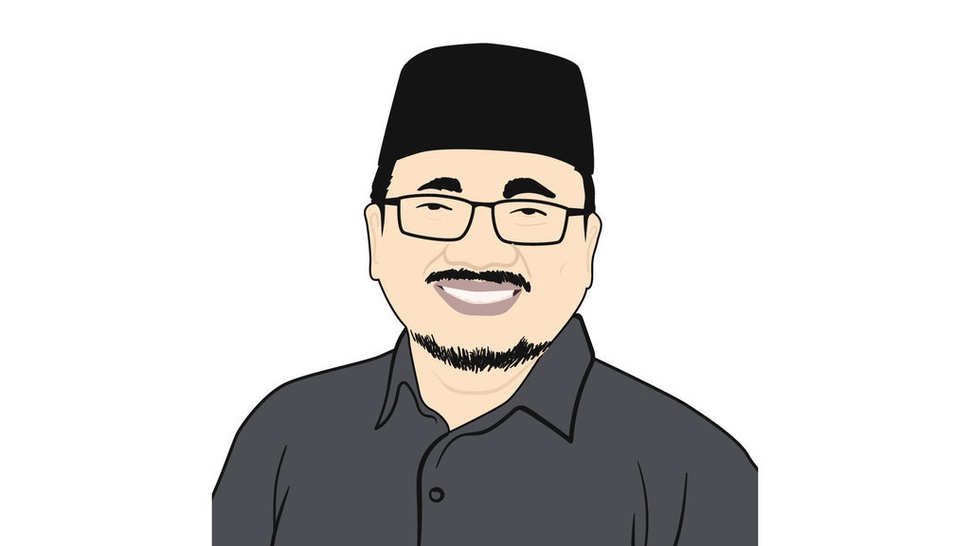tirto.id - Di tengah sebagian besar masyarakat yang berjibaku mengatasi macet untuk mudik ke kampung halaman, Sabtu, (1/6/2019) lalu, mayoritas aparatur sipil negara (ASN) di seluruh nusantara mengikuti upacara Hari Lahir Pancasila.
Melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016, Presiden Jokowi telah menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. Terhitung sejak 2017, 1 Juni adalah hari libur nasional. Di luar perdebatan seputar kapan kelahirannya, Pancasila sudah menjadi pilihan dan kesepakatan para pendiri negara sebagai ideologi dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang majemuk—tentu dengan proses dan perdebatan yang panjang.
Konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kali dikemukakan Sukarnon dalam pidato “Lahirnya Pancasila” di sidang Dokuritsu Junbi Cosakai (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan) pada 1 Juni 1945. Dalam kesempatan itu, Sukarno menyampaikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Pidato yang awalnya tanpa judul ini baru mendapat sebutan "Lahirnya Pancasila" oleh mantan Ketua BPUPKI Dr. Radjiman Wedyodiningrat dalam kata pengantar sebuah buku berisi pidato yang dicetak BPUPKI.
Disepakatinya Pancasila sebagai ideologi dan falsafah hidup bangsa juga diterima Nahdlatul Ulama (NU). Pada Munas Ulama 1982, NU menerima Pancasila sebagai asas dalam organisasi. Muktamar NU di Situbondo dua tahun kemudian menyatakan Pancasila sudah final. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Rais Aam Pengurus Besar NU KH Achmad Siddiq yang secara gamblang menyatakan Pancasila merupakan ideologi dan dasar negara yang menjadi asas bangsa Indonesia.
Hubungan Islam dan Pancasila dalam pandangan Kiai Achmad Siddiq bukan berarti menyejajarkan Islam sebagai agama dan Pancasila sebagai ideologi. Penyejajaran semacam itu dapat merendahkan Islam dengan ideologi atau isme-isme tertentu. Permasalahan ini muncul seiring isu yang berkembang di kalangan umat Islam saat itu.
Kiai Achmad Siddiq menegaskan bahwa Islam yang dicantumkan sebagai asas dasar itu adalah Islam dalam artian ideologi, bukan Islam dalam artian agama. Ini bukan berarti menafikan Islam sebagai agama, tetapi mengontekstualisasikan Islam yang berperan bukan hanya sebagai jalan hidup, tetapi juga ilmu pengetahuan dan tradisi pemikiran yang tidak lekang seiring perubahan zaman.
Beberapa Masalah
Tantangan bangsa Indonesia belakangan ini kian besar. Setidaknya ada tiga masalah besar yang tengah kita hadapi. Pertama, keberadaan sekelompok kecil masyarakat yang ingin mengubah konsensus nasional, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Survei SMRC tahun 2017 menunjukkan kenyataan ini. Meski terdapat 79,3 persen responden menyatakan bahwa NKRI adalah yang terbaik bagi Indonesia, namun 9,2 persen responden setuju apabila NKRI diganti menjadi negara khilafah atau negara Islam.
Survei Alvara Research Center pada 2018 menunjukkan fenomena serupa. Survei tersebut mendapati sebagian kalangan milenial atau generasi kelahiran akhir 1980-an dan awal 1990-an menyetujui konsep khilafah sebagai bentuk negara. Survei dilakukan terhadap 4.200 responden yang terdiri dari 1.800 mahasiswa dan 2.400 pelajar SMA di seluruh Indonesia.
Menurut survei Alvara, mayoritas milenial memang memilih Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara. Namun, ada 17,8 persen mahasiswa dan 18,4 persen pelajar yang setuju khilafah sebagai bentuk negara ideal. Alvara juga melakukan survei terhadap 1.200 kalangan profesional. Sebanyak 15,5 persen dari kalangan ini menyepakati Islam sebagai ideologi Indonesia.
Kedua survei tersebut memperlihatkan bahwa ideologi Islam transnasional sangat dominan memengaruhi sikap dan pandangan sebagian kecil masyarakat terhadap Pancasila dan NKRI sebagai ideologi dan bentuk negara. Sekelompok masyarakat itu adalah Al-Ikhwanu al-Muslimun (IM) yang sejak 1980-an masuk ke Indonesia dan berkembang di kampus-kampus negeri serta berkeinginan mendirikan negara Islam.
Selain IM, terdapat pula Hizbut Tahrir (HT) yang masuk Indonesia pada kurun waktu yang sama, berkembang di kampus-kampus negeri, dan bercita-cita mendirikan khilafah Islamiyah. Dari pengaruh mereka—IM dan HT—sekarang kita bisa melihat gambaran sikap dan pandangan sebagian kecil umat Islam di Indonesia yang menginginkan perubahan dasar dan bentuk negara. Setidaknya itulah yang tercermin dalam survei SMRC dan Alvara.
Masalah kedua adalah klaim kebenaran (Islam) sepihak. Sebagian kecil umat Islam— yang biasa disebut “salafi” atau “wahabi”—menganggap gagasan dan praktik keberislaman merekalah yang benar, sementara di luar kelompok mereka adalah salah, sesat, kafir, musyrik, dll.
Klaim kebenaran tersebut mulai marak di tengah-tengah muslim perkotaan. Salah satu cara yang ditempuh kelompok ini adalah mempromosikan konsep hijrah. Narasinya kira-kira berbunyi seperti ini: sebelum ‘hijrah’ mereka adalah orang-orang yang salah dalam berislam, namun setelah ‘hijrah’, orang Islam selain dirinya adalah salah. Mereka sangat mudah menyalahkan dan mengkafirkan orang lain yang berbeda pandangan.
Bibit intoleransi di Indonesia salah satunya lahir dari ajaran salafi/wahabi, yang bertentangan dengan sikap bangsa Indonesia yang serba saling menolong, gotong royong, dan teposeliro terhadap orang lain.
Kebencian dan permusuhan terhadap segala hal yang berada di luar diri dan kelompok Islam transnasional ini semakin besar ketika mendapatkan landasan teologis dari nash-nash ajaran Islam yang mereka pahami secara serampangan. Dari situ muncullah cita-cita politik sektarian dengan mengusung identitas Islam di mana setiap sistem politik yang tidak sesuai dengan pemahaman mereka disebut thoghut, kafir, dan anti-Islam.
Padahal, persoalan bentuk negara dan kepemimpinan dalam Islam, misalnya, sudah lama selesai dibahas oleh para ulama ahlussunnah waljamaah yang otoritatif.
Masalah ketiga adalah kalangan mayoritas yang cenderung diam (silent majority). Meski kelompok yang menginginkan Pancasila sebagai ideologi negara ditanggalkan jumlahnya tak signifikan, namun karena silent majority yang hanya memilih ‘diam’ dan tidak bergerak ‘melawan’ dan bersikap tak acuh, pengaruh propaganda khilafah pun meluas.
Narasi Kebencian
Ideologi politik Islam transnasional ini belakangan menjadi semakin populer. Ada yang dibawa oleh tokoh-tokoh yang memiliki hubungan dengan kelompok-kelompok politik Islam di luar negeri, ada pula yang masuk ke dalam keyakinan seseorang melalui apa yang disebut oleh Caroline Joan Picart sebagai self-radicalization (radikalisasi diri). Proses yang terakhir ini terjadi ketika seseorang mengonsumsi konten-konten yang mengandung ajaran radikal dengan kemauan sendiri tanpa ada ajakan dari orang yang dikenalnya.
Indonesia memang semakin terancam oleh sektarianisme yang disokong tafsir radikal atas nama agama, baik yang dinyatakan lewat sikap politik, kegiatan keagamaan, tindakan terorisme, ujaran kebencian, perilaku intoleran terhadap sesama warganegara, hingga intimidasi terhadap kelompok lain yang berbeda pendapat atau pilihan politik.
Dengan keyakinan dan pemahaman radikalnya, para pengusung Islam Politik ingin memaksakan pandangan dan keyakinannya kepada semua muslim di Indonesia. Jika tidak mungkin dilakukan, maka mereka merasa berkewajiban untuk mengambil alih kekuasaan dengan cara apapun, sehingga bisa menerapkan sistem pemerintahan yang mereka anggap paling benar menurut Islam. (Selengkapnya bisa dibaca di laporan kajian Hasyim Muzadi, anggota Wantimpres, dalam Pengaruh Jaringan Islam Lokal dan Trans-Nasional Terhadap Instabilitas Negara, Jakarta, Wantimpres, 2015, hlm. 104-108).
Masih menurut klaim kelompok ini, umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia berhak menentukan bentuk negara dan sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia. Namun, mayoritas umat Islam di Indonesia berpaham moderat dan tidak pernah setuju dengan cita-cita politik yang dijajakan oleh ideologi Islam politik. Karena tidak sejalan dengan cita-cita mereka, tak heran jika kelompok Islam moderat menjadi sasaran ujaran kebencian dan berbagai macam tuduhan. Bentrokan-bentrokan kecil tidak jarang terjadi di antara kedua kubu.
Sebagian pengamat dan peneliti telah menunjukkan keberadaan pihak-pihak tertentu yang sengaja memancing kerusuhan untuk menciptakan ketidakstabilan politik, sehingga mereka bisa melancarkan agenda politiknya. Beberapa aksi politik kelompok-kelompok sektarian ini kerap sengaja digiring untuk menciptakan kondisi politik yang seolah-olah kacau dan tak terkendali dengan tujuan melemahkan pemerintahan yang sah.
Sementara itu, masyarakat Indonesia yang tidak beragama Islam merasa terancam dengan sikap dan tindakan kelompok-kelompok intoleran yang mengusung ideologi Islam Politik ini. Sebutan “kafir” atau “non-pribumi” yang ditujukan kepada kelompok minoritas agama dan etnis, serta kekerasan verbal maupun fisik bermotif kebencian telah menghantui masyarakat non-muslim Indonesia. Tak sekali dua kali mereka jadi korban.
Dari kasus-kasus yang ada tentu kita bisa ingat: ketika kerusuhan sudah terjadi dan meluas skalanya, baik muslim maupun non-muslim sama-sama bisa menjadi korban.
Dalam pengamatan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), kelompok-kelompok pengusung politik identitas yang membawa nama Islam ini sengaja menyebarkan konten-konten tertentu dengan bertujuan untuk menanamkan pemahaman radikal. Mereka bahkan tak segan menggunakan kebohongan dalam narasi-narasinya. Setidaknya ada empat macam narasi yang disebarluaskan kelompok-kelompok ini untuk memperkuat politik identitas sektarian.
Pertama, narasi militansi yang mengajak orang untuk membenci orang lain yang berbeda agama, ras, atau bahkan sekadar berbeda pendapat.
Kedua, narasi terzalimi untuk meyakinkan orang bahwa eksistensi mereka sedang terancam pemerintah dan kelompok tertentu. Yang diharapkan dari narasi ini adalah kebencian dan perlawanan terhadap pemerintah atau kelompok yang mereka anggap musuh.
Ketiga, narasi intoleran yang dibuat dengan menggunakan kebohongan tentang kelompok lain yang bersifat merendahkan, menghina, dan memusuhi. Narasi ini disertai ajakan untuk membalas dan melawan.
Keempat, narasi konspiratif yang berisi tuduhan bahwa pemerintah bekerjasama dengan asing untuk menindas Islam, sehingga harus dilawan dengan aksi kekerasan, termasuk tindakan teror.
Meskipun tak jarang berbeda pendapat dan bertikai di kalangan mereka sendiri, tetapi kelompok-kelompok intoleran di Indonesia menggunakan narasi-narasi yang sama untuk mencapai tujuannya. Pancasila—yang selama ini diterima sebagai jalan kemaslahatan hidup berbangsa dan mampu menengahi berbagai macam perbedaan—akhirnya dijadikan musuh bersama. Padahal, kelahiran dan disepakatinya Pancasila sebagai dasar negara dan perekat berbagai macam perbedaan di dalam tubuh Indonesia sudah melalui perjalanan panjang dan banyak pertimbangan.
Rongrongan ideologi Islam transnasional terhadap Pancasila hari ini semakin nyata. Sebagai bangsa, kita sedang diuji untuk bisa bersama-sama merawat Pancasila sebagai satu-satunya asas dan—saya yakin—sebagai kalimatun sawa’ alias titik temu antar suku, agama, etnis, ras, dan ragam identitas lainnya.
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.