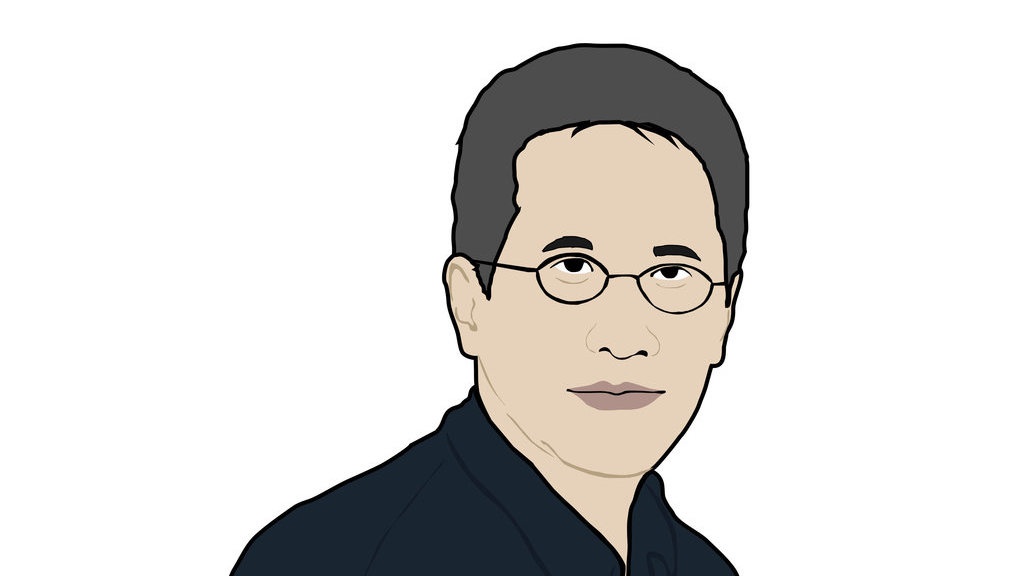tirto.id - Saya lahir dan besar di Jawa. Bahasa Melayu campur Jawa Timuran merupakan bahasa utama dalam kehidupan keluarga sehari-hari. Tapi, masa ketika saya tumbuh besar kurang ramah pada pendidikan sejarah.
Tak hanya di lingkungan sekolah. Dalam kehidupan sosial, generasi kami tidak pernah dididik agar terpesona dan terkagum-kagum pada ilmu sejarah. Mungkin hal yang sama terjadi pada generasi sebelum dan sesudah kami. Kisah masa lampau yang kami telan adalah narasi yang dikemas dalam bentuk propaganda politik oleh kelompok yang sedang berkuasa.
Walau terlambat, saya bersyukur masih sempat jatuh cinta pada sejarah sebelum mati. Bukan fakta-fakta kesejarahan (nama orang atau tempat, tanggal peristiwa, jumlah orang atau benda) yang memikat saya, melainkan gambaran umum tentang sebuah masyarakat, sebuah dunia yang sangat berbeda tapi masih terkait dengan dunia yang saya tinggali.
Yang pertama kali mengubah wawasan saya dan membuat saya terpesona pada sejarah bukan buku sejarah atau guru sejarah, alih-alih empat novel (Tetralogi Buru) yang ditulis Pramoedya Ananta Toer selama di Pulau Buru. Proses penulisan Tetralogi Buru memakan waktu 20 tahun, diawali dengan penelitian tekun belasan tahun atas sejarah terbentuknya bangsa Indonesia.
Saya baru selesai membaca sebuah novel sejarah lain: Mataram, karya fiksi perdana sejarawan legendaris Anthony Reid yang terbit pada akhir tahun 2018.
Pramoedya adalah seorang novelis yang menggali sejarah sebagai bahan berkisah. Sementara Anthony Reid, salah seorang peneliti sejarah terbesar yang kita kenal abad ini, mengandalkan kekuatan bahasa sastra untuk berbagi pengetahuan dan imajinasi tentang kehidupan sehari-hari di Jawa pada kurun 1608-1624.
Ketika Tetralogi Buru diterbitkan, Pramoedya menegaskan novelnya bukan karya sejarah. Dengan pemikiran serupa, saya menikmati Mataram, pertama-tama dan khususnya sebagai karya sastra—sebagai jendela untuk menengok dan berimajinasi tentang sebuah dunia yang berbeda dari hari ini. Tanpa pengetahuan tentang Jawa 400 tahun lalu, saya tak berhak dan tak berminat menilai sejauh mana kisah ini sesuai dengan fakta kesejarahan.
Bagi saya, banyak yang menarik dari kisah tentang Jawa 400 tahun lalu yang dituturkan dalam Mataram. Dalam kesempatan di sini, ada dua yang ingin saya bahas.
Yang pertama, apa yang disebut “globalisasi”. Walau ramai dibahas di awal abad 21, globalisasi adalah kenyataan sehari-hari di Jawa 400 tahun lalu. Kedua, ketegangan antara sinkretisme Islam-Jawa versus Islam fundamentalis yang melanda perpecahan elite kerajaan maupun kehidupan rakyat sehari-hari, bahkan dalam satu keluarga.
Lampaunya Globalisasi
Di layar perak, fotografi, lukisan, dan sejumlah kisah tekstual lain, masa lampau sering kali digambarkan secara eksotik: kehidupan sederhana tapi damai, alam yang indah dan ramah, masyarakat rukun dan tentram, serta orang-orang yang baik dan berbahagia.
Mataram berbeda. Walau diuntai romantika kisah cinta dua tokoh utama (Thomas Hodges dan Sri), novel ini padat kisah kebencian, kekejaman, perang, dan intrik. Bahkan alam tidak selalu indah. Ledakan Gunung Merapi digambarkan panjang lebar, bukan sebagai sesuatu yang elok.
Bukannya tak ada yang indah dalam Mataram. Yang indah di novel ini bukanlah alam atau tarian atau musik etnik, melainkan perjumpaan dan benturan aneka bangsa dan budaya besar dari berbagai benua di tanah Jawa, mulai dari India, Arab, hingga Cina. Yang mendapat perhatian lebih besar adalah kehadiran bangsa Portugis, Belanda, dan Inggris.
Seperti dalam Tetralogi Buru, tokoh-tokoh Mataram tidak tampil sebagai stereotipe kebangsaan atau agama. Mereka tampil sebagai sosok individu unik nan kompleks. Berbagai bangsa Eropa yang tiba di Jawa saling bermusuhan dalam persaingan global perdagangan rempah dan hasil bumi Nusantara.
Tokoh utama pria, Thomas Hodges, adalah pelaut Inggris yang memutuskan batal pulang ke tanah air bersama rombongan kapalnya. Ia memilih menetap di Banten setelah jatuh cinta pada gadis setempat bernama Sri.
Bisa dibayangkan betapa langka, rumit, subversif, dan berbahayanya pernikahan campur semacam itu di masa itu—seperti juga hari ini di Indonesia. Berkali-kali Thomas dan Sri harus merahasiakan hubungan mereka, bahkan setelah menikah.
Demi cintanya pada Sri, Thomas Hodges tak hanya merelakan kesempatan pulang ke Inggris. Selama tinggal di Jawa, ia berjuang menghadapi serangkaian tekanan bahkan siksaan untuk “menjadi Jawa”. Padahal, sesama tokoh-tokoh Jawa sendiri masih berdebat dan saling-tikam tentang apa makna “menjadi Jawa”.
Pada akhir novel, Thomas mati sebagai prajurit kerajaan Mataram di bawah pangeran Anggalaga (Sultan Agung). Ia terbunuh sebagai korban sampingan dalam sengketa antar-pangeran Mataram yang berebut takhta.
Sri adalah salah seorang tokoh paling aktif dan cerdas dari semua tokoh di novel ini. Lebih kuat dari protagonis pria yang menjadi suaminya. Ia mengingatkan saya pada tokoh Nyai Ontosoroh dalam Tetralogi Buru.
Sri adalah putri kedua dari kawin campur antara ibu Jawa dan bapak Cina. Bapaknya menduduki jabatan yang cukup tinggi di kerajaan Banten sebagai Bintara. Ia beragama Islam sambil meneruskan tradisi menghormati arwah nenek moyangnya yang Cina.
Sebagai tokoh Islam, sang bapak meninggal dibacok seorang pemuda dengan seruan “Allahu Akbar” dalam bentrok lokal antara kelompok Muslim yang masih melangsungkan tradisi Kejawen dan kelompok Muslim puritan yang diikuti Khalid, kakak Sri.
Sinkretisme Agama
Bagaimana “menjadi Jawa” dan “Muslim” harus dirumuskan sehingga memuaskan yang bersangkutan? Apakah—dan sejauh mana—menjadi Muslim bagi orang Jawa harus menanggalkan berbagai tradisi nenek moyang yang oleh kaum fundamentalis dianggap bertentangan dengan ajaran Islam? Seperti Islam, apakah Kristen layak di-Jawa-kan dengan berbagai tradisi dan kepercayaan leluhurnya?
Sejauh mana kerajaan (atau negara) harus ikut mengurus kehidupan agama warganya? Bagaimana sebaiknya negara dengan penduduk mayoritas Muslim memberi ruang gerak pada agama-agama minoritas: Buddha, Hindu, Katolik, Kristen Protestan?
Kita semua paham pertanyaan-pertanyaan demikian sudah hadir sejak masuknya Islam ke Jawa. Tapi, mungkin banyak orang (seperti saya) yang awam bagaimana persisnya semua itu dialami dalam kehidupan pribadi dan batin individu-individu sehari-hari.
Mataram menyajikan pergulatan itu dalam rincian detail kecil-kecil yang indah. Bukan rumusan abstrak seperti uraian ilmu sejarah. Persis seperti semua novel yang bagus.
Kita juga sudah tahu pertanyaan-pertanyaan di atas bukan hanya berlanjut pada masa kini. Semua pertanyaan itu telah menjadi pusat sengketa politik nasional (dan sesekali konflik berdarah di tingkat lokal) selama dua dekade pasca-Orde Baru. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi tema-utama keseluruhan novel Mataram. Itu sebabnya, Mataram layak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sesegera mungkin dan dibaca seluas-luasnya di tanah air.
Kerja menerjemahkan novel seperti Mataram tentu tak mudah. Novel ini berkisah tentang orang-orang Jawa-Muslim awal abad ke-17, dan ditulis dalam bahasa Inggris pada awal abad ke-21.
Penulisan Mataram merupakan upaya penerjemahan raksasa. Yang diterjemahkan bukan hanya istilah, tetapi rasa, kerangka berpikir, zaman dan wawasan. Untuk mengalihkan novel itu ke Bahasa Indonesia, si penerjemah harus menguasai beberapa bahasa dan kerangka berpikir sekaligus: Jawa, Islam, dan Eropa modern.
Mataram layak dibaca bagi siapa pun yang ingin memahami Indonesia hari ini dalam bentangan sejarah yang besar. Ia memikat siapa pun yang tertarik pada masalah kemajemukan budaya, globalisasi perdagangan, isu kawin-campur, Kejawen, sinkretisme agama, persinggungan politik-agama, feminisme, dan sejarah modernitas Eropa yang membawa pistol, kacamata, peta, dan teleskop ke tanah Jawa.
Tapi saya juga yakin Mataram takkan mengecewakan bagi mereka yang tidak peduli pada semua problem sosial yang berat-berat itu dan hanya ingin menikmati kisah cinta dua manusia dengan latar belakang sangat berbeda. Dengan keberanian dan kecerdikan luar biasa, sepasang kekasih ini mengambil risiko menghadapi tantangan dan rintangan lingkungan yang tidak memahami atau merestui hubungan mereka.
Berhari-hari setelah selesai membaca, satu kutipan Mataram masih berdenyut di benak saya: “The first thing I learned in Java was that we cannot serve god by fighting, killing and burning each other over how each understands some partial aspect of his truth. We can best approach the larger truth that is god in silence, prayerfulness and discipline”.
Editor: Windu Jusuf
 Masuk tirto.id
Masuk tirto.id