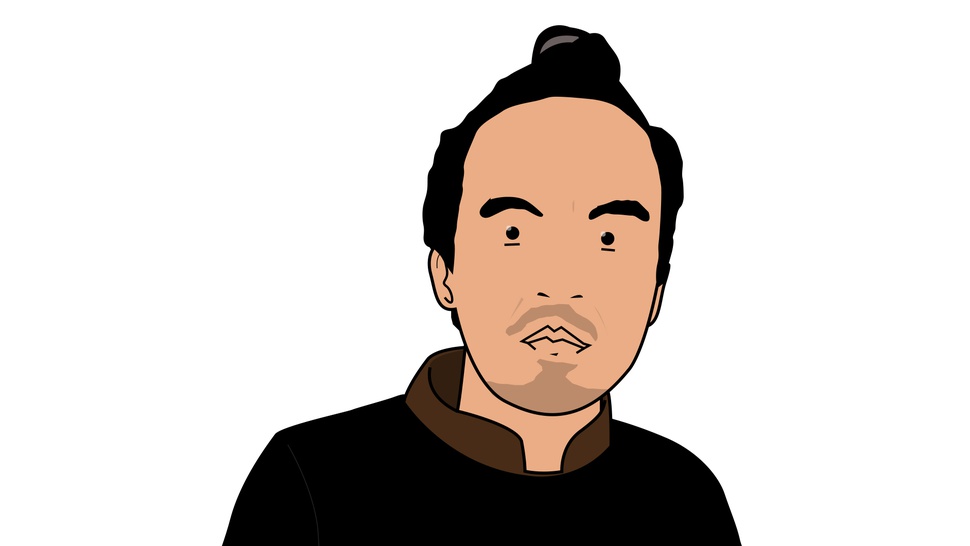tirto.id - Sekali malam kelam di Bandung, Agustus 2016. Serdadu-serdadu "menggaruk" perpustakaan jalanan milik para pemerhati literasi urban. Malam kelabu itu hanyalah satu dari kesekian deret contoh ketegangan antara literasi dan militer. Penggarukan buku itu sesungguhnya bukan domain spesifik militer, melainkan rupa-rupa kekuasaan, seperti lembaga keagamaan, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan.
Dari situ kita menempatkan mula-mula aparatus militer adalah satu dari kaum yang terlampau sering bersitegang di lapangan literasi. Intimidasi, teror, dan penebar paku-rasa-takut dalam banyak hal dinisbahkan kepada militer lantaran memiliki perangkat legal yang tak dipunyai kalangan sipil di luar mereka: bedil!
Sebelum dikembalikan ke barak oleh Reformasi '98, militer berkeliaran di mana-mana; mulai dari perusahaan, organisasi olahraga, parlemen, hingga di ruang-ruang makan keluarga Indonesia. Begitu sentralnya kekuasaan militer ini sehingga tak heran Jurnal Indonesia yang diterbitkan Cornell University dan diasuh antara lain Kahin dan Ben Anderson selalu menyediakan ruang istimewa berisi ulasan apa saja soal militer, bahkan hanya soal pergantian jabatan yang sifatnya reguler.Jurnal Indonesia seperti memberitahu jangan pernah lupakan dan sepelekan militer dalam perikehidupan berbangsa dan bernegara. Termasuk soal-soal yang terkait dengan literasi.
Saya orang yang sangat percaya bahwa selalu ada amal baik dari sebuah kaum sejahanam apa pun kaum itu. Dalam sejarah literasi, buku, perdebatan, militer memang kalangan punya rekam jejak yang buruk. Dalam sejarah pemberedelan koran dan majalah, pelarangan dan perampasan buku, pencidukan sastrawan dan penulis sejak era Karno hingga Harto, cap tangan militer selalu ada.
Bisa Anda bayangkan saat Pramoedya Ananta Toer lagi sengit-sengitnya menebar tantangan yang lantang soal plagiasi Hamka di bulan Oktober 1962, eh tahu-tahu keluar surat edaran dari Penguasa Militer Jakarta Raya untuk segera menghentikan rupa-rupa polemik karena mengancam "ketertiban umum". Ya, berhenti! Jika pun masih ada, sayup-sayup belaka.
Saat terpojok karena tak bisa menyeret D.N. Aidit ke penjara lantaran pleidoinya tentang Madiun 1948 (MDN48) di pengadilan Jakarta pada 1955, buku pleidoi Aidit itu disikat dengan cara melarangnya. Kalah di pengadilan, militer memilih jalan menutup akses buku itu ke pembaca luas.
Jika pun bukan militer yang langsung menindak, ormas dan partai politik yang memiliki masalah dengan produk literasi seperti media, buku, brosur, kerap menjadikan militer sebagai dalih. Militer adalah alamat dari mana restu didapatkan untuk bergerak melakukan tindakan teror dan menebar ketakutan pada kaum yang menggunakan literasi sebagai media kritik dan ekspresi progresif.
Sampai di sini, hubungan literasi dan militer memang sangat rentan, jika tak bisa dibilang seperti air dan minyak. Namun, kultur literasi tak bisa berkembang dalam tubuh organisasi bersenjata yang menjadi pilar utama pertahanan dan keamanan negara. Militer—dalam hal ini polisi dan tentara—mesti diingat lahir dalam tubuh rakyat jelata oleh sebuah revolusi yang kemudian diingkari oleh mereka sendiri tatkala merumahkan laskar rakyat dengan jalan kekerasan antara Mei-September 1948. Alasannya: negara RI yang modern hanya butuh tentara sekolahan (baca: KNIL), bukan kerumunan orang-orang menenteng bedil tapi tak punya isi kepala. Dari ingatan sederhana soal ari-ari tentara yang teringkari itu dan hanya dipakai untuk melegitimasi hubungan tentara-rakyat saban tahun di tanggal 5 Oktober, kita bisa menjahit lagi hubungan literasi dan militer yang naudubillah sulitnya itu.
Caranya? Ingat kembali rumus ini: setiap kaum, sejahanam apa pun kaum itu, selalu punya amal baik. Begitu juga dalam soal literasi dan militer. Ingatlah, bahwa dalam tubuh tentara ini lahir jenderal-jenderal pemikir. Pribadi-pribadi itu tak hanya menjadi pembaca yang rakus, tapi penulis yang prigel. Hario Kecik yang mendirikan Badan Intelijen Negara (BIN) di Yogya dengan mula-mula mengedarkan ganja untuk membiayai lembaga mata-mata ini karena negara tak punya uang, adalah tentara cerdas andalan Sukarno. Ia bukan hanya pembaca buku yang rajin, tapi penulis yang cermat, detail, dan lancar.
Jenderal Nasution yang bersinar setelah menghancurkan “tentara rakyat” yang tergabung dalam berbagai organisasi laskar di Surakarta, Yogyakarta, Kediri, Madiun pada 1948 adalah jenderal pemikir sekaligus penulis yang legendaris. Karena kelewat cerdas, bintangnya pun cepat redup oleh peristiwa 17 Oktober 1952 sebelum diampuni Sukarno empat tahun kemudian.
Buku karya Nasution tentang Perang Gerilya menjadi salah satu buku paling penting dalam membaca kultur militer kita. Biografi yang ditulisnya sendiri dengan teliti, detail, dan memikat dengan jumlah lebih dari sepuluh jilid itu, Memenuhi Panggilan Tugas, adalah karya tak terbantahkan bagaimana seorang prajurit juga bisa sekaligus penulis dengan tradisi literasi yang kuat.
Adalah T.B. Simatupang yang juga pemikir dalam tubuh tentara yang tegap-tegap itu pernah berkata kepada jurnalis Rosihan Anwar: “Kita berdua mempunyai suatu tugas. Kamu menulis, aku menulis, meneruskan gagasan dan cita-cita kita kepada masyarakat. Tahun-tahun yang akan dating ini penting sekali dalam perkembangan bangsa dan negara kita.”
“Ah, Sim, aku sudah tua. Kalau kau mau menulis terus, silahkan. Ik niet meer, jawab Rosihan Anwar. Sim, panggilan akrab jenderal penulis Laporan dari Banaran itu, ngotot: “Tidak, tidak. Kau harus juga menulis terus. Aku masih punya waktu sepuluh tahun lagi untuk menulis. Itu tanggung jawab kita kepada masyarakat. Zorg dat je er bent.”
Selain bisa menjadi pendeta, sebagaimana jejak yang sama dipilih aktor dan karateka Advent Bangun saat ini, Jenderal Simatupang adalah penulis artikel yang prolifik untuk koran Sinar Harapan, Suara Pembaruan, dan Kompas.
Nama-nama militer yang memiliki arisan dengan kultur literasi karena kebiasaan dalam keluarga dan/atau tekanan lingkungan yang keras masih bisa kita deretkan hingga kini. Kita berjumpa dengan nama jenderal pemikir yang menjadi Presiden RI 2004-2014 Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Wirahadikusuma, hingga Chappy Hakim. Di era yang gandrung dengan microblogging semacam twitter saat ini, tentu kita pernah gemas dan cekikikan dibikin tulisan-tulisan celetukan pendek akun @TNI_AU.
Kemampuan tentara yang separuh usia mereka dididik dengan disiplin yang kuat membuat mereka bisa mengurusi apa saja, termasuk hanya mengurusi soal literasi dan pembentukan postur gizi bagi pikiran. Jangankan bisa membikin tim sepakbola profesional kiwari semacam PS TNI, militer juga bisa buat koran. Jangan ingkari dua koran ini: Berita Yudha dan Angkatan Bersenjata. Tapi itu, kerap kehilangan kontrol dan kebablasan. Ketika mandek dan kena masalah dari ekses persaingan ekonomi dan pengaruh politik, kerap monsternya keluar sebagai makhluk yang punya bedil ketimbang upaya menahan diri untuk mengedepankan percakapan intens sebagaimana yang disodorkan kultur demokratis.
Ini bukan hanya berlaku dalam lapangan sepakbola PS TNI (tapi berlaku juga dalam tim yang dikelola pengusaha-sipil), tapi juga mengiringi sejarah koran Berita Yudha dan Angkatan Bersenjata yang kemudian bubar sendiri lantaran tak punya musuh ideologis.
Dari paparan baik-buruk itu, ringkasnya begini. Saya setuju sepenuhnya kutukan dari Pimpinan Pusat Forum Taman Bacaan Masyarakat (FTBM) yang mengutuk tentara-tentara Siliwangi yang (dianggap) kurang ajar terhadap literasi-urban. Namun, jika kutukan itu hanya kutukan, sangat disayangkan. Mestinya diikuti dengan mendekati mereka untuk masuk dalam shaf terdepan perjuangan literasi dan dokter pemberantas jentik-jentik kebodohan nasional hingga ke pulau-pulau terdepan.
Mari berhitung soal modal dan kemampuan. Militer memiliki personel yang terlatih, kuat fisiknya, armada yang lengkap, rumah/kantor representatif jika dibandingkan dengan aktivis-aktivis literasi yang kekuatan tubuhnya umumnya lembek dengan sarana/prasarana yang terbatas dan tak terukur.
Modal lain, markas-markas militer hadir hingga di tingkat kecamatan sebagaimana kantor pos. Mereka hadir tidak hanya di pulau yang dihuni penduduk, tapi juga hingga jengkal akhir batas negara di timur, barat, utara, dan selatan. Jika tentara bisa punya rumah sakit dan menjadi dokter, bisa menjadi guru di pedalaman yang kekurangan tenaga pengajar hingga di pulau-pulau terdepan Nusantara, mengapa mereka oleh pegiat literasi tak diajak sekalian membikin taman bacaan di markas-markas mereka.
Keuntungannya, di satu sisi tentara bisa lebih dekat dengan literasi, sekaligus markas mereka menjadi taman bermain anak-anak. Markas mereka tak hanya tempat melamun karena ketiadaan musuh berperang atau kamar penyiksaan bagi “musuh-negara”, namun menjadi tempat yang ramah untuk pikiran. Paling tidak untuk remaja-remaja yang haus pengetahuan selain didapatkan dari sekolah jam buka perpustakaan barengan dengan jadwal kantin sedang ramai-ramainya.
Jangankan bendi pustaka, kuda pustaka, ATV Pustaka, mobil pustaka, sepeda pustaka; militer itu bahkan punya kapal perang (atas/bawah laut), pesawat, puluhan truk logistik, bahkan tank. Tinggal ditambahkan semuanya dengan kata “pustaka”, klaar dah!
“Kamu menulis, aku menulis,” kata Jenderal Simatupang, sekali lagi.
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.