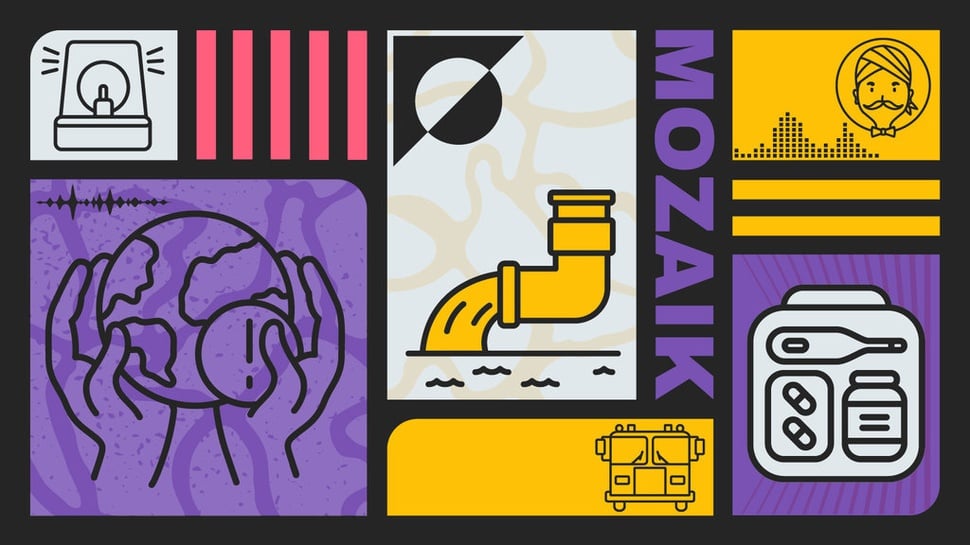tirto.id - Gempa bumi yang terjadi di Cianjur pada 21 November lalu membangkitkan kembali diskusi tentang mitigasi bencana. Para ahli percaya gempa berkekuatan 5,6 Skala Richter itu seharusnya tidak terlalu menghancurkan jika di wilayah terdampak telah menerapkan upaya mitigasi.
“Banyaknya struktur bangunan yang tidak memenuhi standar gempa, dangkalnya pusat gempa, serta lokasi permukiman yang berada di perbukitan dan tanah lunak menjadi alasan gempa kemarin menjadi sangat merusak,” ungkap Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG Daryono, dikutip CNN Indonesia.
Mitigasi adalah upaya mereduksi dampak berlebih dari suatu bencana. Langkah ini menjadi hal mutlak yang harus dilakukan bagi siapapun yang tinggal di wilayah rawan bencana, termasuk Indonesia yang dikategorikan United States Geological Survey sebagai salah satu negara paling banyak mengalami gempa bumi dan sebaran gempa terluas.
Di balik kehidupan yang kelihatannya damai ini sebetulnya ada potensi gempa besar mengintai penduduk kota-kota besar di Indonesia. Jakarta, misalnya, reportase Tirto pada 2017 lalu pernah mengungkap bahwa di ibukota terdapat sesar aktif baribis yang tidak diketahui kapan akan bergerak.
Jika sesar itu bergerak, maka diprediksi puluhan juta warga dan bangunan akan menjadi korban. Sayangnya, kerentanan tinggi ini tidak dibarengi dengan langkah mitigasi konkret. Jika pembiaran ini terus berlanjut, potensi gempa yang lebih merusak hanya tinggal menunggu waktu.
Hidup di zona pergerakan lempeng bumi memang membuat kita tak bisa mengelak dari aktivitas tektonik dan vulkanik. Sekalipun teknologi semakin canggih, belum ada yang mampu memprediksi datangnya dua aktivitas tersebut. Maka, cara terbaik yang bisa dilakukan adalah belajar berdamai dengan alam.
Sayangnya, upaya berdamai ini tampaknya belum berjalan dengan baik. Setiap ada gempa, khususnya dalam skala ringan, kerusakan dekstruktif kerap terjadi. Ini belum lagi mempersoalkan proses evakuasi yang juga carut-marut.
Tanpa informasi yang memadai, masyarakat umum tidak tahu harus berbuat apa dan bagaimana saat menyikapi bencana. Dalam situasi seperti ini, alih-alih terbebas dari bencana, mereka justru menghadapi risiko bencana yang semakin tinggi.
Jika Indonesia bisa dikatakan masih gagap dalam urusan mitigasi, bagaimana dengan pengalaman negara lain?
Jepang Memulainya dari Pendidikan
Sejak terdokumentasi pertama kali pada tahun 416 M, masyarakat di Jepang mulanya tidak peduli terhadap gempa bumi. Tidak ada upaya mitigasi yang kompleks seperti sekarang.
Ini disebabkan karena Jepang masa kuno tidak seramai dan semaju saat ini, baik penduduk ataupun bangunannya. Jadi, sekalipun ada gempa, mereka akan menganggap enteng karena dampaknya tidak terlalu berarti.
Meski begitu, sebagai upaya beradaptasi, mereka juga punya langkah tersendiri, yakni membangun bangunan tahan gempa dengan memanfaatkan kayu. Mereka percaya kayu lebih lentur dibanding batu, sehingga bakal lebih kuat saat terkena guncangan.
Untuk membangun kuil yang menjulang tinggi mereka menerapkan teknik Goju-no-to. Teknik ini mengharuskan kuil memiliki tiang tebal yang tidak terhubung langsung ke lantai. Jadi, ketika terjadi gempa, tiang tersebut tidak menekan ke lantai dan bergerak ke arah berbeda dengan goncangan gempa. Dampaknya, bangunan akan tetap kokoh.
Selama berabad-abad, ketidakpedulian ini nyatanya tidak berubah. Sebab, kata Katsutoshi Suganuma dalam “Recent Trend in Earthquake Disaster Management in Japan” (2006), guncangan gempa yang muncul sepanjang sejarah Jepang tidak ditakdirkan menyentuh kota-kota besar yang berpenduduk padat.
Maka, berdasarkan argumen saat itu, selama berpusat di lokasi terpencil atau minim penduduk, mereka tetap akan cuek menyikapi bencana karena dampaknya tidak berarti bagi mereka.
Sampai akhirnya, ada satu peristiwa yang membukakan mata penduduk tentang pentingnya meminimalkan resiko gempa, yakni Gempa Kanto 1923.
Sesuai namanya, gempa berkuatan 7,9 SR ini berpusat di Kanto dan menjadi salah satu yang terparah di abad ke-20. Dalam catatan Koji Ikeuchi dan Nobuharu Isago dalam “Earthquake Disaster Mitigation Policy in Japan (PDF)”, gempa berdurasi 20 detik itu membuat hampir seluruh bangunan runtuh yang disertai kebakaran hebat.
Parahnya lagi, masyarakat tidak mengetahui langkah-langkah terbaik saat terjadi guncangan. Proses evakuasi dari otoritas pun carut-marut. Akibatnya, lebih dari 100 ribu orang meninggal dan jutaan lainnya kehilangan tempat tinggal.
Kejadian ini membuat Negeri Sakura sadar bahwa kekuatan gempa bukan persoalan utama. Ini jelas tidak bisa diprediksi apalagi dicegah. Maka, satu-satunya cara adalah melakukan upaya mitigasi. Dan Jepang memulainya dari pendidikan.
Dalam kurikulum pasca 1923, anak-anak Jepang mulai diberi materi pendidikan bencana sejak hari pertama sekolah, seperti perlindungan diri, pembentukan mental kebencanaan, dan upaya evakuasi sesama. Kegiatan ini terus berulang tiap bulan sehingga mereka lebih siap menghadapi bencana.
Lalu, cetak biru penanganan gempa pun diterapkan. Setelahnya, otoritas terkait mulai mewajibkan pembangunan konstruksi fisik bangunan tahan gempa yang juga memiliki jalur evakuasi. Setiap tahun, alat pengukur gempa terus dipasang di wilayah-wilayah rawan.
Praktik mitigasi itu tentu tidak langsung mengubah respons masyarakat terhadap bencana. Semua dilakukan perlahan karena mitigasi adalah hasil dari proses terus-menerus selama bertahun-tahun.
Hasilnya dapat kita lihat sekarang: Jepang menempati posisi nomor satu sebagai negara paling siap menghadapi gempa yang menghantam 2.000 kali tiap tahunnya.
Cina: Gempa Sichuan sebagai Momentum Titik Balik
Reformasi ekonomi Cina sejak tahun 1970-an membuahkan hasil. Industri berkembang pesat membuat perekonomian negaranya mampu sejajar dengan negara-negara Barat. Tapi, di balik itu sesungguhnya Cina sangat rentan terhadap bencana, seperti banjir, kekeringan, kebakaran, topan, gempa bumi, dan kemunculan penyakit berbahaya.
Kerentanan ini, kata Steven A. Zyck dalam “Crisis Preparedness and Response: the Chinese Way”, membuat produk domestik bruto Cina merugi minimal 1,6 persen tiap kali bencana datang.
Bencana alam yang mendorong reformasi besar-besaran di sektor mitigasi adalah Gempa Sichuan tahun 2008. Getaran bermagnitudo 7,9 SR ini membuat hampir seluruh bangunan rata dengan tanah. Gempa juga mengakibatkan longsor. Akibatnya, 90 ribu orang dinyatakan meninggal (5 ribu di antaranya anak sekolah) dan hampir 350 ribu orang terluka.
Gempa Sichuan terjadi ketika ekonomi Cina cukup digdaya. Karena tidak mau dilanda kerugian, Cina akhirnya memilih fokus untuk meningkatkan kemampuan negara dalam menyelamatkan nyawa dan mengurangi kerugian ekonomi pada saat atau pasca-bencana.

Mengutip tulisan “Manajemen dan Pengurangan Risiko Bencana di Tiongkok” (LIPI, 2016) oleh Erlina Tantri, pasca peristiwa di Sichuan pemerintah menyiapkan kebijakan besar manajemen bencana:
(1) menyiapkan 30 rancangan kebencanaan, (2) mewajibkan pendirian bangunan tahan gempa, (3) mengadakan latihan kebencanaan di sekolah, (4) penguatan sistem peringatan dini, (5) pengumpulan dana abadi bencana.
Namun, langkah Cina tidak semulus Jepang. Tulisan berjudul “China’s Action for Disaster Prevention and Reduction” (2009) menyebut bahwa masalah utama yang mengadang kebijakan ini adalah mental masyarakat.
Tidak seperti Jepang, penduduk Cina belum sadar bahwa mereka berada di wilayah rawan bencana. Kealpaan inilah yang kemudian membuat segala upaya mitigasi berjalan sangat lambat. Meski demikian, kembali lagi ke pernyataan di atas, mitigasi sejatinya adalah proses bertahun-tahun.
Mitigasi Bencana di Italia Terhalang Korupsi
Berada di batas pertemuan Lempeng Eurasia dan Afrika serta memiliki banyak patahan aktif, membuat Italia menjadi negara di Eropa yang paling rawan bencana. Mengutip Time, selama 2 ribu tahun terakhir, tercatat lebih dari 400 gempa bumi yang sangat merusak terjadi di Italia.
Lima belas di antaranya terjadi pada abad ke-20 dan terparah terjadi pada 1908 di Messina, Italia Selatan, berkekuatan 7,1 SR dan merenggut 75 ribu nyawa. Dalam perhitungan ekonomi, gempa sepanjang abad ke-20 ini juga membuat kerugian 3,5 miliar Euro tiap tahunnya.
Sama seperti yang lain, upaya berdamai dengan gempa pun menjadi fokus utama Pemerintah Italia. Sejak gempa tahun 1908, pengembangan dan penerapan mitigasi mulai diterapkan, seperti upaya membangun konstruksi tahan gempa, pemasangan alat pendeteksi, dan pendidikan kebencanaan.
Langkah ini semakin masif dilakukan setelah negara-negara Eropa lainnya turun tangan setelah tahun 1945.
Dalam studi “Natural disasters in Italy” (2018) oleh Susana Paleari, sejak abad ke-21 Pemerintah Italia juga telah mengucurkan dana 9,9 miliar Euro per tahun khusus untuk keperluan mitigasi bencana, baik gempa, longsor, atau yang lain.
Sayangnya, dana ini justru tidak memiliki nilai manfaat untuk masyarakat. Penyebabnya: korupsi dan kerumitan birokrasi. Dampaknya membuat kebijakan pendirian bangunan baru tahan gempa dan langkah mitigasi lainnya menjadi terhambat.
Penulis: Muhammad Fakhriansyah
Editor: Irfan Teguh Pribadi