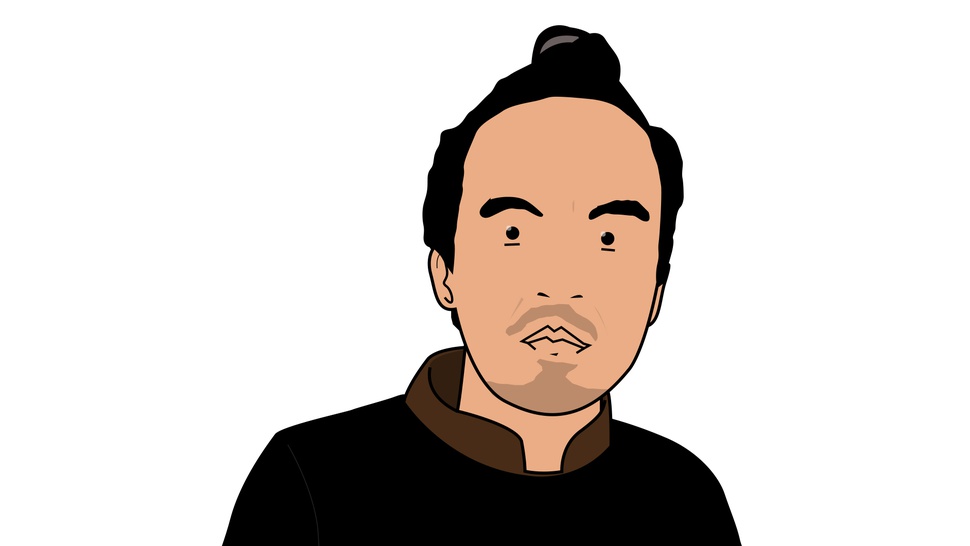tirto.id - Good job, Cops. Akhirnya, dengan semangat nasionalisme yang menyala-nyala, bayangkara negara bernama Kepolisian Republik Indonesia berhasil menangkap dia yang diduga menista bendera merah putih di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kain kebanggaan negara Indonesia yang ditambahi aksara Arab tertangkap kamera dikibarkan salah satu demonstran Front Pembela Islam (FPI) saat berdemonstrasi di depan Mabes Polri, Jakarta, 16 Januari 2017.
Belati tajam UU 24/2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan sudah menunggu nasib malang si rakyat penista bendera negara itu.
Mari tepuk tangan riuh. Pemerintah ini telah betul-betul menegakkan hukum tanpa pandang kelompok dan naga-naganya bakal dikenang seribu tahun lagi oleh generasi entah bernama apa kelak.
Tapi di sinilah titik masuk anomali penegakan ketertiban hukum atas "Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan" itu, sebagaimana tercatat dalam staadblad No 24 Tahun 2009.
Mudah mengecek bagaimana institusi-institusi negara melakukan “penistaan” atas simbol-simbol negara. Lihat saja bagaimana representasi Lambang Negara “Garuda Pancasila” di ruang publik. Anda tak perlu menjadi seorang detektif bergaya Conan untuk mendapatkan tindakan-tindakan menerabas aturan itu berlangsung.
Kita mulai saja pakansi ke Lubang Buaya di mana Pancasila disaktikan. Lambang negara tiga dimensi sebesar raksasa yang biasanya menjadi musuh Power Rangers itu berdiri gagah menanungi pahlawan-pahlawan Revolusi penyelamat Pancasila.
Jika mau menjadi penegak marwah konstitusi, presentasi garuda Pancasila itu melanggar kriteria dan syarat yang diatur secara ketat oleh UU No. 24 Tahun 2009 Pasal 46 hingga 50. Dari segi skala ukuran, garuda raksasa itu menyalahi undang-undang. Sayapnya terlalu melebar. Mungkin dalihnya agar bisa merangkul tujuh patung tentara yang sedang berdiri dalam saf yang rapi.
Cerita soal lambang negara di Lubang Buaya ini menjadi rumpi dari tahun ke tahun di Rumah Garuda, Sewon, Bantul. Sejak rencana pembuatan, seniman pematung asal ISI Yogyakarta Edhi Sunarso yang ditunjuk sebagai pembikin sudah tutup mata tutup kuping dari skala yang ditentukan undang-undang. Dan, jadilah sayap garuda buatannya di Lubang Buaya itu terlihat mengembang lebar. Gagah memang, tapi menerabas aturan main.
Ayo, kita tamasya ke Istana Merdeka sekarang. Garuda dengan formasi yang mulutnya terbuka terlalu lebar--dan tentu saja melanggar aturan standar—kita bisa lihat di tembok paling depan Istana. Hal yang sama kita temukan di ruang sidang Gedung DPR/MPR, Senayan. Wah, di gedung parlemen ini garudanya gahar sekali. Pematung G. Sidharta dipesan untuk bikin garuda dengan bentangan sayap 250 cm. Wah. Di bingkai kamera memang terlihat seru dan artistik, tapi menyalahi ketentuan.
Tentu saja "kreativitas" yang lebih berani dilakukan korpri adalah batik seragamnya berwarna biru dan putih yang lejen itu. Menurut pemilik Rumah Garuda Nanang R. Hidayat dalam Mencari Telur Garuda (2008), di pakaian resmi itu lambang garuda dengan perisainya sudah dikosongkan dari lima sila Pancasila. Juga, tak ada pita Bhinneka Tunggal Ika dan bulu sayapnya cuma 14 helai.
Sebuah "permainan artistik" lambang garuda—dan ini kita temukan di mana-mana di ruang publik (dalam maupun luar negeri)—adalah lambang “logo khas” Kementerian Pariwisata. Sejak era “Visit Indonesia Year” hingga “Pesona Indonesia”, bidang pariwisata ini salah satu yang paling kreatif melakukan modifikasi lambang negara bernama Garuda ini.
Jika garuda di Lubang Buaya dan di Gedung DPR/MPR menjadi “pelopor” deformasi Garuda dalam tiga dimensi (patung) dengan menerabas aturan skala yang menjadi standar yang diatur UU, maka pemangku yang mengurus pariwisata mewakili aliran abstrak.
Dalam konteks “seni” dan “kreativitas” itu pula kita kembali ke pokok paragraf esai ini. Bisakah kita menafsir bahwa membubuhkan aksara Arab atau nama kesebelasan sepakbola atau grup musik pada kain “Merah Putih” adalah bagian “seni” dan “kreativitas” dan itu tidak dimaksudkan sebagaimana termaktub dalam pasal 57 ayat a UU No. 24 Tahun 2009 yang berbunyi: “mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara”.
Ini tafsir yang bisa dikeret ke sana ke mari. Tergantung kepentingan kekuasaan si bayangkara penegak UU.
Nah, untuk melakukan perlawanan tafsir atas pemidanaan ini, maka jalan beradab yang bisa ditempuh Front Pembela Islam (FPI) atau organ-organ kemasyarakatan yang dirugikan atas pemidanaan ini bisa menempuh jalan yang sudah ditempuh Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) pada 2015 dan Koalisi Gerakan Bebaskan Garuda Pancasila (2013).
Judical Review (JR) pada 2013 itu berhasil “melokalisasi” kebuasan dua ayat di pasal 57 (c dan d) yang jika diterapkan letterlijk akan memakan banyak korban pidana. Namun, JR 2015 yang menuntut pasal 57 dan 69 yang berkait dengan hukum pidana ditolak dan bahkan hukuman penjara dan dendanya diperjelas.
Sambil menunggu FPI memasuki aula sidang agung Mahkamah Konstitusi untuk perkara “Lambang Negara”, mari kita gubah selarik puisi Wiji yang terangkat lagi dari kubur oleh film biopic Istirahatlah Kata-Kata (2016): Kemerdekaan adalah nasi, dimakan jadi tai.
Gantilah frase “Kemerdekaan” itu dengan “Nasionalisme”.