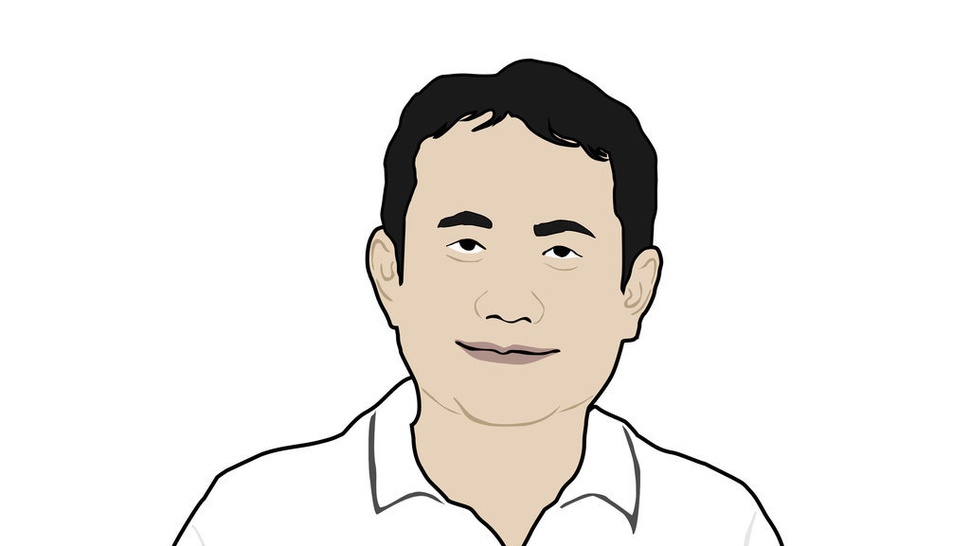tirto.id - Kritik Sukarno dalam esai legendaris "Islam Sontoloyo" yang terbit di berkala Pandji Islam (1940), juga gema yang terdengar lebih verbal dari puisinya Sukmawati Sukarnoputri, bukanlah pikiran tanpa preseden. Kritik terhadap lelaku agama Islam formal -- atau “Arab Islamic Orthodoxy” dalam istilahnya Ben Anderson -- sudah berlangsung lama.
Hal itu bisa dilacak dari sejumlah karya sastra Jawa, seperti Suluk Gaṭolojo dan Serat Darmogandul yang mengkritik dengan terang lagi tajam maupun Serat Wedhatama anggitan KGPAA Mangkunegaran IV yang kritiknya lebih samar. Tulisan ini mencoba menukil sejumlah bagian yang terdapat dalam kitab-kitab di atas, memaparkan muatan kritiknya, dan terakhir melihatnya dalam konteks kekinian.
Kritik yang Samar-Tajam
Wedhatama adalah puisi yang disenandungkan melalui aturan konvensi pelaguan yang memuat tuntunan moral (a didactic poem) yang ditulis pada akhir 1870an. Ia memang diniatkan sebagai kitab tuntunan moral seperti tercermin dalam bait pertama yang menjelaskan tujuan dianggitnya Wedhatama. Pada bait itu, muncul frase mardi siwi yang kira-kira berarti "untuk menuntun anakku" (Robson 1990).
Selain itu, Wedhatama juga kaya dengan kritik terhadap perilaku agama Islam yang lebih sering merujuk Arab daripada Jawa itu sendiri. Atas dasar tersebut, sosok panembahan Sénapati layak menjadi suri tauladan bagi orang Jawa daripada menghadirkan tokoh asing yang berasal dari Arab atau lainnya. Hal itu didasari atas laku asketik yang ditempuh Panembahan Senapati dalam keseluruhan hidupnya.
Hal itu diuraikan dalam pupuh II (canto) metrum Sinom:
Nulada laku utama
Tumrap ing wong tanah Jawi
Wong Agung ing Ngèksiganda
Panembahan Sénapati.
Mencontoh laku hidup utama
Bagi orang yang hidup di Jawa
Orang mulia dari Mataram
Yakni Panembahan Senapati.
Secara implisit, teks ini menganjurkan bahwa tokoh panutan haruslah memiliki jarak referen yang dekat dan sesuai dengan ruh budaya Jawa. Maka, dalam serat tersebut, ditampilkanlah sosok Panembahan Senapati sebagai figur yang dekat dengan orang Jawa. Figur yang berasal dari Arab atau lainnya memiliki jarak referen yang jauh sehingga kesulitan untuk dijangkau.
Hal itu diuraikan dalam baris ke-10:
Lamun sira paksa nulad
Tuladhaning Kangjeng Nabi
O nggèr kadohan panjangkah .
Tatkala dirimu membutuhkan panutan
Lantas dirimu mengikuti Kanjeng Nabi)
Oalah, Nak, apa yang kamu lakukan tersebut terlalu jauh.
Selain itu, metrum sinom baris sembilan juga menggambarkan perilaku orang yang memegang aturan fikih (hukum tuhan), tetapi tidak memahami esensi hukum tersebut. Hal ini mungkin yang paling cocok dengan kondisi Indonesia hari ini.
Deskripsi detailnya sebagai berikut
Anggung anggubel saréngat
Saringané tan dén-wruhi
Dalil dalaning ijemak
Kiyasé nora mikani
Katungkul mungkul sami
Béngkrakan mring masjid agung
Kalamun maca kutbah
Lalagone dhandang gendhis
Swara arum ngumandang céngkok palaran.
Mereka senantiasa melilitkan diri pada hukum Islam
Tetapi esensinya tidak mereka tangkap
Dalil hukum sebagai dasar kesepakatan
Analogi sebagai dasar pengambilan hukum mereka tidak paham
Mereka terlalu berlebihan dalam banyak hal
Berjalan gagah ke masjid agung
Tatkala membaca khutbah
Pelantunannya melalui metrum dhandanggula
Dengan suara manis menggelegar dengan gaya palaran.
Gambaran di atas adalah kritik terhadap praktik ber-Islam yang terjadi pada awal abad ke-19 yang ditandai banyaknya orang yang melilitkan diri (anggubel) pada hukum Islam (fikih), tetapi tidak memahami inti dari hukum tersebut. Mereka bersikukuh memegang dalil, menguasai cara-cara pengambilan hukum melalui qiyas dan ijma’, tetapi mereka tidak menyadari Jawa sangat berbeda dengan Arab. Maka, apa yang mereka lakukan cenderung mengganggap agama sebagai festival atas ketimpangan dan ketidakselarasan atas yang terjadi.
Kritik yang Terang-Tajam
Berbeda dengan Serat Wedhatama, Serat Gatolojo terang-terangan mengkritik praktik Islam. Tidak hanya terang-terangan, malahan disebut memiliki daya ungkap yang kasar. Secara jelas ia memuat daya ungkap yang jorok dan tabu sehingga hal ini membuat priyayi Jawa malu dan merasa marwahnya turun (Anderson 1981). Saking kontroversial isinya, dan memungkinkan menimbulkan kegaduhan di masyarakat, serat ini pernah dilarang peredarannya, dan hanya diedarkan melalui jaringan bawah tanah.
Saya menggunakan sumber dari Serat Balsafah Gaṭolotjo: Ngemot Balsafah Kawruh Kawaskiṭan yang ditulis ulang oleh R. Tanojo bertarikh awal abad XX yang diterbitkan S. Muljo, Solo. Saya akan menukil bagian yang terdapat dalam bab tentang bebantahan ilmu (perdebatan ilmu) yang menggunakan metrum dhandanggula.
Berikut nukilannya:
Gaṭolotjo anauri aris
Rasul Mekah ingkang sira-sembah
Ora nana ing wudjude
Wes séda séwu taun
Panggonané ing tanah ‘Arbi
Lelakon pitung wulan
Tur kadangan laut
Mung kari kubur kewala
Sira-sembah djungkar-djungkir saben ari
Apa bisa tumeka
Gaṭolotjo menjawab dengan bijak
Rasul di Mekah yang kamu sembah
Sudah tidak berwujud lagi
Sudah meninggal seribu tahun lamanya
Tempatnya berada di tanah Arab
Ditempuh perjalanan selama tujuh bulan
Dan terhadang laut
Hanya tinggal makamnya saja
kamu sembah jungkir balik setiap hari
Memangnya yang kamu lakukan bakal sampai?
Teks di atas menggambarkan perdebatan sengit antara Gatolotjo dan Abduljabar tentang tauhid Islam. Bagian di atas adalah jawaban atas pertanyaan tentang kedudukan Nabi dalam Islam yang harus ditiru semua tingkah lakunya oleh umat Islam. Gatolotjo kemudian menyodorkan jawaban yang lugas sekaligus memicu pertanyaan dan perdebatan yang tak berkesudahan.
Apa yang saya paparkan di atas menunjukkan bahwa kritik terhadap Islam tersaji secara gamblang dalam teks klasik Jawa. Di sana terdapat pertarungan memperebutkan wacana dan kuasa seperti diulas oleh Drewes (1966) dalam “The struggle between Javanism and Islam as illustrated by the sĕrat dĕrmagandul”.
Menilik dua serat di atas, Wedhatama memiliki komposisi puitik yang indah dan proposisi kalimat yang tertata sehingga mengakibatkan kritiknya bisa diterima oleh priyayi Jawa dan umat Islam. Setidaknya, serat tersebut masih banyak dilantunkan dan diproduksi hingga sekarang.
Berbeda nasibnya dengan Suluk Gatolotjo dan Serat Darmogandul yang memiliki komposisi kurang indah (ditakar dari sudut pakem) dan cenderung jorok bahkan sejak dari judul. Hal ini mengakibatkan dua teks itu sempat dilarang pada 1963 karena isinya dianggap anti-Islam dan bermuatan pornografis (“Kitab Lelaki Sejati”, Historia).
Poin pentingnya adalah bahwa penyampaian kritik harus dibarengi dengan kejernihan berpikir atau ketuntasan proposisi, apalagi bentuk kritiknya melalui piranti kesusasteraan. Maka, kompetensi kebahasaan dan kesusasteraan yang memadai menjadi prasyarat penting untuk membangun kritik. Dengan demikian, kritik dalam bentuk puisi itu bisa lebih elegan secara bentuk dan makna sehingga substansi kritik dapat terus bergema.
Yang tidak kalah penting adalah efek politik yang ditimbulkan. Di balik produksi teks dan kritik, terselip secara halus pertarungan memperebutkan kuasa dan wacana publik. Pujangga Jawa abad ke-19 memahami dengan baik ihwal kuasa kata yang terselip dalam sastra. Adakah generasi sekarang memahami hal yang sama?
Daftar Pustaka
Anderson, Benedict. 1981. “The Suluk Gaṭoloco: Part One” dalam Indonesia, Vol. 32 (Oct., 1981), pp. 109-150.
Drewes, G.W.J. 1966. “The struggle between javanism and islam as illustrated by the sĕrat dĕrmagandul” dalam Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 122, 3de Afl. (1966), pp. 309-365
Historia, Desember 2012 “Kitab Lelaki Sejati”
Robson, Stuart.1990. The Wedhatama: An English Translation. Leiden: KITLV Press.
Tanojo, R. Tanpa Tahun. Balsafah Gaṭolotjo: Ngemot Balsafah Kawruh Kawaskiṭan. Solo: S. Muljo.
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.