tirto.id - Beberapa minggu yang lalu, mungkin kamu sempat menemui konten “how to not be tone-deaf in social media” di Instagram milik Annisa Steviani, certified financial planner dan content creator tentang pengembangan diri.
Unggahan di akun @annisast ini sukses memicu beragam reaksi dari puluhan ribu follower, apa kamu termasuk di dalamnya?
Dalam kontennya, Annisa membahas tentang orang-orang dengan keistimewaan atau privilege yang cenderung tidak peka secara sosial (socially tone-deaf) saat mengomentari isu-isu di masyarakat.
Annisa terinspirasi untuk membuat konten ini setelah mendapati berbagai komentar di unggahannya sebelumnya yang membahas tentang liburan sebagai kemewahan bagi sebagian besar penduduk Indonesia.
Menurut laporan tentang Milenial dan Gen-Z di Indonesia yang disusun oleh IDN Research Institute pada 2022, hanya 32 persen Milenial dan 20 persen Gen Z yang bisa pergi liburan. Presentasenya lebih mungil lagi bagi yang dapat berlibur ke luar negeri: 5 persen Milenial dan 2 persen Gen Z.
“Di konten itu, saya melihat ada komen-komen seperti, ‘Itu kan hanya masalah prioritas aja’ atau ‘itu mah mereka nggak bisa mengatur keuangan aja’. Lalu saya baca ada satu yang menulis kalau banyak orang privileged yang tone-deaf di kolom komentar ini. Komen ini membuat saya jadi terinspirasi membuat konten tentang tone-deaf di media sosial. Selama ini saya memang banyak bicara tentang privilege dan kesetaraan di konten, karena melihat orang-orang tidak menyadari kalau hidup mereka seberuntung itu,” jelas Annisa.

Privilege atau hak istimewa, didefinisikan di situs dictionary.com sebagai hak atau keuntungan yang diperoleh oleh seseorang atau sekelompok orang akibat lahir, kedudukan sosial, usaha, atau konsesi.
Sebab, orang-orang dengan privilege menjalani keseharian di dalam ruang yang membatasi interaksinya dengan sesama orang ber-privilege saja—bahkan ada yang mengalaminya sedari kecil sampai dewasa.
Tanpa disadari, mereka jadi tidak peka secara sosial karena tidak terpapar pengetahuan tentang pengalaman orang-orang di luar lingkup pergaulannya.
Kebalikan dari kondisi privileged adalah underprivileged—ketidakmampuan untuk menikmati hak-hak istimewa atau bahkan hak-hak normal karena rendahnya status ekonomi dan sosial.
Kondisi underprivileged dikaitkan dengan masyarakat kurang sejahtera dan miskin. Mereka biasanya terbelenggu dalam kemiskinan struktural sehingga kesulitan mengakses pendidikan terbaik dan keterampilan.
Kondisi demikian sulit dihindari karena orang-orang yang sedari kecil terbiasa hidup dalam keterbatasan biasanya takut untuk bermimpi tinggi—dan menganggap segala macam mimpi akan sulit diwujudkan karena tidak adanya dukungan.
Apa saja faktor yang jadi pembeda signifikan antara orang-orang dengan privilege dan kalangan yang underprivileged?
Annisa menuturkan, yang pertama adalah pendidikan. Kalangan underprivileged yang dapat menyelesaikan kuliahnya adalah yang berpotensi untuk mengangkat derajat keluarganya. Sebab, mereka berpeluang mendapat pekerjaan yang lebih baik daripada lulusan SMA.
“Pembelaannya kan, (alm.) Bob Sadino saja dulu tidak kuliah. Namun lihat dulu, dia bisa keliling dunia itu biayanya dari mana kalau tidak dibiayai keluarganya. Balik ke Indonesia, dia tinggal di Kemang (Jakarta) dan punya dua mobil mewah. Kalau kita belum punya privilege seperti itu, lebih baik berusaha keras untuk bisa kuliah. Soalnya, pendidikan itu yang akan berhasil membawa seseorang ke taraf kehidupan yang lebih baik,” jelas Annisa.
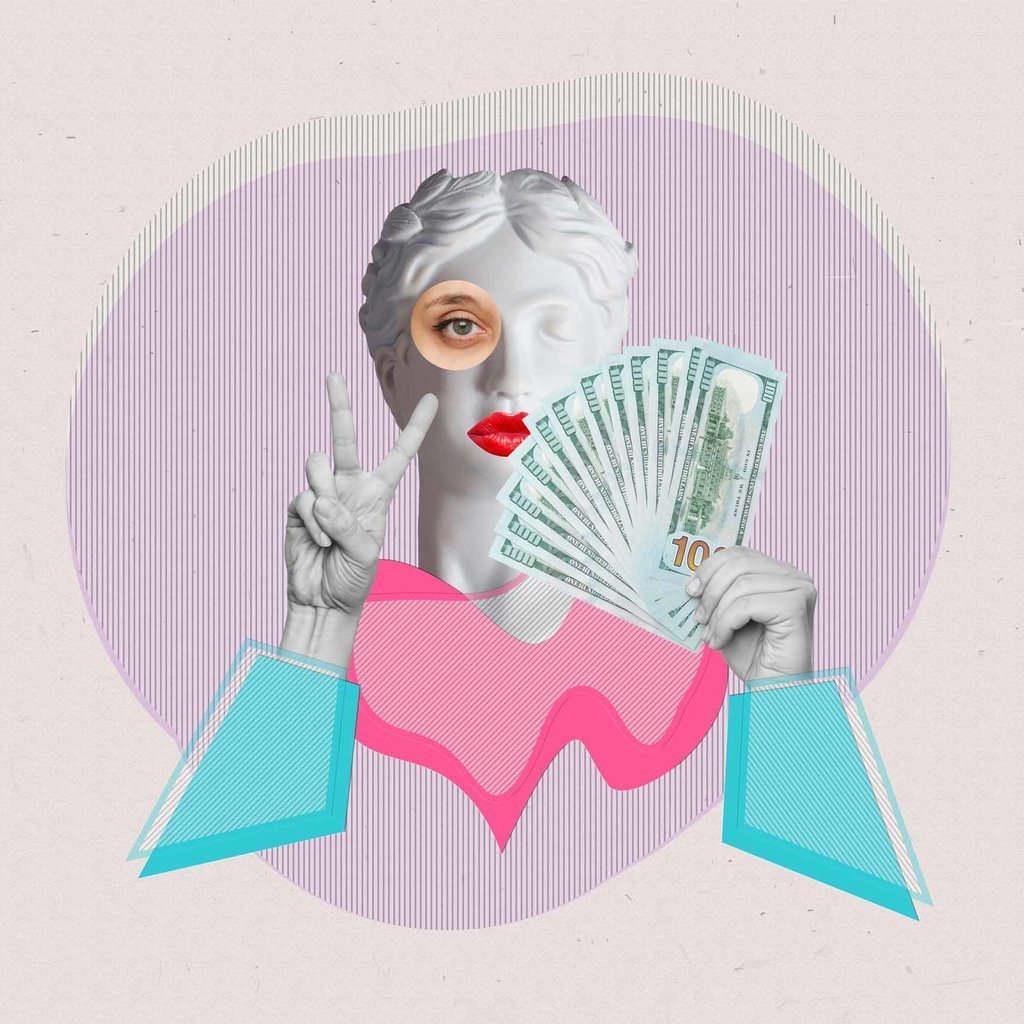
Faktor kedua adalah kesehatan. Menjaga kesehatan anak sejak kecil dan memastikan asupan gizinya tercukupi merupakan investasi agar ia memiliki hidup berkualitas di masa depan. Dengan demikian, anak dapat menjalani tumbuh-kembang dengan optimal, leluasa bermain dan belajar.
Namun perlu diingat, menjaga kesehatan membutuhkan biaya besar. Di Indonesia, tak semua vaksinasi diberikan secara gratis. Biaya untuk memenuhi asupan gizi juga tak sedikit. Ini yang membuat orang tua dari kalangan underprivileged cenderung kurang optimal dalam menjaga kesehatan anak.
Faktor terakhir adalah akses. Ambil contohnya masyarakat Jakarta. Meski sebagian tergolong kelas bawah, mereka cenderung memiliki privilege lebih besar daripada masyarakat di pelosok daerah.
Jumlah sekolah yang banyak membuat akses pendidikan menjadi lebih mudah bagi anak-anak Jakarta. Jarak antara rumah dan sekolah pun cenderung dekat—berbeda dari anak-anak di desa yang terkadang perlu menempuh jarak lebih jauh untuk mengakses sekolah dan area kota.
Akses infrastruktur seperti listrik, internet, jalan raya, air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah dapat tersedia dengan cepat. Sayangnya, tak semua penghuni ibukota menyadari privilege yang mereka miliki ini.
Lalu, apa artinya kelompok privileged akan secara otomatis menjadi tone-deaf secara sosial, sementara kelompok underprivileged selalu rendah diri dan merasa kalah?
Belum tentu. Semua kembali lagi ke masing-masing orang.
Orang privileged misalnya, apabila sadar betul dengan keistimewaannya, tentu akan berusaha keluar dari gelembung zona nyaman untuk belajar berinteraksi dan bergaul dengan orang-orang yang punya keseharian berbeda.

Satu hal yang ditekankan oleh Annisa, kamu tak perlu malu atau merasa bersalah apabila terlahir atau tumbuh dewasa dengan privilege.
“Kalau ada yang bilang orang-orang yang privileged ini tone-deaf dan tidak berempati, menurut saya bukan seperti itu, ya. Bisa jadi karena mereka memang tidak paham kalau menilai sesuatu itu tidak bisa berdasarkan circle mereka saja, tapi dari kondisi seluruh masyarakat Indonesia,” jelas ibu satu anak ini.
Apabila kamu masih berjuang dengan segala keterbatasan, jangan sampai pasrah dengan kondisi. Perjuanganmu, seperti menjalani kuliah sembari bekerja sampingan atau merawat orang tua, tentu sangat berat. Namun penting diingat, sesuatu yang sulit bukan berarti mustahil dilakukan.
Kerja kerasmu boleh jadi akan jauh lebih bermakna dan berbuah lebih manis daripada kalangan privileged yang biasanya mudah terjebak rasa nyaman sehingga cenderung enggan berusaha lebih keras.
Agar semakin bersemangat, tak ada salahnya untuk menyimak kisah inspiratif orang-orang dari keluarga sederhana yang bekerja keras sampai sukses mewujudkan mimpi dan penghidupan lebih baik. Tetap semangat, ya!
Penulis: Yunita Lianingtyas
Editor: Sekar Kinasih












