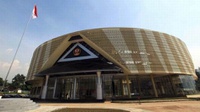tirto.id - Jadi wartawan? Pernah. Jadi pelawak? Itu juga dilakoninya. Jadi aktor? Dia bisa. Jadi penyiar radio? Sudah dicoba.
Dia adalah Soleh Solihun, si orang Bandung kelahiran 1979, yang pengalamannya semasa studi ilmu komunikasi di Universitas Padjadjaran melapangkannya menjadi jurnalis hiburan dan kemudian selebritas.
“Saya sama teman-teman merasa tersesat di Fikom Unpad. Dikiranya Unpad itu di Dipati Ukur (nama seruas jalan di Kota Bandung), tetapi ternyata di Jatinangor (Kabupaten Sumedang),” ujar Soleh.
Masuk kuliah pada 1997, Soleh merasakan gelora gerakan mahasiswa yang sedang memuncak.
“Tahun 1997-1999, di Fikom Unpad Persma (pers mahasiswa) yang ada serius semua, tentang politik dan hal-hal yang berat. Jauh dari kehidupan mahasiswa. Itu bukan selera saya,” ujar Soleh.
Merasa tidak punya wadah, akhirnya Soleh bersama beberapa temannya mendirikan persma Karung Goni (Kabar Ungkapan Gosip dan Opini). Seperti namanya, Karung Goni memproduksi berita ringan seputar kagiatan mahasiswa Unpad, dari profil tim basket fakultas sampai gosip mahasiswa, plus resensi festival, album, dan film teranyar.
Keisengan Soleh nyatanya membawa berkah. Kemampuannya menulis hiburan mengantarnya diterima sebagai wartawan di Trax Magazine. Awal kariernya pun tak jauh dari dunia jurnalisme hiburan, khususnya musik. Selepas Trax (2004-2005), Soleh melanjutkan karier di majalah Playboy Indonesia (2006-2008) lalu Rolling Stone (2008-2012). Setelah itu barulah Soleh menekuni stand-up comedy.
Jumat, 27 November 2017, Soleh Solihun berkunjung ke kantor Tirto. Bukan sebagai komika tunggal, melainkan seorang sutradara sekaligus aktor dalam film Mau Jadi Apa? Bersama sejumlah rombongan kru dan pemain film yang dirilis akhir bulan November ini, Soleh Solihun berbincang dengan redaksi Tirto.
Apa bedanya jadi pemain atau aktor dan sutradara?
Perbedaannya banyak. Kalau jadi pemain, kendali kreatif kita hanya sampai di take, atau pas reading kita bisa kasih saran ke sutradara. Kalau jadi sutradara, saya punya kendali banyak, dari pra-produksi sampai pos-produksi. Bedanya di situ.
Sebagai aktor, begitu beres syuting, ya sudah. Menyerahkan sepenuhnya ke editor, sutradar, produser. Ketika jadi sutradara saya punya suara menentukan arah film ini mau ke mana. Misalnya, editing jangan begini, atau scoring-nya jangan begitu, dan grafisnya seperti apa.
Susah enggak, sih, jadi sutradara?
Ya lebih susah jadi gubernur (sambil tertawa). Anggarannya banyak.
Kalau bedanya menjadi stand-up comedian?
Beda-beda. Semua ada kenikmatan masing-masing. Jad stand-up comedian kerjanya cepat. Jadi sutradara kerjanya lama. Kalau stand-up comedian, kan, hasilnya dinikmati segelintir orang kalau tampil di program televisi yang ratingnya kecil. Atau kalau kita main off-air, orang juga tahunya sedikit. Kalau jadi sutradara, ada kemungkinan karya kita dinikmati banyak orang.
Jadi stand-up comedian itu tekanannya gede banget. Karena kita sendirian, kalau lucu itu usaha kita sendiri, kalau enggak lucu enggak ada yang nolongin. Kalau bikin film banyak yang bantu. Mau jadi pemain, kita dibantu skrip, dibantu sutradara, editing, scoring. Adegan yang biasa aja bisa jadi sangat lucu. Kalau bikin film, orang enggak akan menyalahkan satu pihak karena itu kerjaan banyak orang.
Stand-up comedian lagi dapat momen, nih. Seperti itu enggak?
Karena stand-up comedian, kan, sudah terbiasa menulis. Skrip lawakannya bikin sendiri. Mungkin kalau di luar negeri, stand-up comedian yang sudah puluhan tahun, mungkin punya tim penulis. Kalau sekarang kami menulis sendiri. Itulah mengapa sekarang stand-up comedian lagi laku karena mereka bisa bikin adegan lucu.
Kalau bikin film komedi, ini ada anak-anak yang segar, umurnya muda, tapi lucu, dan budget-nya lebih rendah dari pemain-pemain senior. Dan produser enak, dengan harga yang relatif murah, tapi dapat hal bagus. Angkanya bersahabat tapi hasilnya maksimal.
Kalau ngambil pelawak-pelawak yang sudah terkenal, budgetnya besar. Dibanding 5 stand-up comedian masih lebih mahal 1 Gading Martin.
Sekarang banyak komika bikin film. Menurut pandangan Soleh Solihun, itu film yang dihasilkan benaran berkualitas atau aji mumpung karena komikanya yang terkenal?
Kalau bicara stand-up comedian yang bikin film baru 3 orang, Raditya Dika, Kemal Pahlevi, dan Ernest Prakasa. Yang laku baru Raditya Dika sama Ernest Prakasa. Kemal Pahlevi belum laku.
Kalau kita bicara kualitas, ya relatif siapa yang melihat. Kalau misalnya dari sisi penonton, filmnya Raditya Dika bagus. Tetapi kalau dari sisi kritikus, filmnya Raditya Dika tidak bagus karena tak mendapat penghargaan satu pun. Kalau bicara Ernest Prakasa, dari sisi kualitas diakui kritikus, dapat penghargaan, kemarin menang Piala Citra, dan dapat banyak penonton.
Buat menghargai seni tidak ada yang pasti. Kata kritikus filmnya Raditya Dika jelek, tetapi kata ABG-ABG yang nonton film itu bagus.
Tergantung siapa yang melihat, ukurannya apa dulu.
Kalau seorang Soleh Solihun melihat film yang bagus seperti apa? Atau film komedi yang bagus seperti apa?
Film komedi yang bagus itu, ya, yang lucu. Kalau enggak lucu ya enggak bagus. Kalau kita bicara film komedi yang bagus, apakah itu lucu, itu nomor satu. Yang kedua, secara produksi bagus, itu juga bisa dilihat dari banyak hal. Mulai dari lighting, scoring, editing, atau skripnya. Bisa dilihat juga dari sisi aktor atau aktris mainnya bagus apa nggak. Kalau untuk film tidak bisa dilihat dari satu sisi saja.
Popularitas komika sangat berpengaruh bagi film yang mereka buat?
Raditya Dika enggak bisa dipungkiri sudah terkenal dari dulu, sejak dia menulis Kambing Jantan. Tapi kita bisa lihat apakah nama menjadi satu-satunya faktor yang membuat sebuah film laku? Filmnya Raditya Dika yang The Guys cuma 500 ribu yang nonton. Mungkin tema yang diangkat tidak disukai penggemarnya Raditya Dika, atau mungkin promonya kurang.
Sedangkan pemain film Pengabdi Setan tidak ada yang begitu terkenal. Tara Basro meskipun terkenal tetapi bukan tipe terkenal seperti Tora Sudiro. Film itu bisa mencapai 4,2 juta penonton.
Ada juga kasus Reza Rahardian, Chelsea Islan, Bunga Citra Lestari main di satu film, itu enggak laku. Filmnya Fedi Nuril dan Acha Septriasa yang Bara Kaki tidak laku.
Sebetulnya kalau bicara film, soal nama berpengaruh hanya satu faktor. Faktor berikutnya adalah promosi. Ambil contohnya Pengabdi Setan. Di posternya enggak ada muka pemainnya, tetapi tetap laku.
Film yang dibintangi stand-up comedian sebenarnya sudah banyak. Tema-tema yang diangkat kebanyakan personal. Namun seiring waktu, mereka mulai berani membuat film-film bertema sensitif, seperti The Interview yang membahas Korea Utara dan AS hingga The Big Sick tentang pernikahan orang Pakistan dengan orang AS, padahal mereka dilarang menikah beda agama dan beda negara. Di Indonesia, saya belum melihat film stand-up comedian seperti itu...
Pertama, karena baru 3 stand-up comedian yang bikin film. Jadi ibaratnya masih terlalu dini untuk menilai. Kedua, karena keresahan. Ya mungkin belum ada tema-tema yang Anda sebutkan itu yang meresahkan mereka. Kalau pasar, kan, pasti, ya. Karena dari awal bikin sinopsis harus dilihat sama produsernya. Pertimbangan film ini bakal laku apa enggak pasti ada.
Sering mendengar tentang film yang dibilang receh banget? Apakah itu sebuah konsekuensi?
Saya, sih, tidak masalah, ya. Mungkin dia bermaksud seperti itu. Itu lagi-lagi tergantung yang melihat. Ada yang bilang receh, ada yang bilang itu bagus.
Bodo amat gitu, ya?
Selama enggak menghina orang. Kalau karya dia dianggap receh atau dangkal, ya sudahlah, toh dia juga enggak korupsi, enggak ngambil uang rakyat, enggak nyerang orang yang berbeda keyakinan. Kalau pun saya enggak suka dengan yang receh-receh itu, mending saya bikin aja karya yang bagus.
Ternyata Soleh Solihun orangnya serius.
Saya lucu kalau dibayar saja. Penyanyi kalau diwawancara emangnya nyanyi? Enggak kan?
Gimana bedanya, dulu mewawancara sekarang diwawancara?
Bedanya sekarang kalau diwawancara saya suka menganalisis si pewawancara. Misalnya, kalau saya jawab begini kok dia enggak nanya ini lagi yang mestinya bisa di-follow up? Bagi saya, ‘Oh ini orangnya enggak terlalu ngerti temanya’ atau ‘oh, ini orangnya belum melakukan riset’.
Sebagai narasumber, ekspektasi terhadap sebuah wawancara asal dikutip aja syukur. Soal tulisannya bagus apa enggak itu urusan kedua. Sudah terlalu banyak bertemu wartawan, benar konteksnya saja sudah syukur. Masalah enak apa enggak tulisannya enggak jadi soal, yang penting enggak salah kutip.
Termasuk Rolling Stone?
Saya belum pernah diwawancara Rolling Stone. Saya waktu itu mau masuk Rolling Stone yang 4 halaman itu pun wawancara orang lain. Ada edisi saya dan Pandji (Pragiwaksono). Mereka tulis pun berdasarkan blog atau pres rilis yang saya kasih.
Belum pernah diwawancara Rolling Stone, belum ada yang dianggap layak mungkin.
Sebelum malang-melintang di dunia film, lalu di dunia stand-up comedy, Anda, kan, wartawan. Masih merhatiin dunia jurnalisme dan digital?
Ya, masih. Saya sebel dengan media-media yang ngasih judul bombastis. Bahkan, media-media gede pun ikutan ngasih judul-judul berita yang bombastis. Saya sering mikir, “Judul macam apa ini?”
Mungkin trennya sekarang seperti itu yang biasanya orang baca.
Kok bisa Soleh Solihun sampai sejauh ini?
Enggak tahu. Saya bukan tipe yang merencanakan yang jauh-jauh hari. Saya terbiasa hidup untuk hari ini. Semua yang didapatkan sekarang bukan sesuatu yang saya rencanakan. Saya jadi stand-up comedian pun enggak saya rencanakan. Tiba-tiba aja saya ditawari Metro TV karena saya pernah bikin video stand-up comedy. Itu pun karena di Rolling Stone saya jadi MC setahun sendirian, terus orang menganggapnya lucu.
Orang yang pertama kali bilang saya stand-up comedy itu Cholil (Mahmud) Efek Rumah Kaca. Cholil bilang, “Kok lu nge-MC nya kayak orang lagi stand-up?”
Saya bukan orang yang suka stand-up comedy. Pas ditawarin Metro TV, bayarannya gede, ya ambil aja. Itu pun tiba-tiba ditawarin aja.
Pas wisuda dari Fikom Unpad, memangnya ingin kerja apa?
Kan sudah tahu sebelum wisuda saya sudah kerja. Karena bikin Karung Goni tadi. Ada satu dosen, namanya Pak Sahala, mengajar di jurnalistik. Saya ngeh, ternyata saya bisa nulis. Ya sudahlah jadi wartawan aja.
Setelah bikin Karung Goni, saya mau jadi wartawan musik. Karena suka musik dan malas baca berita lain. Tahu-tahu seminggu sebelum wisuda, ditawari kerja di Trax. Tahu-tahu bikin Playboy. Begitu Playboy bubar, tahu-tahu ditawari Rolling Stone.
Enggak pernah merencanakan jauh-jauhlah. Karena kalau terlalu merencanakan jauh-jauh, suka lupa mensyukuri nikmat.
Penulis: Husein Abdulsalam
Editor: Zen RS