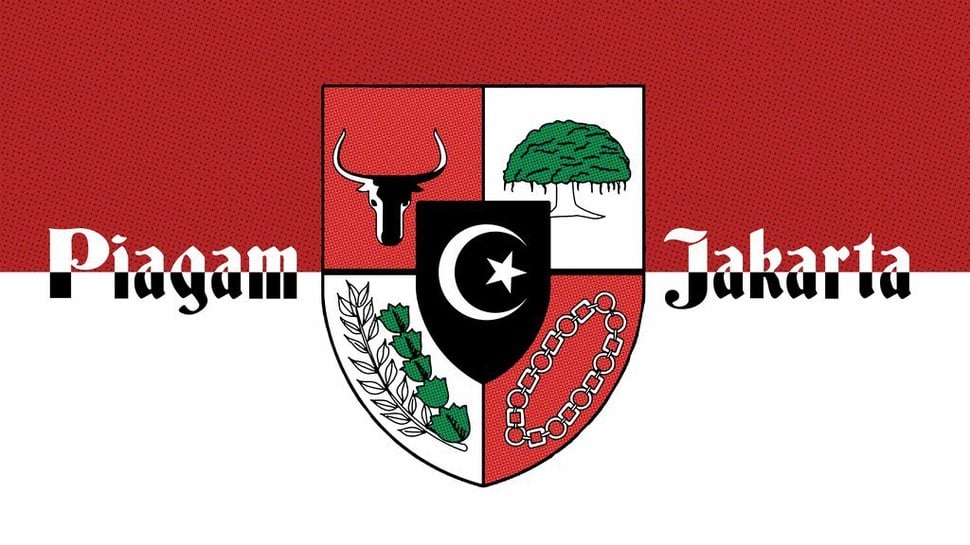tirto.id - Kamis malam, 16 Agustus 1945, Mohammad Hatta baru pulang dari Rengasdengklok. Ia harus begadang dan sahur di rumah Laksamana Maeda. Hatta dan Sukarno harus merampungkan naskah Proklamasi. Sesudahnya Hatta sahur dengan roti, telur, dan sarden. Setelah pulang sebentar, pagi hari 17 Agustus, ia berdiri di samping Sukarno untuk membacakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
Namun, situasi di masa revolusi itu tak bikin jenak. Baru tadi pagi Proklamasi dibacakan, Hatta mesti menghadapi situasi pelik yang bisa bikin negara baru ini terancam cerai.
Sore itu, 17 Agustus, sebagaimana ditulis dalam autobiografinya, Mohammad Hatta: Memoir (1979), ia kedatangan seorang opsir Angkatan Laut Jepang (Kaigun). Di Indonesia, Kaigun berkuasa di wilayah Indonesia timur plus Kalimantan.
“Opsir itu, yang aku lupa namanya, datang sebagai utusan Kaigun untuk memberitahukan sungguh, bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik, yang (tinggal di wilayah yang) dikuasai Kaigun, berkeberatan sangat terhadap bagian kalimat dalam pembukaan Undang-undang Dasar, yang berbunyi: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”
Kalimat itu bagian dari kesepakatan yang disusun oleh Panitia Sembilan, bentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Kesepakatan tersebut ditandatangani pada 22 Juni 1945, tepat hari ini 75 tahun lalu, dan dikenal sebagai Piagam Jakarta. Tujuh kata itu sensitif serta dianggap menusuk hati orang-orang Indonesia nonmuslim.
“Akibatnya mungkin besar, terutama terhadap agama lain [….] kalimat ini bisa juga menimbulkan kekacauan...,” protes Johannes Latuharhary, dikutip dalam Piagam Jakarta 22 Juni (1981).
Meski golongan Islam mengakui kalimat itu tidak mengikat warga nonmuslim, dan hanya ditujukan kepada rakyat beragama Islam, tetapi bagi Hatta, “tercantumnya ketetapan seperti itu di dalam suatu dasar yang menjadi pokok Undang-Undang Dasar berarti mengadakan diskriminasi terhadap mereka (yang) golongan minoritas.”
Ancamannya sangat serius, tulis Hatta. “Jika diskriminasi itu ditetapkan juga, mereka lebih suka berdiri di luar Republik Indonesia.”
Hanya salah satu anggota Panitia Sembilan beragama Kristen; ia adalah A.A. Maramis. Sisanya beragama Islam, dan empat di antaranya mendaku sekuler: Sukarno, Hatta, Achmad Soebardjo, M. Yamin, Wahid Hasjim, Abdoel Kahar Moezakir, Abikusno Tjokrosoejoso, dan Haji Agus Salim.
“Mr. Maramis, yang ikut serta dalam Panitia Sembilan, tidak mempunyai keberatan apa-apa, dan pada 22 Juni, ia ikut menandatangannya [...] mungkin waktu itu Mr. Maramis cuma memikirkan, bahwa bagian kalimat itu hanya untuk rakyat Islam yang 90 persen jumlahnya, dan tidak mengikat rakyat Indonesia yang beragama lain. Ia tidak merasakan bahwa penetapan itu adalah suatu diskriminasi,” pandangan Hatta mengenai Maramis.
Namun, tetap saja, di mata Hatta, “Pembukaan Undang-undang Dasar adalah pokok dari pokok, sebab itu harus teruntuk bagi seluruh bangsa Indonesia dengan tiada kecuali.”
Menurut H. Endang Saifuddin Anshari, yang berlatar belakang aktivis Pelajar Islam Indonesia (PII), dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945, “Kesembilan penandatangan Piagam Jakarta itu sungguh-sungguh representatif mencerminkan alam dan aliran pikiran dalam masyarakat Indonesia.”
Esok harinya, 18 Agustus—tepat hari ke-10 bulan Ramadan 1364 H, Kasman Singodimedjo diminta Sukarno datang untuk membicarakan masalah itu dengan Hatta dan beberapa tokoh lain. Kasman adalah tokoh Islam dari Muhammadiyah.
Dalam buku tentang dirinya, Hidup Itu Berjuang: Kasman Singodimedjo 75 Tahun (1982), Kasman berkata bahwa bukan Sukarno yang pagi itu datang untuk bicara dengan dia. Melainkan Hatta dan Mr. Teuku Mohammad Hasan.

Sukarno tak muncul, menurut Kasman, karena “merasa agak kagok untuk menghadapi Ki Bagus Hadikoesoemo (Ketua Muhammadiyah) dan kawan-kawannya.” Jadi, Sukarno diwakili Mr. Hasan ke gelanggang lobbying.
Menurut Dwi Purwoko dalam Dr. Mr. T.H. Moehammad Hasan (1995), “Teuku Mohammad Hasan diundang karena kehidupan keagamaannya serta hubungan baiknya denga kalangan Islam.”
Tak lama setelah Kasman datang, sebelum Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dimulai, Hatta dan beberapa tokoh Islam melakukan pembicaraan terbatas. Hatta mengajak “Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo dan Teuku Hasan dari Sumatera mengadakan rapat pendahuluan untuk membicarakan masalah itu.”
“Ingin sekali mempertahankan Piagam Jakarta sebagai unit secara utuh, tanpa pencoretan atau penghapusan dari tujuh kata termaksud [….] tetapi saya pun tidak dapat memungkiri untuk menghilangkan, (karena) adanya situasi darurat dan terjepit sekali itu,” ujar Kasman dalam bukunya, lebih dari tiga dekade sesudahnya.
Meski alot, setelah rapat selama 15 menit, tujuh kata dalam Piagam Jakarta itu pun dihapus. Alasan dominan: Republik Indonesia harus berdiri dengan menyertakawan kawasan Indonesia timur.
“Perubahan yang disetujui lima orang tadi, sebelum rapat resmi, disetujui oleh sidang lengkap PPKI dengan suara bulat. Sesudah itu dipersoalkan Undang-undang Dasar yang seluruhnya, dengan mengadakan sedikit perubahan sana-sini yang tidak prinsipil,” tulis Hatta.
Ancaman tentara Sekutu kala itu membuat Kasman setuju sila pertama itu diubah. Sebagai perwira PETA, Kasman sadar bahwa kekuatan persenjataan Indonesia tidak mumpuni menghadapi Sekutu. Pisahnya Indonesia timur sama saja memperlemah Republik Indonesia yang baru berumur sehari.
Perubahan pada sila pertama itu, seperti yang kita kenal sekarang, berbunyi: Ketuhanan yang Maha Esa. Ia menjadi landasan pokok untuk seterusnya bagi Republik Indonesia.
==========
Artikel ini pertama kali ditayangkan pada 20 Juni 2017 dan merupakan bagian dari laporan mendalam tentang Piagam Jakarta. Kami melakukan penyuntingan ulang dan menerbitkannya kembali untuk rubrik Mozaik.
Editor: Fahri Salam & Ivan Aulia Ahsan