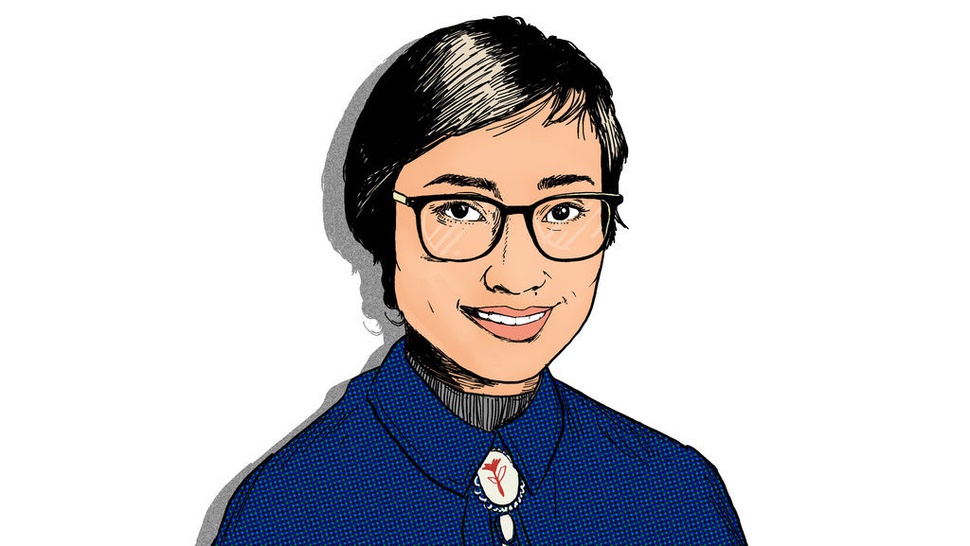tirto.id - Di tengah peringatan kemerdekaan Indonesia, asrama mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya diserang. Para penghuninya diteriaki “monyet”. Kabar ini tentu tak mengejutkan bagi siapa pun yang paham isu Papua dan penderitaan yang dialami masyarakatnya.
Serangan terhadap orang Papua sudah berulangkali terjadi, baik di dalam maupun luar Papua, dan dilakukan oleh polisi/militer Indonesia dan/atau warga sipil. Tanggal seperti 1 Juli, 17 Agustus, dan 1 Desember adalah waktu ketika polisi dan tentara akan mengambil tindakan keras terhadap orang Papua—sebagai catatan, operasi militer di Nduga berlangsung sekitar 1 Desember 2018. Serangan yang baru-baru ini terjadi di Surabaya relatif bisa diprediksi.
Namun, di luar tanggal-tanggal itu, orang Papua terlalu sering mendapatkan serangan. Tak berlebihan mengatakan setiap hari ada orang Papua mengalami kekerasan dan dibunuh di kampung halamannya sendiri. Di rantau, mahasiswa Papua akrab disergap oleh ormas dan/atau polisi/tentara ketika mengadakan diskusi, pemutaran film, atau sekadar berkumpul.
Pasal 28E UUD 1945 menjelaskan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Ini berarti mahasiswa Papua berhak menggelar pertemuan, dan hak itu dijamin oleh konstitusi. Namun, kenyataannya, negara sering (membantu) menghentikan paksa pertemuan-pertemuan ini.
Sudah seharusnya kita bertanya: Kalau Papua bagian dari NKRI, mengapa hak konstitusional mereka diinjak-injak?
Serangan terhadap orang Papua kerap mendapat pembenaran atau pemakluman dari pemerintah Indonesia. Mahasiswa Papua di Surabaya diserang karena bendera Indonesia ‘ditemukan’ di selokan persis di depan asrama mereka pada hari peringatan kemerdekaan Indonesia—dengan kata lain, ketika mereka diharapkan untuk mengibarkan dan menghormati setinggi-tingginya bendera merah putih yang dianggap mewakili para pejuang Indonesia.
Ironisnya, bendera yang sama digunakan untuk membenarkan aksi-aksi pembunuhan sadis terhadap orang Papua yang memperjuangkan kemerdekaan mereka dari Indonesia. Tahun lalu, serangan militer di Nduga—yang telah mengakibatkan banyak orang mengungsi hingga hari ini—dijustifikasi sebagai respons atas pembunuhan pekerja konstruksi oleh 'kelompok bersenjata'.
Semestinya kita bertanya: jika pekerja Indonesia memang dibunuh kelompok bersenjata, mengapa pembalasan dendam tertuju kepada warga sipil? Berbagai macam pembenaran ini menyatakan serangan-serangan terhadap orang Papua adalah salah orang Papua sendiri.
Haruskah kita menerima narasi victim blaming (menyalahkan korban) ini sebagai satu-satunya kebenaran?
Meski begitu, Papua punya narasi sendiri yang, sayangnya, jarang diangkat sebagai narasi tandingan oleh media-media arus utama. Narasi-narasi ini muncul di media Papua, misalnya JUBI dan West Papua Updates.
Jika kita membandingkan narasi Indonesia dan Papua, terlihat pemerintah Indonesia selalu memainkan narasi besar yang sama untuk bermacam-macam kasus—dan saking seringnya diputar, nadanya seperti kaset rusak. Sangat disayangkan mayoritas orang Indonesia gagal menyadari unsur ‘kaset rusak’ dalam pernyataan-pernyataan para pejabat Indonesia, meski bukan tanpa alasan.
Sepanjang sejarah Indonesia sebagai negara-bangsa, orang Papua dilihat sebagai masalah. Bukan masalah yang harus dipecahkan lewat pembicaraan dan perundingan, melainkan masalah yang harus "diurus", sebagaimana tersirat dalam kata "tumpas" yang digunakan untuk membungkam setiap gerakan dari Papua. "Tumpas" di sini bermakna mengganyang, menghabisi, membasmi dengan segala cara, entah itu lewat wacana maupun tindakan militer.
Penumpasan lewat wacana memili daya hancur yang kuat. Saking kuatnya, narasi-narasi tandingan sangat sulit diterima oleh masyarakat umum dan mementahkan—jika bukan membungkam—segala ikhtiar untuk mencari keadilan.
Sejak dianeksasi Indonesia pada 1960-an, tanah Papua telah direbut dan dieksploitasi oleh banyak pihak, sementara rakyatnya menjadi—meminjam Frantz Fanon—kaum “yang terkutuk di bumi” (les damnés de la terre). Orang Papua dianggap "primitif", "tak berpendidikan", "setengah binatang", sasaran pembangunan yang sia-sia, sekaligus penghalang masuknya investasi asing ke pegunungan Papua yang kaya sumber daya alam.
Singkatnya: orang Papua cuma dianggap masalah, tetapi tidak sumber daya alamnya.
Sebagai masalah, orang Papua tidak pernah dilihat setara dengan orang Indonesia. Orang Papua tidak dipandang sebagai manusia dan bangsa yang mampu menentukan nasib sendiri serta mengelola tanah dan kekayaan secara mandiri. Asumsi ini jelas terlihat selama Operasi Trikora (1961-62) untuk mencegah pembentukan “Negara Boneka Papua”.
Di bawah Presiden Sukarno, Indonesia yang belum lama merdeka memilih untuk percaya bahwa Belanda bermaksud menyerahkan kemerdekaan kepada orang Papua sambil melanggengkan kontrol atas bekas jajahannya itu. Konsekuensi dari posisi ini: Indonesia harus bergegas "menolong" Papua—menyelamatkan Indonesia dan Papua sekaligus.
Tak bisa tidak, tindakan semacam itu berwatak kolonial dan rasis.
Pertama, "menyelamatkan sekumpulan khalayak" adalah alasan mendasar di balik kolonialisme yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa. Kedua, klaim Papua hanya akan jadi "negara boneka" jika merdeka didasarkan pada asumsi bahwa orang Papua tak memiliki kapasitas untuk memerintah masyarakatnya sendiri.
Sejak itulah pembayangan orang Papua tak punya kemampuan memerintah bangsanya sendiri (sehingga perlu diselamatkan) melandasi hubungan antara orang Indonesia dan orang Papua.
Seribu Wajah Rasisme
Rasisme bukan sekadar tindakan diskriminatif secara manasuka. Dalam pelbagai wujudnya, rasisme adalah keyakinan struktural dan sistemik bahwa kelompok-kelompok manusia tertentu lebih rendah derajatnya.
Dalam kasus Indonesia dan Papua, ekspresi rasisme tak sebatas serangan terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan kota-kota lain di Indonesia, bukan juga sekadar olok-olok yang menyamakan orang dengan "monyet".
Rasisme terhadap orang Papua tampil dalam banyak wajah, dari kelangkaan guru dan dokter di banyak daerah di Papua hingga proyek-proyek pembangunan (termasuk jalan dan jembatan) yang lebih menguntungkan pendatang Indonesia ketimbang orang asli Papua.
Rasisme juga terlihat dari penggambaran personel militer Indonesia sebagai "pekerja kemanusiaan" alih-alih pasukan bersenjata, hingga penggambaran orang Papua sebagai "pemberontak" berbahaya yang membawa penderitaan bagi rakyat Papua sendiri.
Rasisme muncul pada diri orang Indonesia yang memakan mentah-mentah narasi besar bikinan para pejabat negara, orang-orang Indonesia yang menutup telinga dari suara-suara orang Papua dan menyebut kisah-kisah orang papua sebagai "provokasi". Rasisme hadir dalam sikap orang Indonesia terhadap orang Papua yang seringkali dilandasi belas kasihan ketimbang solidaritas.
Rasisme juga muncul dalam pelabelan orang Papua sebagai "orang bodoh", "pemabuk", "kasar", "monyet dungu" yang menjalani hidup bak mop Papua yang patut kita ditertawakan. Kita lupa bahwa mop Papua, lelucon-lelucon khas ini, adalah cara orang Papua menertawakan kekerasan brutal yang mereka alami, lengkap dengan logika kekuasaan dan dominasi kolonial yang menyertainya.
Setelah kejadian di Surabaya, orang Papua mengubah olok-olok "monyet"—dari semula merendahkan kemanusiaan menjadi seruan untuk bertindak. Dari sana, orang-orang Papua di Jayapura dan Manokwari turun ke jalan untuk melawan dehumanisasi atas diri mereka dan mengutuk rasisme Indonesia yang terang-terangan.
Tekanan besar ini rupanya cukup mampu memaksa Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk minta maaf. Meskipun disambut baik, permintaan maaf ini hanya awal dari kerja-kerja berat melawan prasangka orang Indonesia terhadap orang Papua dan menghabisi rasisme.
Orang Papua tak perlu diselamatkan. Mereka lebih dari mampu untuk berdiri di atas kaki sendiri. Yang mereka butuhkan adalah solidaritas agar kita, orang Indonesia, membersihkan hati nurani dan membiarkan orang Papua menentukan nasib sendiri.
Jika ada yang perlu diselamatkan adalah "kemanusiaan" Indonesia. Kita perlu menyelamatkan diri dari rasisme kita sendiri, dari rasa kemanusiaan kita yang telah rusak, dari mental kolonial yang bersemayam dalam diri.
============
Versi awal tulisan ini berbahasa Inggris. Diterjemahkan oleh Irma Garnesia
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.