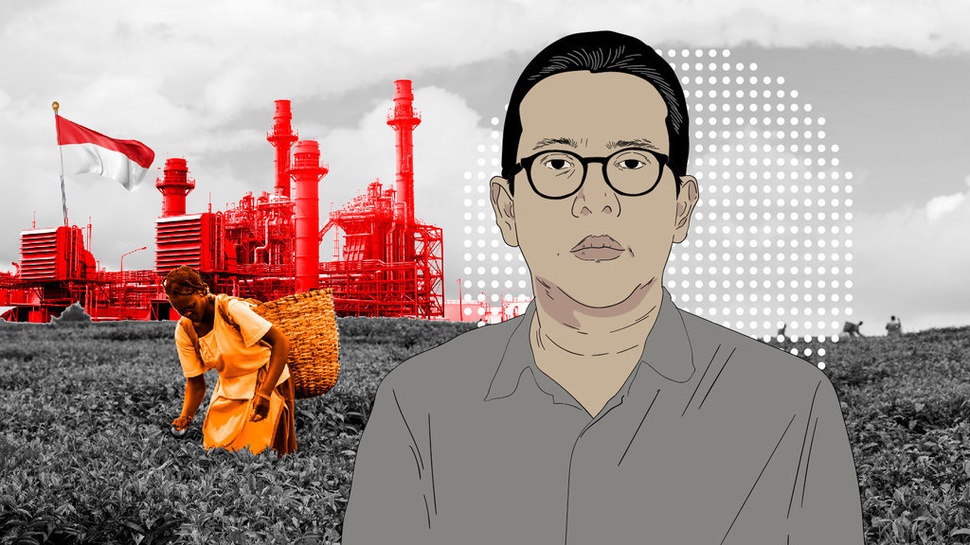tirto.id - Nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia pada 1957 dilakukan dengan terburu-buru. Saat itu Indonesia belum memiliki tenaga profesional yang siap untuk menjalankan perusahaan. Kekosongan tersebut diisi dengan melibatkan tentara di level kepemimpinan dan manajemen.
Sebenarnya kelompok kiri adalah pihak yang paling berkehendak menguasai perusahaan yang dinasionalisasi. Apalagi para buruh lah yang mula-mula melakukan nasionalisasi lewat aksi-aksi mereka. Tapi pemerintah mencegahnya dengan keterlibatan tentara. Masalahnya, tentara bukan pihak yang cakap mengelola bisnis. Dan dari situ lah korupsi di tubuh perusahaan milik negara mulai merajalela.
"[...] ketika tentara yang memimpin, perusahaan juga tidak jalan. Sama saja, terjadi KKN. Itu memang penyakit karena nasionalisasi [dilakukan] tanpa kesiapan," tutur Bondan Kanumoyoso, sejarawan dan pengajar Departemen Ilmu Sejarah FIB UI
Penulis Tirto Fadrik Aziz Firdausi mewawancarai Bondan Kanumoyoso pada Kamis (8/8/2019). Pada 2001 Bondan menerbitkan buku bertajuk Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia. Buku tersebut diangkat dari tesis masternya di Universitas Indonesia.
Berikut wawancara utuh dengan doktor sejarah lulusan Universitas Leiden itu.
Literatur yang khusus membahas peristiwa nasionalisasi perusahaan Belanda 1957-1958 dan dampak setelahnya sangat minim. Buku yang Anda tulis adalah satu-satunya yang membahasnya secara khusus. Jadi, bagaimana nilai peristiwa ini dalam sejarah Indonesia merdeka?
Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Merdeka itu, kan, bukan hanya soal politik, tapi juga soal ekonomi, budaya, sosial, dan aspek-aspek lain. Tapi yang menonjol saat itu memang kemerdekaan politik. Sehingga ketika merdeka dan menegakkan kedaulatan selama revolusi, masalah-masalah itu kurang terperhatikan. Baru setelah Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949 isu ekonomi mulai terekspos. Dalam KMB Belanda memperjuangkan kepentingan ekonominya di Indonesia agar tetap bertahan, karena kolonialisme Belanda coraknya memang kolonialisme ekonomi.
Gara-gara itu, tujuan proklamasi dan perjuangan Indonesia dalam KMB untuk menegakkan kedaulatan tidak sepenuhnya tercapai. Kedaulatan Indonesia di bidang ekonomi patut dipertanyakan. Itu jadi masalah sepanjang tahun-tahun 1950-an. Isu ini lama-lama jadi besar karena pemerintah sendiri juga tidak bisa memberi jawaban yang memuaskan kepada masyarakat.
Puncaknya, masyarakat memutuskan sendiri bahwa persoalan ini harus segera diatasi. Kemudian inisiatif itu diwujudkan dalam bentuk pengambilalihan perusahaan Belanda. Dalam konteks itu, nasionalisasi sudah tentu peristiwa besar. Ini upaya masyarakat menegakkan kedaulatan ekonomi. Ini tonggak penting.
Jadi, nasionalisasi ini adalah kebijakan yang berkait dengan hasil-hasil KMB?
Ini memang satu tahap perkembangan. Dalam KMB ada klausul yang mengakomodasi kepentingan ekonomi Belanda, agar perusahaan-perusahaan Belanda tidak diganggu. Juga kemudian bank sentral itu harus tetap De Javasche Bank. Padahal Pemerintah Indonesia sudah mempersiapkan BNI pada 1946 untuk jadi bank sentral. Jelas gila jika suatu negara berdaulat, kok, bank sentralnya kepunyaan negara asing.
Jadi sebetulnya Belanda itu tidak memberikan pengakuan kedaulatan secara utuh. Pengakuan kedaulatan di KMB adalah keterpaksaan Belanda yang saat itu ditekan secara internasional. Kedaulatan ekonomi itulah yang kemudian [hendak] direbut.
Lalu, bagaimana kondisi ekonomi dan pelaku bisnis Indonesia sendiri pada dekade 1950-an?
Ketika Indonesia merdeka, lapisan-lapisan masyarakat sebenarnya belum siap. Karena selama dihegemoni Belanda, mayoritas masyarakat Indonesia ada di lapisan bawah. Kolonialisme menyebabkan kelas menengah Indonesia diisi oleh orang-orang timur asing, yaitu orang Cina dan Arab. Jadinya, ketika Indonesia merdeka, kelas menengah pribuminya kosong. Kalaupun ada, tipis sekali dan konsentrasi mereka kebanyakan di bidang politik, bukan ekonomi. Sehingga perusahaan-perusahaan Belanda itu sukar diganggu karena orang Indonesia sendiri belum siap.
Secara manajerial dan pendidikan kita belum kuat. Warga terdidik sampai jenjang tinggi totalnya paling hanya dua persen dari populasi. Lulusan tingkat SMA saja jumlahnya baru seribu atau dua ribu di seluruh Indonesia. Jelas tidak cukup untuk mengelola Indonesia yang penduduknya saat itu sekitar 60 juta. Kondisi riil itu tidak menguntungkan. Yang ada, kita punya semangat tinggi, tapi secara profesional belum siap.
Dalam kondisi macam itu, desakan untuk nasionalisasi datang dari mana?
Justru dari masyarakat bawah. Tapi kemudian tidak terakomodasi oleh kelompok elite politik di pemerintahan. Hanya beberapa elite politik yang melihat masalah ini. Kalau kita ingat, Tan Malaka semasa revolusi itu punya program “Merdeka 100 Persen”. Nah, pengikutnya dan orang-orang kiri umumnya sangat mendukung nasionalisasi.
Tapi ada yang tidak terpikirkan oleh mereka: jika ada nasionalisasi, apakah orang Indonesia bisa mengelolanya? Itu masalah. Antara semangat dan realitas bertentangan. Dan lagi selama itu, isu ini dijadikan jargon politik oleh kelompok tertentu untuk menekan pemerintah. Aspirasi ekonomi masyarakat dijadikan alat untuk kepentingan politik. Jadi, nasionalisasi ini rumit sebenarnya.
Hanya berselang beberapa hari setelah PBB menolak membicarakan sengketa Irian Barat, para buruh melakukan pengambilalihan perusahaan Belanda. Apakah momentum ini kemudian jadi kunci melakukan nasionalisasi?
Dua isu ini memang saling memengaruhi. Masalah Irian Barat itu menambah masalah kedaulatan jadi kian besar. Indonesia sudah merdeka, tapi masyarakat merasa pengaruh Belanda, kok, tetap kuat. Yang terasa, di bidang ekonomi kiprah Indonesia tidak terlihat. Keutuhan wilayah juga tidak terwujud sepenuhnya karena Irian Barat masih dikuasai Belanda.
Kalau salah satu saja dari dua masalah itu tidak ketemu solusinya, kemungkinan akan pecah jadi konflik. Terbukti ketika untuk kesekian kalinya PBB menolak usulan Indonesia membahas masalah Irian Barat. Itu menimbulkan kemarahan masyarakat yang sudah menunggu momentum untuk mengambil tindakan terhadap Belanda.
Bisa dibilang, masalah Irian Barat adalah pemicu untuk mempercepat nasionalisasi. Tapi sebetulnya tanpa ada masalah itu pun Indonesia akan tetap melakukan nasionalisasi di kemudian hari.
Pemerintah juga berencana melakukan nasionalisasi?
Proses nasionalisasi sebenarnya sudah berlangsung. Misalnya De Javasche Bank yang dinasionalisasi secara gradual, tidak dadakan, dan dilakukan oleh serikat-serikat buruh seperti pada 1957. Pemerintah secara bertahap membeli sahamnya mulai 1951. Pada 1953 sahamnya terbeli semua dan ganti nama jadi Bank Indonesia. Tapi direksinya masih diisi orang-orang Belanda yang baru diganti semua pada 1957.
Apakah wacana nasionalisasi di kalangan buruh mengemuka gara-gara masalah Irian Barat di akhir 1957?
Tidak, karena sebelum tahun itu wacana sudah ada. Bahkan dari daerah-daerah, bukan hanya dari Jakarta. Saya temukan arsip sekretariat kabinet adanya surat tuntutan dari buruh perminyakan di Sumatra dan Cepu sekitar 1953. Tuntutan juga ada dari buruh perkebunan. Mereka menuntut harus ada tindakan dari pemerintah terhadap perusahaan yang dikuasai orang Belanda. Demonstrasi-demonstrasi sporadis di beberapa tempat juga ada.
Ketika sengketa Irian Barat gagal dibawa ke PBB, sebagai balasan pemerintah menyerukan agar buruh-buruh di perusahaan Belanda mogok kerja. Mereka kemudian bertindak lebih jauh melakukan pengambilalihan aset. Bagaimana reaksi masyarakat atas peristiwa itu?
Masyarakat yang jenuh dengan dominasi Belanda tentu menyambut hangat. Aksi pengambilalihan itu disambut sebagai kemenangan ekonomi. Setelah sekian lama bekerja di bawah bos-bos orang Belanda, akhirnya perusahaan itu jadi milik Indonesia. Mereka senang tapi tidak sadar bahwa masalah sebenarnya adalah bagaimana menjalankan perusahaan itu. Para buruh, kan, tidak mengerti persoalan manajerial perusahaan modern. Orang-orang kiri juga punya banyak jargon, tapi tidak mengerti soal-soal manajerial macam itu. Itulah ironinya.
Beberapa tokoh elite, seperti Sjafruddin Prawiranegara dan Hatta, sebenarnya mengerti bahwa nasionalisasi tidak bisa berjalan tanpa persiapan matang. Karena itu mereka selalu bilang, nasionalisasi itu sebenarnya masalah gampang. Kesiapan kita mengelola itulah masalah sebenarnya.
Sementara Sukarno memandang nasionalisasi itu sebagai kesempatan untuk menyelesaikan Revolusi Indonesia. Maka lakukan saja. Jika di kemudian hari timbul masalah, bisa diselesaikan bertahap. Yang penting kedaulatan tegak dulu.
Jadi, bisa dibilang nasionalisasi 1957 itu adalah proses yang tergesa-gesa?
Kalau melihatnya dari perspektif saintifik, tentu saja terburu-buru karena masyarakat belum siap. Tapi, sekali lagi, bagi masyarakat yang merasakan tekanan dominasi Belanda, saat itu adalah momentum terbaik.
Lalu, bagaimana reaksi internasional?
Bagi Amerika Serikat atau anggota PBB lainnya konflik Indonesia dan Belanda itu sudah bukan lagi isu strategis. Kebanyakan sudah tidak peduli. Toh, kepentingan-kepentingan mereka di Indonesia tidak ikut diganggu.
Tapi bagaimana dampak nasionalisasi terhadap usaha Indonesia merebut Irian Barat dari Belanda?
Saya kira itu jadi tekanan bagi Belanda. Peristiwa nasionalisasi juga menunjukkan bahwa jika PBB tidak mau mendukung penyelesaian sengketa Irian Barat, Indonesia bisa bertindak lebih tegas.
Dampak bagi perekonomian Indonesia sendiri?
Jelas kacau. Perusahaan-perusahaan itu jadi berhenti produksi sampai keluarnya Undang-Undang Nasionalisasi pada 1958. Semua jadi stagnan karena buruh-buruh itu tidak mengerti bagaimana manajemen dan alur produksi perusahaan. Akhirnya pemerintah menugaskan golongan yang di masa itu dianggap punya tingkat pendidikan paling lumayan di antara golongan lain, yaitu Angkatan Darat.
Setidaknya tentara punya standar pendidikan, walaupun sebenarnya bukan untuk mengurusi perusahaan. Tentara punya struktur dan kepatuhan pada hierarki, sementara buruh tidak. Akhirnya merekalah yang diutus untuk menertibkan proses pengambilalihan perusahaan yang berantakan.
Nah, saat itulah awalnya konsep dwifungsi yang disuarakan Nasution diimplementasikan. Setelah itu banyak tentara yang jadi pemimpin perusahaan, seperti Ibnu Sutowo yang menguasai perusahaan minyak. Itu juga jadi masalah di kemudian hari.
Gerakan pengambilalihan dilakukan pada Desember 1957, tapi aturan resminya baru terbit Desember 1958. Dalam jangka waktu setahun itu apa saja yang terjadi pada perusahaan-perusahaan yang diambilalih?
Untuk tindakan yang sebelumnya tidak direncanakan, undang-undangnya bisa terbit dalam setahun itu termasuk cepat sebenarnya. Pemerintah, kan, tidak merencanakan nasionalisasi, tapi mereka membiarkan para buruh bergerak mengambilalih perusahaan Belanda. Ketika nasionalisasi terjadi, pemerintah tentu tidak siap. Maka itu Undang-Undang Nasionalisasi 1958 berlaku surut.
Undang-undang itu mengamankan tindakan pengambilalihan oleh para buruh sebelumnya agar tidak muncul kekacauan dan tuntutan hukum. Tindakan pengambilalihan itu, kan, bisa dibilang perebutan aset orang dan tidak ada payung hukumnya. Pengambilalihan itu sebenarnya bisa dituntut ke pengadilan internasional. Pemerintah pun pada akhirnya harus bayar ganti rugi karena aset-aset perusahaan itu diambil secara ilegal dan aset-aset itu juga diasuransikan.
Perusahaan-perusahaan itu lalu diubah statusnya jadi BUMN. Direksinya diisi tentara, karena tentu saja tidak mungkin mempersiapkan kelas menengah profesional hanya dalam setahun. Pada akhirnya perusahaan-perusahaan itu stagnan juga.
TNI ditempatkan di perusahaan yang dinasionalisasi untuk mencegah orang-orang kiri mengambil keuntungan. Tanggapan Anda?
Ya memang begitu. Kalau dikuasai kelompok politik tertentu, aset-aset perusahaan itu nantinya juga bisa digunakan untuk kepentingan politik. Kelompok yang paling bersemangat dalam isu nasionalisasi juga memang orang-orang kiri. Bagi mereka, ini kesempatan yang tidak boleh dilewatkan untuk menanamkan pengaruh di sektor ekonomi. Hal itu yang kemudian dicegah oleh pemerintah dengan menugaskan tentara.
Tapi, ketika tentara yang memimpin, perusahaan juga tidak jalan. Sama saja, terjadi KKN. Itu memang penyakit karena nasionalisasi [dilakukan] tanpa kesiapan. Jadi masalahnya itu bukan siapa yang pegang kendali, tapi memang Indonesia belum siap.
Lantas, bagaimana nasib buruh setelah perannya digeser tentara?
Ya balik ke posisinya semula, jadi pekerja tingkat bawah lagi karena posisi-posisi manajerial diisi tentara. Tentara memang lebih rapi dalam hal organisasi, tapi tetap tidak bisa mengembangkan lebih lanjut. Mereka-mereka ini yang kemudian menumbuhkan kelas menengah baru di masa Soeharto. Bahkan saya kira pengaruhnya merentang hingga kini. Tapi seperti yang dikatakan Yosihara Kunio, kelas menengah Indonesia itu kelas menengah semu. Mereka lahir karena patronase, persekutuan politik, dan KKN, bukan dari profesionalisme.
Terakhir, refleksi apa yang bisa dipetik dari peristiwa ini?
Saya kira pelajaran dari proses nasionalisasi dan setelahnya, bahwa setiap kebijakan yang fundamental semestinya dipersiapkan dengan matang. Jangan sampai dikalahkan oleh kepentingan politik jangka pendek. Karena dampaknya terasa sampai puluhan tahun kemudian.
Penulis: Fadrik Aziz Firdausi
Editor: Ivan Aulia Ahsan