tirto.id - Apa yang ada di benak khalayak umum ketika membayangkan sosok pegawai CIA (Badan Intelijen Amerika Serikat)? Industri perfilman Hollywood kerap mencitrakannya dengan aktor laga gagah perkasa, seperti Alec Baldwin, Harrison Ford dan Ben Affleck yang memerankan tokoh agen CIA dalam franchise film Jack Ryan pada dekade 1990-an. Ben Affleck juga pernah memerankan orang CIA dalam film peraih Oscar, Argo (2012), yang naskahnya diadaptasi dari kisah nyata agen CIA tentang misi penyelamatan diplomat Amerika dari Teheran semasa Revolusi Iran.
Namun demikian, pegawai CIA tak melulu staf operasional di lapangan, dan tak mesti melibatkan laki-laki mapan berkulit putih—setidaknya demikian yang berusaha disampaikan CIA belakangan ini. Melalui serial iklan Humans of CIA yang rilis sepanjang tahun 2021, CIA gencar mempromosikan inklusivitas dalam program rekrutmen staf mereka. Setiap video berisi pengalaman pribadi segelintir anggota masyarakat minoritas yang berhasil lolos jadi pegawai CIA.
Figur-figur tersebut meliputi perempuan dengan gangguan penglihatan yang diterima sebagai resepsionis kantor CIA, sampai laki-laki gay sebagai staf Perpustakaan CIA di Langley, markas besar CIA di Virginia. Tatkala kamera menyorot wajah sang pustakawan yang tersenyum sumringah, terdengar suaranya bernarasi dengan meyakinkan, “Inklusi adalah nilai inti di sini. Pegawai dari level atas sampai bawah, bekerja keras untuk memastikan bahwa setiap orang—terlepas dari jenis kelamin, identitas gender, ras, disabilitas, hingga orientasi seksual—bisa membawa diri mereka seutuhnya untuk bekerja setiap hari.”
Iklan lainnya menyorot sosok perempuan berkulit hitam dengan model rambut kepang cornrow, dan perempuan keturunan Asia sebagai staf sekuriti.
Dari sekian iklan yang sudah disiarkan, publik memberikan reaksi paling heboh pada iklan yang rilis akhir Maret silam dan menampilkan tokoh perempuan Latina bernama Mija. Alih-alih mempromosikan CIA sebagai institusi yang berorientasi misi dan tujuan, tokoh Mija cenderung fokus pada identitas dirinya. “Aku perempuan kulit berwarna. Aku seorang ibu. Aku adalah milenial cisgender yang pernah didiagnosis dengan gangguan kecemasan umum,” ujarnya penuh percaya diri.
“Aku berpendidikan, berkualifikasi dan kompeten, dan terkadang aku pun kerja banting tulang,” lanjutnya. Maksudnya: ia memenuhi tugas sebagai ibu untuk kedua anak laki-lakinya, di samping menyelesaikan pekerjaan kantor. Mija juga mengaku pernah berjibaku dengan sindrom impostor. Namun, sebagaimana ia tegaskan, “Memasuki usia 36 tahun, aku menolak untuk menginternalisasi ide-ide sesat patriarki tentang apa yang bisa atau seharusnya perempuan lakukan.”
Dalam rangka menarik minat kaum milenial untuk bergabung bersama mereka, CIA serius menampilkan iklan dengan isu-isu hangat di kalangan muda Amerika: marginalisasi, feminisme, interseksionalitas, sampai kesehatan mental. Belakangan ini, beragam diskursus yang populer dengan istilah “woke” itu menjadi perangkat ampuh untuk mengkritik ketimpangan sosial.
Istilah “Woke” merujuk pada kesadaran akan keadilan sosial, biasanya terkait ras dan gender, yang ramai disuarakan oleh komunitas kulit hitam Amerika. Istilah ini semakin mainstream semenjak maraknya kasus kematian orang-orang kulit hitam di tangan polisi, terutama sejak 2014, ketika Michael Brown tewas ditembak di Ferguson, Missouri. Seiring waktu, “woke” erat asosiasinya dengan gerakan Black Lives Matter.
Semangat “woke” disambut dengan sinis oleh kelompok konservatif sayap kanan dari Amerika Serikat sampai Inggris Raya. Mereka memandang arus politik ini tak lebih sebagai kedok baru dari gerakan kiri lama, yang bagi kaum konservatif berimbas pada intoleransi atau penindasan terhadap pihak-pihak yang punya pandangan berbeda.
Ketika CIA ikut menggunakan narasi “woke” tersebut dalam program rekrutmennya, respons ganas pun muncul dari kalangan konservatif. Mengomentari video iklan yang menampilkan staf perempuan Latina, jurnalis di situs berita ultra-konservatif Breitbart John Nolte menulis, “Video ini membuktikan bahwa CIA tidak hanya bertekuk lutut pada Kultus ‘Woke’, tapi juga mempekerjakan dan aktif merekrut orang-orang paling tidak sopan, narsis, dan egois di seluruh dunia—Generasi Milenial yang ‘Woke’.”
Putra mantan presiden Trump, Donald Trump Jr., sempat berkicau bahwa intelijen Cina dan Rusia bakal terpingkal-pingkal setelah mengetahui CIA berusaha membangkitkan semangat “woke” dalam institusinya. Sementara itu, kantor berita Fox mewawancarai mantan pegawai CIA Bryan Wright yang menganggap pendekatan “woke” dalam iklan rekrutmen CIA sebagai “sampah propaganda”.
Pada waktu sama, CIA juga dikritik karena sudah memanfaatkan narasi “woke” untuk membingkai ulang dirinya sebagai “start-up gaul” semata-mata agar kaum muda terpesona. Layaknya kembang gula untuk memoles pahitnya riwayat misi-misi rahasia mereka selama ini, narasi “woke” dipakai untuk mengalihkan perhatian publik dari peranan CIA sebagai otak di balik kejahatan-kejahatan politik yang telah terdokumentasikan secara masif: memata-matai dan menindas tokoh pejuang hak-hak sipil dan aktivis anti-perang, merencanakan pembunuhan dan rekayasa kudeta terhadap pemimpin-pemimpin Dunia Ketiga yang tak disukai Paman Sam, mengerahkan praktik-praktik penyiksaan dalam rangka memperoleh jawaban informan, sampai mendukung penumpasan gerakan kiri di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara selama Perang Dingin yang mengorbankan rakyat sipil.
Jejak Berdarah CIA di Afrika
Iklan CIA berusaha memikat kalangan kulit berwarna Amerika, terutama orang-orang kulit hitam. Padahal, merunut sejarahnya, CIA pernah melibatkan mereka untuk mengawasi para aktivis kulit hitam penggerak kampanye hak-hak sipil sejak dekade 1960-an.
Melansir artikel New York Times pada 17 Maret 1978, terungkap bagaimana CIA merekrut orang-orang kulit hitam untuk memata-matai Black Panther Party, baik di Amerika Serikat maupun Afrika. Organisasi politik revolusioner ini berdiri pada 1966 di Oakland, California sebagai bentuk kekecewaan atas kegagalan gerakan hak-hak sipil dan perbaikan kesejahteraan komunitas kulit hitam. Dikutip dari laman Smithsonian Institution, para pendiri Black Panther Party, Huey Newton dan Bobby Seale, memandang kebrutalan aparat terhadap aktivis pembela hak-hak sipil sebagai tradisi warisan dari kekerasan polisi dan penindasan oleh negara.
Ada dua program utama yang dilancarkan CIA kepada Black Panther. Pertama, CIA mengerahkan agen-agen kulit hitam dalam operasi “Merrimac” di kawasan Washington D.C. Dokumen yang diterima The Times menunjukkan bagaimana para agen rahasia berkulit hitam menghadiri protes dan acara publik lainnya, termasuk upacara pemakaman, untuk mendandai siapa saja anggota Black Panther. Sekiranya 12 orang agen dilibatkan untuk memotret dan mendokumentasikan aktivis Panther, menguntit mobil mereka sampai ke rumah. Program lainnya adalah penempatan sejumlah agen Amerika kulit hitam di Afrika Timur dan Utara, di antaranya di Aljazair, Kenya dan Tanzania, untuk mengawasi kegiatan aktivis kiri Amerika kulit hitam di sana.
CIA juga punya rekam jejak kelam di sejumlah negara bekas koloni di Afrika. Sebut salah satunya terkait tokoh nasionalis Pan-Afrika, Patrice Lumumba, perdana menteri pertama Kongo tak lama setelah negara tersebut merdeka dari Belgia pada 1960. Selama pemerintahan Lumumba, Kongo dihadapkan pada pemberontakan militer, perlawanan dari kelompok-kelompok separatis di provinsi Katanga yang kaya mineral, hingga kehadiran kembali prajurit Belgia. Karena Lumumba merapat ke Uni Soviet, Paman Sam pun khawatir Soviet akan dengan mudah menyebarkan pengaruhnya di Afrika.
Menurut informasi yang diperoleh New York Times pada 1981, CIA menyusun segudang rencana untuk melenyapkan Lumumba, mulai dari menggantinya dengan pemimpin yang pro-Amerika, sampai membubuhi racun pada pasta giginya. Meskipun rencana-rencana tersebut tak kesampaian dilakukan, bukti-bukti mengarah pada keterlibatan kaum elite diplomat Amerika dan intelijen CIA di ibukota Léopoldville untuk membantu musuh-musuh politik Lumumba. Pada akhirnya, Lumumba tewas di tangan kelompok separatis pada Januari 1961.
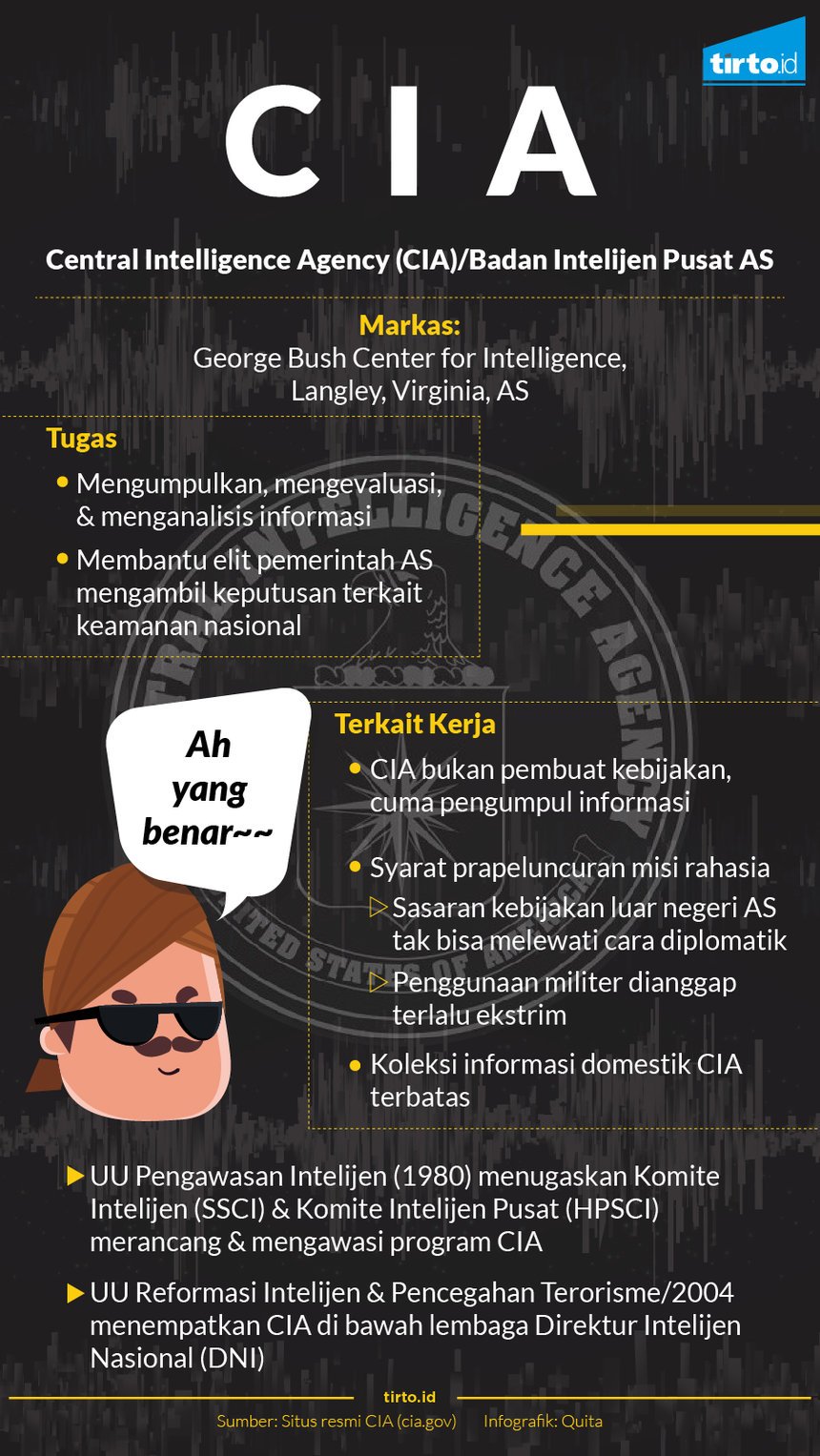
Beberapa tahun kemudian, diktator sokongan Amerika, Mobutu Sese Seko, mulai berkuasa. Selama 32 tahun berada di pucuk kepemimpinan Kongo, ia mendapatkan perlindungan luar biasa dari Paman Sam yang membanjirinya dengan dana bantuan sekitar USD 2 triliun.
Selama itu pula, intelijen Amerika dapat kemudahan akses untuk menjalankan misi-misinya di Angola, negara tetangga Kongo. Di Angola, front pembebasan Angola (FNLA) memperjuangkan kemerdekaan negeri dari pemerintahan kolonial Portugis (1961-74). FNLA rutin mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat, sampai akhirnya Portugis undur diri. Setelahnya, Angola jatuh dalam perang sipil. Dalam carut-marut konflik, CIA bersama dengan intelijen Afrika Selatan, memberikan sokongan terhadap organisasi anti-komunis UNITA dalam rangka menumbangkan MPLA (Popular Movement for the Liberation of Angola), partai politik berhaluan Marxis yang sejak 1975 berkuasa di Angola dengan dukungan pasukan Kuba dan Uni Soviet.
Dalam buku United States Foreign Policy Towards Southern Africa (1987), H. E. Newsum dan Olayiwola Abegunrin menyebutkan, sepanjang tahun 1975-76, CIA menyuplai FNLA dan UNITA dengan persenjataan bekas Perang Dunia II. Masih dilansir dari buku yang sama, tim propaganda CIA juga berperan menyebarluaskan artikel-artikel berita untuk memperkuat dukungan terhadap FNLA/ UNITA. Staf-staf CIA di Lusaka (ibukota Zambia) dan Kinshasa/Léopoldville (Kongo) dikabarkan suka memberikan bahan berita kepada koran-koran setempat, di samping juga mengirimnya kepada kantor-kantor perwakilan CIA di penjuru dunia agar agensi berita internasional ikut mempublikasikannya. Sebagai contoh, Reuters pernah menerbitkan berita palsu dari Lusaka tentang penangkapan 20 orang penasihat dari Soviet dan 35 dari Kuba oleh pasukan UNITA. Washington Post ikut mempublikasikannya pada November 1975.
CIA juga pernah dikabarkan berada di balik penangkapan tokoh anti-apartheid Afrika Selatan tahun 1962, Nelson Mandela, yang juga pemimpin angkatan bersenjata Kongres Nasional Africa (ANC). Kala itu, Amerika Serikat memandang pemerintahan apartheid sebagai sekutu untuk melawan gerakan komunis. Mandela pun dicap sebagai komunis dan teroris. Organisasi ANC sendiri diketahui mendapat dukungan dari pemerintah Uni Soviet, Kuba, dan Libya. CIA tak pernah berkomentar tentang tuduhan keterlibatan mereka dalam penangkapan Mandela, meskipun setelah bebas dari penjara tahun 1990 intelijen Washington dipastikan masih terus memonitor Mandela karena memandangnya sebagai tokoh komunis berbahaya.
Slogan Inklusif dan “Woke”: Sekadar Ikut-ikutan Tren?
Sejak dekade 1960-an, CIA terlibat dalam misi-misi yang menindas orang-orang kulit hitam: mulai dari mensabotase gerakan hak-hak sipil orang kulit hitam di Amerika, sampai mengacaukan pemerintahan negara-negara Afrika yang baru merdeka. Tidaklah mengherankan, semangat inklusivitas dan “woke” yang digaungkan CIA belakangan ini menimbulkan tanda tanya karena terkesan kontras dari misi-misi CIA yang menindas kelompok minoritas dan bangsa asing.
Sebelum serial iklan rekrutmen CIA yang “woke” dirilis, CIA sebenarnya sudah mendompleng gerakan solidaritas kulit hitam lewat film box office produksi Marvel, Black Panther (2018). Melalui karakter intelijen CIA berkulit putih, Everett Ross (diperankan oleh aktor Martin Freeman), CIA menampilkan agennya sebagai figur heroik yang tulus membantu rakyat Wakanda menyelamatkan bangsanya dari ancaman tokoh antagonis Erik “Killmonger” Stevens. Singkatnya, CIA mencitrakan dirinya sebagai ally alias sekutu bagi bangsa kulit hitam.
Saking hebohnya film ini, CIA sampai mengulas teknologi futuristik vibranium yang diperebutkan di Wakanda, lewat artikel serius nan informatif berjudul “Wakandan Technology Today: A CIA Scientist Explores the Possibilities”.
Menurut Douglas Taylor dari California State University, artikel teknologi tersebut bisa disebut sebagai “alat rekrutmen” untuk penggemar film Black Panther yang rata-rata anak muda dan berasal dari kalangan kulit berwarna. Terlepas dari itu, seperti Taylor tegaskan dalam studinya yang berjudul “Black Panther: Cinematic Masterpiece or CIA Recruitment Video?” (2019), bukan berarti sutradara film Ryan Coogler terang-terangan membantu CIA untuk merekrut kaum muda kulit hitam. Justru, menurut Taylor CIA sekadar oleh cerita yang sudah disediakan Black Panther”.
Editor: Windu Jusuf












