tirto.id - Wawan membuka sebuah warung di Kampung Wadat. Tak banyak yang ia jual, hanya kopi kemasan siap seduh dan setalam gorengan berbonus cabai rawit.
Warung yang menyatu dengan rumahnya ini terletak di Desa Cikawao, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Dari jalan raya Pacet, posisinya di sebelah timur, dihubungkan oleh jalan desa yang semakin menanjak.
Nama aslinya Wawat, tapi waktu kecil dia cadel, sehingga setiap melafalkan namanya sendiri yang terdengar justru kata “Wawan”. Maka sampai hari ini, pada usianya yang sudah berkepala enam, nama yang biasa dipakai laki-laki inilah panggilannya.
Menurutnya, ia lahir pada 1956 di Kampung Legok Ombol, Desa Nagrak, Kecamatan Pacet. Masa kecilnya dipenuhi kisah tentang pengungsian. Rumah orang tuanya dibakar kelompok bersenjata. Seperti penuturan sejumlah orang tua pada laporan saya yang pertama, ia menyebut kelompok ini dengan sebutan “gerombolan”.
“Zaman Pak Kartosoewirjo,” katanya.
Dalam ingatannya, selain Kampung Legok Ombol, beberapa kampung lain pun ikut hangus dibakar, di antaranya Kampung Selaawi, Kampung Bojong, Kampung Cikaso, dan Kampung Pelag. Sementara Kampung Panca yang menjadi salah satu markas tentara hanya diserang tembakan.
Sebelum rumah orang tuanya dibakar, setiap malam ia dan keluarganya bersembunyi di sekitar rumpun-rumpun bambu yang rapat. Tidur sekadarnya, yang penting aman dari gangguan gerombolan. Berangkat menjelang magrib, dan kembali ke rumah setelah matahari cukup hangat, sekitar pukul tujuh atau delapan pagi.
Sebelum bersembunyi, setiap hari orang tuanya menyediakan beras di depan rumah untuk gerombolan, dan adakalanya ditambahi lauk pauk sekadarnya. Bahan makanan itu diletakkan di papanggé atau tangga kecil untuk naik ke rumah.
Wawan mengatakan, selain bersembunyi di sekitar rumpun-rumpun bambu, sejumlah warga juga bersembunyi di lubang-lubang kecil yang sengaja digali dekat rumahnya masing-masing.
Ia berkisah, setiap hari di tahun-tahun genting itu, hampir tak ada pemuda di kampung, para gadis pun amat sedikit. Yang tersisa hanya orang tua dan anak kecil. Para pemuda takut dibawa paksa gerombolan untuk turut dalam barisannya, sementara para gadis, terutama yang berparas cantik, takut diculik.
“Sora tembakan kadangu unggal wéngi, mung abdi teu kantos ningali tentara atanapi gorombolan. Atuda alit kénéh, sieun, mung ngingiring sepuh wé (Suara tembakan setiap malam terdengar, tapi saya tak pernah melihat langsung tentara [TNI] maupun gerombolan. Maklum masih kecil, takut, hanya ikut saja ke mana orangtua pergi),” ujarnya.
Setelah rumahnya hangus, dan tinggal sepanjang hari di sekitar rumpun-rumpun bambu tak memungkinkan, ia dan orang tuanya akhirnya mengungsi ke Kota Bandung. Mereka menumpang di rumah saudaranya di Gang Halte, Kelurahan Ciroyom, Kecamatan Andir.
Setelah situasi aman, ia dan keluarganya kembali ke kampung dan tinggal di rumah neneknya. Pada usia 13, tepatnya setelah lulus sekolah dasar, ia menikah dengan Adang yang saat itu bekerja sebagai juru tulis di balai desa Cikawao, Kecamatan Pacet.
“Da kapungkur mah biasa yuswa sakitu téh tos dinikahkeun ku sepuh (Dulu usia segitu biasanya sudah dinikahkan oleh orang tua),” ucapnya sambil tersenyum.

Mengungsi ke Paledang dan Sawah Kurung
Wawan memberitahu, jika hendak menggali cerita-cerita lain seputar zaman gerombolan, sebaiknya menemui suaminya yang usianya jauh lebih tua.
"Nuju di tonggoh ngalereskeun jalan, di payun bumi pun anak, caket pom bensin (Sedang di sebelah atas membetulkan jalan, di depan rumah anak saya, dekat pom bensin)," ucapnya menunjukkan posisi suaminya.
Hari telah beranjak siang, sebentar lagi tiba waktu zuhur, saat saya menemui Adang. Ia tengah istirahat di sebuah tempat duduk tembok di depan rumah anaknya yang nomor lima, persis di pinggir jalan berlubang yang tengah ditambal bebatuan. Sisa lelehan keringat tampak di wajahnya.
Jika istrinya berasal dari Kampung Legok Ombol, Desa Nagrak, maka ia adalah warga asli Kampung Wadat, Desa Cikawao. Sebuah rumah semipermanen yang terletak di sebelah rumahnya adalah rumah peninggalan orang tuanya. Rumah itu tak dibakar gerombolan.
Menurutnya, selain rumah itu kokoh di masanya, rumah tersebut juga sempat dijadikan markas tentara dari Batalion Infanteri (Yonif) 328 dan 330 dalam operasi penumpasan DI/TII di Kabupaten Bandung.
Ia dan orang tuanya mula-mula mengungsi ke Desa Wangisagara di Kecamatan Majalaya. Setelah itu mengungsi ke Kota Bandung, tepatnya ke Kelurahan Paledang, Kecamatan Lengkong. Tak lama di sana, ia dan ibunya pindah ke Jalan Sawah Kurung, Kelurahan Ciateul, Kecamatan Regol.
Ihwal kepindahan itu Adang bercerita, karena bapaknya yang kerja di Jawatan Pertanian memboyong istri pertama dan anak-anaknya yang berjumlah enam orang dari Banten. Agar tidak seatap, maka ia dan ibunya sebagai istri kedua dibelikan rumah di Jalan Sawah Kurung.
Barangkali gaji seorang Jawatan Pertanian pada masa itu sangat besar, sehingga baik di Kelurahan Paledang maupun di Jalan Sawah Kurung, rumah yang mereka tempati adalah hasil pembelian dari warga setempat.
Dan ternyata perjalanan bapaknya tidak berhenti sampai di situ. Ia yang mula-mula ditugaskan di Banten dan menikah dengan istri pertamanya, lalu dipindahkan ke Bandung dan menikah dengan ibunya Adang, setelah situasi aman ternyata dipindahkan lagi ke Tambun, Kabupaten Bekasi, dan menikahi istri ketiganya yang melahirkan enam orang anak.
Setelah kembali ke rumah yang sempat dijadikan markas tentara, ibunya Adang menikah lagi dengan orang Kampung Selaawi dan mempunyai enam orang anak.
“Janten totalna genep kali tilu (Jadi total [saudara kandung, baik beda ibu maupun beda bapak adalah] enam kali tiga),” ujarnya sambil tersenyum. Anak Adang yang nomor lima, yang mendengarkan percakapan ikut tersenyum mendengar cerita ayahnya.
Gelombang pengungsi yang datang ke Kota Bandung saat pemberontakan DI/TII mengobrak-ngabrik wilayah Priangan, sempat dicatat oleh Us Tiarsa (mantan wartawan Pikiran Rakyat) dalam memoarnya yang bertajuk Basa Bandung Halimunan (2011).
Menurutnya, pada 1950-an saat ia masih duduk di kelas empat sekolah dasar, banyak warga baru yang mendatangi rumah bapaknya selaku ketua RT. Mereka hendak mendaftar agar tercatat dalam cacah jiwa Kebon Kawung.
“Ditenget-tenget dina buku cacah jiwa téh, bet aya ratusna warga anyar téh. Cék bapa, éta nu dalaptar téh lolobana ti Tasik pangpangna ti pilemburan bawahan Ciawi. Aya éta gé nu ti Garut, malah nu deukeut gé aya nyaéta ti Ciparay, Manggahang, jeung Dayeuhkolot,” tulisnya (hlm. 39)
(Melihat dengan saksama buku catatan kependudukan, ternyata ada ratusan warga baru. Kata bapak, yang daftar itu kebanyakan dari Tasikmalaya terutama dari perkampungan di Ciawi. Ada juga yang dari Garut, malah [dari daerah] yang dekat juga ada, yaitu dari Ciparay, Manggahang, dan Dayeuhkolot).”
Us Tiarsa yang penasaran bertanya-tanya kenapa orang-orang ini pindah ke kota. Bapaknya memberi tahu, warga baru tersebut meninggalkan kampungnya karena ketakutan oleh konflik bersenjata antara pemerintah dengan DI/TII.
Adang mengaku kelahiran 1944. Menurutnya, ia terpaut usia 10 tahun dengan istrinya. Artinya, istrinya kelahiran 1954, bukan 1956 seperti yang dituturkan Wawan.
Saat masih tinggal di Jalan Sawah Kurung, ketika usianya telah belasan, Adang pernah ikut operasi Pagar Betis selama seminggu di Kecamatan Cililin yang sekarang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Bandung Barat. Ratusan pos didirikan setiap 50 meter, berisi 4 orang warga yang bersenjatakan golok dan senjata tajam lainnya.

Markas Terakhir Kartosoewirjo
Setelah situasi aman dan kembali ke Kampung Wadat, Desa Cikawao, ia mendengar dari para tetangga bahwa beberapa tahun sebelum Kartosoewirjo ditangkap, ada seorang anggota Organisasi Keamanan Desa (OKD) yang bernama Endang tewas dibunuh gerombolan.
“Dikieu (Dibeginikan),” ucap Adang sambil menggerakkan tangannya ke leher dengan gerakan seolah tengah menyembelih.
Menurutnya, saat kejadian kemungkinan Endang sedang tidak bertugas dan disergap di rumahnya.
Seingatnya, gerombolan biasanya datang dari arah Bongkaran (areal perladangan yang sekarang banyak ditanami padi dan palawija), Kampung Gunung Manik, dan Kampung Péréng. Di atas perkampungan ini terdapat jajaran pergunungan, yakni Gunung Rakutak, Gunung Dano, dan Gunung Geber.
Saya pun melanjutkan perjalanan ke arah Bongkaran seperti yang dikatakan Adang. Jalanan terus menanjak, dan dari sebuah titik yang cukup tinggi, jajaran pergunungan itu tampak jelas di kejauhan.
Seorang peladang bernama Ibay (sekitar 45 tahun) bersama istrinya tengah bersiap meninggalkan ladang. Ibay memberi tahu nama-nama gunung yang berjajar itu. Keterangannya sama dengan yang dikatakan oleh Adang.
Sejumlah catatan, seperti misalnya yang ditulis Cornelis van Dijk dalam Darul Islam: Sebuah Pemberontakan (1995), Kartosoewirjo ditangkap di Gunung Geber bersama istri dan komandann pengawal pribadinya yang bernama Kurnia pada 4 Juni 1962.
Sementara dalam 328 Para Battalion: The Untold Stories of Indonesian Legendary Paratroopers (2015), penyusun buku tersebut menulisnya tanggal 5 Juni 1962. Di luar perbedaan titimangsa itu, penyusun cukup detail menceritakan detik-detik tertangkapnya Kartosoewirjo.
Dalam operasi penumpasan DI/TII yang bernama operasi Bharatayudha, sejumlah batalion infanteri TNI dikerahkan, salah satunya Batalion 328. Pada Maret 1962, tentara telah mendapat beberapa informasi tentang keberadaan Kartosoewirjo.
Pada 1 Juni 1962, komandann kompi dari Batalion 328 yakni Letda Suhanda bertemu dengan Kapten Hasan—salah seorang komandann kompi dari Batalion 327—di Cihejo. Mereka membicarakan sebuah peristiwa perampokan yang terjadi di Kampung Pangauban dan Jalan Cagak.
Beberapa hari kemudian, TNI melakukan konsolidasi setelah menemukan jejak kaleng kerupuk yang diduga bagian dari ceceran barang yang dirampok.
“Penyusuran jejak dilanjutkan ke sepanjang Gunung Rakutak dan menuju kali Cijaha, terus ke Gunung Malang. Namun, sampai di Danau Ciharus pasukan kehilangan jejak,” tulisnya.
Sampai di situ TNI kehilangan jejak, sebelum akhirnya ditemukan kembali jejak ke arah barat. Para pengesan jejak itu di antaranya adalah Serda Ara Suhara, Entur, Omon selaku komandan regu penembak runduk, dan Letda Suhanda. Dari sebuah titik, mereka melihat seorang anggota DI/TII.
“Dalam jarak 25 meter pengintai DI/TII melihat gerakan pengendapan. Terpaksa tembakan tak terhindarkan. Saat tembakan terjadi anggota DI/TII angkat tangan, yakni A. Mujahid, pengawal Kartosoewirjo. Di tenda [persembunyian], Kartosoewirjo sedang terbaring. Ia menyerahkan diri pada komandann kompi, Letda Suhanda,” imbuhnya.
Informasi dari dua sumber tertulis itu mendukung keterangan Adang yang menyampaikan bahwa gerombolan kerap datang dari arah sejumlah perkampungan yang berada di bawah pergunungan tersebut.
Ujung jalan yang saya susuri, salah satunya ternyata berakhir di Kampung Péréng Pojok. Semakin ke atas hanya ada dua rumah warga yang disebut Loa. Dan setelah itu jalan semakin menyempit menuju pergunungan.

Suhana Menembaki Tentara
Suhana tinggal di Kampung Lemburawi, Desa Maruyung, Kecamatan Pacet. Ia suami dari seorang penjual nasi tempat saya makan. Sebelum berbincang dengan Suhana, saya sempat bertanya kepada istrinya tentang pengalamannya saat zaman gerombolan. Tak banyak yang diingat dan dialami istri Suhana, sebab ia mengaku lahir pada 1952.
Mula-mula garis wajahnya seperti menyimpan ketakutan atau curiga saat ditanya tentang zaman DI/TII. Namun, beberapa kisah akhirnya ia tuturkan. Menurutnya, ia berasal dari Kampung Paninggaran, tak jauh dari Kampung Lemburawi.
Ia masih ingat peristiwa pembakaran Kampung Cinanggela—letaknya di atas Kampung Paninggaran—yang dilakukan gerombolan. Situasi yang sangat genting membuat setiap rumah harus menyembunyikan pelita di dalam ember atau apapun yang bisa mencegah cahayanya terlihat dari luar pada malam hari.
Pada awal 1960-an, ia mulai melihat para anggota Organisasi Keamanan Desa (OKD) berlalu-lalang di Kampung Lemburuawi, tempat pengungsiannya. Suhana, suaminya, adalah salah seorang anggota OKD.
“Abdi mah dipasihan bedil ku tentara, bedil él-é (Saya dikasih senapan oleh tentara, [namanya] senapan él-é),” ucap Suhana.
Bedil él-é yang disebut Suhana barangkali maksudnya Lee-Enfield, senapan buatan Inggris yang mulai digunakan pada akhir 1890-an.
Suhana lahir pada 1939 di Desa Magung, Kecamatan Ciparay. Pada 1982 Desa Magung dimekarkan menjadi dua, yaitu Desa Manggungharja dan Desa Mekarsari. Masa kecilnya yang pernah ditendang gerombolan serta rumahnya dibakar membuat ia bersemangat menjadi anggota OKD untuk membantu tentara menumpas pemberontakan DI/TII.
Menurutnya, saat rumahnya dijarah gerombolan, ia berdiri di dekat pintu rumah sehingga menghalangi pergerakan para penjarah. Ia pun ditendang hingga terpelanting ke halaman. Sementara sebelum rumahnya dibakar seluruh warga kampung disuruh pergi ke rumah sakit (sekarang Puskesmas Ciparay), setelah itu kampung mereka dibakar.
“Neuteuli abdi mah (saya masih mengingatnya [diiringi sakit hati]),” ujarnya.
Saat menjadi OKD, Suhana terlibat dalam pelbagai pertempuran. Bedil él-é menjadi andalannya. Meski nyalinya besar, tapi suatu hari ia tak berani mengeksekusi seorang anggota gerombolan yang terluka parah karena lengan kanannya tertembak.
Orang yang terluka itu bersembunyi di balik rumpun bambu, tapi raung kesakitannya terdengar keras. Ia dan Dodo—kawannya sesama anggota OKD—mendekati orang yang sudah tak berdaya itu.
Karena khawatir terdengar oleh gerombolan yang lain, dan merasa kesal sebab raungannya mengganggu konsentrasi Dodo dalam pengintaian, kawan Suhana itu kemudian menyeretnya ke tepi jurang dan menembaknya tepat di dahi. Saat tentara bertanya kenapa orang tersebut dihabisi, Dodo menjawab, “Lumpat, Pak (Melarikan diri, Pak).”
Masa-masa itu disebut Suhana sebagai masa yang pabaliut atau kacau balau, karena setiap orang bisa dianggap sebagai pendukung TNI atau pendukung DI/TII. Bahkan tak jarang ada warga kampung yang menjadi kombatan DI/TII, yang pada siang hari beraktivitas di kampung untuk mengumpulkan informasi.
Tutur kata amat dijaga. Salah ucap bisa menyebabkan kematian. Orang dengan mudah bisa menuduh orang lain sebagai mata-mata TNI, yang akhirnya akan dibunuh oleh gerombolan.
“Ieu téh seukeut pisan. Taak bapa mah (Ini—sambil menggerakkan dua telunjuk tangannya sebagai ungkapan saling tuduh antarwarga—sangat tajam. Saya tak sanggup lagi [melewati situasi seperti itu]),” ungkapnya.

Namun, ada juga kisah agak lucu yang ia tuturkan. Suatu malam di pinggir hutan sekitar Gunung Rakutak, Suhana tengah ikut berpatroli. Tiba-tiba dari arah bawah, terlihat samar, tampak beberapa orang tengah berjalan ke arah Suhana dan kawan-kawannya. Ia pun tak pikir panjang, bedil él-é andalannya segera diberondongkan ke arah orang-orang tersebut.
Dari bawah terdengar teriakan berkali-kali, “Woooii, ieu mah babaturan, tong ditembak! (Woooii, ini kawan, jangan ditembak!)”
“Aaahh…Euweuh, dipodaran siah ku aing! (Aaahh…Tidak, kubunuh kau!)” jawab Suhana keras karena tak percaya dengan ucapan “musuhnya”.
Tak lama kemudian sebuah tembakan kode melesat dari bawah. Suhana pun segera membalasnya dengan tembakan kode. Kontak senjata pun berakhir. Orang-orang yang diserang Suhana ternyata pasukan dari Batalion 301 yang juga tengah berpatroli.
Suhana menyebut peluru yang ditembakkan sebagai kode sebagai “peluru sen-sen”. Menurutnya, untuk mengakhiri kontak senjata, peluru kode yang ditembakkan antara kedua belah pihak warnanya harus sama. Merah dibalas merah, hijau dibalas hijau. Jika warnanya berbeda, maka pertempuran akan berlanjut.
“Teu lami maranéhna ting pucunghul tina rungkun, sihoréng 301 (Tidak lama kemudian mereka muncul dari balik semak, ternyata [pasukan dari batalion] 301),” ujarnya sambil tersenyum.
Peristiwa salah serang yang diceritakan Suhana, karena menggunakan bahasa Sunda, membuat saya tertawa dan langsung teringat novelet yang ditulis Adang S.—pernah ikut Wajib Militer Darurat (Wamilda) pada 1959 dan berpangkat Prajurit Dua—berjudul Ngepung Kahar Muzakkar (1983).
Novelet berbahasa Sunda itu, meski menceritakan operasi militer dan dipenuhi kisah pembunuhan, disisipi beberapa kisah konyol. Dan bahasa Sunda dalam benak saya sebagai penutur selalu menguarkan cita rasa humor, termasuk dalam cerita penuh ketegangan.
Saat DI/TII di Jawa Barat semakin terdesak, Suhana pun ikut dalam operasi Pagar Betis di kaki Gunung Kolotok dan Gunung Rakutak.
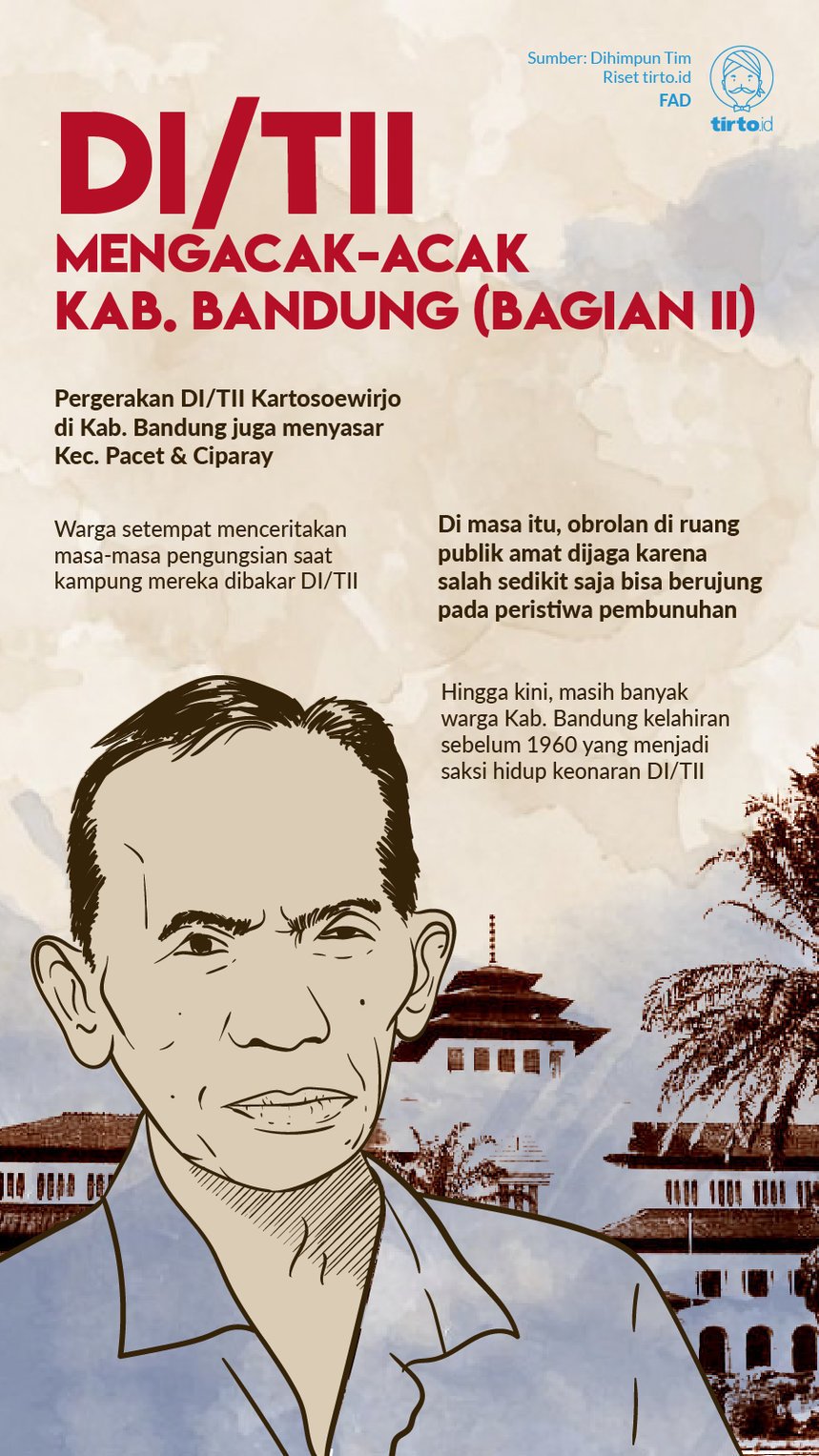
Jembatan Sayuran dan Tumbal Terbesar
Di pengujung pembicaraan, Suhana menyebutkan sebuah jembatan yang katanya pernah menjadi tempat pembantaian warga oleh gerombolan, yaitu jembatan di Kampung Sayuran.
Sebelum menuju jembatan tersebut, saya terlebih dulu ke Kampung Cinangggela, tempat yang kata istri Suhana dulu pernah dibakar. Setelah itu memutar balik ke Kampung Paninggaran dan melaju menuju Kampung Sayuran.
Perjalanan menyusuri jalan desa terus menanjak. Jalan aspal, jalan beton, jalan berlubang, jalan berlumpur, terus dilalui. Pada sebuah pertigaan, saya berbelok ke kiri. Sebelum melalui turunan curam, terdapat permakaman cukup besar. Entah Tempat Permakaman Umum (TPU) atau permakaman keluarga.
Turunan tajam itu dilindungi rumpun-rumpun bambu yang rimbun, membuat petang yang basah oleh hujan semakin terasa temaram. Di ujung turunan, jembatan Sayuran berada: pada sebuah lembah yang jauh dari perkampungan. Di bawahnya mengalir Sungai Ci Hejo yang dipenuhi bebatuan alam. Air keruh pekat mengalir deras. Tak jauh dari jembatan tampak sebuah spanduk program Citarum Harum yang menyertakan logo Kodam Siliwangi.
Selepas jembatan, jalanan menjadi menanjak, kiri kanannya juga dilindungi rumpun-rumpun bambu yang lebat. Sedikit ke atas juga terdapat permakaman yang tampak kurang terawat.
Diawali dan diakhiri lingkungan seperti itu, juga letaknya yang jauh dari perkampungan, membuat jembatan Sayuran terasa agak wingit. Jika yang dikatakan Suhana tentang pembantaian di jembatan ini benar-benar terjadi, jembatan Sayuran memang tempat yang “kondusif” untuk melakukan kengerian itu.

Dalam menggali cerita-cerita lisan tentang tahun-tahun konflik bersenjata antara pasukan Republik dengan DI/TII di Kabupaten Bandung (perjalanan kedua dilakukan bersama Komunitas Aleut—komunitas sejarah di Kota Bandung), saya tak pernah mengantongi nama narasumber sebelumnya, kecuali Omay di Kampung Ciwangi.
Sejumlah nama lainnya, baik yang mengalami langsung maupun cerita dari orang tuanya, saya dapatkan secara acak ketika singgah di warung-warung. Dalam mengumpulkan kisah-kisah ini, saya juga mencoba mencari para mantan kombatan DI/TII yang barangkali masih hidup dan mau bercerita. Namun, sampai saya pulang dari jembatan Sayuran, tak seorang dari mereka yang berhasil saya temui.
Kenangan akan peristiwa berdarah ini begitu hidup dalam ingatan para orang tua. Sebarannya—setidaknya di empat kecamatan di Kabupaten Bandung—cukup luas. Saya yakin, siapa pun yang melakukan kerja-kerja seperti yang saya lakukan di wilayah ini akan mendapatkan cerita-cerita serupa dari para orang tua.
Laporan yang hampir di sekujurnya dipenuhi kisah kepiluan ini merupakan bagian dari riwayat panjang Indonesia dalam usaha meneguhkan kesatuan. Pemberontakan DI/TII hanya salah satu dari sejumlah pemberontakan setelah proklamasi kemerdekaan dibacakan pada 17 Agustus 1945.
Dan dari seluruh pemberontakan yang datang silih berganti itu, korban terbesar adalah warga sipil tak bersenjata yang kerap terjebak dalam pertikaian antarkubu. Menyurat yang silam tidak dimaksudkan untuk menggarami luka lama.
Editor: Ivan Aulia Ahsan












