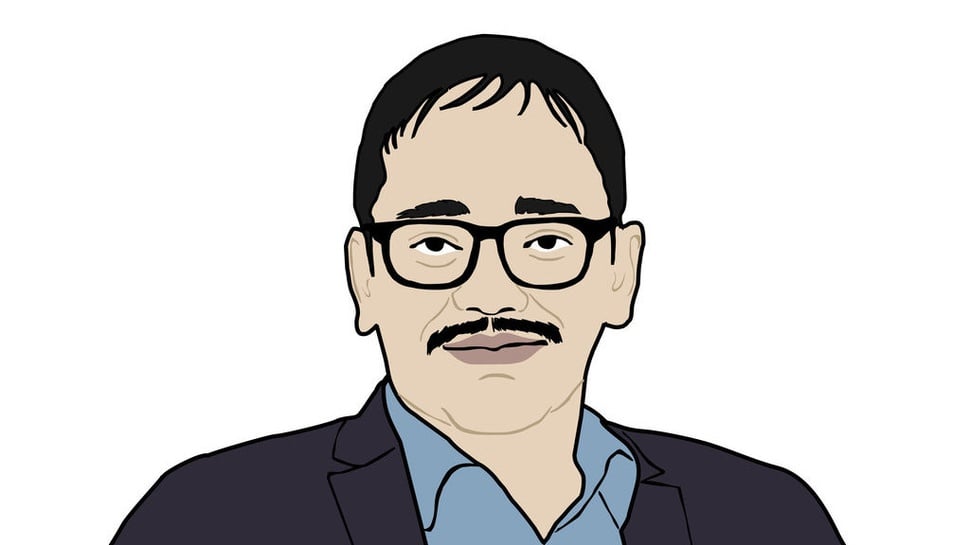tirto.id - Kekayaan warisan sejarah bawah laut dirusak dan dihancurkan secara sistematis di tengah siang bolong. Laporan Tirto.id tentang penjarahan bangkai kapal perang yang tenggelam di Laut Jawa pada Perang Dunia II menampilkan gambaran kelam ini ke publik. Mengapa bisa terjadi?
Ada banyak jawaban—dan tentu sejumlah apologia—terhadap pertanyaan ini. Laporan Tirto.id menguak masalah lama terkait urgensi perlindungan cagar budaya bawah air. Kasus ini mengangkat kembali problem sinkronisasi perundang-undangan nasional terkait kekayaan benda bersejarah di bawah air.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki kewajiban melindungi cagar budaya bawah air untuk kepentingan kekayaan pengetahuan umat manusia. Namun, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2009 yang melihat kapal karam sebagai benda berharga bernilai komersial, yang dijalankan Kementerian Kelautan dan Perikanan, menciptakan inkonsistensi dalam ranah hukum terkait bagaimana perlindungan tersebut dapat dilakukan.
Persoalannya menjadi semakin rumit dengan perkembangan teknologi, misalnya penemuan aqua lung yang memudahkan para pemburu harta karun melakukan penjarahan dan pencurian terhadap benda-benda berharga tersebut. Laporan Tirto.id menunjukkan bagaimana mudahnya operasi penjarahan dilakukan. Ironisnya, praktik ini dapat berjalan secara sistematis dalam waktu panjang tanpa tersentuh jerat hukum.
Indonesia memang tidak tercantum sebagai penandatangan konvensi internasional perlindungan cagar budaya bawah air tahun 2001. Namun, setidaknya, ada kewajiban etis untuk menghormatinya sebagai kuburan perang dari para prajurit kapal yang karam tersebut.
Dalam kaitan ini, protes masing-masing negara terhadap perusakan makam para prajurit dapat dipahami, meski pemerintah Indonesia secara teoritis tidak memiliki tanggung jawab langsung untuk menjaganya. Lemahnya payung hukum untuk melindungi keberadaan kapal perang sebagai cagar budaya bawah air, pada akhirnya, memberi peluang para pelaku penjarahan untuk bertindak bebas.
Kesadaran Sejarah
Selain masalah hukum seperti itu, ada dua persoalan lain yang memberi latar mengapa penjarahan terjadi.
Pertama, bentuk kesadaran sejarah yang melihat perkembangan sejarah Indonesia sebagai gejala yang berjalan tunggal tanpa persinggungan dengan dunia luar. Satu hal mencengangkan terkait peristiwa penjarahan adalah kesan bahwa keberadaan kapal-kapal karam ini tak memiliki persinggungan dengan sejarah Indonesia.
Kita di Indonesia sama sekali tidak merasa kehilangan dan terganggu dengan penjarahan tersebut, dan menganggapnya seakan sebagai persoalan di negeri Belanda dan Inggris. Sikap ini memang menjadi masalah akut terkait kesadaran yang menempatkan perkembangan sejarah Indonesia sebagai sebuah proses yang terjadi tanpa sangkut paut dengan perkembangan di luar Indonesia. Gambaran ini warisan lama yang perlu dibenahi dalam pertentangan antara sejarah Indonesiasentris dan Neerlandosentris (Belanda-sentris).
Dalam Runtuhnya Hindia-Belanda (1989), Onghokham memberikan catatan terkait alasan dia menulis sejarah dari sudut pandang orang Belanda, dengan mengatakan bahwa “paling tidak mereka pernah hadir dalam sejarah Indonesia”. Pernyataan Onghokham di sini menjadi pengingat betapa mudah kita mengabaikan warisan sejarah berharga hanya karena ia lahir dari rahim yang asing. Kontroversi “Rumah Cimanggis” yang dianggap “produk kolonial” semata sehingga seolah pantas digusur menunjukkan alam pikir yang serba abai itu.
Pengagungan secara berlebihan terhadap sejarah sendiri membuat kita lupa bahwa Perang Dunia II pernah terjadi di Indonesia; bahwa wilayah lautan Indonesia menjadi gelanggang pertempuran penting dalam sebuah perang global yang kemudian memungkinkan pembentukan negara republik yang merdeka.
Kedua, sindrom memunggungi laut tampaknya masih menjadi penyakit akut yang menjangkiti alam pikiran banyak pihak, termasuk di antara pihak berwenang. Mengubahnya tak semudah membalikkan telapak tangan. Kendala alam seperti badai, ombak besar, dan keluasan lautan yang mencapai 3,1 juta kilometer persegi (United Nations Conventions on the Law of the Sea) adalah satu faktor utama. Kendala ini bersinggungan dengan persoalan lemahnya teknologi, sumber daya material, dan tenaga ahli kompeten yang bersumber pada persoalan kekurangan dana.
Jadi, meski Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan mereka telah mengidentifikasi 463 titik warisan budaya bawah air berupa kapal, pesawat, keramik, senjata dan lainnya, pemerintah baru berhasil memetakan 42 titik dari jumlah tersebut (“Warisan Budaya Bawah Air: Potensi Melimpah, tetapi Ancaman Besar”, Kompas, 27 Agustus 2014).
Sejumlah capaian memang sudah terjadi belakangan ini. Pada Juni lalu, tim UGM Maritime Culture Expedition (UMCE) berhasil memetakan 25 titik situs baru yang tersebar di tiga kecamatan Sangihe, kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Pembangunan museum dan galeri penyimpanan kekayaan barang muatan kapal tenggelam (BMKT) oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah capaian lainnya.
Namun, jalan masih panjang apabila kita membandingkannya dengan keberhasilan Proyek Arkeologi Maritim Laut Hitam yang dipimpin tim peneliti dari Universitas Southampton, Inggris, yang menemukan 40 bangkai kapal dari masa Kekaisaran Byzantium dan Ottoman, termasuk interkonektivitas masyarakat pesisir di Laut Hitam sampai periode prasejarah.
Sesungguhnya kasus ini adalah kehilangan besar bagi orang Indonesia. Semakin sulit kita memahami sejarah Indonesia sebagai bagian dari dunia yang lebih besar.
Petikan wawancara Tirto.id terkait sikap pejabat pemerintah Indonesia terhadap warisan itu sekali lagi menunjukkan kecenderungan lama pemerintah: Benda cagar budaya sekadar dilihat dari sisi pemanfaatan (pembangunan museum, pariwisata, dan lainnya), sembari mengabaikan aspek perlindungan terhadap benda cagar budaya dari bencana alam dan buatan manusia seperti yang tertuang dalam UU Nomor 11/2010.
Perlindungan adalah syarat mutlak sebelum kita dapat memelihara dan memanfaatkan setiap warisan budaya yang ada di dalam wilayah Indonesia. Memang ini bukan langkah yang murah, tetapi penting dilakukan.
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.