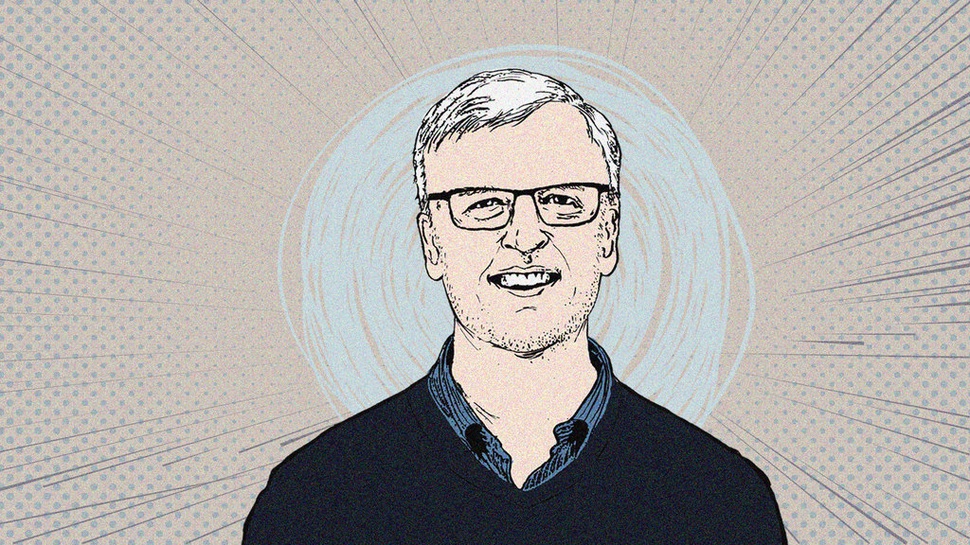tirto.id - Politik Indonesia semakin lama tampak semakin ditentukan oleh Islamisme. Kecenderungan itu menguat sejak aksi-aksi Bela Islam pada 2016 yang turut mengkondisikan pemidanaan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), wakil gubernur DKI Jakarta yang juga calon gubernur dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Pada Pilkada 2017, beberapa calon kepala daerah menggamit pasangan dengan unsur identitas keislamanan yang menonjol. Termasuk Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin, yang maju bersama Joko Widodo, sebagai calon wakil presiden.
Sejauh mana Islam-politik akan mempengaruhi Indonesia? Untuk menjawab hal itu, Tirto mewawancarai Greg Fealy, sarjana dalam bidang politik Islam di Indonesia dari Australian National University (ANU), di sela kesibukannya sebagai convenor konferensi Indonesia Update 2018 yang diselenggarakan ANU pada 15-16 September 2018.
Fealy mengemukakan dua hal menarik. Pertama, masyarakat muslim menjadikan Islam sebagai pertimbangan dalam memilih, tetapi mereka juga ingin kepala daerah yang bisa menjalankan pemerintahan. Hal ini menjelaskan mengapa rata-rata "tokoh Islam" menjadi kandidat wakil, sedangkan calon bupati atau gubernur tetaplah mereka yang punya pengalaman administratif-teknokratik.
Kedua, Fealy berpendapat Islam secara substansial tak akan mempengaruhi kehidupan Indonesia, setidaknya lima tahun mendatang. Ia hanya dijadikan instrumen untuk menaikkan elektabilitas dalam pemilihan umum. Kekuatan Islam juga tak mudah bersatu, termasuk gerakan 212 yang sudah terfragmentasi.
"Islam telah digunakan oleh Jokowi, Prabowo, Sandiaga, dan sebagainya untuk kepentingan politik," demikian Fealy. Berikut wawancara lengkapnya.
Saya akan mulai dengan pemerintahan Jokowi. Pada bagian mana menurut Anda perlakuan Jokowi berbeda dengan perlakuan dari pemerintahan SBY atau Megawati?
Menurut saya, satu hal yang Jokowi lakukan dan buruk bagi demokrasi Indonesia adalah ia menggunakan negara untuk melarang dan menindas oposisi Islam. Misalnya, pembubaran HTI. Saya pikir, pembubaran itu adalah langkah politis. HTI selama bertahun-tahun masih bersikap sama, sudah lama terkenal soal sikapnya terhadap khilafah, Pancasila, dan sebagainya. Terutama di tingkat nasional, tidak ada perubahan sikap kepemimpinan HTI tentang Indonesia, tentang UUD 1945, dan sebagainya. Jadi, saya kira ini direkayasa. Ada mobilisasi dari NU untuk melawan HTI untuk memberikan dalih kepada pemerintah guna menindak tegas HTI.
Menurut saya, hal ini bertentangan dengan hak untuk berserikat dan berkumpul. Apakah HTI betul-betul melanggar hukum? Menurut saya, itu belum jelas. Pemerintah menggunakan HTI untuk mengirim sinyal kepada organisasi-organisasi yang lebih kuat seperti FPI. HTI seperti pion, alat untuk mengirim pesan yang lebih besar.
Ini simbolis?
Ya, tepat. [Hal lain], ada kasus Habib Rizieq. Habib Rizieq tidak mengumumkan teks-teks [percakapan] dia sama Firza. Jadi, siapa yang meletakkannya ke public domain, saya kira sangat mungkin pemerintah, bukan dia sendiri. Jadi, yang melanggar hukum sebenarnya pihak lain.
Menurut saya, alasan menuntut dia dengan kasus itu adalah alasan politis. Pemerintah memanipulasi informasi.
Kita juga melihat apa yang terjadi dengan #2019GantiPresiden. Semakin banyak Polda, misalnya, menolak izin rally #2019GantiPresiden. Menurut saya, hal ini menyalahgunakan kekuasaan mereka. Sebenarnya kampanye seperti itu tidak melawan prinsip demokrasi. Ada backlash yang lebih serius lagi kalau pemerintah bersikap secara sewenang-wenang.
Jika kita melihat Jokowi, Islam, dan demokrasi, ia tak membuat jejak rekam yang baik, lebih buruk dari SBY. Jokowi lebih baik dalam toleransi keberagamaan ketimbang SBY. Namun, saya kira ia lebih buruk dari SBY dalam menggunakan negara untuk menindas oposisi Islamis.
Jokowi lebih baik dalam toleransi keberagamaan?
Saya pikir SBY presiden terburuk dalam toleransi keberagamaan. Ia menggunakan undang-undang penodaan agama, mendorong MUI untuk fatwa yang sangat sektarian; anti-Syiah, anti-Ahmadiyah, dan sebagainya. Menurut saya, Jokowi lebih baik dalam toleransi keberagamaan, tapi lebih buruk: ada kemunduran demokratik, karena ia tak menghormati kebebasan berpendapat serta kebebasan untuk berkumpul dan berserikat.
Apakah ada kemungkinan Jokowi [menekan oposisi Islamis seperti] membubarkan HTI sebagai hal yang harus dilakukan oleh Jokowi untuk mempertahankan toleransi keberagamaan?
Mungkin. Tapi menurut saya Jokowi melarang HTI karena dia ingin memperingatkan gerakan 212; lebih sebagai pembalasan negara. Pembubaran HTI lebih dari sekadar untuk toleransi keberagamaan. Jokowi khawatir soal penetrasi Islamisme secara umum. Namun, menurut saya, bukanlah cara yang benar untuk mengatasinya dengan prosedur informal yang mendiskriminasi rakyat.
Saya akan mencoba melihat dari perspektif pemerintah. Banyak anggota HTI yang berstatus sebagai pegawai negeri. Dalam jangka panjang, bukankah ini akan membahayakan demokrasi [terkait doktrin HTI yang anti-demokrasi dan anti-nasionalisme]?
Saya paham karena saya juga menganggap kelompok yang intoleran, yang sektarian, betul-betul membahayakan kualitas demokrasi di Indonesia. Namun, juga harus diakui bahwa dalam sistem demokrasi, akan muncul kelompok seperti itu, karena memang semakin populer dalam masyarakat.
Selain isu gerakan politik dalam umat Islam sendiri, tuntutan [hidup sesuai hukum] Islam semakin kuat. Semakin kuat bukan karena intervensi luar, tetapi karena doktrin yang lebih islami itu sekarang lebih menarik, terutama bagi kelas menengah. Mereka menganggap doktrin Islam lebih cocok dengan tantangan kehidupan mereka. Tantangan di kota besar, pekerjaan profesional, dan sebagainya. Begitu banyak perubahan dalam hidup mereka dan mereka mencari kepastian. Salah satu cara mencari kepastian adalah merengkuh versi agama yang hitam-putih, yang sangat jelas tentang apa yang boleh dan tidak, dan sebagainya.
Saya kira ini fenomena sosial yang kemudian punya dampak politik. Itu realitas di Indonesia. Kalau ingin menindas atau menghambat penyebaran itu, itu sebenarnya anti-demokratis. Mungkin Jokowi tidak setuju dengan ideologi PKS dan sebagainya, tetapi PKS adalah partai legal. PKS punya basis di masyarakat. Dia punya basis yang cukup kuat sebagai partai politik.
Seberapa besar Jokowi harus mengkhawatirkan Islamisme? Apakah Anda akan memisahkan Islamisme secara umum dengan yang terjadi pada 2016 (Aksi 212)?
Saya bisa paham mengapa Jokowi khawatir, karena dia dan orang yang di sekitarnya berpikir bahwa karakter politik Indonesia dan hukum publik Indonesia akan berubah karena pengaruh Islamisme. Akan menjadi lebih Islami, lebih banyak syariat, kurang toleran, atau kurang berkomitmen terhadap Pancasila. Saya paham mengapa ia khawatir.
Namun, jika melihat masalah ini secara netral, itulah demokrasi. Hal itu mencerminkan perasaan dari bagian masyarakat. Yang menjadi masalah saat ini adalah proporsi pengaruh kelompok-kelompok Islamis.
Tetapi, itulah yang publik mau ketika Anda bertanya kepada publik "Apakah Anda menginginkan orang Islam saleh yang menjadi presiden?" Mereka mengatakan, "Iya." Bahwa hal ini menjadi persyaratan yang penting [bagi publik].
Tapi, di sisi lain mereka juga menginginkan presiden yang bisa menjalankan pemerintahan dengan baik. Inilah demokrasi. Terkadang demokrasi mengarahkan ke orientasi yang lebih doktrinal. Kita lihat ini terjadi di Eropa, kebangkitan partai sayap kanan di Eropa. Itulah demokrasi.
Kita mungkin tidak menyukainya. Bagaimana cara menghentikan laju partai sayap kanan dalam demokrasi? Pemerintah harus mempromosikan gagasannya. Mereka harus membujuk publik bahwa Islamisme seperti itu berbahaya. Bukan menggunakan hukum untuk melawan Islamisme seperti itu, atau untuk melarangnya, atau mengkriminalisasikannya. Tetapi, dengan menggunakan argumen yang baik. Itu tantangannya.
Apakah Anda melihat itu sebagai pergerakan yang tidak bisa dihentikan?
Saya melihat risiko. Ada risiko apabila Anda memilih untuk membatasi Islamisme. Ada sebuah analogi. Islam itu seperti paku. Semakin keras Anda memukulnya, paku itu akan menancap lebih ke dalam kayu dan paku itu akan selamanya ada di sana. Usaha apa pun yang Anda lakukan malah membuatnya menancap semakin dalam dan dalam lagi.
Analogi itu berguna karena masyarakat yang didiskriminasi, orang yang dihukum secara tidak adil menggunakan itu, jika mereka berkuasa, mereka bisa balas dendam. Akan ada prasangka dalam masyarakat.
Lebih parah lagi dalam jangka panjang, kalau pemerintah memakai kebijakan yang diskriminatif. Sasaran target kebijakan itu semakin pahit, semakin ngotot melawan pemerintah, dan dengan segala macam cara. Saya kira itu juga lebih bahaya kalau memakai cara itu.
Pada dasarnya demokrasi itu seperti pasar. Ada pertukaran ide di sana. Pemerintah mestinya tidak memaksakan pendapat kepada kelompok tertentu.
Apa pandangan Anda soal Jokowi yang menjadikan NU sebagai penyangga [pengaruh kelompok] Islamis?
Saya pikir dua hal terjadi di sini. Pertama, penggunaan Islam secara politis. Islam sebagai simbol. Itu yang Jokowi lakukan dengan NU dan Ma’ruf Amin. Namun, apa pengaruh Ma’ruf Amin dalam pembuatan kebijakan [nanti]? Belum tentu besar. Menurut saya tidak [akan] banyak perubahan.
Jokowi juga merangkul alumni 212. Tetapi, pengaruh mereka dalam pengambilan keputusan pemerintah saya kira minim sekali. Jadi, Islam telah digunakan oleh Jokowi, Prabowo, Sandiaga, dan sebagainya untuk kepentingan politik.
Kelompok-kelompok Islam sendiri belum punya program politik yang jelas yang berdasar prinsip-prinsip Islam. Sekarang, penekanannya lebih sering simbolis saja. Ma’ruf Amin tidak bisa menjadi capres, hanya cawapres, karena publik tidak menginginkan ulama untuk menjalankan pemerintahan. Jokowi akan memerintah, tetapi dia butuh ulama sebagai tameng. Di situlah peran Ma’ruf Amin. Seperti alat, instrumental.
Saya juga ragu, meskipun penggunaan Islam secara simbolis meningkat, saya tidak yakin kebijakan politik bernapaskan Islam meningkat. Islam hanya digunakan untuk memenangkan pemilu, untuk memobilisasi massa.
Tapi bagaimana dengan yang terjadi di parlemen, misalnya dalam kasus revisi KUHP? Mungkin dalam kebijakan pemerintah tidak tampak, tapi Islamisme tampak [dalam pembuatan produk hukum] di parlemen?
Itu contoh yang tepat. KUHP disusun dengan berbagai pertimbangan. Saya pikir versi selanjutnya dari [rancangan] KUHP akan seperti RUU Anti Pornografi. Mereka akan berpikir ulang soal apa yang telah mereka ajukan.
Anda juga bisa melihat sistem kehakiman. Ada keputusan Mahkamah Konsitusi terhadap UU Penodaan Agama. Yang terjadi di pengadilan untuk penodaan agama itu sangat konservatif. Jadi, kami melihat pengaruh itu.
Namun, secara politis, saya masih berpandangan Islamisme lebih banyak digunakan sebagai simbol ketimbang diambil hal-hal substantifnya. Sangat sulit untuk membuktikan bahwa Islam menyediakan sebuah agenda perubahan, misalnya, kebijakan ekonomi apa yang bisa dilakukan dalam napas Islam?
Hal yang lebih penting lagi ialah kepentingan politik kelompok-kelompok tertentu. Lihat Gerakan 212. Dalam periode singkat, mereka mengumpulkan aliansi besar. Dalam periode singkat, mereka boleh jadi seperti hal baru. Namun, 1,5 tahun kemudian, fragmentasinya cukup gawat, saya kira.
Berapa banyak kelompok berbeda 212? Banyak dari mereka yang tidak terawat. Mereka tidak sepakat dalam suatu isu. Mereka sangat memungkinkan untuk dikooptasi oleh pemerintah dan oleh oposisi. Jadi, sekali lagi, Islam gagal bersatu menjadi kekuatan oposisi.
Kami pernah menulis partai Islam yang suaranya stagnan dari satu pemilu ke pemilu. Di sisi lain, ada 212 yang sukses menarik banyak massa. Bagaimana menurut Anda?
Suara yang diperoleh partai-partai Islam sekitar 30 persen di Pemilu 2014. Tidak terlalu tinggi memang. Namun, seperti kata Anda, ia berpengaruh di parlemen, pengadilan, penegakan hukum, dan pendidikan. Beberapa dari hal itu terjadi secara kultural dan hukum, tidak melulu secara politis.
Lalu, kita melihat ke DKI Jakarta (peristiwa 212) dan dipilihnya Ma’ruf Amin sebagai cawapres, kemudian ada kesimpulan bahwa Islam telah menguat jauh. Sampai derajat tertentu, itu benar. Tetapi, tidak bisa dikatakan juga bahwa ia akan mengarahkan arah bangsa atau kebijakan pemerintah dalam 5 tahun ke depan.
Jika Prabowo terpilih, saya tidak melihat ada jaminan bahwa akan ada lebih banyak pengambilan keputusan berdasarkan Islam.
Ada yang mengkhawatirkan bahwa agenda #2019GantiSistem ada di balik kampanye #2019GantiPresiden, bagaimana menurut Anda?
Kelompok Islam berhati-hati sehingga tidak sampai menyebut “ganti sistem.” Habib Rizieq memang mengatakan tentang NKRI Syariah atau UUD 1945 plus dengan unsur Islam. Jadi, ini bukan memperbaiki sistem atau kembali kepada sistem yang murni.
Hal-hal semacam “ganti sistem” menurut saya lebih berbahaya karena karena akan memungkinkan aparat keamanan untuk melibatkan agen intelijen.
Ini dari luar gerakan #2019GantiPresiden atau dari dalam?
Memang ada orang-orang dalam gerakan tersebut yang ingin ganti sistem. Kalau HTI jelas, mereka ingin ganti sistem, mereka menolak demokrasi. Jelas sekali. Namun, sejak mereka muncul pada 2000, sikapnya selalu begitu. Jadi, apa yang berubah [dari sikap itu] tahun lalu ketika mereka dibubarkan?
Tapi, kebanyakan organisasi Islamis jauh lebih hati-hati. Kalau ditanya kepada Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Persis, mereka tidak ingin ganti sistem. Memang mereka punya agenda yang sangat Islamis dan konservatif, tetapi untuk sistem politik mereka tidak mau berganti.
Bagaimana menurut Anda tentang kondisi PKS yang sekarang melunak, bilang tidak ingin sistem syariah?
Saya tahu kebanyakan kader PKS menginginkan syariah. Ini [sikap partai tidak tegas mengatakan ingin sistem syariah] adalah strategi politik untuk memaksimalkan perolehan suara dan mengurangi pandangan bahwa mereka anti-sistem. Itu adalah taktik yang digunakan oleh Anis Matta dan Hilmi Aminuddin, menyebut bahwa ini partai nasionalis-religius.
Ikhwanul Muslimin [partai politik di Mesir yang menjadi patron PKS], juga menggunakan strategi ini, menyatakan bahwa mereka adalah partai yang berada di tengah spektrum politik. Tapi, setengahnya, di belakang layar, mereka masih cukup kanan dan Islamis. Saya sendiri tidak percaya mereka tidak menginginkan syariah.
Bagaimana menurut Anda soal PKS yang pandai mengkondisikan diri [seperti pada 212 dan memenangkan Anies Baswedan], tetapi kemungkinan tidak akan mendapat suara yang terlalu baik?
PKS ini menarik. Namun, saya pikir agak susah bagi mereka untuk [memperoleh suara yang baik] dalam pemilu tahun depan. Pasalnya, ada keretakan internal di antara mereka. Antara kubu Sohibul Iman dan Salim Assegaf melawan kubu Anis Matta dengan, salah satunya didukung, Fahri Hamzah.
Saya dengar kabar bahwa di cabang-cabang PKS ada cukup banyak yang agak kecewa terhadap kepemimpinan Sohibul. Kekecewaan mereka lantas berubah jadi keengganan untuk ambil peran dalam pemilihan umum maupun pemilihan presiden 2019. Banyak caleg yang cukup terkenal dan punya profil yang tinggi tidak mau dicalonkan lagi. Ini tentu menjadi kerugian bagi PKS. Mereka akan banyak kehilangan modal politis yang cukup signifikan.
Keretakan internal dalam PKS bisa dilihat dengan gambaran seperti ini. Ada sebagian yang setuju mendukung Sohibul. Mereka yang mendukung Sohibul ini beranggapan PKS kembali ke khithah dan melaksanakan mandat asli PKS. Ada juga yang menilai bahwa PKS di bawah Sohibul jadi lebih bersih. Tidak banyak korupsi.
Sementara di lain sisi, mereka yang kontra-Sohibul berpandangan bahwa sosok Sohibul akan jadi musibah bagi PKS, karena tidak banyak tokoh yang terkenal dalam komunitas mereka. Mereka ingin kembali ke kepemimpinan Anis Matta.
Persentase suara PKS pada Pemilu 2014 enam persen. Jika nanti perolehan suara PKS di bawah lima atau empat persen, sangat mungkin Sohibul digulingkan setelah pemilu. Gelagat semacam ini sudah dilihat kala mulai banyak bermunculan partisan baru di Jawa Timur yang dimotori simpatisan Anis Matta. Partai ABI. Juga ada semacam DPW tandingan atau bayangan. Jadi dengan kondisi semacam ini, saya kira Anis sudah siap menantang Sohibul, tetapi tunggu sampai akhir proses pemilihan.
Jadi, PKS tidak punya duit, kekurangan tokoh, kekurangan pentolan, juga kurang solid. Dan yang paling krusial bagi mereka, tidak mendapat posisi cawapres. Tentu akan sedikit beda apabila salah satu kader mereka, entah Salim Assegaf atau Ahmad Heryawan, menjadi cawapres. Apabila ada kader jadi cawapres, mereka akan mendapat efek ekor jas, mereka akan mendapat perhatian karena kader mereka menjadi cawapres.
Dari banyak segi, PKS saat ini lebih lemah dibanding 4-5 tahun yang lalu. Dan saya kira, daya tarik PKS untuk kalangan swing voters juga merosot drastis.
Tetapi, di lapangan, mereka bisa menjadi mesin politik yang signifikan. Pilkada Jakarta dan Jawa Barat, misalnya. Bagaimana Anda menjelaskannya?
Itu poin yang menarik. Namun, saya belum melihat bukti tentang pengaruh PKS di pilkada. Tapi, sangat logis jika hal itu benar-benar kejadian. Dari yang saya dengar, kader-kader PKS di Jawa Barat agak malas menyongsong pilkada. Alasannya, PKS kecewa memilih Sudrajat sebagai calon gubernur, alih-alih kader PKS sendiri. Mobilisasi akar rumput jadi tidak efektif. Kader PKS yang kecewa ini lantas mengambil jarak dengan partainya sendiri. Menjelang akhir kampanye, mereka baru bergerak mengerahkan massa.
Pemandangan di atas hampir mirip dengan kondisi 2014 ketika mereka, dalam hal ini kader PKS, kecewa dengan partai dan memutuskan untuk bergerak lambat dalam mendulang suara. Namun, lagi-lagi menjelang babak akhir, mereka memutuskan untuk kembali mendukung PKS. Pertimbangannya: daripada golput atau pilih partai lainnya, kader PKS ini akhirnya memilih partainya sendiri. Walhasil, suara mereka di 2014 pun naik.
Ini bukti juga bagaimana PKS sebetulnya mampu memanfaatkan jaringan liqo dengan baik. Tidak ada partai lain seperti PKS yang punya sistem kaderisasi berdasarkan ideologis macam liqo ini. PKS punya pandangan yang berbeda dibanding partai-partai berhaluan Islam lainnya. Ini pertanda liqo punya perkembangan yang menarik. Berdasarkan sistem kader, ideologi. Tidak ada partai Islam lainnya yang seperti itu. PKS punya pandangan berbeda. Tapi, yang jelas, sulit memprediksi apa yang bakal terjadi dengan PKS dalam 2019 nanti.
Bagaimana menurut Anda tentang relasi PKS dan NU sekarang (beberapa kali ada saling-serang verbal di antara keduanya)?
Hal itu bisa dipahami karena NU memasukkan PKS ke dalam kategori Wahabi-Salafi dan NU sedang memerangi kelompok itu. Salafi, PKS, Hizbut Tahrir, Jamaah Tabligh, banyak sekali kelompok [lain], menurut NU, punya orientasi yang sama dengan Wahabi. Jadi, bagi NU, PKS adalah musuh mereka.
Bagaimana situasi permusuhan itu akan mempengaruhi masing-masing NU dan PKS?
NU merasa terancam dengan Islam transnasional, Wahabisme. Ini cerita lama, orang-orang Salafi mengkritik akidah orang-orang NU. Dan orang-orang PKS adalah saingan bagi orang-orang NU dalam meraih suara nahdiyin. Jika Anda melihat figur-figur PKS di Jawa Timur pada dua kali pemilu terakhir, suasana persaingan ini cukup kuat. PKS bertumbuh dengan lumayan cepat, sebetulnya.
Jadi ada orang PKS yang anak-cucu dari orang-orang NU?
Ada, sebagian. Mereka sangat kompetitif. Dan yang jelas bukan dari golongan “Gus.” Kalau “Gus,” kan, sudah dapat jalur cepat, berbakat atau tidak. Tetapi kalau orang nahdiyin biasa dan ingin maju, itu lebih susah. Mereka lebih mendapat kesempatan di HTI, FPI, PKS. Ada orang HTI yang berasal dari keluarga NU. Muhammad al-Khaththath (HTI), misalnya. Dia berasal dari keluarga kiai di Jember. Ismail Yusanto (Jubir HTI) ayah atau ibunya juga berasal dari NU. Tokoh PKS seperti Rahmat Abdullah cara ibadahnya sangat tradisionalis, membaca qunut dan semacamnya, sangat NU.
Kembali lagi ke fakta bahwa keduanya saling serang. Saya pikir [itu terjadi] karena yang satu melihat yang lain sebagai pesaing. Tapi juga karena NU merasa ditantang oleh keberadaan Salafi. Salafi melihat ajaran NU moderat, punya bias kebudayaan, Islam Nusantara. [NU seperti] Walisongo yang melakukan Islamisasi dengan tradisi kebudayaan. Hal seperti ini diserang oleh kelompok Islam transnasional.
Jadi suasana persaingan ini ada karena hal doktrinal, selain ada faktor kepentingan. Jika lebih banyak nahdiyin bergabung dengan kelompok-kelompok Salafi, santri akan berkurang. Bagi mereka, wilayahnya seperti direbut oleh Islam transnasional. Itu sebabnya mereka sangat menyerang PKS.
Kalo baca situsweb Duta Islam [bukan situsweb NU, tetapi situs yang apologis terhadap NU], PKS disebut komunis gaya baru, dengan logo yang diedit dengan memasukkan unsur palu-arit.
NU kemudian mendukung Jokowi karena melihat Jokowi menantang kelompok-kelompok [Islam transnasional] ini. Bahwa Jokowi memihak Islam kultural, bukan Islam ala Timur Tengah.
Ada komentator yang mengaitkan suasana permusuhan ini dengan "politik aliran" pada Pemilu 1955, juga konfigurasinya ketika Masyumi bersama PSI melawan Sukarno (PNI) yang menggandeng NU. Apakah soal ini masih relevan?
Saya agak skeptis dengan "teori" ini. Ada orang NU yang masih punya sentimen soal Masyumi, tetapi PKS tak punya kepentingan soal ini. Bagi PKS, Masyumi adalah Islam lama. Orang-orang PKS mengatakan, "Kami menciptakan [arah] baru Islam." Adapun yang masih relevan adalah bagaimana persoalan perbedaan ideologis dan doktrinal sejalan dengan urusan kepentingan lembaga, akses terhadap kekuasaan dan ekonomi.
Semua kelompok Islam itu mendaku sebagai ahlus sunnah waljamaah. Jika ahlus sunnah waljamaah versi NU terkikis, maka semua basis otoritas kiai juga ikut tergerus. Dalam hal ini, soal ideologis mengiringi soal ekonomis, sama seperti dulu NU meninggalkan Masyumi karena Masyumi dianggap menyingkirkan para kiai.
Dengan situasi seperti ini, bagaimana kira-kira demokrasi yang ada dalam tegangan dengan Islam dapat berjalan?
Ini semakin sulit. Seperti yang Sidney Jones katakan, siapa yang memenangkan klaim-klaim keadilan yang berkompetisi satu sama lain. Dalam hal ini, keputusan akan ditentukan oleh muslim [sebagai mayoritas]. Muslim mana? Bukan NU, meski mereka mencoba terus menancapkan pengaruh di hadapan Salafi, melainkan muslim sehari-hari yang akan menentukan. Entah mereka baca qunut atau tidak, entah berapa jumlah rakaat tarawihnya, entah baca kitab kuning atau cukup Alquran dan hadis. Itu tantangan bagi NU, semakin berat bagi mereka.
Secara ritual, semakin banyak yang meninggalkan NU. Apakah secara politik juga?
Iya, betul. Persis seperti itu. Sekarang, pengaruh kiai secara politik merosot drastis. Apabila dilihat dari perspektif kiai sebagai tokoh spiritual, masih banyak yang mengikuti. Tapi kalau misalnya kiai bilang pilih tokoh A atau B, akan ada hanya sebagian kecil dari mereka yang mengikuti titahnya. Lihat saja di TPS dekat pesantren.
Salah satu masalah adalah keluarga besar kiai tidak cukup solid. Dalam satu kasus, bisa saja dalam keluarga kiai, satu ke PKB, satu Golkar, satu ke PPP. Hal tersebut membuat santri bingung. Dan pada akhirnya mereka memilih berdasarkan rasionalitas, bukan atas ajakan kiai. Ini menjadi fenomena yang berbeda dibanding yang terjadi pada 1950-an ketika satu pesantren punya satu suara. Kalau sekarang terjadi fragmentasi elit.
Apa yang harus Jokowi lakukan dengan kelompok-kelompok ini?
Kalau ke PKS, rasanya susah sekali. Sementara dengan NU, Jokowi sudah menggandeng Ma’ruf. Saya kira alasan utama dia memilih Ma'ruf adalah karena takut NU akan meninggalkan koalisi, walau saya pikir mereka tak akan pergi. Jika [nanti] Jokowi terpilih lagi, ia harus kasih mereka uang, jabatan menteri di kabinet, dan menempatkan orang-orang NU di BUMN. Itu yang sudah dia lakukan juga. Dengan cara itu Jokowi bisa mendapatkan loyalitas mereka.
Penulis: Maulida Sri Handayani
Editor: Windu Jusuf