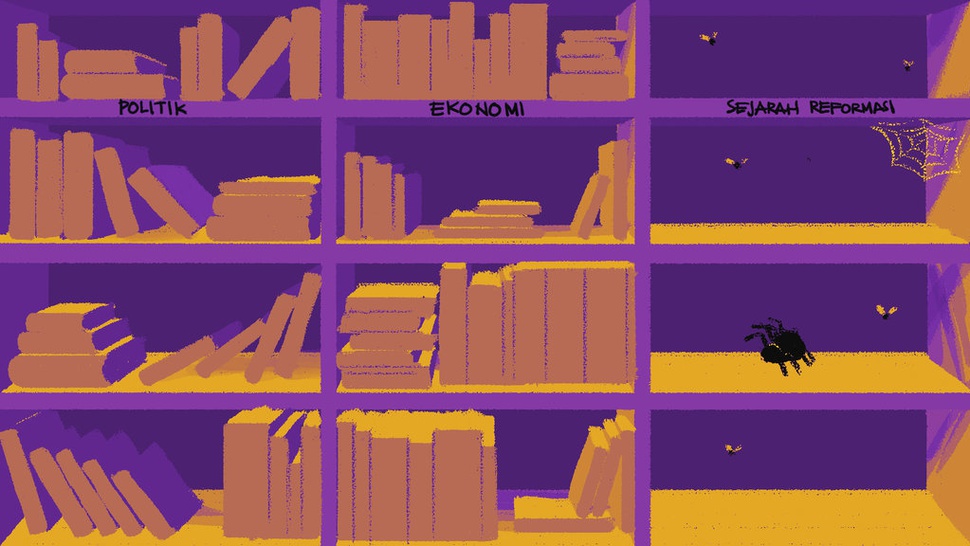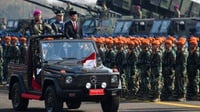tirto.id - Dalam percakapan politik kontemporer Indonesia, Reformasi dikenang sebagai peristiwa. Itu adalah momen ketika ribuan mahasiswa, buruh perkotaan, aktivis pro-demokrasi dan LSM, serta para pembangkang rezim turun ke jalan menuntut turunnya Soeharto dari puncak kekuasaan pada Mei 1998.
Sejumlah peristiwa sejarah yang padat memang menandai momen tersebut. Pada 12 Mei, empat mahasiswa Universitas Trisakti tewas diterjang peluru aparat dalam demonstrasi yang mereka lakukan di halaman kampus. Selanjutnya, kerusuhan anti-Tionghoa meletus sepanjang 13 sampai 15 Mei di Jakarta dan kota-kota lain.
Memasuki 18 Mei, mahasiswa menduduki gedung DPR/MPR yang menjadi puncak aksi pendudukan serupa yang telah bergulir di beberapa daerah. Puncaknya adalah keputusan Soeharto untuk lengser keprabon pada 21 Mei.
Di antara para sejarawan Indonesia, reformasi 1998 telah menjadi titik tolak baru untuk menilai ulang sekaligus mengkritisi penulisan sejarah resmi yang tercantum dalam enam jilid buku Sejarah Nasional Indonesia, khususnya jilid VI. Buku itu memaparkan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam proses peralihan kekuasaan sepanjang 1965-1966 yang memunculkan rezim Orde Baru, tentu saja menurut versi mereka. Sejarawan Asvi Warman Adam menjadi juru bicara utama dalam apa yang disebutnya sebagai “pelurusan sejarah” yang dibuat kabur dalam versi penulisan sejarah resmi.
Bagaimanapun, perdebatan yang terjadi belum menyentuh peristiwa reformasi itu sendiri. Meski sudah terdapat rentang waktu dua dekade sejak bergulirnya reformasi, dan telah lahir satu generasi baru tanpa kaitan historis dan ikatan emosional apapun dengan momen tersebut, penulisan sejarah reformasi masih belum melahirkan sejarawannya. Ia hanya hadir melengkapi narasi yang menandai akhir sistem kekuasaan Orde Baru dan masih menyisakan pertanyaan bagaimana momen itu layak dikenang, bagaimana ia dituliskan?
Reformasi sebagai Tonggak
Tidak dapat disangkal, ada beberapa faktor yang menjadikan narasi sejarah reformasi masih tetap menyisakan sejumlah masalah. Sebagai sebuah peristiwa sejarah, momen reformasi memang belum cukup memberikan perspektif kesejarahan yang lebih luas dibanding, katakanlah, revolusi Indonesia, kebangkitan nasional, atau G30S dan peristiwa sesudahnya.
Sejumlah orang yang turut melahirkan peristiwa tersebut masih tetap hadir dalam pusaran politik nasional, lengkap dengan serangkaian kontroversi-kontroversinya. Sebut saja Amien Rais yang turut melahirkan reformasi bersama tokoh-tokoh penting lain, serta Prabowo Subianto dengan langkah kontroversialnya mempertahankan ancien régime. Keduanya tetap menjadi bagian penting dalam gravitasi politik dan tetap terbuka pada perubahan orientasi dan aksi-aksi politik mereka.
Termasuk juga sejumlah “pemuda”—sebuah kata yang memiliki resonansi kuat dalam tradisi politik Indonesia—yang dahulu bergerak aktif menentang rezim dan sekarang menjadi sosok-sosok terhormat di komisi-komisi negara, Dewan Perwakilan Rakyat, dan pemerintahan. Dengan katan lain, reformasi adalah peristiwa “kemarin sore” yang belum dapat kita tentukan dengan pasti episode akhir dari keseluruhan kisahnya.
Apabila episode akhir reformasi merupakan gambaran yang belum pasti dalam satu atau dua dekade ke depan, sejarawan dan ilmuwan sosial memiliki keyakinan soal kapan momen reformasi dimulai. Ada kesepakatan di dalam kepustakaan untuk menyebut bahwa picu yang membawa kejatuhan kediktatoran Soeharto dan rezim Orde Baru yang dipimpinnya bermula dari rangkaian krisis keuangan yang terjadi di Asia Tenggara pada awal 1997.
Ketika itu, sejumlah investor, manajer keuangan, dan pialang saham global menarik investasi mereka secara besar-besaran dari kawasan ini. Perekonomian beberapa negara seperti Indonesia, Thailand, dan Malaysia, rontok seperti rumah kartu. Di Indonesia, rupiah terdepresiasi hingga 70% dan Bursa Ekonomi Jakarta (BEJ) mencatat penurunan indeks sampai 50% memasuki paruh kedua 1997. Perekonomian Indonesia berada di ambang kebangkrutan, dan keajaiban ekonomi negara industri baru berumur pendek saja.
Padahal, empat tahun sebelumnya, Bank Dunia baru saja membuat sebuah laporan tentang keajaiban pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu dari newly industrializing economies (NIES).
Perkembangan yang kemudian melahirkan momen reformasi di Indonesia adalah efek politik krisis tersebut. Tekanan IMF terhadap pemerintah Indonesia untuk melakukan restrukturisasi perbankan menyebabkan likuidasi enam belas bank pada November 1997. Salah satunya adalah Bank Andromeda milik Bambang Trihatmodjo. Gara-gara itu, Bambang menyatakan kebijakan tersebut merupakan konspirasi yang berusaha menjatuhkan nama baik keluarganya.
Aroma politik mulai mewarnai gelombang krisis yang terjadi. Menteri Keuangan Mar'ie Muhammad dan Gubernur Bank Indonesia Soedrajad Djiwandono sebagai arsitek di balik kebijakan likuidasi tersebut dicopot dari kedudukannya. Keengganan Soeharto mengikuti kebijakan restrukturisasi ekonomi untuk mendapatkan pinjaman IMF sebagai cara keluar dari krisis menyebabkan kondisi ekonomi Indonesia semakin memburuk. Nilai rupiah merosot sampai Rp17.000 per $1 memasuki akhir 1997. Pada awal Januari 1998, Soeharto akhirnya menandatangani kesepakatan yang ditetapkan IMF untuk mencegah meluasnya krisis.
Pada saat bersamaan, Soeharto dan menteri kabinetnya melontarkan secara terbuka ketidaksesuaian kebijakan IMF dengan konstitusi Indonesia dan Pancasila sebagai ideologi negara. Sentimen nasionalisme ekonomi dikobarkan sebagai perlawanan terakhir. Pemerintah menggemborkan gerakan “Aku Cinta Rupiah” dan membentuk badan yang menetapkan kebijakan ambang batas nilai tukar rupiah sebesar Rp5.500 per $1. Sentimen nasionalisme ekonomi ini juga mengarah pada upaya pengkambinghitaman para pengusaha Tionghoa yang mulai secara terbuka melontarkan pandangan kritis terhadap kebijakan Soeharto dan kroninya dalam mengatasi krisis.
Bukan suatu kebetulan bila dalam proses perubahan politik yang terjadi di Indonesia pada 1998, sentimen anti-Cina menjadi bagian tak terpisah dari perkembangan politik yang terjadi. Mereka dianggap sebagai pengkhianat yang menyebabkan terpuruknya perekonomian Indonesia.
Meski Soeharto telah melakukan berbagai upaya untuk tetap melanggengkan kekuasaannya, tetapi sejarah berkata lain. Soeharto yang beranjak tua menjadi semakin berjarak dengan militer yang menjadi pendukung utama kekuasaannya. Lingkaran politiknya pun kian menyempit. Ia juga mulai ditinggalkan sejumlah pendukung. Pada 20 Mei, 14 menteri yang dikoordinasi Ginandjar Kartasasmita mengeluarkan pernyataan menolak duduk dalam kabinet baru yang digagas Soeharto sehari sebelumnya.
Perpecahan yang terjadi dalam elite politik Indonesia pada akhirnya menggerakkan energi perlawanan yang tidak dapat dibendung Soeharto secara pribadi dan para loyalisnya. Untuk menyelamatkan sistem yang telah ia bangun selama tiga dekade lebih, Soeharto memutuskan mundur. Langkah ini melahirkan sebuah tonggak di antara berbagai tonggak yang membentuk mosaik sejarah reformasi politik yang kita kenal sekarang.
Belum Menjadi Memori Kolektif
Selain persoalan perubahan di dalam sistem kekuasaan, reformasi politik di Indonesia melibatkan pula beragam persoalan yang bersentuhan dengan pengalaman banyak orang. Ada serangkaian kisah terkait nasib para aktivis yang hilang, pengalaman traumatik dalam peristiwa kerusuhan anti-Cina dan kasus pemerkosaan terhadap warga Tionghoa, mahasiswa yang menjadi korban penembakan aparat dan orang tua mereka yang terus berjuang mendapatkan keadilan. Pengalaman tersebut terus membayangi perjalanan politik Indonesia. Tidak mengherankan bila kemudian terdapat makna bersifat jamak terkait arti dan relevansi reformasi dalam kehidupan politik kontemporer.
Bagi sejumlah pihak yang turut menggulirkan reformasi—termasuk bekas pendukung Soeharto dan para petinggi militer—ia dianggap telah selesai segera setelah terbentuknya pemerintahan baru dan berlakunya politik multipartai serta pemilihan presiden secara langsung. Di sini, katup utama yang menghambat sirkulasi dan mobilitas vertikal sejumlah elite politik telah selesai dengan mundurnya Soeharto dari puncak kekuasaan.
Setelah dua dekade reformasi, suatu elite baru yang menguasai kehidupan politik Indonesia kontemporer pun telah terbentuk. Mereka lahir dari rahim elite lama yang membuahkan para pengusaha, teknokrat, dan juga perwira militer dari keluarga-keluarga yang tumbuh besar di era Orde Baru.
Dalam kehidupan politik, mereka hadir melalui wajah-wajah yang diusung partai-partai politik di Indonesia untuk menduduki posisi di lembaga dewan atau pemerintahan di pusat dan daerah. Di lapangan ekonomi, mereka mewarisi perusahaan-perusahaan keluarga yang turut bersaing merebut kue ekonomi yang merentang dari tingkat nasional hingga lokal.
Di luar kalangan elite lama yang mengalami penyesuaian dan perubahan bentuk sepanjang dua dekade ini, bagaimanapun juga terdapat sejumlah aktivis yang turut melahirkan reformasi tetapi berada di luar pusaran utama lingkaran kekuasaan politik dan ekonomi. Beberapa dari mereka duduk di dalam lembaga-lembaga negara, menjadi anggota formal partai politik dan organisasi massa, menjadi jurnalis, dan tetap aktif di kampus-kampus serta mengisi aktivitas sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Di dalam kelompok inilah kita mendapatkan elan politik yang menyuarakan semangat zaman masa lalu yang menjadi alasan bergulirnya reformasi 1998. Tapi, suara dan pengaruh mereka tetap berada di pinggiran dan minor saja meski bukan tidak ada sama sekali.
Karena itu tidak mengherankan bahwa kenangan tentang reformasi sampai sekarang masih tetap berada di luar lingkaran kenangan resmi negara dalam kalender nasional. Di sana-sini, yang muncul adalah kisah yang mengisi narasi media nasional dengan orang-orang dari masa lalu yang bercerita tentang momen traumatik dan penuh gelora, atau dari sejumlah aktivis yang mencoba mengukuhkan kenangan itu sebagai ingatan kolektif. Namun tidak lebih dari itu.
Tidak seperti Sumpah Pemuda 1928 yang dianggap sebagai momen sakral dalam pembentukan sebuah bangsa, memori tentang reformasi belum menjadi kenangan kolektif yang mengingatkan banyak orang tentang nilai atau norma tertentu dalam tradisi politik Indonesia kontemporer.

Reformasi sebagai Lensa Kritik
Seperti pengalaman aksi mahasiswa Mei 1968 di Perancis, Mei 1998 tetap hidup dalam kenangan banyak orang dan memberi makna penting sebagai lensa kritik terhadap bekerjanya praktik politik di Indonesia. Tidak dapat disangkal, ia adalah suara pinggiran. Namun, ia paling tidak membentuk kesadaran sejarah dalam gerak linear yang membentuk momen reformasi dalam agenda politik masa depan.
Terlepas dari inkonsistensinya, setiap kekuatan politik di Indonesia senantiasa menyatakan diri berada dalam arus semangat yang sama dengan menghidupkan roh sejarah reformasi dalam agenda politiknya. Tidak mungkin bagi setiap kekuatan politik di Indonesia menyatakan secara terang-terangan bahwa agenda politik mereka bertentangan dengan semangat reformasi 1998.
Sulit dibayangkan sekarang ini bahwa di Indonesia, kaum militer akan melakukan tindakan seperti yang dilakukan angkatan darat Thailand di bawah Sondhi Boonyaratkalin ketika menggulingkan Thaksin Shinawatra dari kursi kekuasaan pada September 2006. Kenyataan menarik dalam kasus Thailand adalah Jenderal Sondhi menyatakan tindakannya sebagai upaya “mengembalikan kekuasaan kepada rakyat” melalui pembentukan Dewan Reformasi Administratif dan tampil dengan pakaian sipil di hadapan publik.
Seperti di Thailand, reformasi di indonesia tetap menjadi kata kunci dalam kehidupan politik. Setiap pemerintahan yang muncul setelah keruntuhan Orde Baru akan membawa janji-janji yang membentuk semangat reformasi, untuk kemudian mengingkarinya. Ini dilakukan bukan karena ada nilai-nilai yang berseberangan dengan semangat reformasi di dalam pemerintahan yang dibentuk, tetapi demi alasan “real politik” semata: bertahan dalam koridor kekuasaan.
Pemakzulan presiden ketiga Abdurrahman Wahid sepertinya telah memberi pelajaran bagi pemerintahan selanjutnya untuk menempatkan “real politik” sebagai pertimbangan utama dalam kalkulasi politik mereka. Pertimbangan “real politik” inilah yang kemudian menjadi norma standar kehidupan politik sekarang. Ini adalah buah nyata reformasi sekaligus menjadi norma yang paling terlembagakan dalam setiap pemerintahan pasca-Soeharto.
Pembahasan tentang periode reformasi pada akhirnya adalah pembahasan tentang pengalaman kontemporer kita sendiri. Mungkin masih diperlukan waktu satu atau dua dekade ke depan untuk kita semua mendapatkan akhir perjalanan periode ini. Ia bukan sejarah yang sudah final dan masih menyisakan persoalan yang belum tuntas.
Mengenang reformasi setelah dua dekade berlalu dengan demikian adalah upaya membersihkan kembali lensa kritik terhadap sistem politik Indonesia sekarang ini. Bertahun-tahun kemudian, ia akan menjadi kisah utuh di tangan para sejarawan.
==========
Andi Achdian, sejarawan dan pengajar di FISIP Universitas Nasional, pernah menjadi aktivis LBH pada 1994-1999.
Artikel dari para kolumnis adalah rangkaian dari laporan dapur redaksi Tirto mengenai 20 tahun reformasi. Kami menyiapkan sejumlah pembahasan lewat Kronik Reformasi, beberapa artikel lepas yang menyoroti beberapa peristiwa penting pada Mei 1998 lewat Mozaik, serta peristiwa politik yang menyulut huru-hara di tahun-tahun terakhir kekuasaan Orde Baru lewat laporan Indepth. Kami juga mengajak Anda terlibat dalam peristiwa besar tersebut yang akhirnya mendorong Soeharto mundur lewat Tirto Visual Report.
Editor: Ivan Aulia Ahsan