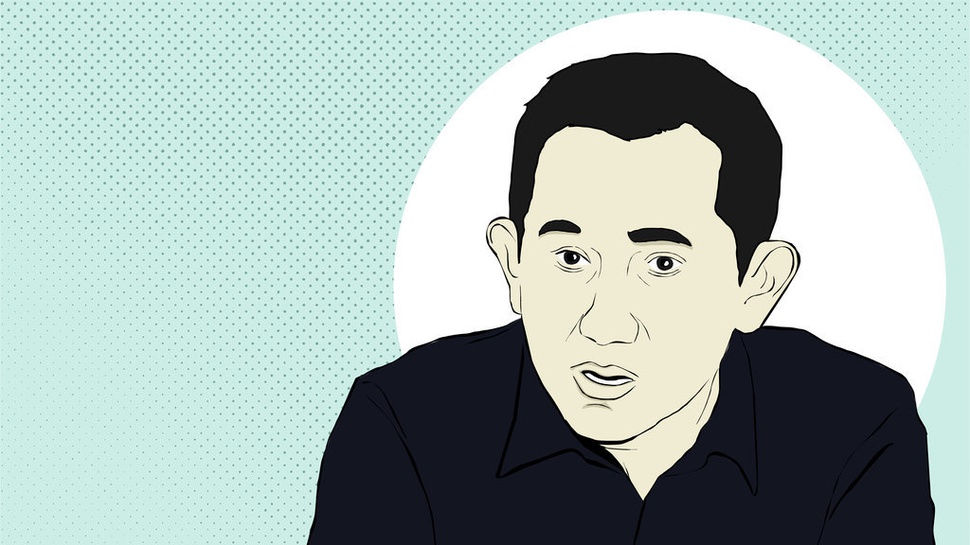tirto.id - Dua kali berturut-turut Eep Saefulloh Fatah berhasil terlibat memenangkan kandidat dalam Pilkada DKI Jakarta. Bersama PolMark yang ia dirikan pada 19 Oktober 2009, Eep ikut membantu Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno memenangi Pilkada DKI Jakarta pada 2012 dan 2017.
Baik Pilkada DKI Jakarta 2012 maupun 2017 punya makna khusus bagi Eep. Untuk Pilkada DKI 2012, Eep menganggap keberhasilannya membantu Jokowi-Ahok memang sangat penting dalam tonggak perjalanan Polmark.
"[Pilkada DKI 2012] itu pertama kali Polmark muncul di pentas nasional sebagai lembaga konsultan. Tidak ada satu pun kegiatan pendampingan kami sebelumnya yang ada di bawah spotlight," kenang Eep.
Khusus untuk 2017, Eep tidak hanya sekadar konsultan, tetapi juga elemen penting dari tim pemenangan.
"Saya itu konsultan, bukan tim pemenangan. Satu-satunya saya terlibat begitu jauh di Pilkada adalah Jakarta 2017," kata Eep kepada Tirto.
Polmark sudah bekerja untuk Pilkada DKI Jakarta 2017 sejak awal 2016. Sejak Februari 2016, Eep mengaku sudah bekerja sama dengan Sandiaga Uno sebagai tim survei. Namun ia tidak hanya bekerja untuk Sandiaga, pada Juli 2016 ia juga bekerja sama dengan Sjafrie Sjamsoeddin, lagi-lagi untuk kerja survei.
"Kalau survei tidak ada istilah mau tidak mau. Kami bersedia melakukan survei dengan siapa pun. Kalau sudah melakukan pendampingan [tim konsultan], baru kemudian memakai banyak pertimbangan," tutur Eep.
Ia tidak menyangkal jika Pilkada DKI 2017 sangat menyita tenaga. Namun, dalam Pilkada serentak 2017 kemarin, kendati sangat disibukkan oleh kontestasi politik yang begitu sengit di Jakarta, Polmark tidak hanya bekerja di Jakarta saja. Pada saat berbarengan, PolMark juga menggarap pilkada di Sulawesi Barat dan Bangka Belitung.
"Bagi saya," kata Eep, "Pilkada DKI Jakarta 2017 itu terbagi menjadi tiga babak. Masing-masing babak strateginya lain. Ini tidak banyak dimengerti. Banyak juga yang salah paham dengan sentimen SARA, politisasi masjid, dan isu penolakan salat jenazah."
Tirto berkesempatan mewawancarai Eep Saefulloh Fatah pada 5 Juni 2017 lalu. Eep bercerita banyak tentang strategi politik yang ia jalankan selama Pilkada DKI 2017, termasuk bantahan-bantahannya terhadap tudingan bermain sentimen SARA. Ia juga menceritakan beberapa tindakan yang diambilnya langsung selama Pilkada, termasuk ketidaksetujuannya terhadap Aksi 313. Juga relasinya dengan Presiden Joko Widodo yang, pada 2012, ia bantu dalam Pilkada.
"[Pada Pilpres 2014 saya] memilih Jokowi-JK dengan sadar, membantu probono [juga] dengan sadar," kenang Eep.
Setelah berseberangan secara posisi politik dengan Jokowi pada Pilkada 2017, apakah Eep menyesal memilih dan membantu Jokowi pada Pilkada 2012 dan Pilpres 2014? Simak wawancara khusus dengan Eep yang berlangsung pada 5 Juni 2017 di kantor Polmark. Selama kurang lebih tiga jam, Eep melayani pertanyaan Zen RS dan Windu Jusuf yang ditemani fotografer Andrey Gromico dan videografer Naomi Pardede dari Tirto.
Apa yang membuat Anda memutuskan terlibat jauh di Pilkada Jakarta 2017?
Pertama, kandidatnya. Anies ini, kan, teman sejak lama. Sandi juga segenerasi dengan saya. Bahkan dilihat dari kelahiran, saya dua tahun lebih tua dari mereka. Mas Anies ini sejak sebelum pulang dari Amerika [sudah] berinteraksi dengan saya, sekalipun tidak intens karena sibuk masing-masing.
Anda ditawari Ahok juga?
Saya tidak ditawari, tapi ada satu pihak yang mengaku dari tim pemenangan Ahok. Tapi itu [terjadi] setelah saya terlibat sebagai konsultan tim pemenangan Anies. Kalau dari pihak Mas Agus-Mpok Sylvi, enggak ada yang minta.
Lalu mengapa memilih Anies?
Saya lihat banyak orang yang salah melihat tentang kerja pemenangan di Jakarta. Orang banyak melihat, kalau orang menentang Basuki menjadi gubernur lagi karena dia Tionghoa atau dia Kristen. Saya pribadi tidak punya masalah dengan dia Tionghoa atau dia Kristen.
Jakarta saya lihat, dengan ekspos media dan media sosial yang luar biasa, butuh pemimpin yang bukan saja punya kemampuan teknokratis yang cukup, tetapi [butuh] “pemimpin”. Kalau sekadar mampu secara teknokratis, seorang manajer bisa melakukan itu. Kalau sekadar kemampuan teknokratis, tidak perlu pemimpin untuk melakukan itu.
Di Jakarta dibutuhkan pemimpin yang komunikasinya harus terjaga, yang membuat orang menganggap ia layak diteladani, dan seterusnya. Yang tidak arogan. Menurut saya arogansi [yang] dilakukan di mana saja, [oleh] siapa saja, apapun agamanya, apapun suku bangsanya, tidak menarik. Dan [orang yang melakukannya] tidak punya kelayakan sebagai pemimpin. Itu pendapat pribadi saya.
Tapi saat mengadakan pertemuan dengan Rizieq Shihab, Anies bicara soal superioritas keturunan Arab dalam pergerakan Indonesia. Dia bicara bahwa tidak ada etnis lain selain Arab yang menyatakan membela Indonesia, bukan membela homeland-nya. Padahal, etnis Tionghoa dengan Partai Tionghoa Indonesia-nya dan Douwes Deker dengan Indo-nya [Indische Partij] sudah terlebih dulu melakukan itu. Bagaimana ini?
Kita pernah diskusikan ini secara terbatas, ya. Problemnya adalah tidak ada chauvinisme Arab, yang ada kekeliruan fakta. Artinya, ada fakta yang tidak diceritakan [oleh Anies] secara seimbang. Saya kira itu. Karena tidak ada sikap komunikasi yang persisten, yang menunjukkan kalau Anies Baswedan punya sikap Arab chauvinistik.
Sebenarnya kalau tidak ada kekeliruan fakta itu, komunikasi yang dilakukan Anies sangat wajar dilakukan. Kalau seorang calon bertemu dengan jajaran polisi, maka dia akan mengungkapkan betapa besar peranan polisi. Kalau dia bicara di Padang dengan tokoh-tokoh Sumatera Barat, dia akan cerita Indonesia merdeka itu otaknya orang Padang. Itu sangat umum dalam komunikasi. Jadi, mengatakan bahwa satu kelompok masyarakat punya peranan, itu bukan berarti menegasikan yang lain. Ketika bicara terlalu superlatif, sampai "tidak ada kelompok yang lain", di situlah fakta sejarah dikhianati.
Waktu isu penolakan salat jenazah, Anies bikin pernyataan resmi bahwa muslim harus menyalatkan. Tapi, dalam pernyataan yang sama, Anies mengatakan penolakan isu salat jenazah adalah dampak kampanye hitam bahwa Anies dan Sandi akan menghapus KJP. Nyambung-nya di mana [antara penolakan salat jenazah dengan isu penghapusan KJP]?
Itu sangat nyambung karena data lapangannya seperti itu. Sejarahnya begini. Putaran satu baru saja berakhir, lalu kegiatan penggalangan akan dilakukan di berbagai tempat untuk putaran kedua. Dari situ ada laporan dari para relawan, kalau di berbagai tempat, ada door-to-door marketing tentang dihentikannya KJP, dibubarkannya pasukan oranye, dan lain-lain, sebagai materi kampanye di saat-saat yang paling menentukan menjelang pencoblosan putaran satu.
Nah, dari situlah muncul gelombang kemarahan di mana-mana. Sayalah yang mendapat kabar bahwa akan ada rencana perlawanan. Sebetulnya, awalnya hanya beberapa masjid yang punya rencana itu [penolakan salat jenazah]. Dan sikap saya, Anies, Sandi tegas waktu itu: tidak elok itu. Akan merugikan. Kampanye [seperti] itu sangat merugikan Anies-Sandi.
Dari sisi apa merugikannya?
Lho, citranya.
Dari sisi elektoral merugikan?
Iya, dong. Marketing itu begini cara berpikirnya. Kalau kita ketemu orang di masjid, [mereka] pasti milih Anies-Sandi. Please! Isu Al-Maidah 51 itu sudah begitu rupa. Pertengahan November kita bikin survei, 94 persen orang Jakarta sudah tahu isu itu. 70 persen mengatakan Ahok penista agama, 50 persen minta Ahok dipenjarakan. Itu captive market. Ngapain lagi kampanye di masjid?
Tapi, kan, penolakan salat jenazah ini dampaknya bukan hanya untuk orang-orang yang senang berkumpul di masjid [termasuk seluruh muslim yang mungkin tidak aktif di masjid]?
Begini, lho. Kalau ada isu bahwa pengurus masjid melarang menyalatkan pendukung Ahok, yang paling dirugikan itu Anies. Karena citranya, karena soal kemanusiaan, soal macam-macam. Kalau kita punya akal sehat, enggak mau kita kampanye itu.
Jadi penolakan salat jenazah bukan bagian dari kampanye Anies-Sandi?
Sama sekali bukan. Teman-teman media enggak pernah tahu, kan, apa yang terjadi di lapangan sesungguhnya ketika menghadapi orang-orang itu? Ketika orang-orang dikumpulkan, yang ada golok segala macam itu, Sandi tidak mungkin tiba-tiba pergi. Dia sudah mengatakan, "Jangan pakai itu, dong." Enggak bisa dihentikan. Tiba-tiba bubar gitu, enggak bisa.
Jadi Anda tidak [merasa] mengkapitalisasi sentimen SARA ini?
Saya tidak mengkapitalisasi sentimen SARA. Jadi begini. Segera setelah putaran satu selesai, saya mendatangi satu pondok pesantren, namanya Miftahul Ulum di jalan Madrasah, Gandaria, Jakarta Selatan. Itu salah satu pesantren besar di Jakarta yang paling terkemuka. Saya mendatangi K.H. Muhidin Ishaq yang merupakan pendukung Agus-Sylvi. Untuk pertama kali sepanjang sejarah, ia kalah di TPS-nya.
Kiai Muhidin ini jagoan, jawara. Ayahnya ulama. Saya datang ke rumahnya, dia sudah marah dan sudah membuat investigasi. Orang-orang di TPS-nya dikasih uang 700 ribu sampai 1 juta sehingga kalah. Marahlah dia. Dia punya pemakaman, wakaf dari kakeknya, 2,6 hektar di pusat kota. Dan waktu saya datang ke sana, dia baru saja memasang spanduk besar: "Pendukung Ahok haram dikubur di sini."
Saya datang, lalu saya jelaskan segala macam bahwa itu kontraproduktif. Karena tidak ada untungnya sama sekali buat Anies-Sandi ada kampanye semacam itu. Kerugiannya berlipat-lipat. Tidak akan menambah suara dan tidak akan mengurangi suara Ahok, sementara citra publiknya akan rusak. Lalu Pak Kiai bilang: "Cara apa yang bisa membuat Anies menang?"
Saya buka Ipad saya, saya perlihatkan rencana strategi pemenangan putaran kedua. Saya perlihatkan data-data survei segala macam. Saya usulkan cara-cara alternatif kepada dia. Lalu saya pulang. Sebelum saya pulang, spanduknya sudah diturunkan. Salah besar kalau kami dibilang mengkapitalisasi sentimen SARA atau politisasi masjid.
Situasi sudah telanjur terjadi, kan?
Semua orang harus bertanggung jawab atas situasi ini.
Termasuk Anda yang banyak dituduh soal ini [sentimen SARA dan politisasi masjid]?
Ceritanya begini. Sebenarnya ada ceramah saya di Al-Azhar yang dilakukan pada Agustus 2016. Pada waktu itu, nama Anies belum ada. Anies-Sandi belum ada tentu saja. Kemudian mereka bikin diskusi, seperti mabit-mabit biasanya. Salah satu diskusi itu mengundang saya, Mas Yoyo Bupati Batang dan Mas Khusnil, salah satu orang IT di tim Jenggala, timnya Pak JK waktu Pilpres kemarin. Yang menyelenggarakan adalah pengurus masjid Al-Azhar bersama Pejuang Subuh. Lalu saya ceramah dan mereka rekam.
Yang pertama saya menjelaskan apa itu kontestasi politik karena temanya "Umat Islam dalam Kontestasi Politik Jakarta." Bagian kedua, umat Islam ini harus mengoptimalkan semua resources-nya ketika melakukan kontestasi. Lalu, saya mencontohkan satu versi analisis yang menjelaskan kenapa partai FIS bisa menang di Aljazair. Dia tidak punya jaringan partainya, dan seterusnya.
Menurut analisis itu, FIS bisa menang karena ada jaringan masjid yang berfungsi. Tapi saya katakan bahwa yang dimaksud bukan seruan-seruan politik partisan, [semacam] pilih si A, jangan pilih si B. Melainkan seruan-seruan politik agar umat menegakkan hak mereka. Tahu dan pandai menjaga hak mereka, hak orang lain, dan hak orang banyak. Bertumpu pada diri sendiri, bukan pada orang lain. Aktif, tidak menunggu. Dan melawan dengan beradab dengan cara yang diajarkan Islam ketika haknya dicederai. Itulah yang harus diserukan.
Lalu sampailah di bagian ceramah saya yang paling panjang. Saya diminta cerita bagaimana dulu saya bisa memenangkan Jokowi-Ahok 2012 di Jakarta. Saya katakan bahwa [caranya] seperti yang diajarkan Islam, seperti yang saya percaya sejak di Madrasah Ibtidaiyah yaitu pakai ilmu. Kalau tidak pakai ilmu, enggak bisa menang.
Saya cerita kalau Jokowi itu walikota yang hanya punya waktu 38 hari untuk kampanye. Sementara lawannya incumbent yang bisa setiap hari. Lalu, kami membuat peta pemenangan di Jakarta. Kemudian terakhir saya sampaikan bahwa untuk menang umat Islam harus mengubah dirinya, dari kerumunan menjadi barisan. Saya kutiplah As-Shaf ayat 4.
Lalu yang dilakukan oleh si pengedit video adalah menyambungkan tentang analisis kemenangan FIS dengan [momen ketika] saya [mengatakan] ingin menggunakan “itu” untuk mengalahkan Ahok. Maksud sebenarnya dari “itu” berkaitannya dengan ilmu, bukan dengan politisasi masjid. Dari situlah sumber dari segala kerusakan.
Di video itu Anda memilih membuka ceramah dengan FIS. Kenapa FIS? Kenapa bukan, misalnya, Ikhwanul Muslimin atau AKP?
Saya hanya mau menyitir peristiwa di mana jaringan masjid digunakan dan bisa efektif waktu itu. Buat orang yang belajar politik, kemenangan FIS di Aljazair itu sangat mengejutkan. Waktu saya di Amerika, saya pernah membaca analisis tentang kemenangan FIS yang bisa menang itu enggak terduga sama sekali. Ternyata FIS punya jaringan yang kasat mata yaitu masjid.
Jadi sebenarnya saya mau menggarisbawahi bagaimana masjid digunakan dalam sebuah peristiwa politik dan bisa fungsional. Lalu yang mau saya garis bawahi bukan partai Islamnya, tapi masjidnya. Terutama salat Jumat. Karena pada waktu itu khatib-khatib di Aljazair yang menyerukan bahwa umat harus menegakkan hak mereka. Konteksnya itu sebetulnya.
Sejak kapan yakin Anies-Sandi akan menang?
Sejak saya membantu, saya yakin menang. Sejak 23 September ketika Anies-Sandi didaftarkan resmi.
Tapi putaran pertama, kan, kalah?
Enggak ada istilah kalah [di putaran pertama]. Yang saya optimis, kan, memenangkan Pilkada. Putaran satu, masuk putaran kedua.
Anda yakin dua putaran?
Saya dari awal melihat dua putaran. Tidak pernah ada pembicaraan soal satu putaran. Ahok itu potensi kalahnya sudah terlihat sejak awal sebelum ada isu Al-Maidah.
Potensinya di mana?
Orang yang puas sama dia di atas 70 persen. 72 koma sekian persen. [Tapi] yang menginginkan dia jadi gubernur [hanya] 40 persen. Ketika dilacak, salah satu sebabnya, ya, itu: Ahok dianggap tidak bisa jadi teladan yang baik. Ahok dianggap punya masalah dalam komunikasi.
Jadi, dari data yang terlihat resistensi terhadap Ahok sudah muncul sejak Februari 2016 dan Juli 2016. Terus sebagai incumbent dia hanya punya elektabilitas sedikit di atas 40 persen, itu indikasi buruk. [Padahal] belum ada Al Maidah waktu itu. Jadi sudah kelihatan dari awal. Tetapi yang kuat dari Ahok itu resources-nya yang gila-gilaan.
Jadi Anda membantah argumen yang mengatakan Ahok kalah karena Al Maidah?
Al Maidah punya peranan. Tapi harus dilihat secara proporsional peranannya dalam tiga pengertian.
Pertama, Al Maidah itu bukan kehebatan orang lain, tapi kesalahan Ahok. Kalau Ahok tahu dia adalah minoritas, dia harus berkampanye dengan hati-hati dan kreatif. [Ini] unsur sangat elementer dalam kampanye dan itu diabaikan. Di Indonesia ada bendungan besar, namanya sensitivitas agama. Kadang jebol. Pernah dijebol sama Arswendo Atmowiloto. Dan yang terbesar itu kemarin. Dan yang menjebol bendungan itu Ahok, bukan orang lain. Kemudian meluaplah kemarahan orang. Dan kita tidak bisa mengendalikan kemarahan yang luar biasa besar itu.
Kedua, ketika putaran satu ditanya di exitpoll, hanya 9,7 persen yang memilih semata-mata karena sebab agama. Jakarta itu suasananya begitu. Orang yang memilih semata-mata karena agama, [memang] ada, tapi bukan segmen yang terbesar. Dan itu captive market-nya Agus dan Anies. Jadi bukan mereka yang mengalahkan Ahok, kalau mereka sudah serta merta tidak memilih Ahok.
Survei bulan Juli itu situasinya 30-40-30. 30 persen mati-matian mau Ahok, 30 persen mati-matian tidak mau Ahok. 40 persen itu yang di tengah. Makanya kampanyenya, kan, di tengah. Tidak di kanan. Yang 30 persen tidak mau Ahok itu pun hanya sebagian kecil yang karena agama. Ada orang yang tidak suka dengan cara berkomunikasinya Ahok. Ada orang yang digusur, lalu tidak memilih Ahok. Itu kumpul semua menjadi 30 persen itu. Bukan karena Ahok Kristen, bukan karena Ahok Tionghoa. Itu kesalahan kalau menggeneralisasi.
Sebenarnya captive market Ahok lebih besar, 30 persen. 30 persen yang lain, kan, terbagi dua, tuh, antara Anies dan Agus. Makanya fokus kebijakan tim pemenangan Anies-Sandi mau mengambil yang tengah, yang 40 persen. Karena itulah muncul salam bersama. Waktu launching, kalau teman-teman media meliput, itu sangat Sukarno, sangat tengah. Tidak pakai peci waktu itu. Jadi bukan memainkan isu agama yang harusnya dilakukan, tapi berkampanye beyond itu.
Ketiga, yang penting menurut saya adalah penciptaan diferensiasi yang tepat. Kelemahan Ahok yang terpenting adalah dianggap tidak membela rakyat. Itu sudah terlihat sejak survei Februari dan Juli sebenarnya. Nah, di mana-mana Anies-Sandi ngomong tiga hal itu: lapangan kerja, pendidikan, dan biaya hidup. Selalu itu.
Hasil putaran pertama seperti dugaan anda?
Sebenarnya meleset dari yang kami duga. Berdasarkan hasil kajian kami, sebenarnya Anies nomor satu, tapi tipis di atas Ahok. Yang tidak pernah kami duga adalah ada 247 ribu DPTP yang mayoritas terkonsentrasi di TPS-TPS yang dimenangkan dengan telak oleh Ahok.
Lalu apa yang Anda lakukan terkait strategi pemenangan?
[Pilkada] Jakarta kemarin itu bisa dibagai menjadi tiga. Putaran satu sebelum isu Al Maidah, putaran kedua setelah isu Al Maidah, dan putaran kedua. Babak pertama itu akhir September sampai pertengahan November, jadi satu setengah bulan [untuk] babak pertama. Kemudian pertengahan November sampai 15 Februari [babak kedua]. Lalu kemudian 15 Februari sampai dengan 19 April, itulah babak ketiga.
Di putaran pertama setelah isu Al Maidah kami berebut suara dengan Agus. Maka, foto surat suara kemudian diganti memakai peci. Sebelumnya tanpa peci, latar belakangnya biru karena tidak ada satu pun partai pengusung Anies-Sandi yang identitasnya biru. Kami ingin memisahkan Anies-Sandi dengan partai pengusung. Maka [setelah isu Al Maidah, foto] diganti pakai peci, baju putih, latar belakangnya merah. Salam bersama, tetap. Lalu roadshow ke tokoh-tokoh Islam untuk merebut suara Agus.
Pada babak pertama ini bekal yang kita punya adalah survei Februari dan Juli. Dua-duanya mengindikasikan bahwa peta elektoral di Jakarta adalah 30-40-30. Kemudian strategi Anies-Sandi adalah mengambil yang 40. Jadi tidak bergerak ke kanan. Bukan meneriakkan takbir berulang-ulang, bahasa sederhananya.
Yang 40 ini mengambilnya bukan lewat takbir. Lewat jalan menengah. Mereka adalah kelas menengah, berpendidikan, mereka anak muda, milenial, dengan segala kemandiriannya, netizen, orang-orang yang sangat pandai bergaul di media sosial. Maka Anies-Sandi harus berkampanye dengan bahasa yang sama dengan yang 40 persen ini.
Dari awal putaran satu, definisi kami itu, kami tidak berhadapan dengan Ahok, tapi kami berhadapan dengan Agus. Data survei menunjukkan Ahok kemungkinan besar lolos di tahap satu. Teman Ahok di putaran kedua itulah yang harus dijawab oleh strategi pemenangan. Karena itu, fokus kami ke Agus.
Kemudian kami mendapatkan limpahan keuntungan, karena kekeliruan strategi Ahok dan Agus yang saling menyerang. Anies-Sandi melipir. Dan kalau kami menyerang Agus, kami tidak pernah mengkritik kebijakan-kebijakan tertentu yang sesuai dengan 3 isu kami (lapangan kerja, pendidikan, dan biaya hidup). Itulah babak satu.
Babak satu ini berakhir karena isu Al Maidah. Lalu ada survei dari lembaga second opinion. Datanya amat sangat meyakinkan: 94 persen tahu soal Al Maidah, 70 persen menganggap Ahok penista agama, 50 persen minta Ahok dipenjara. Data itu membuat suasana peta elektoral berubah. Dari 30-40-30, menjadi 30 dan sisanya. 30 itu adalah captive market-nya Ahok, sisanya itulah yang harus direbut.
Lalu berubahlah kampanye kami. Berubah ke kanan, bukan untuk menyerang Ahok. Tapi bergerak ke kanan untuk merebut suara yang bisa diambil Agus. Itu yang sering salah paham orang. Makanya, Anies-Sandi berkeliling ke tokoh-tokoh agama Islam. Tanpa terkecuali, dari spektrum yang paling lembut sampai spektrum yang paling keras.
Kebetulan ada limpahan keuntungan lagi bagi kami. Yaitu Pak SBY membuat konferensi pers yang memisahkan dengan Bela Islam, dengan bahasa-bahasa yang artikulatif, dan membuat Agus punya ruang manuver yang sangat sempit. Dengan konferensi pers itu, Agus sangat terbatas manuvernya untuk bertemu dengan banyak tokoh-tokoh Islam yang terlanjur sudah diidentifikasi sebagai tokoh Bela Islam. Anies tidak punya masalah. Maka Anies sapu semuanya, bersamaan dengan tokoh yang lain. Sekalipun yang diberitakan kemudian adalah [bertemu] Habib Rizieq [saja].
Inilah babak kedua. Jadi putaran kedua kami ambil haluan kanan, menambahkan peci pada foto surat suara lalu menggenjot habis pendekatan terhadap tokoh-tokoh yang menjadi simpul jaringan pemilih Islam. Untuk merebut suara dari Agus.
Ketika ini sudah selesai, dan kami berhasil mendapat 40 persen suara, Ahok 43 persen suara, maka kemudian kami masuk ke babak ketiga.
Balik lagi ke tengah?
Kita balik lagi ke tengah karena suara kanan sudah kita ambil. Dalam beberapa pertemuan di kompleks masjid Baitul Muqni, di tempat Kiai Luthfi Fatullah Muqni, saksinya banyak yang di pertemuan itu. Saya berulang-ulang menyampaikan dan mempresentasikan ini, dengan mengatakan bahwa: "Kita tidak lagi memfokuskan diri dalam merebut suara kanan, karena mereka sudah bersama kita. Dan pesan kita sekarang adalah pesan yang bisa diterima oleh sebanyak mungkin orang. Karena itu kita harus berhenti mengatakan 'Jangan pilih kafir.' Dan mengubahnya dengan, 'Mari saatnya umat memilih'. Komunikasinya harus berubah total.”
Jadi masuk babak ketiga, pendekatan kita adalah Merah Putih, bukan kotak-kotak. Kalaupun ada, satu-satunya identitas kanan yang kita masukkan bukan “Kerja, Kerja, Kerja,” tapi "Kerja berbasis akhlak, adab, iman, dan takwa." Hanya itu saja dalam rumusan strateginya.
Saya terbuka saja bilang, saya adalah salah satu yang tidak setuju dengan aksi 313. Walaupun katanya tidak berkaitan dengan pilkada, tetap saja dampaknya secara media tidak menguntungkan Anies-Sandi. Saya termasuk yang berulang-ulang mengatakan ke teman-teman GNPF supaya Tamasya Al Maidah dibatalkan.
Bagaimana dengan sikap Anies-Sandi?
Anies sependapat [dengan saya]. Tapi, kan, Anies tidak leluasa ngomong. Sandi tidak leluasa ngomong. Kalau kandidat, kan, harus jaga betul omongan. Ada banyak omongan yang bagus diucapkan, tapi tidak oleh kandidat. Oleh orang lain. Buat saya, sih, aman-aman saja kalau saya ngomong. Karena selain tim pemenangan, saya juga konsultan.
Ketika sudah pengumuman resmi KPU [memenangkan Anies-Sandi] sudah selesai kerja sama?
Kami punya kebiasaan menyelesaikan 1 bulan setelah pencoblosan. Kalau enggak salah kita berakhir di Jakarta pada akhir Mei. Kalau sebagai tim konsultan, sejak saat itu saya sudah tidak terlibat. Tapi kalau sebagai temannya Anies, temannya Sandi, saya masih intens berkomunikasi. Beberapa grup Whatsapp masih dipertahankan sebagai bagian dari sinkronisasi, dan lain-lain.
Anda menyebut bendungan “sensitivitas agama” yang dijebol oleh Ahok melalui ucapan Al-Maidah. Apakah bendungan [yang jebol] ini bisa digunakan oleh kelompok Islam Politik untuk melampaui mediokritas mereka secara elektoral?
Semua partai Islam yang menggunakan Islam Politik sebagai senjata, saya yakin akan terpuruk secara elektoral. Karena kunci memenangkan suara umat Islam bukan di Islam Politik. Tapi penyejahteraan umat. Jadi kalau ada yang menjanjikan isu-isu formal, semisal Perda Syariah, apalagi sampai mengganti dasar negara, saya yakin partai itu akan hancur. Kepercayaan [ini] tumbuh sejak lama, sejak survei-survei prevalensi politik semenjak tahun 1999. Tidak pernah ada data [yang menunjukkan] partai-partai yang menawarkan Islam Politik, Islam secara formal, mendapatkan tempat yang luas. Di Jakarta pun tidak.
Kalau ada pertanyaan "Apakah Islam Politik bisa digunakan partai-partai Islam supaya tidak jadi partai rata-rata?" ada dua masalah di sini. Pertama, Islam Politik sendiri tidak laku dijual di Indonesia. Kemudian, masalah partai-partai Islam dalam elektoral adalah gagal masuk ke isu-isu yang konkret buat umat, buat warga. Ketika partai-partai Islam itu tidak punya diferensiasi dengan partai-partai lain, makin terpuruklah mereka.
Jadi, kalau kita menganjurkan partai Islam untuk menaikkan isu Islam Politik dalam elektoral, ini seperti menggaruk kening ketika lutut kita gatal. Tidak saling berkaitan.
Anda menganggap kekhawatiran politik SARA dan Islam Politik berlebihan?
Nah, kekhawatiran terhadap Islam yang menggeliat sekarang ini adalah warisan dari Pilkada Jakarta 2017. Di Pilkada Jakarta, diakui atau tidak, ada satu perangkat yang dikembangkan oleh pihak Basuki-Djarot yaitu islamofobia sebagai political marketing. Dengan harapan ada ketakutan terhadap hantu yang gambarnya jelas. Dan mengalihkan suara dari hantu itu. Itu yang gagal.
Islamofobia diciptakan dengan begitu kuatnya, sehingga hantu itu sebenarnya jauh lebih besar dari yang sesungguhnya. Tidak ada suasana yang beda ketika Anies berkunjung ke FPI dengan ketika Anies berkunjung ke organisasi Islam lain. Yang membedakan adalah adanya kapitalisasi bahwa pemilih Anies-Sandi adalah pemilih Habib Rizieq. Sehingga [diharapkan] menurunkan daya elektoral Anies-Sandi. Nah itu yang gagal. Mengaitkan semua pemilih Anies-Sandi dengan Habib Rizieq itu sangat bermasalah. Jadi, jangan-jangan Habib Rizieq dibesarkan oleh mereka-mereka yang ketakutan akan hantu yang ada di kepala mereka sendiri.
Lalu soal rekonsiliasi?
Rekonsiliasi ini perlu pikiran sehat tentang warga Jakarta, pemilih Jakarta, dan apa yang terjadi di Pilkada kemarin. Kalau cara berpikir yang sehat itu tidak bisa kita bangun, rekonsiliasi akan bisa tersendat-sendat.
Misalnya, sekarang [ada] upaya untuk mem-frame bahwa memilih Ahok Pancasila(is), toleran, sementara yang tidak memilih Ahok sebaliknya. Itu bermasalah sekali. Bahkan pernah beberapa kali saya katakan, mengidentikkan memilih Ahok dengan kesetiaan terhadap Pancasila itu menyesatkan sekali.
Orang menjadi tidak rekonsiliatif pikirannya ketika memiliki frame itu, atau dipaksa melihat dengan frame itu. Itulah yang terjadi.
Anda tidak menyesal memilih Jokowi?
Tidak. Selalu banyak waktu untuk menjatuhkan opsi. Dan pada Pilpres 2014, saya punya data tentang dua opsi itu [memilih Jokowi dan membantu Jokowi secara probono]. Dan dengan sadar saya menjatuhkan opsi ke Jokowi.
Semua saya lakukan seperti relawan. Tapi berbeda dengan relawan kebanyakan, saya membawa kompetensi saya di situ. Saya bahkan membawa karyawan PolMark dalam urusan itu. Jadi saya bekerja penuh sebagai konsultan, tapi probono [tanpa dibayar].
Sepanjang sejarah PolMark Indonesia, itu probono kedua yang kami lakukan. [Pertama] Sofyan Tan di Medan, kemudian Pilpres kemarin. Jadi ketika pilihan saya ambil, saya pilih dengan sadar. Memilih Jokowi-JK dengan sadar, memilih probono dengan sadar.
Saya merasa, ikut terlibat dalam pilpres kemarin [adalah hal yang] saya perlukan sebagai warga negara. Saya harus bersikap atas pilihan yang tersedia pada saat itu. Dan saya sebagai pemimpin perusahaan merasa bahwa ini tidak buruk untuk perusahaan. Yang buruk adalah kalau Jokowi kalah, lalu orang mencatat PolMark adalah lembaga konsultan yang gagal di Pilpres 2014. Dan risiko itu harus diambil, karena selalu tersedia risiko itu.
Jadi saya tidak pernah menyesal menjadi tim kerja pemenangan Jokowi, memilih Jokowi. Yang harus saya sikapi dengan kritis, kan, apa yang terjadi kemudian. Bahwa setelah pilpres, posisi Jokowi dengan saya kan [antara] kepala negara dan warga. Dan saya punya hak untuk kritis, tidak setuju, yang dilindungi konstitusi.
Apa yang Anda rasakan setelah bisa membantu memenangkan Jakarta?
Saya biasa aja. Wallahi, perasaan saya biasa aja. Karena ini bukan menang pertama kali. Dan saya selalu percaya di mana-mana, dalam suatu kerja pemenangan Pilkada, tidak pernah ada satu pihak yang bisa dianggap pahlawan sebagai [faktor] determinan pemenangan. Kerja pemilu dan pilkada itu ikhtiar kolosal yang semua orang berkontribusi. Kita tidak bisa menilai siapa yang lebih besar dan siapa yang lebih sedikit.
Nanti 2018 atau 2019 Anda akan semakin banyak dibutuhkan, dong. Memengaruhi bujet [harga]?
Memengaruhi bujet, tidak. Karena kerja sama konsultan politik ini berhadapan dengan orang-orang yang bahkan harus diyakinkan dulu bahwa cara kerja semacam ini layak digunakan. Jangankan ngomong soal bujet. Mereka banyak yang tidak percaya bahwa kerja strategi pemenangan dan macam-macam itu bermanfaat untuk menang, sampai kemudian mereka membuktikan.
Satu contohnya begini. Titik balik kami sebenarnya bukan Jakarta 2017. Titik balik kami adalah Jakarta 2012. Pada waktu itu, ketika kami membantu Jokowi, pada Desember 2011 Jokowi elektabilitasnya masih di bawah 3 persen. Orang enggak kenal dia. Sampai kemudian banyak isu yang membuat dia beruntung. Ada ESEMKA, ada uji emisi, dan lain-lain.
Pada waktu itu dibutuhkan waktu yang tidak pendek dan tidak sederhana untuk meyakinkan Jokowi bahwa strategi pemenangan yang disusun itu berguna untuk menang. Tapi untungnya, dia percaya data. Dia rasional. Sekali dia percaya, semua lebih mudah dikelola. Nah, itulah yang membuat kami leluasa untuk mengembangkan metode baru.
Jadi untuk Jokowi, Pilpres 2014 lebih mudah dibanding Jakarta 2012?
Iya. Karena dia sudah punya modal. Jokowi dilantik [sebagai Gubernur Jakarta] 15 Oktober 2012. Mulai November, tiap PolMark bikin survei, kami selalu menyertakan pertanyaan soal Pilpres. "Jika pilpres diadakan hari ini, siapakah yang Ibu/Bapak pilih?"
Jadi kita tahu dari semua survei itu, Jokowi cuma kalah di empat titik survei.
Di mana itu?
Barito Utara, Kalimantan Tengah, kalah sama Bu Mega tapi tipis. Dan tiga kali survei di Makassar.
Titik balik 2012 itu dalam arti apa?
Itu pertama kali PolMark muncul di pentas nasional sebagai lembaga konsultan. Tidak ada satu pun kegiatan pendampingan kami sebelumnya yang ada di bawah spotlight. Sebagai kegiatan marketing amat sangat terbatas. Orang mana tahu kami konsultannya Teras Narang? Mana tahu orang kami konsultannya Sofyan Tan?
Penulis: Zen RS
Editor: Nurul Qomariyah Pramisti & Maulida Sri Handayani