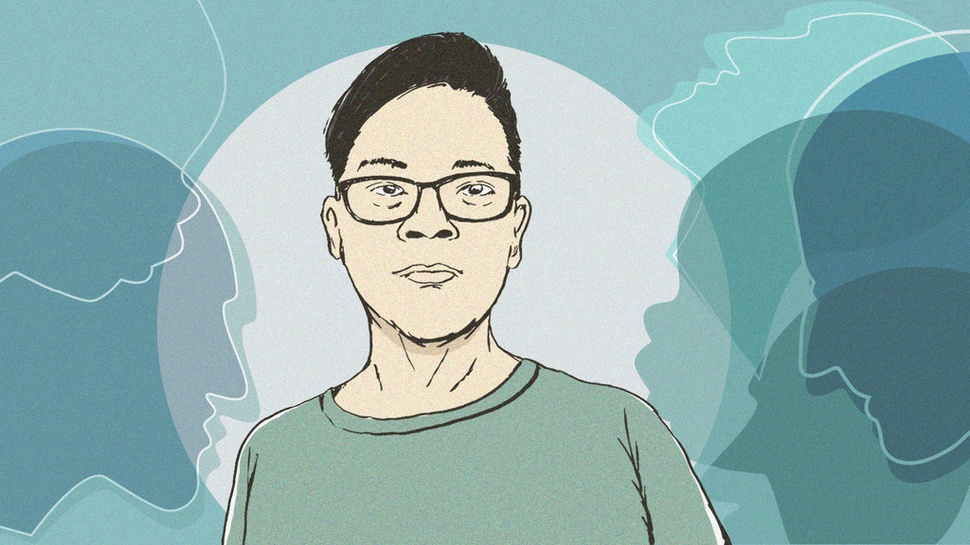tirto.id - Belakangan, kasus bunuh diri mahasiswa yang diduga karena tugas atau skripsi makin banyak. Sejak Mei 2016 sampai Desember 2018 saja, riset Tirto dari beragam pemberitaan online mencatat ada 20 kasus bunuh diri mahasiswa yang diduga terkait dengan tugas atau skripsi.
Fenomena ini dikuatkan oleh riset Benny Prawira Siauw, psikolog dan kepala koordinator Into the Light, komunitas pemerhati pencegahan bunuh diri. Riset Benny menemukan 34,5 persen dari 284 responden mahasiswa Jakarta dari beberapa universitas swasta dan negeri punya suicidal thought. Angka ini cukup tinggi sebab satu dari 3 responden riset Benny punya kecenderungan pemikiran bunuh diri.
Benny mengambil respondennya tidak secara proporsional. “Saya enggak ambil secara proporsional: setiap kampus harus berapa orang, berapa orang. Tapi, emang semua di Jakarta. Beberapa swasta dan negeri.” Umur respondennya antara 18-24 tahun “karena itu memang range umur sarjana.”
Berikut wawancara saya dengan Benny untuk membahas isu depresi dan bunuh diri di kalangan usia remaja beranjak dewasa, masa transisi bagi sebagian besar anak-anak muda Indonesia.
Kenapa tertarik meneliti responden dengan rentang usia 18-24?
Dalam penelitian global, range 18-24 itu memang paling susah nyari bantuan. Bahkan lebih susah (cari bantuan) dibanding (kelompok umur sama) yang enggak kuliah. Umur segitu masa-masa yang paling kritis isu kesehatan mentalnya. Angka-angka di luar negeri, seperti Inggris, US, dan Jepang. Jadi, saya tertarik mau tahu gimana di Indonesia.
Jadi, apa yang jadi faktor risiko terhadap mahasiswa?
Kalau di Jakarta masih belum bisa dijabarkan apa. Perlu penelitian selanjutnya. Into the Light tahun ini berencana akan bikin, sih. Jadi, kalo kayak (studi) Peltzer disebut itu apa-apa aja yang jadi faktor risikonya. Apakah sama? Apakah ada faktor akademisnya?
Jangan-jangan enggak ada faktor akademisnya, malah faktor orangtuanya yang lebih berpengaruh. Atau, bisa jadi, karena situasi kampusnya yang terlalu kompetitif, atau terkait dengan ekonominya? Mungkin September ke Desember [2019], baru kelar [penelitian kami].
Penelitian seperti itu belum pernah ada di Indonesia?
Waktu itu pernah ada. Tapi, kualitatif, dan sampelnya baru 13 orang. Jadi enggak berani digeneralisasi. Dan tidak semuanya mahasiswa. Jadi enggak bisa melihat populasi umumnya gimana.
Into the Light mau bikin survei se-Indonesia?
Enggak. Se-Jabodetabek aja.
Penelitian sebelumnya yang paling baru dari Peltzer dkk. Temuannya, 6,9 persen dari 231 responden mahasiswa Yogyakarta (18-30 tahun) punya pikiran bunuh diri. Nah, apa yang bisa kamu bilang dari risetmu sendiri di Jakarta?
Saya kaget waktu (temuan) saya sampai 30 persen lebih. Saya kaget itu. Saya juga berharap itu bukan angka yang benar, gitu: satu dari tiga responden saya punya pikiran bunuh diri.
Penjelasannya, karena Jakarta adalah kota dengan tingkat stres paling buruk di dunia. Itu pernah ada risetnya dari Zipjet. Penjelasan lain, mungkin dari cara mengisinya. Orang di Jakarta juga mungkin sudah cukup terbuka membicarakan isu ini. Culturally, tidak terlalu ... menekan.
Di Yogya, mungkin mereka lebih malu. Sehingga mereka memutuskan, ya sudah … report aja yang kondisinya baik. So, ada dua kemungkinan itu.
Maka, perlu penelitian lebih lanjut?
Perlu penelitian lebih lanjut. Memang, salah satu kelemahan riset bunuh diri dengan menggunakan alat ukur yang langsung take direction gitu ya dia (responden) akan malu. Tapi, ya kalau dia (responden) masih malu-malu di Jakarta, bisa aja angkanya lebih gede dong. Itu jadi concern saya, sih.
Kalau dibandingkan di luar Indonesia, sudah cukup terbuka kah dengan isu kesehatan mental?
Lagi-lagi ya, riset bunuh diri di Indonesia masih sangat sedikit, jadi agak susah untuk bilang itu (sudah cukup terbuka). Tapi, kecenderungannya sejak 2013, kita sudah lebih intens membicarakan bunuh diri lewat Into the Light.
Lalu, selebgram-selebgram mulai coming out, dengan kondisi suicidal mereka. Ya, narasi yang lebih positif itu sudah terbentuk. 'Ya udah, lo terbuka aja untuk cerita.'
Mungkin, terutama di daerah Jawa, yang jadi central of everything in Indonesia, mungkin lebih gampang untuk bicara kesehatan mental. Asumsinya sih, gitu.
Enggak ada indikator yang bisa dipakai untuk hitung itu?
Enggak ada. Agak susah. Kalau tren global sih mereka bilang, negara-negara Muslim agak susah untuk terbuka. Karena sangat di-condemn-kan. Jadi, kalau kejadian, itu jadi lebih susah (ditangani). Jadi, perlu banget narasi positifnya. Misalnya, jangan bahas dengan embel-embel dosa atau neraka.
Apakah Kementerian Kesehatan cukup perhatian dengan isu bunuh diri?
Ya, sebenarnya udah aware dalam arti sudah menyediakan seminar. Sudah banyak sosialisasi.
Efektif?
Kalau itu kita perlu evaluasi lebih lanjut, deh. Mereka sering kok ngundang sekolah, murid-murid untuk bicarain soal bunuh diri ini.
Tahun lalu, kita sempat juga ngajakin ngomong anak-anak. Sedikit banyak adalah dampaknya. Kita butuh juga yang jangka panjang. Sistem pencegahan bunuh diri itu enggak bisa dengan seminar doang. Kita mesti intervensi yang sangat sistemik.
Misalnya, kalau ditemukan ternyata penyebabnya adalah masalah ekonomi ... ya, berarti ekonominya dong yang diperbaiki. Bisa jadi itu salah satu faktor yang signifikan.
Berarti, sebelum bicara penanganan, kurikulum, dan lainnya, masalah minim penelitian juga harus dituntaskan?
Karena, kalau enggak ada data, gimana mau trouble shooting? Jangan-jangan entar kalau bikin riset yang biasa-biasa aja, trouble shooting-nya salah. Hasilnya normatif. Interpretasinya beda.
Modul dari luar negeri enggak bisa dicontoh?
Modulnya banyak. Tinggal menyesuaikan aja. Tapi, kalaupun mau dicomot dari luar negeri, materinya belum tentu cocok.
Misalnya, jenis stigma di Cina dan Australia itu ternyata beda. Hasil risetnya beda. Di Cina, punya konsep kekeluargaan, bakti pada orangtua. Di Australia, enggak sekuat di sana.
Pemberitaan bunuh diri juga masih banyak stigma. Apa dampaknya pada keluarga yang ditinggalkan?
Sebenarnya saya lebih concern sama keluarga yang ditinggalkan. Mereka berduka. Berduka itu enggak bisa kita omongkan dengan ceramah, dengan hal-hal yang normatif, apalagi menghakimi.
Dalam berbagai literatur, mereka juga suicidal. Karena mereka sedih iya, marah iya. Belum lagi distigma. Mereka butuh perhatian lebih khusus.
Catatan buat media sendiri?
Jangan menulis demi sensasi. Perhatikan rambu-rambunya. Jangan sebut metode, atau menjabarkan identitas pelaku bunuh diri dengan detail. Pikirkan keluarganya.
Penulis: Aulia Adam
Editor: Fahri Salam