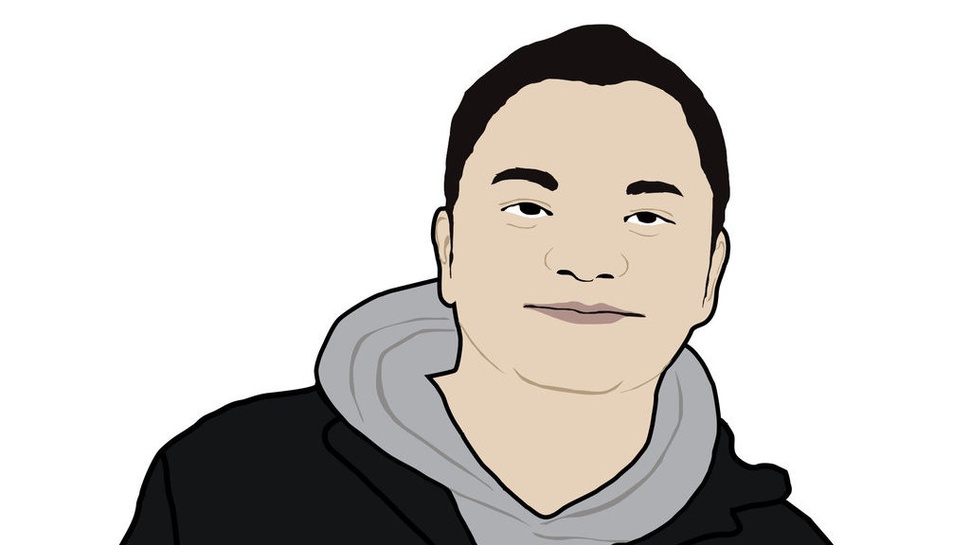tirto.id - Hari ini warga Depok kian akrab dengan kemacetan. Ia adalah kawan seiring terutama di pagi dan sore hari. Kala hujan datang, kawan kita itu makin menjadi-jadi. Bahkan di akhir pekan saat warga ingin melepas penat, urat syaraf mereka konsisten diuji. Warga dipaksa menerima adagium sederhana: kemacetan adalah rutinitas yang tak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat perkotaan.
Kemacetan Depok
Data dari Dinas Perhubungan Kota Depok mengakui beberapa ruas jalan terutama koridor Utara-Selatan seperti Jl. Limo-Cinere, Jl.Margonda Raya dan Jl. Raya Bogor (arus dari dan ke Jakarta) telah mencapai derajat kejenuhan di atas 0,8. Menurut Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI), angka ini menunjukkan ruas-ruas jalan tersebut tergolong jenuh dan terjadi kemacetan.
Sementara koridor penghubung Barat-Timur nasibnya tak jauh berbeda. Warga yang rutin melintasi Jl. Siliwangi, Jl. Pitara Raya, Jl.Raya Sawangan dan Jl. Muchtar Raya harus banyak bersabar setiap hari.
Wali Kota Depok, Idris Abdul Shomad, mengatakan tingginya pertumbuhan angka populasi penduduk dan kendaraan bermotor menjadi akar penyebab kemacetan. Penduduk kota Depok bertambah sekitar 4,7% per tahun atau sekitar tiga kali lipat laju pertumbuhan penduduk nasional.
Pada 2010, jumlah penduduk mencapai 1,7 juta orang, angkanya naik menjadi 2,3 juta orang pada 2017. Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, belum lama mengungkapkan dengan tren pertumbuhan saat ini, Depok akan menjadi kota terpadat kedua di Indonesia pada 2045.
Setidaknya sejak 1960-an, Depok memang didesain sebagai wilayah penyangga yang menerima beban sosial ekonomi dari pusat pertumbuhan yaitu DKI Jakarta. Depok menjadi dormitory town atau kota permukiman yang menampung para pekerja yang tak mampu membeli hunian di ibu kota.
Bertambahnya penduduk berimplikasi pada bertambahnya jumlah kendaraan. Pada 2011, ada sekitar 510 ribu kendaraan di Depok. Angka ini melonjak menjadi 979.868 kendaraan pada tahun 2014 di mana 83 persennya adalah sepeda motor dan sisanya kendaraan roda empat.
Tingginya kenaikan jumlah kendaraan (33% untuk sepeda motor dan 9% untuk mobil per tahun) tidak diimbangi oleh tingkat pertumbuhan jalan yang hanya mencapai 0,7% per tahun.
Lalu apa solusinya? Wali Kota Depok punya jurus ampuh mengatasi kemacetan: bangun lebih banyak jalan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Depok 2016-2021 menegaskan tantangan Depok adalah memaksimalkan pembangunan jalan mengikuti pertumbuhan jumlah kendaraan dan luas wilayah. Pada 2010, Depok seharusnya sudah membangun 1.861 Km jalan kota. Tahun 2015, ternyata baru 476,15 Km yang terbangun.
Bahkan, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2012-2032 kota Depok merencanakan pembangunan jalan tol Depok Outer Ring Road (DORR) dengan alokasi dana APBD. DORR akan menghubungkan Jl. Raya Parung dengan Jl. Raya Bogor melalui koridor selatan dan Jl. Juanda dengan Jl. Cinere Raya di utara. DORR juga akan terhubung dengan jalan tol Depok-Antasari.
Untuk melengkapi strategi Wali Kota, pemerintah juga akan membangun empat koridor jalan tembus (Terminal Jatijajar-Tapos Raya, Juanda-Limo Raya, Jl. Raya Bogor-Parung, Krukut Raya-Petir Raya), sebuah underpass di Jl. Raya Citayam, sebuah flyover Jl. Dewi Sartika - Jl. Raya Sawangan dan sebuah terusan jalan Kota Kembang- Sawangan.
Tapi tahukah anda beberapa penelitian secara empiris telah membuktikan pembangunan lebih banyak jalan tidak mengurangi kemacetan?
Anda pikir setelah membangun underpass dan flyover, kemacetan akan berkurang di Jl. Raya Citayam dan Jl. Raya Sawangan? Atau dengan membangun jalan tol, maka jalan kolektor primer seperti Jl. Margonda berubah lancar jaya?
Tahun 1968, ahli matematika Jerman, Dietrich Braess, membuktikan penambahan kapasitas di jaringan jalan yang padat bisa menambah waktu tempuh semua pengendara yang pada akhirnya menambah kemacetan. Hal ini terjadi karena mayoritas pengendara akan mengambil jalur tercepat tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi pengendara lain. Logika sebaliknya juga berlaku, dalam beberapa kasus seperti di Stuttgart, New York dan Seoul; penutupan jalan justru mengurangi kemacetan. Fenomena ini dikenal sebagai Braess’ Paradox.
Tahun 2009, dua ekonom dari University of Toronto, Gilles Duranton dan Matthew Turner mencetuskan the fundamental law of road congestion: perubahan panjang sebuah jalan akan menimbulkan perubahan yang proporsional terhadap kepadatan lalu lintas. Hasil penelitian mereka di Amerika Serikat menunjukkan pembangunan jalan tol baru sepanjang 10 km meningkatkan 10% jumlah total kilometer yang ditempuh oleh para pengendara mobil. Artinya jalan baru sebenarnya menciptakan kemacetan baru.
Di Inggris, studi yang dirilis CPRE menemukan angka kemacetan justru naik 7% dalam jangka waktu 3-7 tahun dan 47% selama 20 tahun terakhir di 13 ruas jalan baru yang dibangun pemerintah.
Jika data di atas dianggap kurang, Wali Kota bisa menengok Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) yang dirilis oleh Kementerian Perhubungan. RITJ secara gamblang menyebutkan pengembangan jalan baru di perkotaan malah menyebabkan pembelian lebih banyak kendaraan pribadi yang menciptakan car-dependent society.
Sudah tak efektif, pembangunan jalan mahal pula. Pemerintah kota Depok pernah merencanakan pembangunan flyover Markaswangi dengan total biaya Rp2 triliun. Kedodoran, akhirnya pemerintah memilih Detail Engineering Design (DED) yang lebih murah dengan penekanan pada underpass menuju Jl. Dewi Sartika. Itupun masih menelan biaya hampir Rp1,1 triliun. Pertanyaannya, kalau tidak efektif, buat apa triliunan anggaran kota dihabiskan untuk itu?
Inkompetensi Pemerintah atau Tekanan Industri Properti?
Mengapa dengan banyaknya bukti empiris, pemerintah kota Depok malah mengambil kebijakan yang salah? Ibaratnya, mengapa Wali Kota minum air es padahal ingin menyembuhkan radang tenggorokan?
Pertama, sejumlah ahli kebijakan publik telah lama menyebutkan pemerintah atau pengambil kebijakan seringkali mengabaikan prinsip evidence-based policymaking atau kebijakan berbasis bukti. Mereka lupa mempertimbangkan skema input-activity-output-outcome dalam mendesain sebuah kebijakan. Sebelum memutuskan, Wali Kota harusnya bertanya: “dengan menambah jalan sekian kilometer (input), berapa banyak penurunan derajat kejenuhan ruas jalan yang dicapai (outcome)?”
Tanpa ini, pemerintah pasti salah langkah.
Kemungkinan kedua adalah regulatory capture yaitu situasi di mana pemerintah sengaja mengambil kebijakan sesuai permintaan atau tekanan dari pemain-pemain industri tertentu.
Firman dan Fahmi (2017) dalam jurnal berjudul The Privatization of Metropolitan Jakarta’s (Jabodetabek) Urban Fringes: The Early Stages of “Post-Suburbanization” in Indonesia, menyebutkan pengembang swasta biasa bernegosiasi dengan pemerintah lokal untuk mengatur isi dari perencanaan spasial kota agar rencana bisnis mereka terakomodasi.
Dalam konteks Depok, DORR bisa jadi dibangun untuk memfasilitasi pembangunan perumahan-perumahan baru di selatan kota oleh para pengembang besar. Salah satu modus yang kerap terjadi adalah pengembang jauh-jauh hari telah mengakuisisi lahan di sekitar jalan tol yang akan dibangun sehingga mereka bisa menikmati keuntungan dari kenaikan harga tanah.
Yang perlu diingat, tujuan akhir dari para perusahaan pengembang swasta adalah laba dan bukan menciptakan kota yang bebas dari kemacetan.
Reformasi Angkutan Massal dan TOD
Apapun alasannya, kebijakan Wali Kota Depok terkait kemacetan hari ini merugikan warga dalam jangka panjang. Triliunan dana APBD dialokasikan untuk membangun jalan tanpa dampak yang jelas. Oleh karena itu, paradigma sekedar bangun jalan harus segera diubah.
RPJMD sebenarnya telah memuat keinginan pemerintah Depok untuk mengedepankan prinsip Transit Oriented Development (TOD) yaitu mengurangi mobilitas penduduk dengan mendekatkan dan mengintegrasikan sistem transportasi kota, permukiman, sentra bisnis dan pusat kegiatan masyarakat lainnya sehingga tercipta kota yang efisien.
Namun, itu baru sekadar jargon. RPJMD tidak memuat rencana detil tentang apa langkah-langkah yang akan diambil agar TOD terealisasi.
Untuk mewujudkan TOD, pemerintah sederhananya harus mengistimewakan tiga pihak: pengguna kendaraan umum, pejalan kaki dan pesepeda. Di saat yang sama pemerintah harus “mempersulit” pengguna mobil dan sepeda motor.
Buruknya pelayanan angkot di Depok berkontribusi pada rendahnya modal share angkutan umum yaitu sekitar 21% dari total permintaan perjalanan (travel demand). Poin ini harusnya menjadi perhatian Wali Kota.
Akar masalah pelayanan angkot di Depok adalah skema persaingan pasar bebas. Saat ini ada sekitar 2.884 angkot di Depok yang dimiliki oleh puluhan individu dan badan hukum. Mereka beroperasi murni untuk laba dan seringkali abai untuk menegakkan standar pelayanan minimum angkutan massal.
Laba adalah raja. Mengapa supir angkot ngetem? Sederhana, mereka mencari penumpang. Sama halnya dengan supir yang berkendara ugal-ugalan. Mereka tidak mau disalip oleh supir lain karena ada potensi kehilangan penumpang yang sedang menunggu di depan. Masalah yang tak kalah pelik adalah penumpang diturunkan sebelum sampai tujuan karena supir melihat ada potensi lebih banyak penumpang di arus sebaliknya.
Agresivitas pencarian laba juga menimbulkan masalah-masalah yang lebih serius. Keengganan pemilik angkot untuk menyeleksi supir berdasarkan rekam jejak dan profesionalitas, dan lebih mementingkan upah murah, menimbulkan persoalan seperti pelecehan seksual, pemerasan hingga supir merokok di dalam angkot.
Reformasi angkutan massal bisa dimulai dengan menggabungkan seluruh pemilik angkot dalam satu perusahaan yang sama. Hal ini akan mengubah skema persaingan bebas menjadi monopoli terkendali.
Wali Kota bisa mengajak para pengusaha angkot untuk membentuk BUMD seperti PT. Transjakarta. Prioritas utama perusahaan adalah memastikan performa angkot yang memenuhi standar pelayanan minimum.
Dalam jangka panjang, BUMD tersebut bisa mendesain moda transportasi selain angkot seperti trem atau kereta gantung yang semuanya terintegrasi dengan KRL dan LRT. Soal business feasibility, BUMD bisa memanfaatkan sektor bisnis lain seperti periklanan di halte-halte yang dibangun dan ruang interior angkot.
Kedua, pemerintah juga harus mulai membenahi trotoar yang semakin tidak beradab, membangun akses penyebrang jalan yang modern serta jalur khusus pesepeda.
Ketiga, apakah karena TOD lalu jalan baru tidak diperlukan sama sekali? Beberapa ruas jalan baru harus tetap dibangun namun diperuntukkan secara eksklusif bagi kelancaran kendaraan umum, pesepeda dan pejalan kaki.
Agar ketiga langkah ini lebih mudah dilakukan, pemerintah harus secara bertahap menaikkan pajak dan tarif parkir kendaraan pribadi. Kelebihan PAD itu lalu digunakan untuk membiayai ketiga langkah di atas (termasuk subsidi silang bagi BUMD).
Jika Wali Kota Depok memang mampu menyediakan ruang fiskal Rp1- 2 triliun dalam skema tahun jamak (multiyears), lebih baik Ia membatalkan rencana pembangunan DORR atau jalan-jalan baru untuk memuaskan keserakahan kendaraan pribadi. Anggaran tersebut bisa digunakan untuk mereformasi angkutan massal dan mewujudkan TOD.
Jika tidak, maka sampai kiamat Depok akan tetap macet.
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.