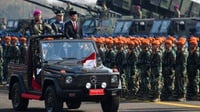tirto.id - Tanggal 21 Mei 1998 adalah momen yang tidak akan pernah dilupakan rakyat Indonesia. Dalam upacara kecil di Istana Merdeka yang dipersiapkan ala kadarnya, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran diri dan melimpahkan wewenangnya kepada Wakil Presiden B.J. Habibie. Rezim kediktatoran Orde Baru, yang selama 32 tampak kokoh, seketika runtuh hanya dalam enam bulan sejak krisis ekonomi menghantam Asia pada pertengahan 1997.
Kini Orde Baru tinggal nama. Bagi sebagian masyarakat, nama ini membangkitkan kenangan buruk lantaran dianggap berlawanan dengan kebebasan berpolitik yang sekarang dinikmati banyak orang. Tapi salah satu hal yang paling menonjol dari Orde Baru adalah rezim itu pernah mencapai "keajaiban" ekonomi.
Dalam tulisan yang terbit di Transitions to Democracy: A Comparative Perspective (2013: 147), dua peneliti dari Australian National University, Edward Aspinall dan Marcus Mietzner, berpendapat kebaikan Orde Baru terdapat pada pencapaian di bidang pertumbuhan ekonomi. Pendapatan per kapita Indonesia tumbuh dari hanya 70 dolar di tahun 1969 menjadi 1.100 dolar pada 1997. Hasil yang memuaskan itu didukung pula oleh ledakan harga minyak dunia yang terjadi antara 1973 hingga 1983.
Pertumbuhan ekonomi Orde Baru yang sedemikian signifikan dapat terjadi berkat program-program ekonominya yang teratur kendati diwarnai perilaku-perilaku koruptif yang menggerogoti institusi pemerintahan. Di masa itu pula kata 'pembangunan' berlaku seperti mantra dan bisa membuldoser siapa saja yang dianggap menghalanginya. Ideologi orde ini seperti bukan Pancasila atau apapun. Ideologi Orde Baru adalah pembangunanisme.
Setelah berhasil mendepak Sukarno secara penuh dari kursi kepresidenan, Soeharto mulai merancang program pembangunan ekonomi yang dinamai Rencana Pembangunan Lima Tahun atau Repelita. Pembangunan terpusat yang kemudian menjadi tradisi ekonomi Orba selama lebih dari tiga dasawarsa ini mulai dilaksanakan pada 1 April 1969, tepat hari ini 51 tahun silam.
Pembangunan Sentralistik
Repelita dirintis di bawah arahan Widjojo Nitisastro, saat artsitek utama ekonomi Orde Baru itu tengah memimpin Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di tahun 1967. Selama kurang lebih satu tahun, pokok-pokok pikiran Repelita terus disempurnakan oleh Widjojo melalui berbagai pertemuan dan sidang. Dia berpendapat proses pembangunan memerlukan waktu yang lama sehingga setiap tahapnya memerlukan perencanaan yang saksama.
“Karena itu, Repelita yang pertama harus dilihat sebagai permulaan sebagai serangkaian pembangunan lima tahun,” tulis Widjojo dalam kumpulan tulisan Pengalaman Pembangunan Indonesia (2010: 166). “[...] rencana lima tahun tersebut masing-masing harus memberikan tekanan kepada bidang-bidang yang berlainan, sesuai dengan tingkat perkembangan ekonomi.”
Dalam Repelita I penekanan pemerintah berada pada bidang pertanian dan pembangunan infrastruktur. Langkah ini dinilai berhasil mengangkat tingkat kemakmuran masyarakat desa. Menurut rincian yang disarikan dalam Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir, 1966-1982 (2005: 387), hasil fisik yang dicapai selama Repelita I meliputi perbaikan 1.600 kilometer jalan dan tidak kurang dari 380 ribu hektare rehabilitasi sawah. Pencapaian ini mampu mengurangi angka pengangguran hingga lebih dari 1,4 juta orang setiap tahun.
Menurut perhitungan Widjojo, peningkatan produksi di bidang pertanian-pangan mampu memberikan pengaruh besar pada langkah pertama Repelita. Melaluinya, harga pangan dalam negeri bisa distabilkan sehingga memberikan pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi di masa mendatang.
“Produksi Indonesia sebagian besar adalah produksi pertanian, sehingga meningkatnya sektor tersebut memberikan sumbangan besar terhadap peningkatan produksi nasional,” tulisnya.
Secara garis besar, Repelita I disusun menggunakan pendekatan realistis dan pragmatis. Sebagaimana diuraikan dalam lampiran Surat Keputusan Presiden No. 319 Tahun 1968 tentang Repelita I bahwa sasaran pembangunan yang hendak dicapai meliputi “pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakjat, perluasaan lapangan pekerdjaan dan kesedjahteraan rochani.”
Selama lima tahun program-program Repelita I berjalan, sasaran pembangunan paling besar adalah wilayah perdesaan. Selain membangun jalan, waduk, saluran irigasi, dan rehabilitasi sawah, pemerintahan Soeharto memberikan dana bantuan pembangunan sebesar Rp100 ribu tiap desa. Agar pelaksanaan pembangunan berjalan seperti yang diharapkan, para pejabat desa diwajibkan mengikuti program pengawasan dan pelaporan proyek.
Menurut Mudrajad Kuncoro, Guru Besar Ilmu Ekonomi FEB UGM, dalam kolomnya di majalah Gatra (17/3/2012), Repelita I menerapkan sistem perencanaan terpusat atau top-down. Berkat implementasinya yang bersifat sentralistik, pembanguan di daerah, khususnya di wilayah perdesaan, menjadi lebih menonjol. Berbagai program bangun desa dapat berjalan cepat karena pejabat daerah hanya tinggal menyalin rancangan yang sudah disediakan pemerintah pusat.
“Pendekatan sektoral amat kuat lewat mekanisme dekonsentrasi. Akibatnya, pemda tak lebih hanya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat,” tulisnya.

Mengandalkan Bantuan Asing
Demi menjalankan ambisi pembangunan ekonomi, Orde Baru banyak mengandalkan uluran tangan negara-negara Barat. Dalam konteks Perang Dingin, negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat, berusaha mencegah kebangkitan ideologi komunis melalui sejumlah bantuan. Di mata AS, Soeharto adalah orang yang berhasil membendung komunisme di Indonesia.
Ketika Soeharto naik ke puncak kekuasaan pada 1967, sebuah kelompok negara-negara donor bernama International Govermental Group on Indonesia (IGGI) dibentuk untuk membantu stabilisasi ekonomi Indonesia lewat utang luar negeri. Jejak-jejak hiperinflasi dan tumpukan utang luar negeri warisan pemerintahan Sukarno yang menembus 2,3 miliar dolar di tahun 1966 dapat diatasi hanya dalam waktu kurang dari tiga tahun.
“Kebidjaksanaan-kebidjaksanaan jang dilaksanakan bersama-sama dengan perbaikan kondisi fiskal serta pemasukan bantuan-bantuan luar negeri jang baru, telah mempunjai efek jang positif didalam tahun 1967 jaitu antara lain berupa tingkatan inflasi jang menurun dengan tjepat,” demikian dicatat dalam lampiran Surat Keputusan Presiden tahun 1968.
IGGI beranggotakan negara-negara Eropa barat, Amerika Serikat, Jepang, Bank Dunia, Dana Moneter Internasional, Asian Development Bank, dan didukung Program Pembangunan PBB. Seperti diuraikan Robert Cribb dan Audrey Kahin dalam Historical Dictionary of Indonesia (2004: 192), IGGI memiliki tugas pokok mengoordinasikan aliran besar bantuan dan aliran modal asing di Indonesia. Berawal dari bantuan yang menekankan stabilitas ekonomi, lambat laun aliran dana juga menyentuh bidang pembangunan.
“Pada tahun-tahun pertama Orde Baru, IGGI memiliki pengaruh besar dalam kebijakan ekonomi Indonesia, dengan menekankan pada perbaikan infrastruktur, stabilisasi mata uang, menjamin investasi asing, dan membatasi perannya dalam masalah ekonomi,” catat Cribb dan Kahin.
Menurut Cribb dan Kahin, IGGI adalah penyumbang terbesar dalam pembiayaan anggaran pembangunan negara. Sekitar 60 persen dana Repelita I yang digelontorkan pemerintah Orde Baru untuk membiayai program pembangunan berasal dari atas meja forum-forum diskusi yang diadakan IGGI. Satu tahun sebelum Repelita I secara resmi dimulai, Amerika Serikat dan Jepang bahkan sudah lebih dulu mengulurkan dana sebesar 163 juta dolar dan 110 juta dolar dalam bentuk pinjaman.
Di bidang pertanian dan irigasi, Orde Baru pernah menerima tidak kurang dari 1 miliar dolar dari International Development Association (IDA) yang merupakan bagian dari Bank Dunia. Seperti dicatat Diana Suhardiman dalam Bureaucracy and Development: Reflections from the Indonesian Water Sector (2014: 50), dana ini diberikan secara bertahap setelah Repelita I dilaksanakan pada 1969 dan berakhir pada 1989.
Soeharto dan para teknokrat ekonominya menyadari bahwa Indonesia masih berada dalam tahap berkembang dan tidak memiliki sektor ekonomi yang menonjol selain pertanian. Demi memaksimalkan potensi di bidang ini, pemerintah merasa perlu menerima kredit luar negeri dan investasi asing yang diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal Asing tahun 1967.
Kelak, ketika krisis moneter mendera Indonesia pada akhir 1997, fondasi ekonomi Indonesia yang mengandalkan utang luar negeri dan modal asing ternyata sangat rapuh. Inilah yang menjadi pintu masuk kejatuhan Soeharto.
Editor: Ivan Aulia Ahsan