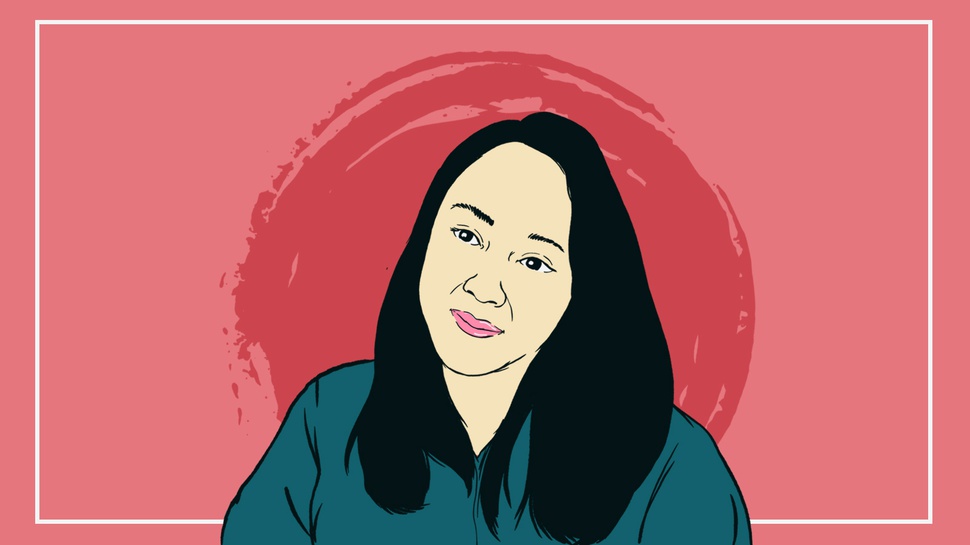tirto.id - Sejumlah penelitian dalam ranah kecantikan menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun ke depan, praktik peremajaan vagina atau rejuvenasi akan semakin diminati. Praktik tersebut diantaranya bertujuan agar vagina lebih kencang dan rapat. Prosedurnya bisa dilakukan melalui tindakan bedah maupun non-bedah.
Dunia medis meyakini bahwa peremajaan vagina didasari alasan kesehatan dan estetika. Namun, perspektif ilmu sosial mengungkap ada faktor lain yang memotivasi seseorang melakukan peremajaan vagina.
Tirto berbincang dengan Angela Frenzia, penulis Demi Keset dan Rapet dan aktivis gender untuk mengetahui sudut pandang lain terkait prosedur estetika seharga puluhan juta rupiah ini.
Melihat tren peremajaan vagina beberapa tahun belakangan, menurut kamu, apakah ini tanda bahwa awareness perempuan terhadap tubuhnya meningkat ataukah sebaliknya, perempuan semakin tidak percaya diri dengan tubuhnya?
Menjawab pertanyaan ini aku perlu sedikit menjabarkan bagaimana perkembangan peremajaan vagina itu sendiri di Indonesia. Sebenarnya peremajaan vagina bukan fenomena yang baru terjadi beberapa tahun belakangan. Praktik ini sudah dilakukan oleh perempuan-perempuan kerajaan Hindu Nusantara menggunakan rempah-rempah yang diolah menjadi ratus dan jamu. Tapi memang menjadi terkenal itu sejak mulai bermunculan produsen jamu-jamu “kewanitaan”. Bahkan nama-nama yang diberikan untuk jamu khusus perempuan ini membangun narasi bahwa vagina itu seharusnya keset, rapet, dan wangi. Beberapa contohnya itu Sari Rapat, Rapat Wangi, Asri Rapat, dan yang paling aneh menurutku itu Empot-Empot Ayam.
Perhatikan iklan jadul jamu khusus perempuan, tagline-nya selalu seputaran “Biar suami makin betah di rumah”, “Biar disayang suami”, dan sejenisnya. Dari situ saja kita bisa bertanya: mengapa kok sebegitu pentingnya perempuan punya vagina keset dan rapet? Mengapa kok perempuan jadi terobsesi meremajakan vaginanya sampai sebegitunya?
Dalam perjalanan penelitianku, aku menemukan bahwa perempuan jadi terobsesi memiliki vagina yang keset dan rapet itu nggak muncul tiba-tiba, melainkan perempuan dibentuk, dibiasakan, dan diarahkan untuk concern dengan vaginanya. Namun, bukan untuk kepentingan dirinya, melainkan untuk orang di luar dirinya. Bagiku ini sebenarnya sudah bentuk kontrol terhadap tubuh perempuan, bahkan bagian privat loh, vagina. Nah, apa atau siapa yang mengontrol dan polanya bagaimana sih sampai perempuan itu sendiri percaya bahwa vagina perempuan memang seharusnya keset dan rapet? Tak lain dan tak bukan ya budaya patriarkal yang membentuk perempuan menjadi aware terhadap tubuhnya tapi sebagai objek pemuasan ego orang lain.
Dengan kata lain, perempuan tidak sadar bahwa tubuhnya disusupi, dijajah oleh wacana patriarkal meski dia tersiksa.
Nah, dalam peremajaan vagina tradisional ini kalau kita sadari adalah salah satu bentuknya. Remaja perempuan kerap diarahkan oleh ibu atau nenek mereka untuk rajin merawat keremajaan vagina dengan minum jamu, agar vagina keset dan rapat. Mengapa? Karena masih banyak yang percaya mitos vagina keset dan rapat bisa meningkatkan kenikmatan pasangan saat penetrasi. Kalau pasangan puas di ranjang, rumah tangga akan awet dan jaminan disayang suami. Bayangkan! Seolah-olah perempuan itu punya nilai, keberhargaan, dianggap berhasil kalau punya vagina keset dan rapet.
Itu temuan-temuan kritis dalam peremajaan vagina tradisional. Peremajaan vagina ini ternyata kan berkembang pesat sekali seiring dengan modernisasi. Teknologi kedokteran berkembang memunculkan bentuk peremajaan vagina menggunakan teknologi laser, radio frekuensi, hingga operasi bedah kemudian dinamai vaginal rejuvenation atau rejuvenasi vagina kalau dialihbahasakan Indonesia.
Ketika membaca artikel-artikel, lalu jurnal-jurnal, aku menemukan alasannya beragam, dari alasan kesehatan, ada yang tidak percaya diri dengan bentuk labianya, ada yang tidak percaya diri dalam relasi seksual, dan lainya. Bahkan ya, seperti yang aku jelaskan di bukuku, aku memulai penelitian mengenai rejuvenasi vagina ini ketika menemui kenyataan bahwa ada seorang korban kekerasan seksual yang ingin melakukan salah satu jenis rejuvenasi vagina karena ingin kembali “perawan” agar dapat diterima oleh suaminya kelak.
Dari temuan-temuan itu, aku memiliki hipotesis sebagaimana peremajaan vagina tradisional, perempuan melakukan rejuvenasi vagina modern juga karena mereka dibuat tidak percaya dengan dirinya dan tubuhnya sendiri oleh wacana patriarkal. Patriarkal ini licik. Bayangkan dari era ke era, tiap budaya patriarkal ini mampu beradaptasi. Bentuknya berbeda tapi semangatnya itu sama “menguasai”, “mengontrol”. Jadi aku pada akhirnya punya kecurigaan yang besar kalau rejuvenasi vagina modern ini adalah salah satu bentuk tubuh perempuan (dalam hal ini: vagina) dikontrol untuk kepentingan orang di luar perempuan.
Selama ini narasi yang beredar terkait peremajaan vagina diantaranya: praktik ini dilakukan atas alasan estetika dan/atau kesehatan. Menurut kamu, apa dimensi yang luput dilihat perihal peremajaan vagina?
Itulah mengapa, sebenarnya kita perlu melihat rejuvenasi vagina bukan sekadar fenomena gaya hidup atau sebagai praktik kedokteran saja. Ini lebih dari itu. Rejuvenasi vagina ini sebuah praktik budaya di mana ada wacana yang bekerja. Artinya ya perlu lebih kritis juga agar melihat praktik rejuvenasi vagina ini agar tidak mudah percaya dengan satu wacana saja ketika, misalnya ada klaim bahwa rejuvenasi vagina ini penting untuk kesehatan seksualitas perempuan.
Ketika kita melihat rejuvenasi vagina ini sekadar gaya hidup, kesimpulan yang kita dapat cenderung akan memperkuat stereotyping gender. Bahwa perempuan itu yang dipikirkan hanya bagaimana memperindah tubuhnya, wajahnya, bahkan vaginanya. Alhasil kita kembali mengajeqkan posisi perempuan dan tubuhnya sebagai objek. Namun ketika melihat ini sebagai praktik budaya, kita akan memperluas perspektif kita, kemudian akan muncul pertanyaan-pertanyaan kritis, seperti: Benarkah narsistik pada perempuan itu terberi ataukah sebenarnya dibentuk?
Bisikan-bisikan wacana apa yang mendominasi seseorang hingga merasa penting melakukan rejuvenasi vagina meski tidak memiliki gangguan kesehatan? Adakah pola penyalahgunaan kekuasaan dalam relasi: baik itu relasi antara subjek dengan dokter atau dengan pasangannya? Siapa yang sebenar-benarnya diuntungkan dengan adanya praktik rejuvenasi vagina ini? Dan pertanyaan-pertanyaan kritis lainnya.
Hal penting namun seringkali luput dari perhatian kita ketika membicarakan tentang rejuvenasi vagina adalah: Subjektivitas perempuan (yang melakukan rejuvenasi vagina) itu sendiri. Dalam banyak artikel, kita akan mendapati testimoni mengenai rejuvenasi vagina dari sudut pandang ahli medis atau psikolog. Kehadiran mereka yang melakukan rejuvenasi vagina diwakilkan oleh data kuantitatif berupa angka atau diwakilkan oleh ahli medis yang menangani tindakan itu sendiri. Jika ada, pertanyaan juga sekadar seputar motif dan bagimana perbedaan sebelum dan sesudah melakukan rejuvenasi vagina, that’s it. Jadi perempuan itu dihadirkan bukan sebagai subjek tapi sebagai angka dan pelengkap data yang menunjang klaim medis.
Apa yang kamu pikir waktu pertama kali dengar kata peremajaan vagina?
Pertama kali mendengar rejuvenasi vagina yang terbayang dalam otakku itu: “Serupa plastic surgery tapi ini untuk vagina.” Otakku langsung menghubungkan itu dengan patriarki. “Gila ya patriarki, tubuh perempuan nggak ada yang luput diatur. Sampai vagina aja harus sesuai standar ideal kecantikan. Gilaaa!”
Berdasar studi yang sudah kamu buat, sebetulnya hal-hal apa saja yang jadi motivasi seseorang mau melakukan praktik peremajaan vagina?
Dari penuturan para perempuan yang melakukan rejuvenasi vagina, mereka ingin vagina mereka kembali “ideal”. Tapi kemudian, saya tertarik mengetahui lebih jauh konsep ideal para perempuan ini seperti apa, bagaimana prosesnya hingga konsep “ideal” itu memengaruhi keputusan mereka?
Setelah saya analisis ternyata tidak sedangkal mengubah vagina kembali “rapet”. Ada proses panjang pada tiap individu yang melakukan rejuvenasi vagina ini. Salah seorang narasumber penelitianku (sebut saja D) mengatakan bahwa dirinya melakukan itu karena faktor kesehatan. Akan tetapi setelah didalami, ditemukan bahwa dia masih terbelenggu sama wacana patriarkal, mengenai bentuk tubuh yang ideal. Konsep idealnya itu merujuk pada perspektif patriakal, begitu. Narasumber lain berinisial (W), menjelaskan bahwa dia kesulitan orgasme saat melakukan hubungan seksual. D adalah perempuan yang memahami soal otoritas tubuh, namun ternyata D tidak memiliki pengetahuan soal kesehatan reproduksi dan seksualitas yang cair, melainkan masih dalam spektrum heteronormatif. Seorang narasumber lain berinisial A menjelaskan bahwa dirinya melakukan rejuvenasi vagina karena itu adalah bentuk self love, setelah dia memprioritaskan tugas tubuhnya sebagai tubuh maternal (hamil, melahirkan, menyusui) dia kemudian hendak meraih kepentingan seksualitasnya. A sangat memahami tubuh dan seksualitasnya, bahkan D juga mengedukasi perempuan-perempuan yang hendak melakukan rejuvenasi vagina karena sudah tidak perawan dan takut diketahui oleh calon pasangan.
Akan tetapi, seperti yang aku jelaskan di awal, kita ini memang mungkin tampak merdeka pada lapisan tertentu, tapi begitu masuk ke lapisan lainnya, kita ternyata kembali terjajah oleh patriakal tanpa kita sadari. Ini dialami oleh hampir semua perempuan aku rasa ya. Dalam kasus A, ketika melakukan konsultasi, ditemukan subordinasi yang dilakukan oleh dokter. Dokter mengkategorikan bentuk vagina A sebagai vagina yang tidak “ideal”. Semacam gashlitghing sih, jadi kita dibuat percaya bahwa memang ada yang salah pada bentuk tubuh kita.
Menurut kamu, apakah motivasi dari orang yang melakukan praktik peremajaan vagina mungkin murni bebas dari narasi patriarkal?
Memang untuk melihat posisi perempuan dalam rejuvenasi vagina ini apakah sebagai objek atau subjek adalah dengan menelaah motivasinya. Apa sebenarnya yang menggerakkan perempuan tersebut. Apakah perempuan yang melakukan rejuvenasi vagina memiliki kesadaran akan wacana-wacana patriarki yang mengkonstruksi, mengontrol, dan membelenggu mereka? Kuncinya adalah kesadaran akan ketimpangan gender yang merugikan perempuan, sehingga perempuan memahami pola kerja patriarkal dan harapannya bisa menjadi agen perlawananan. Ya, memang mungkin tidak secara langsung membebaskan diri dari wacana-wacana itu, tapi paling tidak atas kesadaran tersebut, perempuan menjadi kritis menyikapi fenomena sosial salah satunya soal rejuvenasi vagina.
Jadi jika ditanya mungkin nggak ada perempuan yang melakukan rejuvenasi vagina itu tanpa teropresi wacana patriarkal? Mungkin saja, kalau dia memiliki kesadaran seperti yang kujelaskan tadi. Dalam penelitianku, para narasumber sudah dalam upaya memahami bahwa wacana tubuh dan seksualitas yang ada sampai sekarang itu tidak menguntungkan untuk perempuan dan mereka hendak meraih kembali hak seksualitas itu. Namun, ternyata pada lapisan tertentu, tanpa disadari mereka masih teropresi dengan wacana patriarkal. Ya, mungkin memang kesulitannya adalah karena itu sudah berabad-abad dan menjadi ideologi kan, diwariskan turun-temurun pula. Jadi kayak, udah membaur dengan ciamik gitu, adaptasinya bagus banget. Jadi bahkan kita tidak sadar bahwa kita ternyata masih kebawa pemikiran patriakal. Jadi ya, perjuangannya berat memang membumihanguskan itu.
Sepengamatanmu, bagaimana sih pola konstruksi sosial soal tubuh khususnya alat kelamin perempuan dan juga perihal keperawanan di Indonesia?
Masyarakat Indonesia juga meyakini konstruksi gender itu berdasarkan biologis dan batasannya sangat biner antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki kemudian dikaitkan dengan maskulinitas (kuat, superior, pemikir, dan lain lain) dan perempuan dikaitkan dengan femininitas (lemah, inferior, perasa, dan lain-lain). Ternyata ini pengaruhnya nggak cuma pada urusan ranjang. Berawal dari hal itu, bahkan sampai peran perempuan dan laki-laki saja jadi dibedakan yang mana cenderung merugikan posisi perempuan.
Dalam hal seksualitas (luas bukan sekadar urusan penetrasi), memang wacana-wacana patriarki ini kontribusinya besar sekali membangun konstruksi yang timpang gender. Patriarki mendefinisikan perempuan berdasarkan apa yang mereka inginkan untuk kepentingan status quo hingga untuk ego dan kepuasan mereka. Alhasil, kehadiran perempuan dan seksualitasnya itu untuk mendahulukan kepentingan laki-laki. Kepentingan seksualitasnya sendiri pada akhirnya dibatasi. Makanya, sering kita temui perempuan itu tidak semerdeka itu untuk mengeksplorasi seksualitasnya, karena ya dikonstruksikan untuk menekan seksualitasnya, padahal perempuan itu juga subjek seksual. Sebaliknya kalau ada perempuan yang sangat ekspresif pasti distigma ini dan itu: perempuan agresif, perempuan nggak bener, perempuan gatel, perempuan BO, dan banyak lainnya.
Ada program KB di era Orde Baru. Narasinya perempuan seolah memiliki peran penting dalam bermasyarakat dan bernegara kalau ikut menyukseskan program KB. Tapi yang dibebankan tanggung jawab penuh ya perempuan. Selain jadi pelaksana, perempuan juga yang wajib menggunakan alat-alat kontrasepsi seperti pil, IUD (spiral), dan sterilisasi.
Kalau KB yang dikontrol itu hak reproduksi perempuan. Ada lagi mitos keperawanan, yang dikontrol seksualitas perempuan melalui vaginanya. Ini heteronormatif memang, karena kan konteksnya dalam relasi perkawinan di Indonesia yang heteroseksual. Jadi keperawanan perempuan ditekankan sebagai nilai diri di hadapan suaminya. Kehilangan keperawanan dianggap perempuan itu tidak dapat menjaga dirinya, tubuhnya, seksualitasnya untuk suaminya.
Itulah mengapa di Indonesia urusan pembuktian keperawanan bagi perempuan yang belum menikah, itu menjadi tradisi di beberapa daerah bahkan sempat dilakukan juga oleh instansi tertentu. Jadi tes keperawanan menjadi salah satu syarat penerimaan/ kelulusan.
Kesemuanya itu jika diperhatikan, perempuanlah yang ditimpakan tanggung jawab mengontrol perilaku seksualnya, jika tidak ingin dipermalukan. Laki-laki menjadi tidak tersentuh, tidak menjadi momok bagi mereka. Mereka sangat leluasa mengeksplorasi kenikmatan seksual, misalnya masturbasi (onani) tanpa harus dibayangi ketakutan akan kehilangan keperawanan dan distigma lelaki BO atau lelaki murahan.
Lalu bagaimana perempuan-perempuan bisa menyadari dan kemudian terbebas dari konstruksi yang bisa jadi merugikan perempuan?
Aku sepakat dengan gagasan-gagasan bahwa pembebasan perempuan itu bisa diawali dari kesadaran perempuan akan keterasingan terhadap tubuh dan seksualitasnya sendiri yang disebabkan wacana patriarkal. Selanjutnya, ketika sudah ada kesadaran itu, kita akan lebih kritis terhadap wacana yang ada tentang tubuh dan seksualitas. Jadi lebih mampu membentuk ulang subjektivitas diri. Maksudnya begini, ketika ada aturan atau mitos tertentu yang menyatakan perempuan harus begini begitu, kita tidak menerima mentah-mentah melainkan ditelisik dulu adakah ketimpangan di dalamnya? Pada akhirnya kita nggak akan menggunakan wacana itu, kita bisa menciptakan konsep kita sendiri mengenai tubuh dan seksualitas kita dengan memilih wacana yang mendukung.
Pendapat pribadiku pemahaman seksualitas yang berperspektif gender ini penting dalam membangun kesadaran tersebut, tidak hanya untuk perempuan tetapi semua spektrum gender. Laki-laki juga perlu sekali menjadi bagian dari perjuangan meniadakan patriarkal itu sendiri. Karena aku meyakini bahwa ada banyak juga laki-laki yang sebenarnya tertindas dan menjadi korban dari wacana patriarkal itu sendiri. Jadi memang perlu sinergi untuk membangun pemahaman gender dan seksualitas yang setara ini.
Dimulai aja dengan belajar feminisme atau kesetaraan gender lalu ya ajaklah pasanganmu memahami konsep dasarnya. Atau ya, ketika menjadi orang tua, mulai mengenalkan pendidikan seksual yang menghargai keberagaman dan kesetaraan. Bergabung dengan jaringan yang concern-nya sama ini juga penting bagiku. Patriarkal ini memang tersistem, jadi melawannya perlu strategi juga dan nggak biasa sendirian, kita perlu sekali berjejaring. Bagiku aktivisme baik itu siber maupun offline, sama pentingnya! Kalau patriarkal bisa menyusup ke ranah digital, feminism juga harus bisa menandingi. Kelihatan simpel ya tapi tantangannya banyak loh ketika diimplementasikan.
Sekarang tampaknya Kemendikbud sudah mulai aware tentang pengarusutamaan gender untuk mencegah kekerasan seksual. Ini, sebenarnya harapan yang baik untuk kemudian ada pendidikan seksual yang inklusif dan setara, kelak jadi mata pelajaran atau mata kuliah wajib, kedepannya. Mari kita aminkan.
Hanya orang-orang dengan kelas sosial tertentu yang bisa melakukan praktik peremajaan vagina?
Peremajaan vagina bisa dilakukan oleh semua perempuan tapi bentuknya berbeda. Peremajaan secara tradisional sangat bisa dijangkau semua, tapi peremajaan vagina dengan metode kedokteran modern ini biayanya mehong ya, cyint. Ini kemudian juga menjadi pertanyaan kritis tersendiri bagiku.
Ketika dihadapkan dengan teknologi artinya banyaknya kelompok-kelompok perempuan yang tidak bisa mengakses. Bagaimana dengan prempuan-perempuan suku pedalaman yang menolak modernisasi, memilih untuk hidup di hutan-hutan dan pegunungan yang tersebar di pulau-pulau di Indonesia. Bagaimana pula dengan perempuan disabilitas yang mengalami hambatan dalam mendapat informasi melalui teknologi digital karena “dilupakan”? bagaimana dengan kelompok-kelompok perempuan yang memiliki keterbatasan biaya namun membutuhkan. Adanya keterasingan kelompok-kelompok tertentu terhadap teknologi ini ya tentu aku jadi bertanya-tanya: benarkah kesadaran terhadap tubuh dan seksualitas ini juga jadi semacam privilese nggak sih? Okay, bagi perempuan yang mampu mengakses teknologi mereka punya kesempatan untuk meraih kesadaran akan tubuh dan seksualitasnya, tapi bagi yang tidak dapat mengakses bagaimana? Ada kesenjangan kelas antar perempuan juga ternyata dalam praktik rejuvenasi vagina ini.
Jika memang bermanfaat, bukankah seharusnya peremajaan vagina bisa diakses oleh seluruh masyarakat? Bagaimana kamu melihat ini?
Ini juga perlu dikritisi. Kita perlu lihat juga bagaimana wacana kedokteran menempatkan rejuvenasi vagina ini. Kalau memang ini bukan persoalan gaya hidup dan klaim dunia kedokteran itu untuk kesehatan perempuan, apa mungkin bisa masuk ke anggaran BPJS, misalnya. Tapi jika melihat harganya yang tidak mudah dijangkau oleh semua kalangan, rejuvenasi vagina moden ini ya sangat mungkin disusupi kapitalisasi. Akhirnya memunculkan bentuk penindasan yang baru. Lalu kebebasan perempuan mengambil keputusan untuk rejuvenasi vagina ini dimanfaatkan oleh industri untuk keuntungan mereka.
Kita juga perlu menelisik dalam sesi konsultasi bagaimana relasi dokter dan perempuan yang ingin melakukan rejuvenasi vagina tersebut. Betul bahwa seharusnya posisi dokter dan pasien itu kan setara, bahkan pasien punya hak untuk menentukan. Tapi, ketika ada relasi kuasa/ penyalahgunaan kekuasaan, maka tentu akan timpang jadinya.
Ketika berhadapan dengan oknum yang memanfaatkan pengetahuannya untuk kepentingan pribadinya, kita boleh mempertanyakan kebebasan perempuan dalam mengambil keputusan untuk rejuvenasi vagina tersebut. Karena begini, terkadang kita sebagai pasien, kerap mengglorifikasi dokter dan memposisikan diri kita sebagai inferior.
Nah, ini akan sangat mempengaruhi keputusan untuk melakukan rejuvenasi vagina. Jadi sebagaimana sebelumnya aku jelaskan, kita perlu melihat sesuatu itu lebih luas dan kritis untuk menemukan apa yang tersembunyi di balik itu. Dalam hal ini, kita harus berprasangka juga bahwa mungkin saja wacana kesehatan juga disusupi patriarkal.
Naskah wawancara ini telah dipersingkat
Penulis: Joan Aurelia
Editor: Adi Renaldi