tirto.id - Enam dekade lalu, Jepang memilih menerapkan konsep "deterministik" alih-alih "probabilistik" dalam membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Melalui konsep tersebut, mereka menolak memikirkan apa yang mungkin terjadi di masa depan, melainkan berpijak pada catatan masa lampau.
Karena gempa bumi terbesar dan tsunami tertinggi yang pernah menimpa Jepang "hanya" ber-magnitude 8,0 (1600) dan 3,5 meter (1960), maka Jepang membangun PLTN Fukushima Daiichi NPP untuk tahan terhadap gempa tak lebih dari 9,0 magnitude dan tsunami tak lebih tinggi dari 4 meter.
Dioperasikan Tokyo Electric Power Corporation (TEPCO) sejak 26 Maret 1971, hampir 40 tahun beroperasi tak ada masalah dengan konsep deterministik yang dipilih Jepang. Bahkan, ketika akademisi-akademisi Jepang yang mempelajari keamanan penggunaan nuklir merekomendasikan peningkatan kapasitas keselamatan (tahan terhadap tsunami setinggi 5,5 meter dan gempa bumi yang lebih besar dari 9 magnitude) pada 1981 dan 2002, merwka bergeming--yakin bahwa PLTN Fukushima akan baik-baik saja.
Namun nyatanya gempa bumi yang menimpa pada 2011 berhasil mengoyak kepercayaan diri Jepang terhadap PLTN-nya. Tanggal 12 Maret 2011, tepat hari ini 11 tahun lalu, gempa bumi ber-magnitude 9,0 menghantam Jepang dari Samudra Pasifik--130 kilometer timur Sendai atau 163 kilometer barat laut PLTN Fukushima-- pada pukul 14.46. Gempa dahsyat yang diiringi tsunami setinggi 14 meter ini selain mengakibatkan 15.854 penduduk Jepang menjadi korban, juga melantakkan PLTN Fukushima.
Air laut yang bergejolak merangsek PLTN Fukushima yang tengah beroperasi. Sebagaimana dipaparkan George Steinhauser dalam studinya berjudul "Comparison of the Chernobyl and Fukushima Nuclear Accidents: A Review of the Environmental Impacts" (Science of The Total Environment, 2014), hal ini membuat sumber air yang digunakan generator diesel untuk mendinginkan tiga reaktor (Unit 4, 5, dan 6) tersendat serta perlahan menghancurkan generator.
Dan karena gempa pun mengakibatkan sistem kelistrikan bangunan PLTN rusak, reaktor Units 1, 2, dan 3 yang tengah beroperasi dan tak tersentuh tsunami juga terkena masalah di bagian sistem pendinginan. Akibatnya, reaktor-reaktor menghasilkan panas berlebih.
Sesaat setelah gempa bumi dan tsunami menghancurkan sistem pendinginan PLTN, sebagaimana dipaparkan Matthew L. Wald untuk The New York Times, para pekerja TEPCO berusaha mengaktifkan kembali sistem pendinginan, yakni dengan meminta bantuan perusahaan listrik lain untuk menyediakan generator. Meskipun generator berhasil dinyalakan, namun panas berlebih pada reaktor membuat bangunan yang berdiri di sekitarnya hancur dan merusak kabel generator.
Setelah pukul 3.30, panas pada pelbagai reaktor yang tak berhasil didinginkan mencapai titik 20 MW (juta watt). Ini membuat inti reaktor, termasuk segala elemen yang ada di sekitarnya, meleleh. Seketika bencana nuklir yang pernah menimpa Chernobyl juga dialami Jepang.
Ledakan reaktor nuklir pun terjadi. Meluncurkan cesium-137 dan yodium-131 ke berbagai arah dari titik PLTN Fukushima. Juga merilis isotop radioaktif (radionuclides) sebesar 520 PBq (kuantitas radionuklida per detik, di mana 1 Bq sama dengan transformasi/perilisan satu isotop radiokatif per detik) atau sekitar 15 persen dari yang terjadi di Chernobly.
Hal ini menjadikan Fukushima menjadi lokasi ketiga di Jepang yang mengalami krisis nuklir setelah Hiroshima dan Nagasaki.
Zaibatsu Melahirkan Bencana
"Ini adalah bom atom," ucap Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman pada Agustus 1945.
"Bom ini memperoleh kekuatan dari prinsip dasar alam semesta. Persis matahari memperoleh energinya, tetapi [bom atom] dibawa oleh mereka (para prajurit) ke medan perang di Timur Jauh (Jepang)," terangnya.
Sejak diteliti para ilmuwan mulai tahun 1895, lalu diiringi ketakutan terhadap Nazi Jerman mulai 1939 hingga 1945, sebagaimana dipaparkan James Mahaffey dalam Atomic Awakening: A New Look at the History and Future of Nuclear Power (2009), studi-studi tentang atom/uranium/reaksi fusi/nuklir selalu terfokus pada penciptaan bom atom alias mesin pembunuh. Tentu dengan alasan yang dikarang para politikus/pemimpin untuk menciptakan perdamaian.
Setelah Truman mengalahkan Jepang lewat dua bom atom yang dinamai Little Boy (dijatuhkan di Hiroshima) dan Fat Man (Nagasaki), studi-studi tentang atom/uranium/reaksi fusi/nuklir beralih ke soal penciptaan mesin pembangkit energi. Atom dipercaya sangat baik dan aman dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Bahkan Walt Disney diikutsertakan dalam kampanye ini dengan merilis kartun propaganda berjudul "Our Friend the Atom".
Secara statistik, memanfaatkan reaksi fusi nuklir demi menghasilkan energi listrik memang aman. Per 2021, dari 441 Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang ada di 30 negara di dunia, hanya dua PLTN yang mengalami musibah mengerikan, yakni Chernobly dan Fukushima. Sayangnya, dari dua PLTN ini, korban manusia dan lingkungan terlampau besar. Bahkan, khusus Chernobyl, karena PLTN ini berada di tengah-tengah benua, radiasinya mencapai Skandinavia--tak cuma menjalar di sekitar Ukraina dan Rusia.
Jika kita berpijak pada premis "PLTN aman", pertanyaannya mengapa bencana di Chernobyl dan Fukushima terjadi?
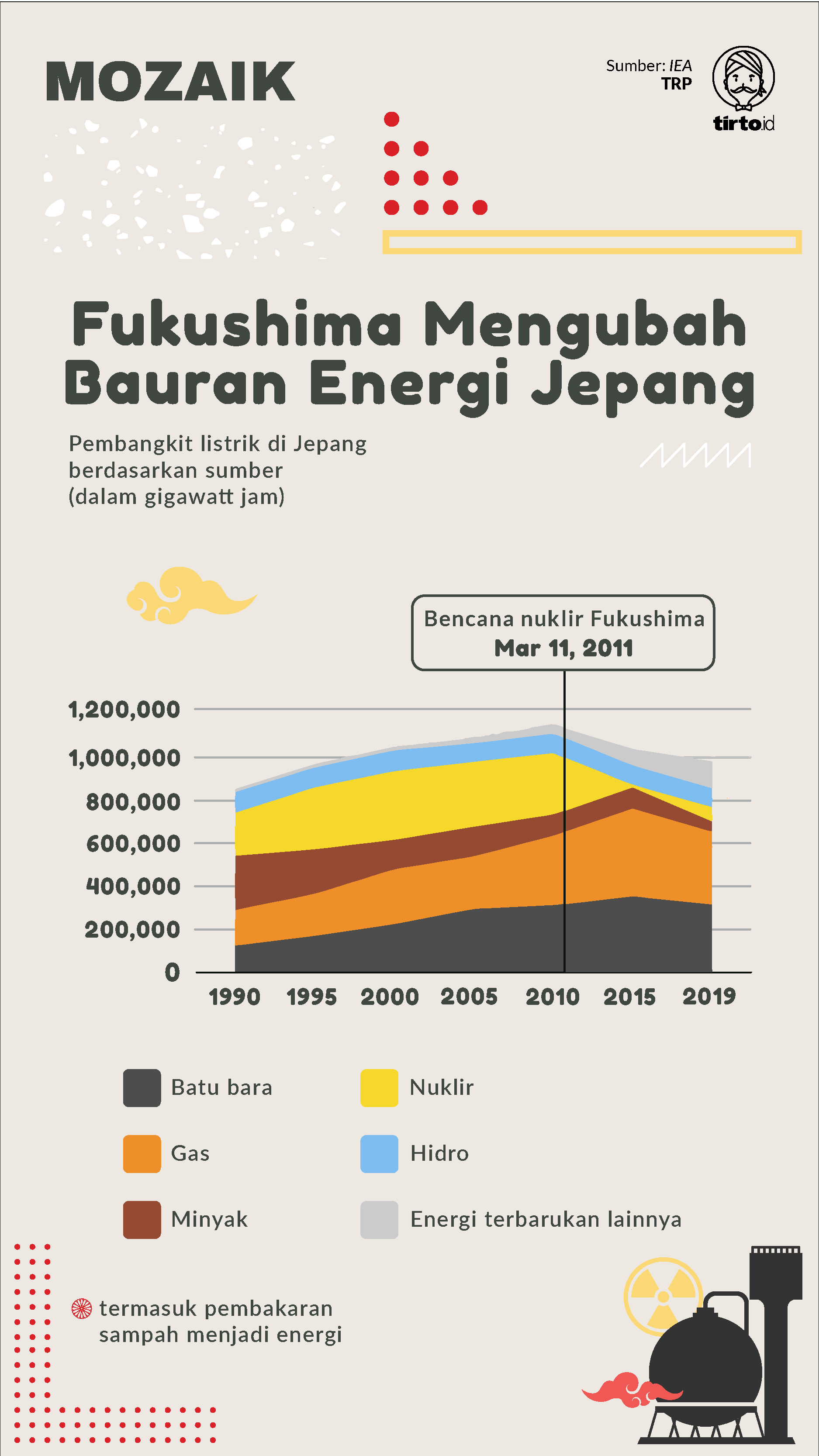
Dalam bencana yang terjadi di Chernobyl, rancang bangun yang buruk ditambah sumber daya manusia (SDA) yang tidak terlatih menangani PLTN adalah kuncinya. Fukushima pun terjadi atas alasan yang hampir serupa.
Menurut Geoffrey Cain dalam Samsung Rising: The Inside Story of the South Korean Giant that Set Out to Beat Apple and Conquer Tech (2020), Jepang adalah negara-- yang dikagumi Lee Byung-chul (pendiri Samsung)--penganut "zaibatsu" atau "klan kaya raya".
Konsep bisnis ini adalah perusahaan yang hanya dibesarkan oleh keluarga dengan menihilkan profesional non-keluarga dari sisi manajemen tingkat menengah-tinggi. Maka, jika pekerja non-keluarga ingin bertahan, mau tak mau ia harus manut alias menuruti segala tetek bengek yang diminta keluarga pemilik perusahaan. Diinisiasi dan dibesarkan oleh Mitsubishi, tabiat buruk ini menjalar di hampir semua perusahaan di Jepang, termasuk perusahaan negara.
Martin Fackler dan Norimitsu Onishi dalam laporannya untuk The New York Times menyebut bahwa beberapa minggu sebelum musibah Fukushima terjadi, komite keselamatan nuklir Jepang menemukan retakan pada salah satu generator diesel dalam sistem pendinginan reaktor. Namun para pekerja PLTN tak mampu membetulkan retakan tersebut. Karena tabiat manut telah menjalar, para pekerja pun hanya bisa diam, menolak memberontak untuk mengabarkan kebenaran demi menjaga pekerjaan.
Dan rekomendasi akademisi-akademisi Jepang yang menyatakan bangunan harus diperkuat (tahan terhadap gempa bumi lebih dari magnitude 9,0 dan tsunami lebih dari 4 mater) akhirnya hanya menjadi "makalah perpustakaan", tak bertransformasi menjadi tindakan karena alasan serupa: manut atau pendanaan studi dihentikan.
Tabiat ini tak hanya menjalar di tubuh pekerja, tetapi juga masyarakat Jepang. Dalam pembangunan PLTN Shimane (berbarengan dengan PLTN Fukushima), misalnya, masyarakat dibungkam dengan aliran dana senilai $35 juta untuk pembangunan gimnasium, kolam renang, dan lapangan olahraga. Lalu dalam upaya membangun PLTN untuk kebutuhan Tokyo pada 2009 lalu, negara membungkam masyarakat dengan potongan pajak, subsidi, dan lapangan pekerjaan senilai $1,15 miliar.
Masyarakat yang diam karena diberi pelbagai fasilitas dan pekerja yang takut kehilangan pekerjaannya--dalam kasus Fukushima--akhirnya hanya menghasilkan bencana.
Editor: Irfan Teguh Pribadi










