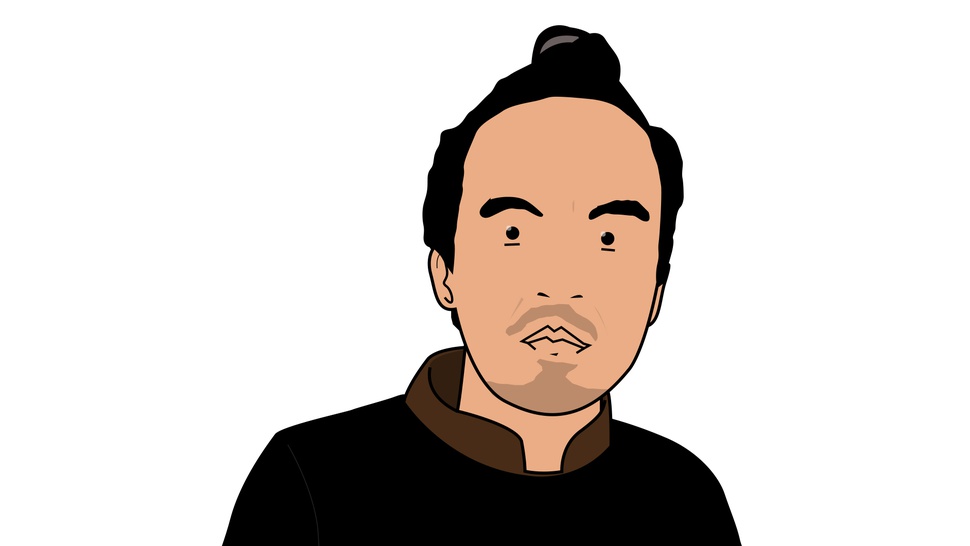tirto.id - Kata “radikal” kembali naik pasang. Kata ini menjadi bahasa yang mempersatukan banyak kementerian dan melakukan perang total dengannya. Bahkan, Kementerian Agama mestilah dipimpin seorang menteri yang berasal dari Angkatan Darat lantaran semangat berapi membekuk apa yang disebut “radikalisme”.
Rupanya, teguran Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa Antonio Guterres kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk berhati-hati memberi "tafsir" atas kata radikal di New York pada 2018 dianggap angin lalu belaka.
Pada pekan pertama Februari 2019, PBNU marah kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan RI lantaran satu paragraf buku pelajaran tematik terpadu Kurikulum 2013 kelas V SD/MI. Saya kutipkan secara utuh satu paragraf bermasalah dari buku berjudul Peristiwa Dalam Kehidupan (Tema 7) di halaman 45 itu:
Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah pada abad ke-20 disebut masa radikal karena pergerakan-pergerakan nasional pada masa ini bersifat radikal/keras terhadap pemerintah Hindia Belanda. Mereka menggunakan asas nonkooperatif/tidak mau bekerja sama. Organisasi-organisasi yang bersifat radikal adalah Perhimpunan Indonesia (PI), Partai Komunis Indonesia (PKI), Nahdlatul Ulama (NU), Partai Nasional Indonesia (PNI).
Pangkal soalnya pada kata “radikal” dan ada nama “Nahdlatul Ulama” di sana yang bersanding dengan—duh—PKI. Centraal bestuur NU berang pada kata “radikal” untuk memberi tonggak sebuah periode perjuangan kemerdekaan. Dengan kata lain, NU fobia dengan yang “radikal” lantaran kata itu memiliki arti negatif jika ditransfer begitu saja tanpa penjelasan apa pun.
Sejatinya, konotasi positif kata ini sudah menjadi bangkai ketika jidat aktivis Islam yang mengerek perlawanan terhadap Asas Tunggal Pancasila dicap militerisme Harto sebagai “kelompok radikal” sepanjang tahun 1980-an dan 1990-an. Kata ini makin bejat maknanya saat pemerintahan sedunia berperang melawan terorisme berjubah Islam. Bayangkan, sinonim “radikal” adalah “teror”, bukan “pokok”, “akar”, “primer”, “dasar”.
Bahkan, kalau kita tak malas mengetik kata “radikal” di KBBI V yang tersedia secara daring, kita temukan tak ada satu pun pengertian radikal itu berkonotasi buruk.
Saya tidak mau ikut-ikutan menjadi penerus sebuah fobia tanpa berpikir historis bagaimana lahirnya kata radikal/radicaal dalam kancah pembibitan pergerakan kemerdekaan di Indonesia. Tanpa berpikir historis, kata radikal selamanya bejat. Tak ada yang salah dengan buku pelajaran itu. Satu-satunya ketidakpekaannya adalah memasukkan NU di antara “koma-koma-dan” itu. Buktinya, PDIP yang “mewarisi” PNI tenang-tenang saja disebut. Apalagi, PKI.
Di masa itu, terutama saat pemerintah kolonial makin keras terhadap bibit pergerakan yang dihelat Sarekat Islam setelah Politieke Inlichtingen Dienst (Dinas Intelijen Politik) dibentuk pada 1916, gelombang perlawanan membesar di seantero Jawa. Suasana itu terbawa hingga ke Volksraad. Di parlemen itu, terbentuk sebuah faksi yang menamakan dirinya Radicale Concentratie. Dalam faksi ini, tergabung Sarekat Islam, Budi Utomo, Insulinde, dan Indische Social Demokratische Party (ISDP). Insulinde adalah nama partai politik bikinan Douwes Dekker dan Tjipto Mangunkusumo, sementara ISDP kelompok yang nantinya mengambil sebagian aktivis Sarekat Islam berkolaborasi membangun partai baru bernama PKI.
Di satu sisi, aksi Radicale Concentratie itu mula-mula menyerukan dalam bingkai parlementer agar pemerintah kolonial tak membabibuta melakukan penangkapan para aktivis buruh dari Sarekat Islam yang tidak saja melakukan pemogokan di mana-mana, namun juga mengobarkan opini “persamaan hak”.
Mereka juga mengajukan beberapa mosi yang kemudian melahirkan salah satu keputusan dari pemerintahan Gubernur Jenderal Graef van Limburg Stirum yang dikenal dengan “Janji November” pada 1918. Salah satu isi penting janji itu adalah perbaikan upah buruh di beberapa perkebunan.
Di tangan Sukarno-lah, makna “radikal” mendapatkan titik panasnya: hak merdeka. Ia bahkan naik ke podium di sebuah rapat Radicale Concentratie di Bandung dan menyerukan ide-ide yang kemudian kita kenal dengan semangat non-kooperatif. Di lapangan pergerakan, radicaal itu diterjemahkan penggawa-penggawa PKI sebagai pemberontakan bersenjata melawan pemerintahan kolonial.
Pada masa itu, radikal adalah pembebasan sepenuhnya dari. Spirit periode radikal inilah yang kita warisi kemudian dalam paragraf pertama Pembukaan UUD 1945 yang setiap Upacara Senin dibacakan siswa dari SD hingga SMA, yaitu “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan ….”
Menyatakan “kemerdekaan itu hak” dan “penjajahan harus dihapuskan” adalah sikap radikal. Karena radikal atau pokok, ia berada di paragraf paling atas. Semangat radikal “menghapus penjajahan” itu tidak sekadar mengusir pemerintahan Belanda dari bumi persada, melainkan juga menasionalisasi semua maskapai kolonial. Bahkan, dengan berselempangkan semangat radikal itu, duet Sukarno dan Ki Hadjar Dewantara menghajar mundur tak bersisa bahasa Belanda dari silabus kurikulum pendidikan untuk para siswa Republik Indonesia.
Jadi, dalam konteks historis, radikal adalah sebuah gaya hidup dalam pembibitan kemerdekaan bangsa dan pembentukan negara. Radikal itu lingua franca dalam sejarah pembebasan nasional. Nama-nama pahlawan perintis kemerdekaan yang selama ini hilir-mudik dalam buku pelajaran para siswa, justru menyandarkan semangat mereka pada satu kata yang keren: “radikal”.
Itu.
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.