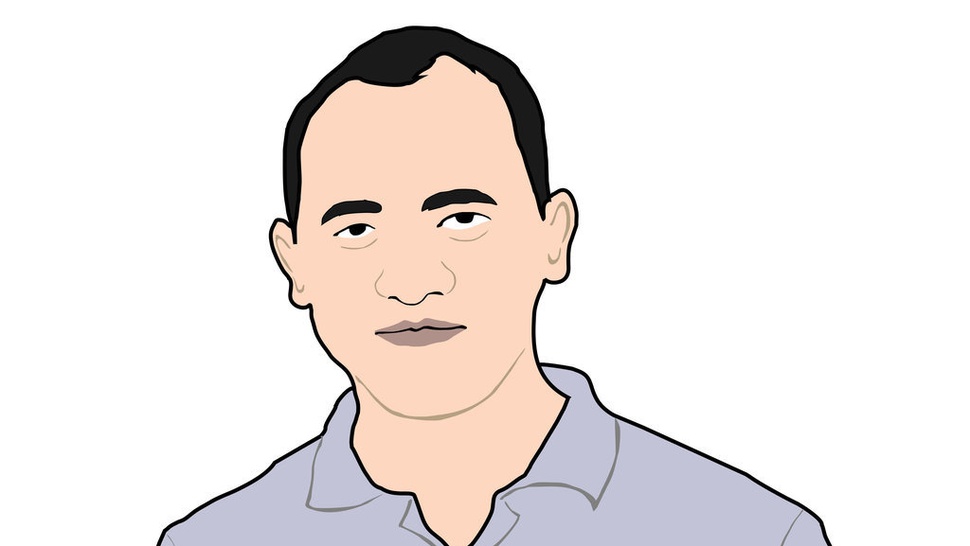tirto.id - Secara prinsipil, semua warga negara setara di hadapan negara. Tak boleh ada kasta sosial atau warga kelas dua yang dipilah berdasarkan agama, mazhab, afiliasi politik, dan seterusnya. Selama warga negara membayar pajak, ia berhak mendapatkan hak yang sama. Negara pun berkewajiban menjaga hak-hak individu—dalam hal berkeyakinan, misalnya.
Teori negara ideal seperti ini bisa dan lazim berlaku di banyak tempat. Kecuali di sejumlah daerah dan negara—termasuk Aceh.
Di Aceh, ada kesan bahwa jika kamu seorang muslim maka kamu mendapat privilese lebih ketimbang keyakinan lain. Sekalipun begitu, sesama muslim pun ada semacam perbedaan perlakuan. Yang ahlussunnah wal jama'ah (Aswaja) dianak-emaskan; sementara yang non-Aswaja jadi anak tiri. Sementara aliran-aliran lain seperti Syiah atau Salafi dicap sebagai anak haram.
Tentu diskriminasi terhadap sesama anak manusia ini tak hanya terjadi di Aceh atau lebih luasnya di Indonesia, tapi juga di pelbagai belahan dunia. Dengan memecah-belah manusia jadi warga kelas satu dan kelas kambing, gelombang populisme sayap kanan adalah ancaman besar bagi gagasan dan praksis kesetaraan.
Barangkali, di masa depan, ide tentang kesetaraan manusia tanpa syarat hanya ada di kitab-kitab filsafat. Mungkin keadilan mutlak cuma utopia belaka. Kebangkitan populisme sayap kanan yang menuntut agar kewargaan didasarkan pada warna kulit, silsilah keluarga, etnisitas, dan agama boleh jadi sedang menubuatkan kiamat kesetaraan itu.
Tak perlu jadi anggota partai populis sayap kanan untuk membenci sesama. Tanpa dinamai populisme, sehari-hari kita sudah diajak merawat sektarianisme dan kebencian.
Pada Oktober 2017, sebuah fondasi masjid di Bireun, Aceh, dibakar oleh sekelompok orang. Cikal bakal bangunan yang dilalap api adalah masjid Muhammadiyah. Paginya dibangun, malamnya hangus. Pelaku pembakaran belum ditangkap sampai sekarang. Alasan yang paling sering disebut: pembakaran itu buntut pertikaian dan persaingan antara Muhammadiyah dan Dayah yang beraliran Aswaja.
Ketika ada dua kubu yang berselisih, pihak ketiga yang welas asih dan bijaksana sudah semestinya hadir menengahi. Di Aceh, pihak ketiga itu bernama Majelis Pertimbangan Ulama (MPU). April ini, MPU Bireuen mengeluarkan keputusan: Muhammadiyah harus menghentikan pembangunan masjidnya.
Kita patut bertanya, apakah ada perwakilan Muhammadiyah di majelis itu sehingga bisa mengambil keputusan yang menguntungkan satu pihak?
MPU mengeluarkan kebijakan tersebut berdasarkan dua dalil. Pertama, pembakaran fondasi dasar masjid menunjukkan masyarakat resah akan kehadiran Muhammadiyah sehingga demi menjaga keamanan, ketenteraman, dan menghindari konflik, pembangunan masjid harus dihentikan. Kedua, karena Muhammadiyah minoritas, maka wajib mengikuti mayoritas. Prinsip keadilan yang dipakai MPU adalah logika utilitarianisme yang menunjukkan situasi bahwa kebahagiaan mayoritas lebih penting daripada kebahagiaan minoritas. Mayoritanisme ini pun dibalut slogan "kearifan lokal."
Dua argumentasi MPU ini mengandung beberapa kejanggalan.
Pertama, membakar fondasi masjid adalah perbuatan kriminal. Yang sepatutnya dikenai hukuman adalah pelaku pembakaran, bukan warga Muhammadiyah. Ia patut dicari, diadili, dan dipenjara sebagai bukti penegakan hukum.
Konsekuensi dari logika MPU: jika masyarakat tak suka pada pendirian rumah ibadah tertentu, maka tinggal bakar saja. Nanti pemerintah akan menghentikan pembangunannya. Toh, para pembakar bebas dari tindak pidana. Dengan kata lain, menghentikan pembangunan masjid menunjukkan MPU mengikuti kehendak sang kriminal (pembakar fondasi masjid). Penting bagi MPU Bireuen untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa Muhammadiyah adalah bagian dari keluarga besar umat Islam. Mereka juga harus mengecam siapa pun yang bertindak intoleran.
Kedua, istilah mayoritas dan minoritas yang dipakai MPU menunjukkan cara berpikir ‘kita’ versus ‘mereka’. Padahal Muhammadiyah sama-sama Islam; artinya sama-sama bersaudara. Argumentasi bahwa minoritas sepatutnya mengikuti mayoritas sejatinya menunjukkan ekspresi kekuasaan yang mencatut nama mayoritas dalam hubungan-hubungan sosial yang timpang.
Sudah selayaknya MPU memberi fatwa agar masyarakat bisa menerima Muhammadiyah terlepas dari perbedaan tafsir. Ulama punya tugas untuk mencerahkan masyarakat bahwa Muhammadiyah adalah bagian dari Islam, dan harus dilihat sebagai saudara seakidah dan seagama.
MPU Provinsi Aceh perlu turun tangan mengatasi permasalahan intoleransi in, misalnya melalui fatwa yang menegaskan bahwa Muhammadiyah adalah saudara seiman dan seagama; tak boleh didiskriminasi serta dipinggirkan hanya karena kedudukannya sebagai minoritas di sebuah wilayah.
Ketiga, seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menyangkut keamanan, MPU perlu secara tegas melarang dan mengecam para pelaku intoleransi di Aceh. Sementara polisi wajib bertindak dan menyeret pelaku ke pengadilan.
Aceh tak punya pilihan selain menunjukkan bahwa syariat Islam di provinsi itu mampu menampung beragam tafsir dan cara pandang dalam memahami Islam. Tak sedikit pula pemuka agama di belahan negara lain yang memelopori resolusi konflik dan membangun sikap menghargai perbedaan. Jika di provinsi lain Muhammadiyah dan Nadlatul Ulama bisa hidup berdampingan, kenapa di Aceh yang bersyariat Islam justru tak mesra?
Perbedaan dalam beragama adalah hal lumrah dan sepantasnya disikapi dengan arif, bukan dengan pemberangusan.
Sayangnya, mengharapkan tiga hal di atas terjadi di Aceh hari ini ibarat pungguk merindukan bulan.
Ketika intoleransi muncul dengan telanjang di depan mata, hampir semua elemen masyarakat memilih diam. Seolah-olah masyarakat Aceh sedang dikutuk untuk takut berbicara, takut digebuk kalau melawan dan bersikap kritis. Tak ada demonstrasi besar-besaran membela Muhammadiyah. Tak ada juga pernyataan sikap yang lantang dari intelektual kampus.
Semuanya diam, seolah yang dibakar cuma sarang semut.
Mungkinkah berharap pada tokoh agama di tingkat nasional? Tentu pimpinan Pusat Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia harus bersuara dan mengusahakan islah antarorganisasi keagamaan di Aceh.
Jika mereka memilih bungkam, ada baiknya mengingat bahwa arus sektarianisme dan diskriminasi, yang beberapa tahun lalu setinggi lutut, kini sudah seleher.
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.