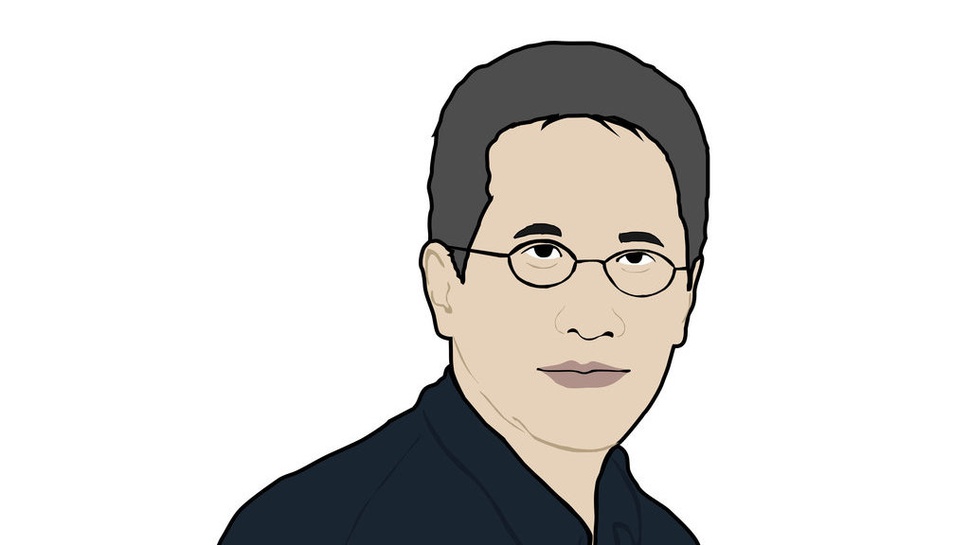tirto.id - Generasi saya adalah satu-satunya generasi yang separuh hidupnya berada di dunia tanpa internet, dan separuh lainnya dengan internet dan berbagai peralatan digital lain. Kami mengalami salah satu perombakan sosial besar-besaran dalam tatanan masyarakat global dalam satu abad terakhir.
Wajah suatu masyarakat memang ditentukan oleh teknologi komunikasi yang dominan. Perubahan teknologi itu akan memaksakan perubahan masyarakat. Begitulah pandangan McLuhan lebih dari setengah abad lalu, yang kemudian dikembangkan oleh para sarjana lain dengan gagasan “modus informasi”, meminjam konsep kunci “modus produksi” dari Marxisme.
Sejauh pengamatan saya, perdebatan publik paling besar (dalam skala jangkauan partisipan) dan penting (dari segi dampak, secara nyata atau potensial) dalam satu dasawarsa terakhir atau lebih di Indonesia berlangsung di dua wilayah. Pertama, di televisi. Kedua, di media sosial.
Tentu saja ada kaitan dan tumpang-tindih di antara keduanya. Debat di televisi kadang-kadang membahas apa yang sebelumnya ramai di media sosial. Sebaliknya, debat di televisi, apalagi bila tersedia rekamannya di YouTube, sering berlanjut di media sosial.
Apa persamaan dan perbedaan debat di televisi dan media sosial? Kita amati bedanya dulu.
TV dan Media Sosial
Perbedaan paling utama: siaran televisi sifatnya searah, media sosial tidak. Debat televisi disiarkan dari satu titik ke jutaan orang yang memiliki akses siaran itu. Debat di media sosial terbuka selebar-lebarnya, kapan saja, dari-oleh-dengan siapa pun yang memiliki akun yang sesuai.
Acara di televisi merupakan bagian dari industri media yang sifatnya komersial. Bukan saja acara debat diselingi iklan di tengah-tengah acara perdebatan. Yang lebih penting, topik dan siapa yang akan diundang ikut dalam debat dipilih dengan perhitungan-akhir komersial. Juga penjadwalan acara debat, formatnya, jenis pertanyaan yang diajukan dan dikawal moderator, bahkan pemilihan hadirin yang diundang ke studio.
Bukannya semua itu jelek. Acara debat di televisi dikurung oleh aneka pagar. Ia terencana, terarah dan terbatas. Semua itu dimaksudkan (sampai batas tertentu) untuk menjaga “mutu” perdebatan sehingga menjadi acara tontonan yang menarik. Daya-tarik acara ini menentukan rating acara serta nilai jualnya pada pengiklan.
Sehebat-hebatnya acara debat televisi, ia adalah komoditas yang dijual tuan rumah acara (pemilik industri media) pada pengiklan. Dan sepandai-pandainya bintang debat di televisi, mereka membantu pengusaha televisi meningkatkan nilai jual komoditas itu di pasaran iklan.
Selain arah, tujuan dan kerangka komersialnya, acara televisi masih dibatasi oleh rambu-rambu hukum dan politik.
Semua itu kontras dengan dinamika debat di media sosial. Walau tidak bebas mutlak dari pagar-pagar komersial, hukum dan politik, media sosial jauh lebih terbuka, lumayan inklusif, lumayan egalitarian, global dan interaktif ketimbang televisi. Ia tidak mengabdi pada satu pusat atau arah kepentingan komersial atau pun politis. Sejak awal sulit memastikan jalannya debat di media sosial. Bahkan sulit memastikan siapa saja yang akan terlibat, kapan mereka ikut berdebat, dan sampai berapa lama, apalagi hasil akhirnya.
Tanpa moderator, perdebatan di media sosial bisa sangat panjang atau tiba-tiba terhenti pendek. Bisa terfokus untuk beberapa saat, lalu menyebar ke berbagai arah. Atau berantakan karena banyak yang tidak bersambungnya satu suara dari yang lain. Kadang-kadang di tengah serunya perdebatan, muncul gurauan tidak berkait yang lucu, konyol, cerdas, jorok, atau yang kasar campur-aduk jadi satu.
Mana yang lebih baik di antara kedua ragam dan media untuk debat itu? Masing-masing punya keunggulan dan kelemahan. Kita dapat memetik yang terbaik dari keduanya, dan belajar menelan atau mengabaikan yang tidak bermanfaat.
Media Cetak Sekarat
Apa persamaan di antara berbagai debat di kedua ragam media tadi? Sebagai bagian dari generasi yang separuh hidupnya di dunia tanpa internet, dan separuh lainnya dengan internet, saya rasa ada yang hilang dari perdebatan publik dalam seperempat abad terakhir. Yakni perdebatan yang sifatnya relatif lebih mendalam dan kompleks, dan dulu pernah berlangsung di media cetak (koran dan majalah). Perdebatan itu mewarnai sebagian besar perdebatan publik selama abad ke-20 di banyak negara. Juga di Indonesia.
Tahun 1930-an berlangsung debat yang kemudian dijuluki Polemik Kebudayaan. Tahun 1960-an perhatian publik nasional terpusat pada perdebatan antara kubu LEKRA dengan lawan-lawan politiknya, terutama kubu Manifes Kebudayaan. Tahun 1980-an diisi oleh perdebatan tentang Ekonomi Pancasila dan Sastra Kontekstual. Semua berlangsung dalam bentuk artikel koran atau majalah, masing-masing sekitar 1.000 kata.
Perdebatan semacam itu sudah lama tidak terjadi lagi. Bukan karena tidak ada topik penting yang dapat diperdebatkan. Bila dibandingkan dengan debat pada masa pra-internet, yang terjadi sekarang sifatnya serba dangkal. Bukan karena yang berdebat kurang cerdas. Tetapi media dan teknologi yang paling siap menampung debat mereka (televisi dan media sosial) tidak memungkinkan hal itu. Sementara media massa cetak seperti koran dan majalah memasuki masa kritis antara hidup dan mati.
Televisi dan media sosial menuntut semua pernyataan peserta debat serba pendek. Secerdas apa pun peserta debat di televisi dan media sosial, mereka tidak diberi kesempatan menyampaikan tuturan yang sifatnya mendalam, kompleks dan kaya-nuansa.
Moderator di televisi membatasi waktu ujar setiap pembicara sependek-pendeknya (mungkin 100 kata setiap ujaran), supaya tidak tampil seperti ceramah. Di twitter orang bisa membuat serangkaian twit yang panjang. Facebook memungkinkan unggahan panjang. Namun, di tengah banjir informasi tanpa-henti, warganet sudah terlatih untuk tidak sabar dan intoleran pada tulisan tentang satu topik berpanjang-panjang atau bersambung-panjang.
Akibatnya, yang banyak tampil di media sosial adalah patahan-patahan pendapat. Seringkali berbentuk kalimat tak lengkap. Banyak penulis twit berjuang menciptakan singkatan tak lazim agar pesannya bisa tertampung dalam batasan karakter. Di televisi, peserta debat saling memotong dan berebut kesempatan bicara, atau belajar tampil dan bicara secara genit, agar tidak kehilangan perhatian juru-kamera yang bergerak cepat dalam hitungan detik.
Masa ini adalah masa meledaknya informasi dan kebebasan berkomunikasi. Masa ini juga ditandai sekaratnya industri media massa cetak, seakan-akan tanggal kadaluwarsa mereka sudah dekat. Di tengah hamburan pesan digital yang murah dan bergerak cepat, debat seperti di koran dan majalah masa lalu terasa lamban, elitis, dan rumit bertele-tele.
Di ruang publik, banjir informasi dan pesan berupa patahan-patahan ujaran. Pesan terpatah-patah itu disampaikan secara terburu-buru oleh warga yang saling berebut perhatian orang lain agar didengar dan dipahami.
Kedangkalan dan pendangkalan komunikasi demikian tak terhindarkan. Bukan direkayasa siapa pun. Tak ada yang mengendalikan. Tak ada yang diuntungkan. Banyak yang dirugikan.
Kedangkalan bertutur ini bermuara pada kuatnya cara berpikir biner dalam masyarakat: salah/benar, baik/buruk, kita/mereka, toleran/radikal. Tak ada atau semakin sempit ruang untuk memahami kompleksitas, kontradiksi dan tumpang-tindih berbagai masalah yang rumit yang terbentang di dua kutub yang ekstrem yang dipromosikan debat publik.
Pemahaman yang kompleks dan rumit membutuhkan uraian panjang yang tersusun utuh dan berfokus tajam. Diskusi demikian membutuh pranata komunikasi publik, yang sayangnya nyaris tak tersedia saat ini. Akibat selanjutnya: terjadi polarisasi besar-besaran dalam masyarakat, sehingga terbelah-belah. Masing-masing membela keyakinan dengan harga mati, sambil mencurigai yang berbeda sebagai ancaman.
Publik masa kini bukan tak punya peluang menikmati perdebatan publik yang bermutu tinggi. Tapi mungkin di luar acara televisi dan media sosial.
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.