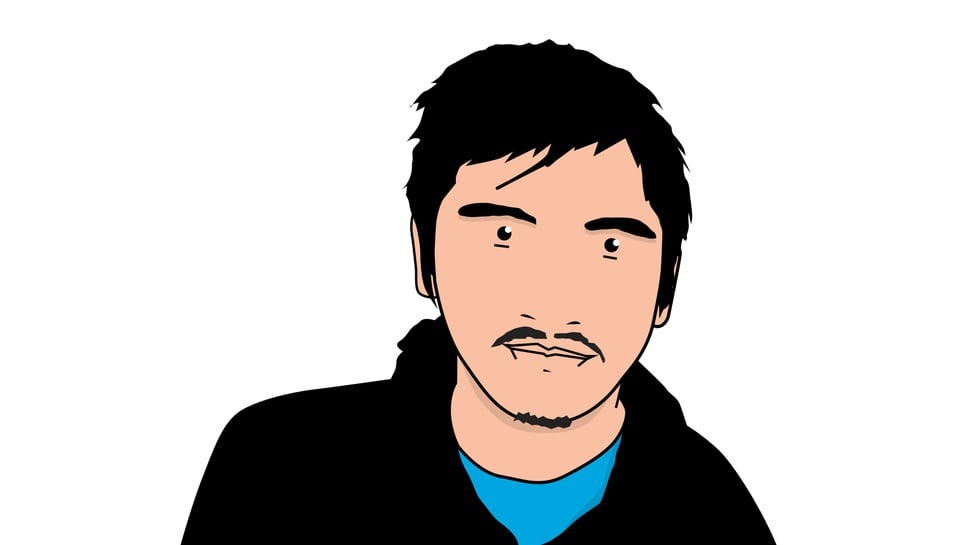tirto.id - Tiap kali para petani menggelar perlawanan, apalagi jika perlawanannya menjadi masif, selalu ada yang sibuk mencari tahu: Siapa otaknya? Siapa aktor intelektualnya? Atau bahkan: siapa provokatornya?
Penalaran yang biasanya keluar dari para birokrat dan aparat keamanan ini adalah usaha mendelegitimasi perlawanan. Melalui pertanyaan-pertanyaan macam itu, perlawanan hendak dilokalisir sebagai persoalan para elite, ketidakpuasan faksi-faksi politik terhadap pemerintah, atau ulah orang-orang terdidik yang sedang mencari proyek dan keuntungan sendiri.
Jika penalaran ini diterima, persoalan utama yang memicu perlawanan dengan sendirinya akan dipinggirkan, bahkan dianggap tidak ada. Perlawanannya akhirnya akan dianggap mengada-ada, dibikin-bikin. Wong tidak ada persoalan, ngapain melawan?
Penalaran macam ini juga meremehkan petani, atau massa rakyat, sebagai makhluk tak berdaya, yang tak punya inisiatif dan kehendak, serba pasif dan nrimo, serta tak sanggup mencerna dan memahami persoalan—pendeknya: tak punya kemampuan berpikir dan bertindak politis.
Setidaknya ada dua bias yang melatarinya. Pertama, bias kelas. Perlawanan atau demonstrasi, apalagi mengorganisir solidaritas, diletakkan sebagai kemampuan elitis yang khas kelas terdidik saja. Hanya para aktivis, para mahasiswa, mereka yang melek informasi dan membaca buku-buku, yang bisa memahami persoalan ekonomi-politik dan hanya mereka juga yang bi(a)sa melakukan perlawanan.
Para petani, massa-rakyat, warga di desa-desa yang terpencil, dianggap “terlalu tidak tahu apa-apa” untuk memahami persoalan. Mereka dianggap tidak berpendidikan, atau naif, lebih menyedihkan lagi dianggap bodoh, hanya karena tidak mencecap pendidikan tinggi, sehingga mustahil punya inisiatif dan kemampuan melakukan perlawanan.
Kedua, bias kota. Para petani yang tinggal di desa, di lereng gunung, di tempat-tempat yang jauh dari pusat ekonomi dan politik, dibayangkan sebagai makhluk-makhluk yang stabil, kebal dari dinamika, sangat toleran dan penuh tepa selira, serta memahami segalanya dalam kerangka takdir. Bias ini berasal dari pandangan romantik yang memandang desa sebagai tempat yang penuh kedamaian, nihil konflik—persis seperti lukisan-lukisan Mooi Indie yang menggambarkan desa sebagai hamparan sawah hijau dengan aliran sungai jernih nan tenang dan tak pernah berubah.
Sehingga, bila para petani di gunung memutuskan untuk berserikat melawan agenda-agenda negara, hal itu sudah pasti bukan tindakan yang alamiah, hasil intervensi pihak luar—entah para aktivis atau makelar-makelar yang sedang mengintai keuntungan.
Ada gema "negara organik", atau "negara integralistik" ala Soepomo, dalam cara berpikir ini. Pandangan negara organik membayangkan tidak ada ketegangan antara negara dan rakyat. Keduanya adalah manunggal. Rakyat dan pemimpin itu tidak terpisah-pisahkan. Negara-bangsa dibayangkan sebagai sebuah keluarga besar, dengan pemimpin sebagai bapak dan rakyat sebagai anak-anaknya. Tidak pada tempatnya mencurigai sang bapak hendak mencederai anak-anaknya. Segala yang dilakukan sang bapak, jikapun dirasa merugikan, semuanya untuk kebaikan anak-anaknya.
Asumsi bahwa para petani di desa-desa itu naif, bodoh, dan tidak mungkin melakukan perlawanan terhadap negara, juga asumsi bahwa desa pada dasarnya penuh kedamaian dan tidak memiliki potensi konflik, sebenarnya ahistoris. Sangat mudah mencari contoh-contoh dalam sejarah yang membatalkan dua asumsi yang berasal dari dua bias itu.
Sejak kekuasaan Mataram Islam (baik di Surakarta maupun Yogyakarta) secara permanen takluk kepada pemerintahan kolonial, inisiatif perlawanan terhadap Belanda nyaris hanya dilakukan oleh para petani atau dari masyarakat petani. Saat para penguasa Jawa sudah mulai nyaman menjadi bagian birokarsi kolonial, bahkan sosok patih yang berperan sebagai kepala pemerintah pun sudah sepenuhnya ditentukan oleh Belanda, tinggallah masyarakat petani yang terus menyalakan perlawanan dengan pelbagai bentuk dan metode aksi.
Historiografi Indonesia kaya dengan kisah-kisah gerakan perlawanan semacam ini. Perang Jawa, masyhur juga dengan sebutan Perang Diponegoro, sebenarnya adalah perlawanan kaum tani. Tanpa dukungan dari para petani, Diponegoro mustahil mengobarkan perlawanan besar yang terakhir melawan kekuasaan kolonial. Didukung oleh masyarakat petani, dan jaringan kiai kampung, Diponegoro sanggup membuat Belanda harus mengerahkan semua-mua kemampuan dan sumber daya. (Baca juga: Patok Menancap di Lahan Diponegoro Hingga Rakyat Kulonprogo)
Onghokham memperkirakan, sejak kekalahan Diponegoro pada 1830 hingga awal abad-20, terdapat sekitar 100 perlawanan masyarakat petani. Dari perlawanan petani di Banten, Ciomas, Cimareme, hingga perlawanan anarkis para petani Samin dan puluhan perlawanan masyarakat petani lain. Mereka bahu-membahu, biasanya dipimpin oleh tokoh lokal yang berlatarbelakang ulama, kiai, atau tokoh spiritual. (Baca juga: Akhir Kehidupan Napoleon van Java)
Perlawanan mengambil bentuk yang bermacam-macam. Dari perlawanan fisik bersenjata, membakar perkebunan, merampok hasil bumi yang hendak disetorkan kepada administrasi kolonial, menolak membayar pajak hingga membangkang terhadap perintah administrasi kolonial.
Pembangkangan terhadap perintah administrasi kolonial ini, dalam rupa-rupa siasat remeh-temeh sehari-hari, mungkin tidak tampak sebagai perlawanan karena tak meledakkan mesiu atau menumpahkan darah. Padahal perlawanan kecil-kecilan, “perlawanan sehari-hari” jika meminjam istilah James Scott, dalam skala yang berkelanjutan bisa efektif. Pun dapat menjelaskan bahwa dalam pasifitas yang terkesan tunduk, bahkan para petani itu tetap menggigit lewat gerogotan-gerogotan kecil yang akhirnya mematikan.
Tentang gerogotan kecil para petani ini, pembaca dapat menelusuri buku Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa: Sistem Priangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa, 1720-1870, studi Jan Breman tentang tanam paksa. Breman menyimpulkan, keengganan para petani yang terus berkelanjutan untuk bertindak sesuai dengan yang diperintahkan oleh pemerintah kolonial merupakan hal yang sangat menentukan dalam memundurkan dan menjatuhkan sistem tanam paksa.
Ada juga perlawanan yang mengambil bentuk perbanditan sosial. Studi Suhartono (Bandit-Bandit Pedesaan: Studi Historis 1850-1942) kaya dengan fragmen-fragmen perlawanan yang dilakukan masyarakat petani terhadap semua lembaga kolonial tanpa berhadapan langsung dengan pemerintah atau pihak perkebunan. Mereka merusak irigasi, membobol gudang-gudang, menggergaji rel-rel lori, hingga membakar ladang-ladang tebu.
Barulah pada abad 20 bentuk-bentuk perlawanan mulai digantikan dengan cara-cara modern melalui organisasi, surat kabar, dan institusi-institusi politik lain. Itu pun para petani masih terus menyumbangkan tenaga dan jiwanya. Perlawanan bersenjata yang diinisiasi oleh Partai Komunis Indonesia pada 1926 di pelbagai tempat, seperti Silungkang hingga Banten, melibatkan partisipasi aktif dan masif dari para petani dan ulama lokal.
Kesadaran politis para petani terhadap ketidakadilan struktural itu mengalami amputasi besar-besaran pasca-1965. Orde Baru benar-benar menghabisi kesadaran kritis para petani dengan pelbagai cara dan indoktrinasi, dari memaksakan cara bertani, memaksakan benih tertentu, memaksa penggunaan pupuk melalui Koperasi Unit Desa, dan menyetor hasil panen pada tengkulak resmi yang ditunjuk (baik itu Bulog untuk padi maupun BPPC untuk cengkeh).
Cukup jelas, perlawanan para petani terhadap kekuasaan bukanlah barang baru, bukan hal yang dibikin-bikin, melainkan berurat-akar dan menancap kuat dalam sejarah negeri ini. Perlawanan para petani Kendeng, misalnya, adalah sesuatu yang historis dan (seharusnya) tidak mengejutkan.
Mengapa tidak mengejutkan? Jawaban atas pertanyaan ini sekaligus mematahkan bias kedua yang meromantisisme desa sebagai kesatuan yang serba-damai, serba-tenteram, serba-teratur dan serba-nrimo.
Perlawanan para petani dipicu karena desa-desa mengalami tekanan luar biasa. Tekanan itu dipicu oleh, setidaknya, dua hal yang satu sama lain saling terkait: perubahan struktur agraria di pedesaan dan terbentuknya negara-birokrasi-kolonial. Studi ekstensif James Scott tentang para petani di Asia Tenggara (The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia) atau studi Sartono Kartodirdjo (Pemberontakan Petani Banten 1888) kaya dengan eksposisi tentang dampak-dampak dua hal itu.
Para petani di perdesaan dipaksa untuk memenuhi kebutuhan negara kolonial. Pelbagai sistem diperkenalkan dari sistem tanam paksa hingga masuknya modal asing dalam bentuk perkebunan-perkebunan berskala masif. Struktur agraria yang pada awalnya bercorak subsisten (untuk memenuhi kebutuhan sendiri) berubah secara dramatis oleh sistem-sistem yang dipaksakan dari atas oleh administrasi kolonial.
Sistem tanam paksa mendesak para petani untuk bekerja lebih keras, sehingga bisa dikatakan dieksploitasi, untuk memenuhi target yang telah ditetapkan oleh pemerintah kolonial. Para petani tidak hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan sendiri, tapi juga untuk memenuhi target-target yang telah ditetapkan. Sedangkan sistem perkebunan swasta, yang dirancang oleh Agrararische Wet 1870, membutuhkan lahan yang luas dan tenaga kerja yang besar, mengondisikan para petani untuk melepas tanah-tanah miliknya dan beralih menjadi buruh penggarap.
Untuk memastikan keberhasilan sistem-sistem itu, negara kolonial tidak bisa tidak mesti membentuk struktur birokrasi yang rapi dan berjenjang hingga level terbawah. Para penguasa lokal diintegrasikan ke dalam struktur birokrasi kolonial sebagai inlandsch bestuur, birokrasi untuk mengurusi kaum bumiputera, dari bupati, wedana, camat hingga kepala desa. Mereka menjadi ujung tombak usaha-usaha kolonial mereguk sebanyak-banyaknya laba. Mereka, aparat birokrasi ini, juga mendapatkan persentase yang besar dari pelbagai pungutan dan tarikan hasil pertanian yang berhasil dikumpulkan.
Desa akhirnya mengalami perubahan struktural dengan skala yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Bayangan tentang desa yang damai, tenteram, tidak memiliki potensi konflik, jelas pandangan ahistoris yang tidak berdasar.
Untuk segala perubahan yang dramatis dan besar-besaran itu, siapa lagi yang paling menjadi korban jika bukan para petani? Inilah yang akhirnya memicu munculnya beragam bentuk perlawanan para petani dalam sejarah kolonial Hindia Belanda, khususnya di Jawa.
Yu Patmi, petani Kendeng yang menyemen kakinya dan meninggal pada 21 Maret, tahu benar hal ini. Ia tak membutuhkan buku-buku tentang ekonomi-politik, bukan karena hal itu tidak penting, melainkan karena tubuh dan biografi mereka sendiri adalah kisah tentang kerumitan ekonomi politik yang mendesak hingga ke petak-petak sawah di pedalaman. Tidak perlu sekolah tinggi-tinggi bagi Yu Patmi untuk memahami dalil ekonomi-politik yang sangat penting: sekali seseorang kehilangan faktor produksi (sawah bagi para petani), posisinya akan sangat rentan diisap mesin besar produksi.
Inilah perlawanan terakhir, sekaligus yang terbesar, bagi masyarakat petani seperti Yu Patmi. Menolak menjual tanah, menolak diam saat sawahnya terancam hancur, adalah titik pijak untuk menghadapi medan ekonomi politik yang ganas. (Baca juga: Selamat Jalan Yu Patmi)
Kaki Yu Patmi yang disemen adalah kaki-kaki yang menolak berpisah dengan tanahnya, dengan sawahnya. Yu Patmi dan kawan-kawannya mengerti bahwa begitu kaki-kaki mereka dijauhkan dari tanah, kaki-kaki itu akan semakin halus, kulitnya semakin lembut, dan pelan-pelan akan menjadi semakin lemah, gampang terluka, dan mudah meringis tiap kali menginjak duri semak-semak.
Mereka memang lebih sering diam, atau tampak bungkam. Namun riwayat perlawanan para petani menjelaskan satu hal bahwa, sebagaimana diingatkan oleh James C. Scott dalam esainya tentang latihan perlawanan kaum anarkis, ”Akan tiba saatnya Anda diminta untuk melanggar hukum besar atas nama keadilan dan rasionalitas. Segalanya akan tergantung pada hal itu. Dan Anda harus siap.” (Two Cheers for Anarchism: Six Easy Pieces on Autonomy, Dignity and Meaningful Work and Play, 2012)
Yu Patmi tahu saatnya telah tiba dan ia bersiap. Inilah yang membuat Yu Patmi, juga kematiannya, menjadi mata rantai yang tak bisa dipisahkan dari sejarah panjang aktivisme politik para petani di negeri ini.
===================
Kabar dan analisis terbaru yang lebih lengkap tentang perlawanan petani Kendeng:
Menuntut Jokowi Mendengarkan Ibu Bumi Petani Kendeng
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.