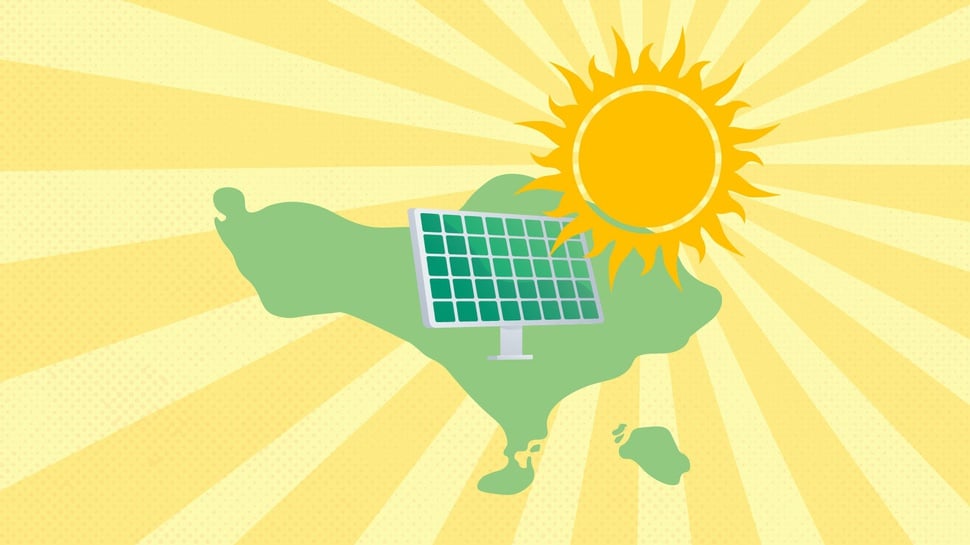tirto.id - Di sebuah desa kecil bernama Baturinggit yang terletak di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem - sekira 95 kilometer dari Denpasar - ada sebuah lahan seluas 1,2 hektare yang diisi puluhan panel tenaga surya. Lokasi ini dikenal dengan dengan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Karangasem.
Kawasan itu terlihat mati. Sunyi, tak ada aktivitas apapun. Saya coba melihat ke arah ruang monitor di dekat gerbang pintu masuk. Hasilnya sama: tak ada aktivitas manusia di dalamnya. Hanya sebuah ruangan kosong, tak ada meja dan kursi, tak ada informasi apapun mengenai proyek besar ini. Papan informasi di depan ruang monitor yang sudah luntur tak menyisakan informasi apapun.
Dari tempat saya memarkir sepeda motor di luar pagar, saya sempat melihat seseorang lelaki dengan kaos dan topi berwarna merah, terlihat berjalan di area dalam PLTS. Saya menduga, dia merupakan salah seorang penjaga. Pada 2016 lalu, Mongabay pernah melaporkan bahwa ada seorang penjaga yang tak diupah sama sekali selama 2,5 tahun bekerja.
Saya berharap mendapat cerita serupa dan memutuskan masuk ke dalam, walau ada tulisan peringatan “Dilarang Masuk Selain Karyawan” di pintu masuk.
Setelah saya masuk dan berkeliling selama 15 menit, lelaki itu entah ke mana. Yang ada hanya tiga ekor kambing yang sedang merumput. Sembari berkeliling, saya juga memperhatikan beberapa inverter—salah satu komponen tenaga surya untuk mengkonversi arus listrik—yang sudah mati.
Dalam laporan Mongabay pada 2016 lalu, diketahui bahwa dari total 50 inverter yang ada, 19 di antaranya sudah rusak. Layarnya kosong, seperti gawai yang sedang rusak.
Proyek pembangkit listrik tenaga surya ini dibangun dan diresmikan pada 2013 oleh mantan Menteri ESDM Jero Wacik. Dibangun di atas lahan seluas 1,2 hektare, PLTS berkapasitas 1 megawatt ini digadang menjadi proyek percontohan untuk energi terbarukan di Indonesia dengan nilai investasi sebesar Rp26 miliar.

Ia menggunakan sistem on-grid yang menyatu dengan PT PLN yang direncanakan selama dua puluh tahun. Warga sekitar akan gunakan energi surya, malamnya pakai listrik dari PLN.
“Proyek ini adalah PLTS yang terbesar sekarang ini. Sementara ini yang terbesar. 1 MW yang terbesar,” kata Jero Wacik saat peresmian. Dua tahun setelahnya, politikus senior Partai Demokrat itu diciduk komisi antirasuah karena kasus penyalahgunaan dana operasional menteri dan menerima gratifikasi.
Saya telah coba menghubungi mantan Kepala Bagian Ekonomi Sekretaris Daerah Karangasem, I Wayan Sutrisna, untuk meminta penjelasan terkait proyek PLTS yang mangkrak ini. Namun, ia enggan berkomentar. Saya juga telah menghubungi pejabat yang sekarang, Made Hadi Susila, untuk bertanya hal serupa dan perkembangannya hingga saat ini lewat pesan singkat WhatsApp, namun pesan hanya dibaca.
Pada 2016 lalu, I Wayan sempat mengakui kalau PLTS ini kurang terurus karena tak ada perhatian dari Pemerintah Pusat. Saat itu, proyek PLTS tersebut tak diurus oleh Pemkab Karangasem karena belum serah terima tanggung jawab pengelolaan.
Namun, pada September lalu, Made Hadi Susila sempat bilang bahwa energi dari PLTS itu akan dijual ke PT PLN. Hingga saat ini, semuanya masih dalam tahap proses persiapan.
Padahal, sejak 2015, Bali sudah digadang-gadang menjadi daerah percontohan untuk menerapkan energi terbarukan di Indonesia. Dimulai dari aturan mengenai pembatasan sampah plastik sekali pakai pada 2018, setahun setelahnya terbit pula Peraturan Gubernur Nomor 45 tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih. Ini membuat Bali menjadi provinsi pertama yang keluarkan aturan mengenai energi bersih.
Dibandingkan energi terbarukan lainnya, energi surya di Bali memiliki potensi yang paling tinggi, yaitu sekitar 98% dari total potensi energi terbarukan yang terdapat di Bali. Kajian IESR tahun ini menyebut potensi teknis energi surya di Bali mencapai 26,4 gigawatt. Sedangkan studi yang dilakukan Asian Development Bank (ADB) pada 2017 lalu malah lebih tinggi. Mereka menemukan bahwa Bali memiliki potensi energi surya mencapai 113,4 gigawatt.
Maka tak heran, pada Februari 2020 lalu, rencana Kementerian ESDM untuk membangun 800 PLTS se-Indonesia juga menetapkan Provinsi Bali sebagai daerah terbanyak, yaitu 90 titik PLTS atap. Semua harus dipasang di gedung-gedung, menggunakan dana APBN.
Belakangan, semakin gencar saat Pemprov Bali menerbitkan surat edaran tentang pemanfaatan PLTS atap pada Juni lalu. Intinya, Pemprov meminta semua gedung instansi pemerintahan untuk memasang PLTS atap paling sedikit 20 persen dari kapasitas listrik terpasang atau luas atap bangunannya.
Rangkaian kebijakan ini bisa dibaca sebagai langkah pembuka jelang COP26—konferensi yang diselenggarakan Perserikatan Bangsa-Bangsa guna membahas perubahan iklim—pada November mendatang. Dengan itu, Pemerintah memiliki target baru untuk mengejar emisi nol karbon—net-zero emission (NZE)—pada 2060 mendatang.
Terlebih, pada 2016 lalu, Indonesia ikut meneken Perjanjian Paris untuk mendukung penurunan emisi gas rumah kaca sesuai Nationally Determined Contributors (NDC) pada 2030 mendatang: sebesar 29 persen secara mandiri, atau 41 persen lewat dukungan internasional. Sejak saat itulah Pemerintah berencana untuk mengembangkan energi terbarukan—salah satunya surya—dan mulai mempensiunkan pembangkit listrik yang berbasis fosil—atau energi kotor.
Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, target itu terbaru termasuk memakai opsi pembangkit listrik tenaga nuklir yang akan dimulai pada 2045 mendatang, dengan kapasitas hingga 35 gigawatt di tahun 2060. Pemerintah juga ingin fokus ke kendaraan listrik, hentikan penjualan motor konvensional pada 2040 dan mobil konvensional pada 2050, serta transportasi publik yang lebih masif.
Dalam forum COP26 pada 1-2 November itu, Presiden Joko Widodo berencana akan memaparkan berbagai strategi mengejar target NDC dan NZE tersebut.
Upaya Warga Berdaulat Energi Bersih
Ni Made Puriati, 47 tahun, menggali kembali kenangan 14 tahun lalu saat datang ke Puncak Mundi, di Pulau Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali. Ia melihat banyak papan panel surya dan sembilan kincir angin raksasa terpasang di atas lahan di ketinggian 500 mdpl.
Beberapa kali Denik—nama kecil sekaligus sapaan akrabnya hingga kini—melihat kincir-kincir itu berputar terempas angin di atas bukit. Saat itu, ia mengaku belum tahu untuk apa dan akan menghasilkan apa kincir-kincir sebesar itu.
“Saya berpikir itu bukan pembangkit listrik,” kata Denik saat saya temui, 19 Oktober lalu.
Apa yang dilihat Denik saat itu adalah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) saat tahun-tahun muncul dan mulai beroperasi. Dua pembangkit itu dibangun hanya satu bulan jelang Indonesia di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi tuan rumah Konferensi Perubahan Iklim PBB pada Desember 2007, di Nusa Dua, Bali.
Dua pembangkit yang dibangun menggunakan dana dari World Bank sebesar 1,8 miliar rupiah—angka yang tidak sedikit—itu ditargetkan memproduksi energi listrik sebesar 700 KW. Namun, saat ini, nasib dua pembangkit itu serupa dengan PLTS Karangasem: mangkrak.
“Masyarakat enggak tahu apakah dapat listrik dari proyek itu atau bagaimana. Apakah listriknya mengalir ke mereka apa enggak. Belum sempet jalan [proyek itu]. Enggak jalan,” tambah rekan kerja Denik, I Gede Sugiarta, 48 tahun. Keduanya aktif di Yayasan Wisnu, organisasi yang fokus mendampingi komunitas masyarakat di bidang lingkungan dan ekowisata.
Kata Gede, masyarakat Pulau Nusa Penida sendiri baru secara penuh menerima aliran listrik PT PLN sejak 2015 saat pariwisat masif digalakkan oleh Pemerintah. Daya listrik untuk tiga pulau—Penida, Ceningan, dan Lembongan—dinaikkan.
“Dulu listrik cuma malam hari. Baru masif 2015, saat pariwisata sudah mulai tinggi,” tambahnya.
Namun, jika kita turun dari Puncak Mundi ke arah Dermaga Banjar Nyuh sejauh 14 kilometer, sekitar 35 menit menggunakan sepeda motor, kita akan bertemu Rumah Belajar Bukit Keker, komunitas masyarakat yang sedang giat menggunakan energi terbarukan selama beberapa tahun terakhir, khususnya panel surya.

Penggunaan PLTS mengenal dua sistem pemakaian: on-grid dan off-grid. Secara umum, sistem on-grid hanya akan menghasilkan listrik saat berbarengan dengan grid dari PT PLN. Sistem ini memungkinkan adanya proses jual-beli daya listrik dengan PT PLN. Para pengguna hanya perlu memiliki panel surya dan inverter—alat untuk mengkonversi arus. Meski simpel, sistem ini masih bergantung dengan PT PLN.
Lain cerita dengan sistem off-grid. Sistem ini memungkinkan menyimpan energi listrik yang didapat dari surya ke dalam baterai dan bisa digunakan kapan saja. Dengan sistem ini, warga bisa lebih berdaya untuk gunakan energi surya dan pakai listrik di rumah masing-masing tanpa tergantung dengan PT PLN.
Kendati demikian, pengguna PLTS off-grid memang kudu lebih keluar tenaga: biaya baterai cukup mahal, perawatan alat yang rutin, dan penggantian baterai secara berkala.
Sistem PLTS off-grid inilah yang digunakan oleh Rumah Belajar Bukit Keker selama dua tahun terakhir. Rumah Belajar Bukit Keker menjadi salah satu komunitas yang didampingi oleh Yayasan Wisnu.
Komunitas itu mulai menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sejak dua tahun lalu, dengan kekuatan masing-masing 3.000 Wh dan 5.000 Wh. Tak hanya itu, komunitas itu juga mulai menggunakan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), biogas, energi angin, hingga pengelolaan pertanian secara alami.
“Baterai bisa menampung 1.000 Wp, bisa gunakan sampai 4.000 Wh. Asal panas. Kalau malam, kita berpikir, kita hanya andalkan baterainya. Selama pengalaman kami, kaalu ada acara malam pakai sound system masih kuat, paling acaranya dua jam. Sisanya hanya lampu bisa sampai pagi. Karena besok ada matahari lagi,” kata Gede bercerita.
Oleh karena itu, menurut Gede, seharusnya Pemerintah bisa lebih memberikan perhatian prioritas kepada komunitas-komunitas di masyarakat yang sudah berinisiatif menggunakan energi terbarukan, jika memang negara mau secara serius beralih dari energi kotor.
Kata Gede, seharusnya Pemerintah bisa membikin aturan yang terperinci di level masyarakat untuk penggunaan energi terbaru. Semisal, pelan-pelan melepas ketergantungan masyarakat atas listrik dari PT PLN.
“Dengan aturan yang ada benar-benar dilakukan secara bertahap di tingkat masyarakat. Dibuat berjangka 3 sampai 4 tahun, pertama 100 persen pakai dari PLN, dipotong 80 persen, hingga 50 persen, dan seterusnya. Pelan-pelan. Ini enggak ada program rinci seperti itu,” kata dia.
Kata dia, Pemerintah tak bisa hanya fokus ke proyek-proyek besar, yang belum ditentu dirasakan masyarakat sekitarnya. “Itu di tingkat megaproyek, [hanya bicara] siapa yang sedang diuntungkan. Masyarakat hanya nonton aja,” tambahnya sembari tertawa.
Apalagi, menurutnya proyek PLTS dan PLTB di Puncak Mundi tersebut bisa tidak berjalan karena memang sedari awal tidak melakukan riset mendalam terkait keadaan lingkungan yang menjadi sumber energi. Seharusnya: ada riset lebih lama dan mendalam terkait kecepatan dan arah angin hingga fluktuasi angi tiap bulannya.
“Namun, karena sudah tenggat proyek, enggak dicek dulu,” kata dia. “Akhirnya mangkrak. Masyarakat hanya sebagai penonton aja. Itu urusan proyek. Masyarakat ditanya juga bingung kenapa mangkrak, mereka enggak pernah merasakan.”
Denik sepakat dengan Gede. Selama proyek-proyek besar energi terbarukan di Indonesia tidak melibatkan masyarakat, atau lebih jauh lagi tidak menjadikan masyarakat sebagai subjek yang aktif, selama itu pula proyek hanya sekadar proyek yang belum tentu bermanfaat.
“Masyarakat ditempatkan hanya objek, bukan subjek yang aktif. Itu kenapa gagal apa pun yang dibuatkan Pemerintah, kalau enggak sesuai kebutuhan masyarakat lokal, akan susah. Tidak mengacu kebutuhan masyarakat dan tidak melibatkan masyarakat,” katanya.
Mendukung Inisiatif Warga
Saya berbicara dengan peneliti kebijakan tenaga surya dari Institute for Essential Services Reform (IESR), Daniel Kurniawan, soalnya fenomena mangkraknya proyek-proyek besar di sektor energi surya yang dicanangkan Pemerintah. Apalagi, pada awal tahun lalu, Daniel dan tim dari IESR juga sempat melakukan survei ke Puncak Mundi, Nusa Penida. Temuannya serupa dengan apa yang dikatakan Gede dan Denik.
“PLTB-nya baling-balingnya patah. Bayu sudah enggak berfungsi. Yang surya, inverter di ruang monitornya juga sama, sudah bunyi-bunyi, kok enggak ada yang urus,” kata Daniel kepada saya, 28 Oktober lalu. “Entah berhenti sejak kapan. Kayanya enggak ada indikasi mau direvitalisasi.”
Kata dia, banyak proyek besar PLTS yang tak jelas kelanjutannya karena masalah ambiguitas kepemilikan. Saat sebuah proyek PLTS selesai dibangun, kebingungan akan muncul ihwal siapa yang mengurus: Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat. Apalagi ketika Pemerintah Daerahnya memang tidak kompeten.
“Biasanya kekurangan ketika nanti misal ada inverter yang enggak rusak, enggak tahu mau hubungi siapa. Bisa juga enggak ada dana mau perawatan itu,” tambahnya.
Apalagi, kata Daniel, secara umum fenomena proyek PLTS yang mangkrak terjadi dimulai dari skema off-grid yang melepas diri dari PT PLN. “Contoh, PLTS Cirata [Jawa Barat] itu ada skema perjanjian dengan PT PLN, makanya bisa jalan. Off-grid pakai dana APBN banyak terlantar, setelah sudah berjalan, entah siapa yang akan urus jangka panjang,” katanya.
“IESR belum pernah tracking berapa PLTS yang mangkrak di Indonesia totalnya, tapi sebagian besar kasusnya sama kaya yang di Bali. Mangkrak setelah dilempar ke daerah.”
Menurut Daniel, seharusnya setelah sebuah proyek PLTS diserahkan ke Pemerintah Daerah, ada peningkatan kapasitas untuk para pejabat hingga warga di sekitar agar bisa mengelola dan merawat dengan baik. “Atau enggak ya sekalian lepas ke swasta aja karena mereka ada dana untuk rawat ini barang. Kalau enggak kaya gitu, ya jadi terlantar saja,” tambahnya.
Terlepas dari proyek-proyek besar PLTS, Daniel bilang bahwa seharusnya Pemerintah juga bisa memberi perhatian lebih ke pengguna energi surya di level rumah tangga atau komunitas. “Kendati segmen pasarnya masih kelas menengah, dan di kota-kota besar, itu masih jadi tantangan,” kata dia.
Apa yang dikatakan Daniel bisa jadi benar. Apalagi data dari Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementrian ESDM sendiri, dari potensi PLTS atap yang dapat dikembangkan adalah sebesar 32,5 gigawatt, sektor rumah tangga adalah penyumbang tertinggi: 19,8 gigawatt.
Dari potensi 32,5 gigawatt itu, hingga Juli 2021, yang baru dimanfaatkan hanya sekitar 35,56 megawatt. Dari angka itu, setidaknya ada total 4.028 pelanggan PLTS se-Indonesia. Lebih rinci, 3.300-nya adalah rumah tangga, sedangkan Pemerintah hanya 133.
Dari total 4.028 pelanggan itu, enam daerah tertinggi: Jawa Barat (8,84 MWp), DKI Jakarta (6,9 MWp), Jawa Tengah & DIY (5,8 MPw), Jawa Timur (4,5 MWp), Banten (2,3 MWp), dan Bali (1,7 MWp).
Hingga 2025 mendatang, Kementerian ESDM memiliki agar kapasitas PLTS se-Indonesia bisa mencapai 3,6 gigawatt, targetnya 772.508 pelanggan di level rumah tangga dari total 72.320.302 pelanggan—lagi-lagi, sektor ini penyumbang terbanyak.
Namun, ketika berbicara masyarakat di level rumah tangga yang ingin menggunakan PLTS, Daniel mengakui salah satu masalah yang paling besar adalah pendanaan. Kendati sudah banyak lembaga keuangan—entah bank maupun non-bank—yang sudah mulai memiliki program cicilan untuk pemasangan PLTS, namun kondisi ini perlu dapat perhatian khusus dari Pemerintah. Salah satunya dengan memberikan insentif.
“Kredit sama kaya beli motor. Sejauh ini lumayan banyak, tapi belum booming. Harusnya bisa dimaksimalkan agar masyarakat lebih banyak yang tertarik. Kalau ada yang bisa 0 persen cicilannya,” kata dia.

Sektor pengkreditan seperti ini yang sudah mulai dijalani oleh Ida Ayu Maharatni, 40 tahun. Ia adalah pendiri sekaligus manajer Koperasi Amoghasiddhi, lembaga yang memungkinkan untuk memberikan kredit di sektor energi terbarukan, jika ada masyarakat yang ingin memasang PLTS. Koperasi ini diklaim sebagai koperasi pertama di Indonesia yang berada di ranah energi terbarukan.
“Itu pembeda kita dengan koperasi lain, kita punya kredit energi,” kata dia kepada saya, 20 Oktober lalu. “Kayanya baru kita yang pertama di Indonesia.”
Koperasi itu di daerah Kesiman Petilan, Denpasar Timur, Bali. Di depan gedung tinggi dengan tiga lantai itu, terpasang sembilan panel surya yang mengarah ke segala sisi. Di lantai satu terdapat NBH Urbanfarming Store yang menjual perlengkapan hidroponik dan pertanian. Sedangkan koperasinya berada di lantai dua.
Nani, sapaan akrabnya, bilang bahwa gedung itu memasang PLTS off-grid sebesar 7,2 kWp. Kapasitas itu digunakan untuk menghidupi jam operasional gedung kurang-lebih 12 jam, dari jam delapan pagi hingga delapan malam.
“Bisa digunakan 12 jam. Siang ada listrik yang dihasilkan, kalau kelebihan ya disimpan di batre untuk malam hari,” kata dia.
Oleh karena itu, menurut Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), Surya Darma, penggunaan energi surya di Indonesia bukan hanya perkara tren, namun juga sebuah keharusan untuk lingkungan yang lebih baik, dunia yang lebih hijau, dan emisi karbon yang lebih rendah.
Apalagi, kata Surya, energi surya di Indonesia relatif lebih aplikatif dan cepat proses ketimbang energi lain yang butuh waktu lama. “Energi air 6-7 tahun pembangunannya. Panas bumi butuh 7-12 tahun. Enggak gampang. Biomass nanam pohon 4 tahun. Baru bisa kita petik. Ini idealnya. Kalau semua diikuti, waktu persiapan akan lebih panjang,” katanya, 29 Oktober lalu.
“Jalan lainnya lebih cepat untuk energi surya, adalah memanfaatkan semua atap yang ada. Rumah, kantor, gedung pemerintahan, dan sebagainya. Tinggal kita semua tutup aja. Paling butuh waktu satu tahun selesai akhirnya. Gedung-gedung besar itu tutup saja pakai PLTS, minimal untuk kebutuhan sendiri,” tambahnya.
“Energi surya sangat rugi jika tidak dimanfaatkan. Matahari setiap hari ada. Mau kita pakai atau enggak, ya tetap ada. Apalagi ini negara tropis.”
Reportase ini merupakan hasil Fellowship Transisi Energi yang diselenggarakan oleh Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) dan Institute for Essential Services Reform (IESR).
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Adi Renaldi