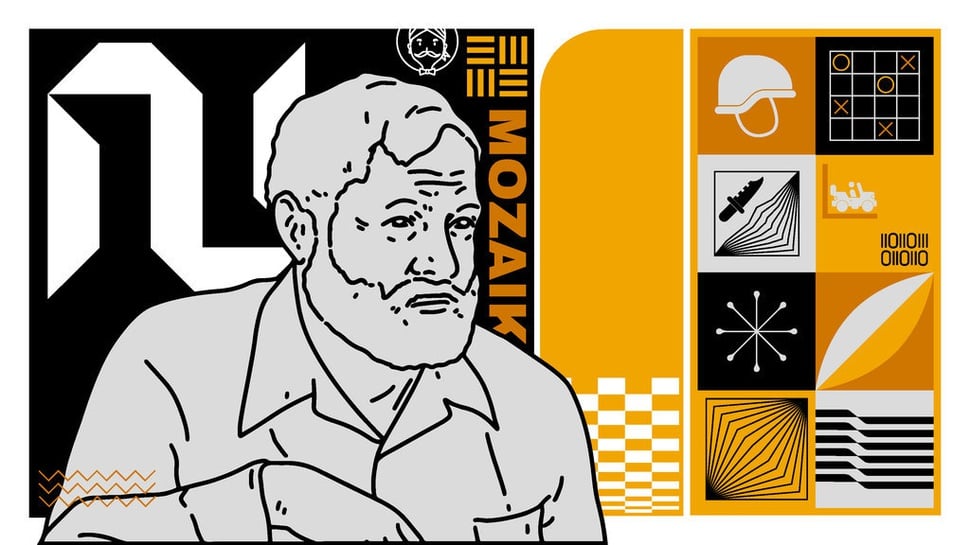tirto.id - Ketika Ernest Hemingway makan malam di sebuah hotel modis di rue de Rivoli, George Orwell sedang berpeluh sebagai pencuci piring. Keduanya sama-sama masih bau kencur sebagai penulis. Dua raksasa sastra ini sama-sama menetap di Paris kala itu. Bahkan, sampai Maret 1928, Hemingway tinggal di rue Férou, hanya beberapa blok dari tempat Orwell. Tak ada pertemuan, tapi keduanya sama-sama berbagi pengalaman sebagai ekspatriat dan penulis yang masih berjuang.
Paris direkam dalam memoar separuh fiksi oleh keduaya. George Orwell dalam Down and Out in Paris and London dan Hemingway dengan A Moveable Feast serta The Sun Also Rise. Orwell dan Hemingway baru bertemu kemudian di Paris pada 1940an, sebagai sesama koresponden Perang Dunia II.
Dua penulis ini memang punya beberapa hubungan menarik. Ada kemiripan gaya penulisan mereka: bahasa konkret, kalimat sederhana dan lugas, serta dialog tangkas. "Jangan pernah gunakan penuturan panjang jika bisa pakai yang singkat," tegas Orwell, yang secara tak langsung diamini Hemingway.
Pada bulan Maret 1937, Hemingway pergi ke Madrid untuk melakukan liputan perang bagi North American Newspaper Alliance (NANA). Hemingway mengirim 31 laporan dari Spanyol. Dia juga membantu produksi film pro-Republikan, The Spanish Earth. Pengalamannya selama perang sipil ini yang kemudian menjadi materi novel For Whom the Bell Tolls.
Novel ini menggambarkan kebrutalan perang saudara di Spanyol. Kisah seorang pemuda Amerika yang bergabung di Brigade Internasional. Diceritakan dengan sudut pandang orang ketiga lewat pemikiran dan pengalaman sang protagonis, Robert Jordan, yang menjadi bagian unit gerilya antifasis sebagai ahli dinamit.
Bergerak di pegunungan Sierra de Guadarrama antara Madrid dan Segovia, latar novel tersebut berlangsung selama empat hari tiga malam. Robert ditugaskan meledakkan sebuah jembatan. Dengan gaya yang berdekatan dengan karya sebelumnya, Farewell to Arms, novel ini mengulas keberanian dan fanatisme, cinta dan kekalahan, dan kematian tragis akan sebuah ideal. Hemingway mempertunjukan kemunafikan, lelucon, dan ketidakberesan yang tercipta berkat perang.
Novel ini sekaligus bisa dibilang kisah cinta terbesar Hemingway. Cerita antara Robert dan Maria jauh lebih dari sekedar romansa kacangan. Kisah cinta penuh gairah dari dua jiwa tersesat. Maria dihadirkan sebagai alusi atas tanah Spanyol. Bagi Robert, Maria memberikan dorongan untuk pengembangan pribadinya dari pemikir dan pelaku tanpa belas kasih menjadi seorang individu romantis.
Bagi Hemingway, novel ini menjadi wahana kritikannya pada kepemimpinan Republikan dan sebuah ratapan atas destruksi fasis pada cara hidup petani Spanyol yang bersahaja. Novel berjalan pada musim semi 1937, saat perang terhenti, sebulan setelah pasukan Jerman meratakan kota Guernica.
"Jika fungsi seorang penulis adalah untuk mengungkapkan kenyataan," tulis Maxwell Perkins, menyurati Hemingway setelah membaca manuskripnya, "tidak ada yang benar-benar melakukannya."

Hemingway menerbitkan tujuh novel, enam kumpulan cerita pendek, dan dua karya nonfiksi semasa hidupnya. Naskah-naskahnya yang lain, termasuk memoar tentang masa mudanya di Paris, A Moveable Feast, terbit di kemudian hari secara anumerta.
Kisah hidup Hemingway, mulai dari masa kanak-kanak dalam keluarga disfungsional (dengan ayah yang kasar dan ibu yang senang mendandani dia seperti anak perempuan), rupa-rupa petualangan, hingga maut yang ia renggut dengan gaya, adalah bahan yang dibicarakan orang sampai kini. Namun, peninggalan terpenting pria yang selamat dari dua perang dunia dan dua kecelakaan pesawat dan tiga perceraian itu tentu bukan riwayat hidupnya. “Kau tahu, Bo, kau bukan tokoh dalam tragedi. Begitu juga aku. Kita adalah penulis dan urusan kita adalah menulis,” ujar Hemingway dalam suratnya untuk F. Scott Fitzgerald.
Pada Oktober 1926, New York Times menyebut novel pertama Hemingway, The Sun Also Rises, telah “mempermalukan karya-karya lain dalam bahasa Inggris.” Teknik Hemingway yang diterangkan ulasan itu sebagai “prosa naratif yang ramping dan keras dan atletis,” plus caranya menciptakan karakter dan lain-lain, adalah pal besar dalam sejarah seni penulisan. Ia adalah bengawan yang darinya banyak sungai lain tercipta.
J.D. Salinger, penulis novel The Catcher in the Rye, menyebut diri sebagai Ketua Kelab Penggemar Hemingway tingkat Nasional dalam sebuah surat. Gabriel Garcia Marquez pernah berseru penuh rasa hormat dan kekaguman (“Maestro!”) saat ia melihat Hemingway di seberang jalan. Dan semua orang tahu bahwa Hunter S. Thompson, pelopor jurnalisme Gonzo, mempelajari teknik menulis dan gaya hidup dan cara mati dari Hemingway.
"Apa yang Diinginkan Orang?"
Pada 2 Juli, Hemingway terjaga menjelang pukul 7 pagi. Ia mengenakan jubah merah yang biasa disebutnya “jubah kaisar”, lalu mengamati istrinya, Mary, yang pulas dalam lindungan selimut. Pria itu sadar penglihatannya benar-benar telah memburuk dan pikirannya, berkat demensia dan terapi setrum, tidak lagi dapat diandalkan, tapi pagi itu ia tahu ia mencintai istrinya. Ia ingat bagaimana mereka berjumpa dan saling jatuh cinta dan meninggalkan pasangan masing-masing untuk bersama.
Diiringi bunyi napasnya sendiri yang berat tetapi lembut, pria itu berpaling. Ia menuruni anak-anak tangga, mengambil shotgun 12 gauge laras ganda yang kerap ia pakai berburu merpati, lalu keluar ke beranda. Saat itu awal Juli dan langit pias dan angin hanya lewat sesekali. Pria itu mencium bau rumput dan logam bergemuk. Chamber diisi dua butir peluru. Ujung laras ditempelkan pada kening. Pelatuk didekatkan ke ibu jari.
“Apa yang diinginkan orang?” tanya pria itu kepada sahabat yang kelak menuliskan riwayat hidupnya, A.E. Hotchner, beberapa pekan sebelum pagi itu. “Kesehatan, pekerjaan yang lancar, keriaan bersama kawan-kawan, kenikmatan di ranjang. Dan aku tidak lagi punya semua itu, kau tahu. Tidak satu pun.”
Ia yang senang menutup surat-surat pribadinya dengan frase il faut d'abord durer atau “di atas segalanya, orang mesti bertahan” itu memutuskan untuk berhenti menjelang usia 62. Namun, tidak seperti Sayid Hamid Benengeli dalam sebuah sajak Goenawan Mohamad yang “membuat tanda terakhir dengan dawat di kertasnya, seperti sebuah titik, seperti melankoli,” Ernest Hemingway memilih berhenti diiringi dentam.
Pada 2 Juli 1961, tepat hari ini 61 tahun lalu, di dinding depan rumahnya, Hemingway membuat tanda terakhir dengan darah dan otak dan serpihan batok kepala. []
Editor: Nuran Wibisono