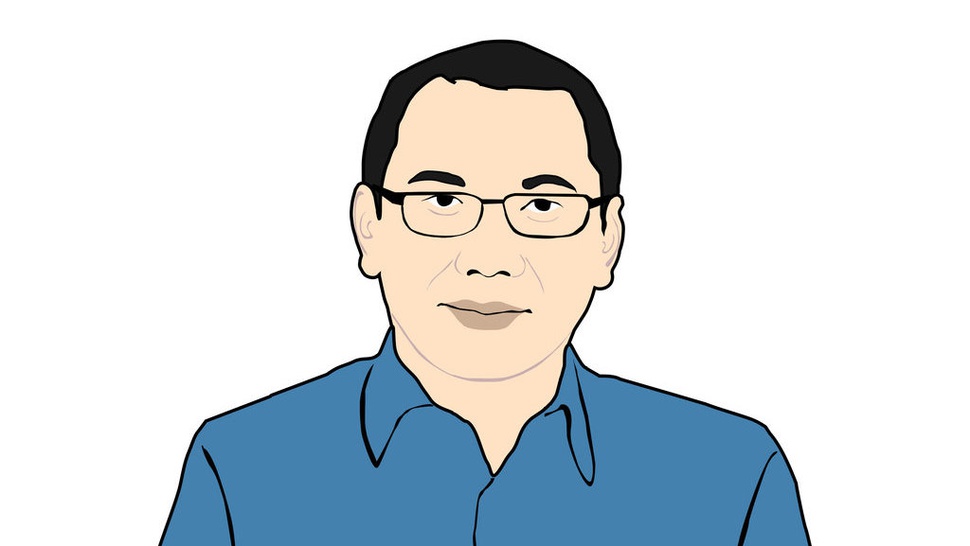tirto.id - Apakah bisa dibayangkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang telah ada (dan akan bertambah) jika nanti penggunaannya berkurang drastis? Apakah nasib pembangkit listrik berkapasitas besar, yang menggunakan batu bara tersebut, akan bernasib seperti ojek pangkalan di tengah serbuan ojek online?
Bayangan itu sepertinya bisa menjadi kenyataan jika melihat langkah akuisisi kontroversial pengusaha AS Elon Musk saat mengintegrasikan produsen mobil listrik Tesla dan SolarCity, produsen panel surya terbesar di Amerika Serikat. Tesla dan SolarCity tengah mengembangkan panel surya pengganti genting sebagai atap rumah. Bentuknya mirip genting biasa. Bedanya, mereka menanam panel surya yang terintegrasi dengan baterai. Energi yang disimpan baterai kemudian bisa dipakai untuk isi ulang mobil listrik.
Genting ini memiliki elemen pemanas, yang berfungsi membersihkan atap dari salju agar tetap menghasilkan energi di musim dingin. Bahan dasar genting adalah gelas kuarsa, yang membuatnya 2-3 kali lebih kuat dari bahan genting biasa. Harganya pun akan dibuat lebih murah dibandingkan panel surya konvensional plus genting biasa.
Musk menyebut ada tiga bagian dari solusi energi surya yang dibuatnya. Produksi energi (panel surya), penyimpanan (baterai), dan transportasi (mobil listrik). Musk menjual ketiga produk tersebut melalui Tesla. Langkah Tesla-Solarcity ini rupanya makin memperpendek jarak antara sektor energi dan industri gelombang keempat, atau sering disebut "Revolusi Industri 4.0."
Sektor Energi dalam Revolusi Digital
Sejarawan ekonomi dari Northwestern University J. Gordon menyebut gelombang pertama industri terjadi ketika penemuan mesin uap dan kereta api (1750-1830). Gelombang kedua: penemuan listrik, alat komunikasi, kimia dan minyak (1870-1900); dan gelombang ketiga: penemuan komputer, internet, dan telepon genggam (1960 hingga sekarang).
Setelah tiga revolusi tersebut, banyak pakar ekonomi yang meyakini sejak dekade terakhir telah terjadi revolusi industri ke-4, ditandai oleh revolusi digital. Istilah industri 4.0 pertama kali diperkenalkan pada Hannover Fair 2011.
Selaras perkembangan itu, sektor energi, khususnya dalam bidang kelistrikan, juga mengalami perubahan. Industri tentu memerlukan pasokan energi yang stabil agar dapat berkembang dengan baik.
Pakar kelistrikan Muhammad Reza dalam artikelnya, “Inovasi Disruptif Listrik 4.0”, membagi sejarah perkembangan kelistrikan menjadi empat pembabakan. Listrik 1.0 lahir pada awal penemuan bohlam oleh Thomas Alva Edison pada 1880-an. Teknologinya masih arus listrik searah (DC/Direct Current). Perusahaannya, Edison Illuminating Company, mengoperasikan generator arus searah berbahan bakar batu bara. Listrik 1.0 hanya bisa dikonsumsi oleh para pelanggan lokal yang rumahnya dekat dengan perusahaan listrik.
Listrik 2.0 diawali “Perang Arus” pada 1880 dan 1890-an. Perusahaan Edison mendapat saingan baru, yakni George Westinghouse-Nikola Tesla, yang membangun teknologi listrik berbasis arus bolak-balik (AC/Alternating Current). Penemuan transformator (trafo) memungkinkan arus listrik bolak-balik dapat dinaik-turunkan tegangan dengan relatif mudah dan efisien. Jaringan listrik menjadi lebih praktis dan efisien untuk disalurkan ke sejumlah wilayah yang sangat luas.
Perusahaan-perusahaan listrik antar-daerah kemudian dapat saling berhubungan dengan relatif mudah dan membentuk satu interkoneksi. Hal ini membuat pembangkit di suatu daerah dapat menyuplai daerah lain yang membutuhkan.
Pada praktiknya, model bisnis listrik 2.0 bersifat monopolistik. Perusahaan memonopoli pembangkitan, penyaluran transmisi, dan penyaluran distribusi, sehingga pelanggan tak mempunyai pilihan lain.
Mayoritas pembangkit listrik 2.0 menggunakan sumber energi fosil, khususnya batu bara. Di masa popularitasnya, pembangkit ini sangat efisien dari segi biaya. Namun, beberapa dekade belakangan, sejalan kesadaran masyarakat dunia mengenai kelestarian lingkungan hidup, sumber energi batu bara semakin didorong untuk ditinggalkan karena menurunkan kualitas udara. Apalagi ancaman pemanasan global kian tampak.
Pemerintah di banyak negara pun menandatangani Kesepakatan Paris pada 2015 untuk memerangi dampak perubahan iklim akibat pemanasan global. Implementasi dari kesepakatan tersebut antara lain memperbanyak penggunaan energi baru dan terbarukan yang lebih bersih, termasuk untuk pembangkit listrik. Energi terbarukan yang kian banyak digunakan adalah angin/bayu dan matahari/surya. Secara teknis, pembangkit listrik tenaga bayu dan surya ini berkarakter non-kontinu.
Pada tahap ini muncullah konsep listrik 3.0, yang berhasil menghubungkan listrik berkarakter non-kontinu dengan jaringan listrik yang kontinu. Pembangkit listrik tenaga bayu dan tenaga surya yang dibangun pun semakin berskala besar guna mendukung interkoneksi ini.
Di Indonesia, pembangkit listrik tenaga surya dan bayu dalam skala besar pun sudah dibangun.
Pembangkit listrik tenaga bayu pertama dan terbesar di Indonesia, yang menggunakan kincir angin raksasa, terletak Desa Mattirotasi, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Pembangkit ini memiliki 30 wind turbin generator atau kincir angin dan kapasitasnya 75 MW, menempati lahan 100 hektare. Pembangkit listrik tenaga surya terbesar ada di Dusun Bajaneke, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Berkapasitas 5 MW, pembangkit ini menempati lahan seluas 7,5 hektare.
Teknologi panel surya juga terus berkembang. Efisiensinya meningkat, sementara biaya produksi terus turun. Di tingkat global, harga panel surya turun dari US$25/watt pada 1980-an menjadi US$1/watt saat ini. Jenny Chase, kepala analisis tenaga surya dari New Energy Finance, memprediksi biaya pendirian pembangkit listrik tenaga surya akan mencapai 73 sen dolar/watt pada 2025.
Prediksi ini diperkuat oleh Bloomberg New Energy Finance, yang menyebut secara global tenaga surya bakal lebih murah dari batu bara pada 2025. Dampaknya, premi resiko pinjaman bank akan lebih rendah, dan karenanya mampu mendorong kapasitas produksi di pelbagai lokasi.
Konsep Gelombang Listrik 4.0
Dalam produk Tesla-SolarCity, perusahaan ini memperkuat karakter panel surya yang fleksibel karena bisa ditempatkan di atap rumah, atau bangunan komersial. Skalanya pun bisa kecil, menengah, atau besar. Pembangunannya bisa bertahap, sehingga meringankan secara finansial. Walhasil, pembangunannya tidak serumit pembangkit listrik tenaga uap yang membutuh pelabuhan dan tempat penimbunan batu bara, selain lokasi yang luas.
Pengoperasian panel surya lebih sederhana dan dapat dikerjakan langsung oleh pemilik rumah atau bangunan, sehingga bisa mengurangi ketergantungan konsumen listrik pada perusahaan penyedia listrik. Pelanggan bisa menjual produksi listrik dari rumah atau bangunannya ke jaringan listrik nasional. Nantinya, antar-pelanggan dapat saling bertukar energi listrik. Kondisinya bisa seperti penyedia jasa rental mobil atau motor, yang dapat dipesan secara online. Jasa energi listrik ini didasarkan pada prinsip tracking the electron.
Prinsip itu akan semakin berkembang ketika beban listrik yang digunakan semakin meluas. Hal ini bisa terjadi khususnya jika mayoritas sektor transportasi sudah menggunakan energi listrik. Kecenderungannnya pun sudah terlihat dengan kemunculan pabrik-pabrik produsen mobil listrik. Bahkan, pabrikan komputer dan telepon pintar Apple juga tengah bersiap memproduksi mobil listrik.
Ketika pembangkit listrik berupa panel surya—bersama beban dan kendaraan listrik—sudah menjadi komponen utama kelistrikan, maka digitalisasi platform pembangkitan dan penggunaan listrik pun sangat dimungkinkan. Pada saat itulah terjadi gelombang kelistrikan 4.0.
Produsen sekaligus konsumen listrik dapat melakukan ”pelabelan” digital (smartmeter plus) dari setiap kWh listrik yang dihasilkan panel surya di rumah/bangunannya. Mereka juga bisa melacak penggunaannya dalam platform digital yang terintegrasi pada telepon pintar (smartphone). Hal-hal ini bisa terjadi lantaran beban listrik, termasuk kendaraan listrik, sudah saling terhubung dengan internet (IoT, Internet of Things).
Di Mana Posisi Indonesia?
Apakah Indonesia sedang mengarah ke tren global tata kelola energi ini? Gerakan untuk melakukan efisiensi energi terus dikampanyekan. Digitalisasi energi pun mulai dirintis. Namun efisiensi yang melandasi praktik konversi energi tidak berjalan baik.
Indonesia sudah memiliki PP 70/2009 tentang Konservasi Energi. PP ini mendefinisikan konservasi energi sebagai upaya sistematis dan terencana untuk melestarikan sumber daya energi di dalam negeri, serta meningkatkan efisiensi energi. Konservasi energi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, pengusaha, serta masyarakat umum.
Peraturan ini mewajibkan setiap pengguna energi sebanyak 6.000 ton ekuivalen minyak per tahun agar memiliki manajer dan auditor energi yang bertugas menerapkan konservasi energi.
Sayangnya, pelaksanaan aturan tersebut tersendat. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat, dari 346 perusahaan dengan konsumsi energi di atas 6.000 ton setara minyak per tahun, ada 137 perusahaan yang belum melapor. Salah satu kendalanya, terbatasnya sumber daya manajer dan auditor energi di Indonesia.
Di sisi lain, sejumlah pihak kini merangsang upaya-upaya rintisan (startup) baru untuk mencari solusi melalui cara smart energy. Caranya dengan mengintegrasikan sumber energi terbarukan, distribusi dan transmisi yang efisien (grid pintar dan lintas batas, pasar energi, infrastruktur), serta konsumsi optimal (manajemen sisi permintaan, penyimpanan, smart meter, prosumer). Solusi ini dipandang sebagai masa depan sektor energi, yang bakal mengoptimalkan efisiensi dan mengurangi biaya.
Solusi smartenergy ini belum tampak hasilnya. Kelistrikan di Indonesia boleh dibilang mayoritas masih menggunakan pembangkit listrik 2.0. Megaproyek listrik 35 ribu MW pun masih didominasi PLTU bersumber dari batu bara. Pembangkit listrik dari energi terbarukan belum menjadi arus utama kebijakan.
Namun, tak ada salahnya pemerintah kita, termasuk pemerintahan Joko Widodo saat ini, perlu bersiap diri agar tidak kaget seandainya ada startup smartenergy yang menawarkan solusi kelistrikan Indonesia, setidaknya di perkotaan, melalui aplikasi.
Ada baiknya pemerintah berkaca dari kasus transportasi berbasis aplikasi online yang mengubah pola transportasi di perkotaan, terutama menggeser akses transportasi konvensional. Ketika angkutan online sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, ternyata pemerintah belum siap dengan regulasi, sampai-sampai muncul gejolak di masyarakat.
Pemerintahan mungkin perlu mulai memikirkan cara mengatur “listrik online” hasil gelombang listrik 4.0 nantinya. Dari sisi operator, dalam hal ini PLN, tidak ada salahnya mulai memikirkan bagaimana sebaiknya kolaborasi yang perlu dilakukan dengan “produsen listrik rumahan”.
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.