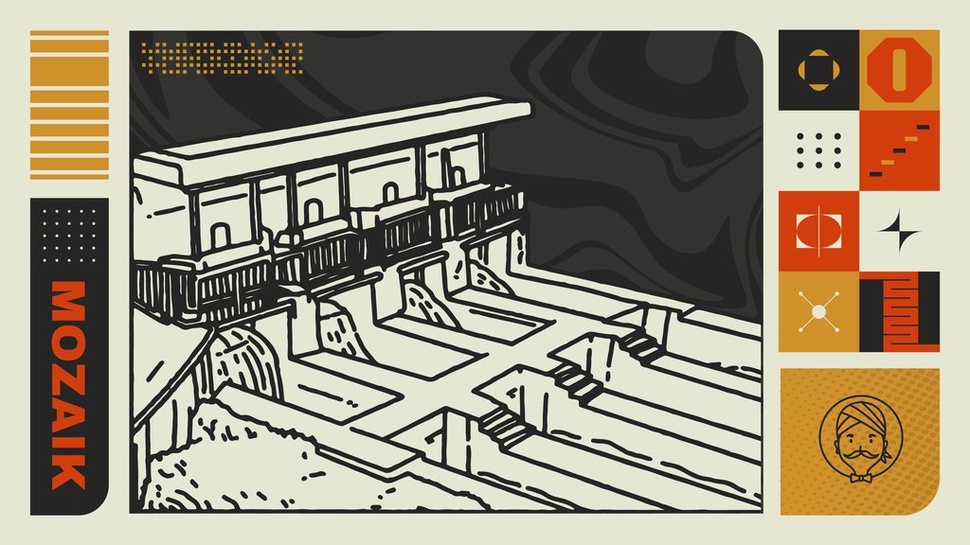tirto.id - Pada 5 Maret 1942, Residen Yogyakarta Lucien Adams agak setengah hati keluar dari kantornya di Gedung Agung. Apa mau dikata, Lucien hari itu harus meneken perjanjian tukar guling antara Pemerintah Hindia Belanda di Yogyakarta dengan Otoritas Militer Jepang. Sejak hari itu, Yogyakarta sah masuk ke dalam wilayah Kekaisaran Jepang.
Di masa yang sama, sejarak beberapa kilo ke selatan dari lokasi itu, hidup seorang raja muda berumur 31 tahun dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Sultan Hamengku Buwono IX menyadari situasinya kini dan apa yang tengah dihadapinya sama sekali berbeda ketimbang yang pernah dialami delapan pendahulunya.
Taktik macam apa yang sebaiknya dilakukan untuk menghadapi para “saudara tua” ini?
Bermula dari selokan
Bagi orang Yogyakarta, Hamengku Buwono IX memiliki asosiasi yang erat dengan Selokan Mataram. Selokan yang dimaksud ini–atau mungkin lebih tepat disebut kanal–didirikan oleh sang Sultan pada periode pertengahan Pendudukan Jepang. Pembangunannya memakan waktu sekira setahun, antara 20 Juli 1944 hingga 5 Juli 1945.
Pembangunan proyek hidrologi itu digawangi oleh Ir. Hiromitsu dari pihak Jepang dan Ir. K.R.T. Martonegoro dari pihak Yogyakarta.
Proyek Selokan Mataram atau yang oleh orang Jepang disebut Kanal Yoshihiro ini bukan proyek main-main. Kanal ini benar-benar membelah dataran Mataram, melintang dari barat ke timur. Titik pemberangkatan air di barat bermula di Desa Karangtalun, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, dan berakhir di timur, tepatnya di Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman.
Total panjang struktur Selokan Mataram mencapai 34,5 km, dengan lebar antara 4 sampai 18 m. Selokan Mataram juga dilengkapi dengan saluran tersier yang menghubungkan saluran pusat ke area persawahan di sekitarnya.
Uniknya lagi, Selokan Mataram merupakan kanal pertama buatan orang Indonesia yang mampu “menyebrangi” sungai-sungai yang dilintasinya. Itu berkat penerapan teknologi akuaduk atau jembatan air dalam pembangunannya. Sampai saat ini, terdapat 27 jembatan air yang masih bisa dijumpai di Selokan Mataram. Bukan saja mengalirkan air di atas sungai, 5 di antaranya bahkan ada yang melintas di bawah sungai.
Mengapa Sultan Hamengku Buwono IX berani mencanangkan megaproyek semacam ini di masa Pendudukan Jepang yang sulit?
M. Roem dkk. dalam Takhta untuk Rakyat: Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX. (2011) menyebut Sultan Hamengku Buwono IX menyodorkan proyek ini kepada Pemerintah Pendudukan Jepang sebagai tanggapan atas keresahan mereka atas daya produktivitas pangan Yogyakarta yang rendah.
Sementara itu, S.S. Lienan dalam Yogyakarta pada Masa Pendudukan Jepang 1942-1945 (1976) menyebut pendirian Selokan Mataram erat kaitannya dengan siasat Sultan Hamengku Buwono IX untuk menghindarkan warga Yogyakarta dari tuntutan romusha (kerja paksa).
Teori ini dikuatkan dengan kesaksian sang Sultan kepada M. Roem dan kaitannya dengan kunjungan Sultan ke Jawa Barat medio Mei 1944. Kunjungan yang diiringi oleh Adipati Paku Alam VIII, B.P.H. Hardjonegoro, K.P.H. Soerrjaningprang, K.P.H. Nototaruno, dan K.R.T. Notonegoro ini seakan membuka mata Sultan akan kekejaman Jepang dalam praktek romusha. Sultan menyaksikan sendiri penderitaan orang Jawa Barat yang dipaksa bekerja di beberapa tambang belerang.

Mempertemukan Dunia Timur dan Barat
Siasat sang Sultan mempekerjakan warga dalam proyek Selokan Mataram untuk menghindari romusha kemudian jadi semacam cerita turun-temurun. Secara kultural, hal itu pun tidak dapat dianggap remeh. Dalam kacamata kebudayaan, ia menyiratkan aspek lain yang lebih laten.
Titik tolak akan hal ini bisa ditelisik melalui kutipan pidato pengangkatan (jumenengan) sang Sultan pada 1939 yang dicatat Roem dkk. berikut ini.
“Sepenuhnya saya menyadari bahwa tugas yang ada di pundak saya adalah sulit dan berat, terlebih-lebih karena ini menyangkut mempertemukan jiwa Barat dan Timur agar dapat bekerja sama dalam suasana harmonis, tanpa yang Timur harus kehilangan kepribadiannya.”
Pidato itu bisa jadi semacam kode dalam menggambarkan prinsip bernegara sang Sultan, yang mengedepankan harmonisasi dua kutub budaya. Secara pragmatik politik, siasat proyek Selokan Mataram itu bisa dipandang sebagai tendensi “kebaratan” sang Sultan.
Sementara dari sisi historis-kultural, proyek itu mengisyaratkan masih langgengnya konsep Dewaraja—konsep purba yang memosisikan seorang raja setara dengan para dewa. Salah satu aspek dari konsep Dewaraja ini adalah hubungan antara raja dan air atau raja sebagai penguasa air.
Mengapa demikian? Jejak raja sebagai penguasa air semacam itu bisa kita jumpai untuk kali pertama pada Raja Purnawarman dari Kerajaan Tarumanagara yang menitahkan pembangunan sungai Candrabaga, seperti dijelaskan G. Coedes dalam Asia Tenggara Masa Hindu-Buddha (2017).
Di masa kuno, seperti dijelaskan Karl Wittfogel dalam Oriental Despotism: a Comparative Study of Total Power (1957), raja-raja di Asia meneguhkan kuasa politiknya melalui penguasaan atas pertanian dan pengairan. Secara tradisional, raja-raja masa lalu dihormati karena merekalah yang mengatur pengairan. Begitulah rakyatnya kemudian mengibaratkan kekuasaannya itu seperti kuasa dewa.
Kerangka berpikir Dewaraja yang turun-temurun itu akan lebih dahsyat lagi efeknya ketika seorang raja mempertunjukkan sisi “keilahiannya” di masa terjepit. Kemerosotan harapan hidup di kalangan orang Jawa, sebagaimana disebut oleh B.J.O. Schrieke dalam Kajian Historis Sosiologis Masyarakat Indonesia: Penguasa dan Kerajaan Jawa pada Masa Awal (2018), memiliki semacam prinsip siklus yang dipercaya turun-temurun. Bahwa suatu masyarakat pada akhirnya akan mencapai keterpurukannya (pralaya) dan pada saat itulah seorang dengan superpower hadir sebagai penyelamat mereka.
Kondisi semacam ini dapat kita tengok misalnya pada kasus Pangeran Diponegoro atau Raja Airlangga di masa klasik. Oleh karena itu, Sultan Hamengku Buwono IX pada hakikatnya sukses mengawinkan teknologi pengairan Eropa mutakhir dengan simbolitas politik tradisional Jawa untuk mengimbangi kekuatan politik Pemerintah Pendudukan Jepang yang ganas nan represif.
Maka pantaslah kita sebut sang Sultan sebagai Dewaraja terakhir Tanah Jawa.
Penulis: Muhamad Alnoza
Editor: Fadrik Aziz Firdausi